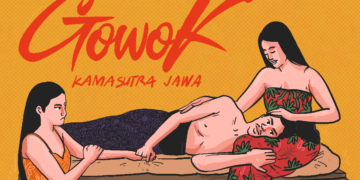MOJOK – Gambaran akan sosok Minke ada banyak ragamnya di tiap kepala pembaca Bumi Manusia. Setiap pembaca punya “Minke”-nya masing-masing. Lantas kenapa “Minke”-nya Hanung Bramantyo harus dicaci hanya karena pemeran sosoknya adalah “Dilan” di kepala kita?
Ganjil rasanya melihat warganet memberikan reaksi tidak suka secara berlebihan atas keputusan Hanung Bramantyo (dan Falcon Pictures tentu saja) memilih Iqbaal Ramadhan untuk memainkan Minke. Ada yang protes dengan bawa-bawa muka ganteng Iqbaal, ada yang menyentil dengan bikin kredo “Dia adalah Minke-ku 1920”, sampai ada yang mengungkapkannya dalam bentuk humor demi menjaga pahala puasa.
Intinya, mudah dibaca bahwa penyebab keberatan itu adalah Iqbaal dirasa tidak cukup matang sebagai aktor untuk memainkan tokoh Minke yang secara umum dianggap sebagai karakter yang sangat kompleks. Dan, yang sulit disembunyikan dari alasan kebanyakan warganet itu adalah; bisa-bisanya bintang muda kemarin sore memerankan tokoh agung dari Bumi Manusia karya legenda Pramoedya Ananta Toer.
Nah, parahnya saya jadi ikut ikut-ikutan melihat reaksi para warganet tersebut. Tapi reaksi saya lebih kepada pertanyaan kritis; Lho, kenapa harus bereaksi keras secara berjamaah begitu sih? Kenapa kita tidak woles dan menontonnya saja nanti (meskipun tujuannya adalah untuk kritik pahit seperti ini) atau mengabaikannya saja (toh semua yang viral bakal berlalu bersama update). Kenapa harus bereaksi dengan sikap yang—nuwun sewu—agak fundamentalis begini, kawan?
Seperti kita tahu, industri perfilman Indonesia sepertinya sudah mulai masuk ke tahap: untuk bisa dapat cerita bagus, pembuat film bisa mengandalkannya pada karya sastra yang sudah terbit. Tentu di sini istilah sastra perlu dimaknai dalam artian yang seluas-luasnya, baik yang serius maupun yang populer.
Tentu ini pertanda bagus, bahwasanya para pembuat film peduli dengan pentingnya menghadirkan cerita yang sudah memiliki dampak bagi para pembacanya. Entah dampak ideologis-historis seperti Bumi Manusia atau dampak romantis-historis seperti Dilan Dia adalah Dilanku Tahun 1990. Yang pasti, film yang memakai cerita karya sastra sudah melewati proses penyaringan dengan ditandai seperti apa kalangan penggemarnya, berikut juga dengan jumlah pembacanya.
Tapi, tentu saja di sini perlu dicatat bahwa proses pengalihan dari satu wahana ke wahana yang lain tentu selalu disertai perubahan-perubahan yang menjadikan filmnya sendiri memiliki selisih dengan bentuk karya pertamanya. Kadang penonton menganggap filmnya lebih bagus dari novelnya atau—biasanya yang terjadi—novelnya jauh lebih bagus daripada filmnya.
Tapi, karena yang namanya film itu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seni peran para pemainnya, maka mungkin wajar saja kalau akhirnya warganet menyesalkan keputusan dipilihnya Iqbaal sebagai tokoh utama di Bumi Manusia.
Saya pribadi—sebagai seorang pengamat film kelas kelurahan—termasuk yang berpendapatan akting Iqbaal di Dilan 1990 kurang begitu bagus. Ekspresi Iqbal saat melontarkan gombalan-gombalan dan ujaran-ujaran hardboiled dari Pidi Baiq terkesan terlalu mekanis. Pada akhirnya, percakapan Dilan dan Milea jadi tidak berdampak kepada saya sebagai penonton.
Persoalan yang mirip dengan percakapan dalam film Love Story (1972) antara Oliver dan Jennifer. Padahal, kalau membaca novelnya (baik novelnya Pidi Baiq maupun novelnya Erich Segal), percakapan kedua pasangan itu mengasyikkan karena gombalan-gombalan amoh-nya.
Baiklah, sepertinya, titik masalah ini ada pada adaptasi naskah yang kurang usaha. Saat membaca novelnya, gombalan-gombalan kedua pasangan itu akan membuat kita berhenti sejenak untuk menikmati hentakan kata-katanya atau sentakan tiap kalimatnya.
Tapi, saat berbentuk film, penonton seperti diburu oleh kalimat demi kalimat tanpa diberi kesempatan sejenak untuk menyesap lalu menikmatinya. Seolah-olah dialog-dialog dahsyat itu langsung tertelan sampai tenggorokan begitu saja dan tidak memberi efek apa-apa.
Si “Dilan” tidak memberi kita waktu untuk mencerna dan menikmati kekuatan gombalannya. Padahal harusnya ada cara-cara lain untuk itu. Misalnya yang paling liar menoleh kepada penonton dan meminta persetujuan penonton apakah gombalannya untuk Milea kena atau tidak, seperti Ryan Reynold-nya Deadpool.
Saat kita mengingat Dilan dan mengingat masalah ini pada akting Iqbaal, kita bisa saja mengatakan akting Iqbaal kurang bagus. Dengan cela pada kemampuan akting seperti itu, bagaimana mungkin Iqbaal bisa memainkan Minke? Begitu selanjutnya logika kita berjalan.
Masalahnya kemudian, memang apa hanya ada satu Minke di dunia ini?
Kalau Anda tanya Pak Max Lane, jawabannya ada tiga Minke. Tapi pertanyaan saya ini lain—maksud saya, bagaimana kalau misalnya Minke yang ada di pikiran para pembaca yang menghargai Bumi Manusia itu berbeda dengan Minke yang ada di kepala Hanung Bramantyo dan Falcon Pictures?
Kalau kita percaya bahwa sebuah karya itu multitafsir (dan bahkan penulisnya sendiri pun tidak lagi memiliki otoritas dalam menentukan makna karyanya ketika karyanya lepas ke publik), maka jawaban dari pertanyaan tadi jelas: ya, memang Minke yang ada di kepala Hanung Bramantyo berbeda dengan Minke yang ada di kepala banyak pembaca lain. Dan masing-masing Minke itu sudah sah adanya.
Bisa saja, di kepala Hanung Bramantyo, Minke adalah seorang pemuda yang seperti Iqbaal yang lagi laris dan telah membuat film Dilan 1990 sukses di pasaran. Bisa saja bagi Hanung, agar Minke bisa hadir dengan cukup baik tidak hanya bagi pembaca generasi tua macam Anda dan saya, tapi juga bisa hadir untuk generasi kekinian, maka diperlukan Iqbaal yang muda, ganteng, dan best-selling itu. Bukan Minke yang rasa orba, tapi Minke dengan rasa milenial.
Pemahaman atas karakterisasi Minke oleh Hanung dan pemilihan Iqbaal pada dasarnya adalah satu paket dari pemaknaan Hanung Bramantyo atas Minke. Dan kita, sebagai pembaca yang lain, hanya bisa mendebat dan menyodorkan bantahan. Tidak lebih.
Kita sering ngotot bahwa pemaknaan yang tunggal dan absolut adalah pencipta hadirnya kelompok-kelompok fundamental yang mendaku diri paling benar. Menganggap penafsiran kelompok lain sesat dan tidak murni.
Bahkan, beberapa waktu silam di Surabaya hidup kita diusik oleh orang-orang dengan pemaknaan tafsir tunggal yang radikal. Tentu saja, kita sebagai pembaca sastra dan penikmat budaya pop tidak ingin pula ikut-ikutan jadi radikal di sektor ini dengan memaksakan pemaknaan Minke yang ada di kepala kita yang harusnya difilmkan oleh Hanung bukan?
Namun, kembali lagi, kita juga masih berhak mendebat pilihan pemaknaan Hanung, asalkan kita bisa mendukung argumentasi kita. Kalau kita hanya ikut-ikutan protes atas pemilihan Iqbaal tanpa benar-benar bisa menunjukkan letak kesalahannya atau menunjukkan bahwa pemaknaan kita lebih tepat berdasarkan kriteria atau standar tertentu—itu artinya kita hanya ikut latah-latahan saja.
Jadi ya, daripada ikut terlibat hanya sebagai bahan bakar tungku pemanasan media sosial, mungkin akan lebih baik kalau kita memilih satu dari beberapa opsi yang saya tawarkan ini.
Pertama, nonton dulu filmnya baru kemudian mengkritisi akting Iqbaal serta pemaknaan Hanung atas Minke. Artinya, kritik ini baru bisa disampaikan kalau filmnya sudah tayang di bioskop.
Kedua, mengabaikan film ini, membiarkannya berlalu bersama linimasa. Lagipula Anda menonton atau tidak juga tidak begitu ngaruh, cuma kehilangan satu penonton ini si Hanung dan Iqbaal.
Ketiga, tetap nonton ke bioskop, tapi bawa bekal nyinyirin Iqbaal sejak trailer “Bumi Manusia the Movie” muncul di Youtube, lalu mencak-mencak di linimasa media sosial bahwa filmnya buruk, akting Iqbaal adalah bencana, karya Hanung ini sampah… meskipun baca novel Bumi Manusia saja belum.