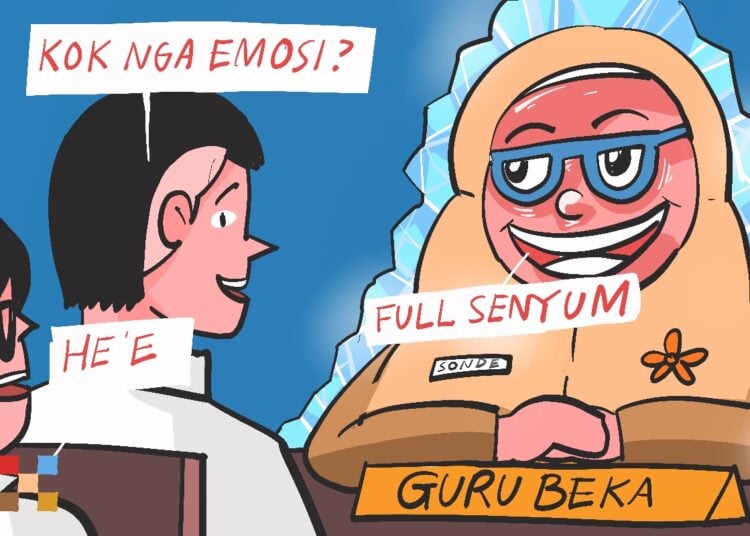Bagi Dyan (29), menjadi guru Bimbingan Konseling (BK) adalah sebuah pekerjaan yang melelahkan. Di permukaan, ruangan berukuran 3×4 meter itu tampak tenang, jauh dari hiruk-pikuk kelas yang bising. Namun, di balik pintu tertutup itu, tersimpan beban mental yang nyaris tak terukur.
Guru BK hari ini tidak sedang duduk santai; mereka tengah bertarung di garis depan kesehatan mental remaja yang kian rapuh. Sialnya, peran vital mereka kerap disepelekan.
***
Dunia pendidikan kita memang sedang tidak baik-baik saja, dan guru BK adalah orang pertama yang harus memungut kepingan masalah tersebut. Terutama, bagi mereka yang mengampu jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pasalnya, demografi yang mereka hadapi adalah Generasi Z (Gen Z), sebuah generasi yang tumbuh dengan berbagai kemajuan, tapi menyimpan kompleksitas masalah psikologis yang jauh lebih rumit dibandingkan generasi-generasi sebelumnya.
Tingkat kecemasan yang tinggi, krisis identitas, hingga perundungan siber (cyberbullying) menjadi menu sarapan sehari-hari para guru BK. Sayangnya, realitas berat ini berbanding terbalik dengan apresiasi yang diterima.
Profesi ini kerap dipandang sebelah mata, dianggap sekadar pelengkap struktur sekolah, atau parahnya, “polisi sekolah” yang menganggur jika tidak ada siswa yang nakal. Padahal, di tangan merekalah karakter siswa dibentuk dan diselamatkan. Ironi inilah yang membuat kepala para guru BK kian pening di tengah tuntutan zaman yang makin gila.
Guru BK mengabdi tanpa apresiasi, kenyang makan hati bukan gaji
Potret buram profesi ini terpampang jelas pada wajah Dyan, seorang guru BK di sebuah SMA di Kabupaten Sleman. Dyan adalah representasi nyata dari betapa beratnya memikul tanggung jawab moral pendidikan di tengah himpitan ekonomi yang mencekik.
Perempuan ini sudah menekuni profesinya sejak tahun 2021. Empat tahun berjalan, tapi nasib baik seolah enggan singgah. Status kepegawaiannya masih terpaku sebagai tenaga honorer. Tidak ada kenaikan pangkat, apalagi jenjang karir yang jelas sejak hari pertama ia menapakkan kaki di sekolah tersebut. Pendeknya, ia seperti “mengabdi tanpa diapresiasi”.
“Tapi in this economy, kita dipaksa buat nggak boleh nyerah ‘kan? Ya itu alasanku tetap bertahan,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).
Alhasil, untuk bertahan hidup di Jogja, yang biaya hidupnya kian merangkak naik, Dyan harus memutar otak. Mengandalkan gaji dari satu sekolah sama saja dengan “bunuh diri finansial”. Ia pun terpaksa mengajar di dua sekolah sekaligus, satu sekolah negeri dan satu sekolah swasta.
Namun, akumulasi lelah itu dibayar murah. Penghasilannya dari masing-masing sekolah itu kurang dari Rp500 ribu per bulan. Angka yang jauh dari kata layak untuk seorang profesional.
“Kalau cuma andalkan gaji sekolah, enggak cukup,” keluhnya dalam hati.
Dyan tidak bisa berpangku tangan. Suaminya, yang bekerja sebagai karyawan swasta, hanya membawa pulang gaji setara UMR Jogja yang pas-pasan. Demi dapur tetap ngebul, Dyan masih harus mengambil pekerjaan lepas (freelance) di sela-sela waktunya yang sempit.
Di sinilah Dyan merasakan beban ganda yang nyata. Di satu sisi, ia dituntut profesionalisme tinggi: harus peka memahami karakter ratusan siswa dan menyelesaikan benang kusut masalah mereka. Di sisi lain, negara dan institusi seolah menutup mata, tak memberikan apresiasi minimal berupa upah yang memanusiakan manusia.
Guru BK bukan lagi “tukang hukum”
Jika ada yang berpikir guru BK kerjanya hanya duduk diam, Dyan bilang mereka perlu menukar posisi dengannya, sehari saja. Padahal, menjadi guru BK itu memusingkan setengah mati. Tiap hari, pintu ruangannya diketuk oleh masalah baru yang dilaporkan siswa.
Menurutnya, stigma lama harus dikubur dalam-dalam. Kultur guru BK saat ini sama sekali berbeda dengan era 10 atau 20 tahun lalu. Dulu, guru BK mungkin identik dengan wajah garang, “tukang gunting rambut”, dan mencatat poin pelanggaran. Pendeknya, sebuah sosok “tukang ngasih hukuman” yang ditakuti.
“Kalau sekarang, guru BK adalah tempatnya berkeluh kesah. Tempat curhat para siswa,” tegasnya. Tugas Dyan kini lebih mirip psikolog klinis ketimbang penegak kedisiplinan.
Syukur-syukur jika masalah itu bisa diselesaikan di sekolah. Sayangnya, seringkali masalahnya jauh lebih pelik. Misalnya, Dyan kerap harus menjadi jembatan antara siswa dan orang tua yang hubungannya merenggang.
Baginya, ini adalah beban emosional tersendiri. Meski akar masalahnya ada “di luar” pagar sekolah, Dyan tetap memikul tanggung jawab moral untuk menyelesaikannya agar siswa tersebut bisa belajar dengan tenang.
Belum lagi urusan asmara remaja. Bagi sebagian orang dewasa, mungkin itu terdengar remeh. Namun, bagi Gen Z masalah ini seperti “kiamat”. Dyan bercerita, tak sedikit siswa yang datang menangis tersedu-sedu karena urusan hati.
Di sini, Dyan harus bermain peran ganda dengan sangat hati-hati. Di satu sisi, ia adalah pendidik yang harus tegas mengedukasi bahwa usia SMA adalah usia minor, di mana prioritas utama adalah belajar dan belum waktunya terjerumus ke dalam pacaran.
Namun, di sisi lain, ia tidak bisa sekadar melarang. Ia harus menjadi sosok yang mendukung, mendengarkan, dan menguatkan mental siswanya yang sedang patah hati itu.
“Kalau pendekatanku salah, anak-anak gen Z ini makin galau, makin nggak fokus belajarnya.”
Masalah Gen Z yang dihadapi Dyan makin bermacam-macam, makin random, dan tidak terprediksi, membuat tantangan menjadi guru BK hari ini jauh lebih besar daripada sekadar mencatat poin kenakalan siswa.
Dianggap lembek oleh boomer
Tantangan Dyan tidak hanya datang dari siswa, tetapi juga dari rekan sejawat. Masalah kerap muncul karena profesi dan pendekatannya dianggap sepele, terutama oleh guru-guru senior dari generasi boomer.
Di ruang guru, tak jarang Dyan mendengar perbandingan yang menyakitkan telinga. Para senior ini kerap membandingkan cara mereka menangani siswa zaman dulu dengan cara Dyan sekarang.
“Dulu, BK itu tegas, ngasih hukuman tak segan-segan,” kira-kira begitu natasi yang sering didengungkan kepadanya. Cara Dyan yang dialogis dan empatik pun dianggap “lembek” dan memanjakan siswa.
Namun, bagi Dyan, ini adalah perbandingan yang tidak apple-to-apple. Tiap masa ada caranya, tiap generasi ada bahasanya. Menghadapi Gen Z dengan gaya “militeristik” ala tahun 90-an hanya akan menciptakan depresi, bukan kedisiplinan.
Baginya, pendekatan hari ini harus berbeda, kudu lebih humanis dan lebih banyak mendengar. Sayangnya, pemahaman ini belum sepenuhnya diterima oleh ekosistem sekolah yang masih didominasi pola pikir lama.
“Biasalah, boomer yang masih terjebak di mentalitas lampau,” kata Dyan.
Penjaga masa mepan yang kerap dilupakan
Tak cuma itu, Dyan melihat peran vital guru BK yang sering luput dari pandangan. Hari ini, guru BK tak sekadar tukang kasih hukuman atau tempat curhat. Mereka adalah penjaga karakter dan pengarah masa depan siswa.
Di tengah kebingungan remaja mencari jati diri, guru BK hadir sebagai pengarah. Siswa yang masih buta arah orientasi pendidikannya, tugas BK-lah yang membukakan peta. Siswa yang bingung mengenali minat dan bakatnya sendiri, tugas BK untuk menggali dan menguatkan potensi tersebut.
Bahkan, keputusan krusial seperti pemilihan jurusan kuliah–yang akan menentukan arah hidup siswa di masa depan–seringkali berada di bawah tanggung jawab dan bimbingan guru BK.
Bagi Dyan, ini bukan tugas main-main. Salah arah sedikit saja, masa depan anak orang jadi taruhannya.
“Jadi, kalau mau jujur-juruan, peran BK itu sentral dan pentin,” kata Dyan. “Sialnya, profesi ini kerap disepelekan aja sih. Secara sosial maupun finansial.”
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Kuliah di “Jurusan Sultan” Berujung Penyesalan Gara-gara Lebih Mendengarkan Google Ketimbang Guru BK, Lulusnya Mudah tapi Cari Kerja Susah atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan