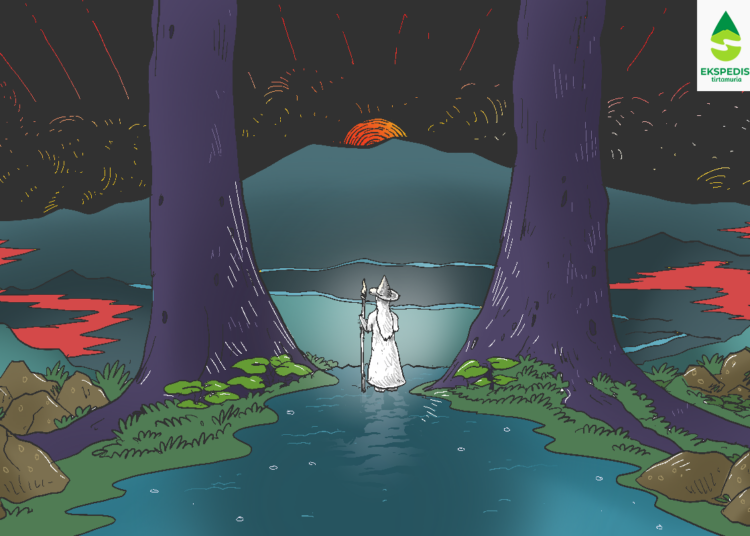Meski sejak kecil sudah akrab dengan ribuan anak tangga menuju makam Sunan Muria, tapi dengkul saya sudah terpancing linu bahkan sebelum menitinya satu persatu. Begitu yang saya alami kala menyusuri jejak-jejak ajaran ekoreligi Sang Sunan di Colo, Kudus, pada Rabu (8/10/2025) pagi.
Sebenarnya ada sarana ojek untuk mencapai puncak Gunung Muria. Tapi sedari kecil, tiap diajak ziarah Wali Songo oleh orang tua, mereka “memaksa” saya meniti anak tangga.
“Bayangkan, dulu Mbah Sunan (Sunan Muria) di sini syiar Islamnya belum ada ojek. Kalau nggak jalan kaki ya pakai kuda. Dulu pasti belum seenak ini jalannya,” tutur ibu saya tiap kali saya mengeluh capek dan menggerutu, “Harusnya naik ojek saja.”
Pitutur itu cukup berhasil membangkitkan semangat saya. Sejenak membuat saya lupa kalau ada ribuan anak tangga yang harus saya tapaki untuk mencapai puncak. Karena pikiran saya mencoba memvisualisasikan: Bagaimana dulu Sang Sunan naik-turun gunung di ketinggian sekitar 1600 mdpl itu untuk mendidik masyarakat.
Perjalanan syiar Sang Sunan yang penuh effort itu agaknya tak sia-sia belaka. Sebab, secara subtil ajarannya mengendap menjadi bagian hidup masyarakat setempat.

Tapa ngeli Sang Wali Lingkungan
Saya dan tim Ekspedisi Tirtamuria telah menyinggahi beberapa titik di lereng Muria: perbukitan Rejenu (Japan), perbukitan Patiayam (Gondoharum), Rahtawu, dan berakhir di hutan Muria di Colo.
Dari perjalanan itu, terbentang garis merah ihwal kesadaran sejumlah masyarakat dalam upaya menjaga alam—terutama kaitannya dengan sumber mata air. Yakni tilas laku hidup dari Sunan Muria sebagai pepunden di tanah Muria.
Dalam buku Sejarah Sunan Muria (UIN Walisongo, 2018), sosok bernama asli Raden Umar Said tersebut sedianya hidup di jantung peradaban Islam Jawa (Demak) pada 1470-an. Ia juga lahir dari sosok berpengaruh: Sunan Kalijaga. Namun, ia justru memilih jalan hidup asketis: Menuju pinggiran, ke Gunung Muria.

Sunan Muria lantas menjalani hidup tapa ngeli (tapa mengalir/hanyut). Bukan dalam arti harfiah, tapi melebur bersama masyarakat awam. Itulah kenapa kemudian dakwah-dakwah tentang Islam menjadi mudah diterima.
Ada beragam ajaran yang Sunan Muria dedah kepada masyarakat. Salah satunya adalah kesadaran menjaga alam dengan nilai-nilai Islam dan budaya setempat (ekoreligi). Maka tak heran jika peneliti atau sejarawan modern menjulukinya “Wali Lingkungan”.
Ajaran bertani hingga legenda parijoto
Merujuk catatan Yayasan Makam dan Masjid Sunan Muria dan cerita tutur yang berkembang di masyarakat setempat, selain mensyiarkan Islam, Sunan Muria juga dikenal concern terhadap pertanian.
Ia mengimbau masyarakat setempat untuk menanam sebagai ketahanan pangan dan ekonomi. Tanaman yang dikaitkan erat dengan Sang Wali Lingkungan misalnya parijoto dan kelor. Kala saya memasuki sisi bawah hutan Muria, dua tanaman tersebut amat mudah dijumpai, tumbuh di tengah pohon-pohon besar dari genus ficus.
“Parijoto ini dipercaya bisa mempercepat proses kehamilan. Konon dulu Sunan Muria menganjurkan wanita (yang sudah menikah) makan buah ini biar bisa hamil,” ungkap Triayanto Soetardjo, Pengasuh Yayasan Penggiat Konservasi Alam (PEKA) Muria yang turut mendampingi ekspedisi.

Sehari-hari Triyanto juga mengolah buah parijoto untuk dijadikan sirup. Katanya, peminatnya masih sangat banyak.
Dalam penelitian Devi Safrina dan Kolega berjudul, “Product Development of Parijoto Fruit (Medinilla speciosa Blume) and Its Potential as a Medicinal Plant: Review”, parijoto (Medinilla speciosa) merupakan buah perdu yang kerap tumbuh di lereng gunung.
Parijoto mengandung kadar flavonoid, tanin dan polifenol yang tinggi, sehingga berkhasiat untuk meningkatkan kesuburan. Selain itu juga berkhasiat sebagai anti-bakteri hingga mencegah sel kanker.
Alhasil, karena ragam khasiatnya tersebut, parijoto juga diolah menjadi produk-produk bernilai ekonomi, seperti sirup, pewarna makanan, permen jeli, dodol, hingga krim kecantikan.
“Sementara pohoh-pohon besar ini untuk menjaga sumber mata air. Kalau air terjaga, hutan terjaga, ekosistem akan berjalan semestinya,” sambung Triyanto.
Ekosentrisme hingga akidah muttahidah
Widi Mulyono dalam bukunya, “Napak Jejak Pemikiran Sunan Muria: Dari Ekoreligi hingga Akidah Muttahidah” mendedah alam pikir menakjubkan dari Sang Wali Lingkungan.
Dalam konteks lingkungan, Widi merumuskan lima fondasi ber-Islam dan berlingkungan ala Sunan Muria. Antara lain, tauhid lingkungan, fikih, lingkungan, tasawuf lingkungan, filanekorelgi, dan akidah muttahidah.
- Tauhid lingkungan: Pemahaman bahwa alam raya adalah teofani Allah Swt (punya hakikat Maha Memberi).
- Fikih lingkungan: Pemahaman perihal maqashid al-syariah (tujuan pokok syariat) atas alam. Dalam fikih, juga dalam Al-Qur’an, Allah Swt menekankan la yuhibbu al-mufsidin (tidak suka para perusak).
- Tasawuf lingkungan: Pemahaman landasan etis-sufistik dan keterhubungan manusia dengan teofani Allah Swt berupa alam. Pemahaman ini mengajak manusia untuk beranjak dari cara pikir antroposentisme ke ekosentrisme.
- Filanekoreligi: Pemahaman untuk membangun keadilan dan kesejahteraan antara manusia dan alam. Alam telah memberi banyak pada manusia, maka manusia harus seminimal-minimalnya menjaganya sebagai wujud terima kasih.
- Akidah muttahidah: Pemahaman bahwa akidah ber-Islam itu mencakup segitiga relasi (Allah, manusia, dan alam). Sehingga ibadah tidak berhenti pada aspek mahdlah (pada Allah) saja, tapi juga mempertimbangkan hablun min al-nas dan hablun min al-alam.
Lima rumusan ajaran itu, diharapkan membuat manusia memiliki kesalehan tidak hanya vertikal, tapi juga horizontal (terhadap sesama manusia dan sesama makhluk Allah Swt yang lain (alam)).
Menjadi saleh lingkungan ala masyarakat lereng Muria
Secara akar tradisi dan ideologi, tilas laku Sang Wali Lingkungan itu—disadari atau tidak—telah mengendap di sebagian banyak alam pikir masyarakat lereng Muria. Dan ini berbasis temuan-temuan tim Ekspedisi Tirtamuria saat berbincang dengan masyarakat di Japan (Rejenu), Gondoharum (Patiayam), Rahtawu, dan Colo.
Memang, tidak semua orang yang saya temui bisa memastikan, apakah gagasan menjaga lingkungan yang mereka pegang bersumber langsung dari Sunan Muria.
Baca juga serial Ekspedisi Tirtamuria lainnya:
- Pohon Beringin, “Si Angker” yang Menyelamatkan Sumber Mata Air di Lereng Muria
- Mata Air Abadi di Lereng Muria: Terus Mengalir dalam Pengkeramatan, Jadi Warisan Hidup untuk Anak-Cucu
- Menghidupkan Kembali Air Muria
Tapi setidaknya, satu, mereka mengamini riwayat bahwa Sang Sunan memang merupakan “Wali Lingkungan”, sehingga perlu diteladani. Dua, mereka menyadari bahwa manusia memang sudah seharusnya hidup bersenyawa dengan alam. Kira-kira begini temuan tim Ekspedisi Tirtamuria:
#A. Lamun siro mandi ojo mateni
Saat berkunjung di Desa Japan pada Rabu (16/07/2025), saya mendapati papan slogan penuh makna di kantor BUMDes Tunggak Jati. Berbunyi:
Lamun siro banter ojo nglancangi (Walaupun kamu kencang jangan mendahului)
Lamun siro landep ojo natoni (Walaupun kamu tajam jangan melukai)
Lamun siro mandi ojo mateni (Walaupun kamu ampuh jangan membunuh)

Landasan itu mendasari masyarakat setempat untuk tidak melukai atau bahkan membunuh alam. Hasilnya, tanah Japan menjadi tanah subur. Beragam jenis tanaman bernilai pangan dan ekonomi tumbuh dan menghidupi masyarakat setempat.
Hidup masyarakat tak kurang-kurang disuplai oleh alam. Begitulah pengakuan dua orang warga yang saya ajak berbincang, Sri Widodo (56) dan Restu (32).
#B. Tanahe ijo wetenge wareg
Di perbukitan Patiayam, Desa Gondoharum, para petani memiliki keyakinan, “Yen tanahe ijo, mesti wetenge wareg (Jika tanahnya hijau (subur), pasti perut kenyang).” Kira-kira begitu yang Masyhuri—ketua kelompok tani setempat—tanamkan ke petani-petani lain, sebagaimana ia tuturkan pada saya ketika berkunjung, Selasa (7/10/2025).
Melalui cara pandang itu, Masyhuri mengajak petani dan umumnya masyarakat di kawasan perbukitan Patiayam giat dalam menaman (melakukan penghijauan). Sebab, tanaman bakal bernilai pangan dan ekonomi. Dan itu membuat kebutuhan perut masyarakat terpenuhi.
Masyhuri memberi buktinya secara langsung. Saat ditemui hari itu, ia dan petani lain di Patiayam tengah dalam masa panen mangga, tanaman yang mereka tanam untuk menghijaukan perbukitan Patiayam.

Lebih dari itu, penghijauan alam juga bisa berdampak untuk “jaga desa”: menjaga dari bencana longsor, menjaga debit mata air yang selama ini mengairi rumah-rumah.
#C. Menjaga alam adalah amanah dan ibadah
“Hutan adalah amanah. Menjaganya adalah ibadah.” Sementara itu adalah semboyan yang dipegang teguh oleh Yayasan PEKA Muria.
“Artinya, kalau kita tidak menjaga alam, kita berarti dosa,” ujar Triyanto saat membersamai tim Ekspedisi Tirtamuria menyibak belantara Muria, Rabu (8/10/2025).
Ini sejalan dengan konsep akidah muttahidah Sunan Muria. Bahwa ibadah tidak berhenti pada aspek mahdlah, tapi juga pada lingkungan. Selazimnya ibadah, jika ditinggal maka bernilai dosa.
Pendekatan ini bisa diterima oleh masyarakat Colo karena masih punya tradisi keberagamaan yang kuat.

#D. Eling lukitaning alam, supadi nir ing sangsaya
Sementara Teguh Wiyono selaku Ketua Yayasan PEKA Muria menyebut, menjaga alam, menjaga mata air, adalah upaya untuk mewariskan kehidupan pada anak-cucu.
“Sumber mata air itu dijaga untuk anak-cucu kelak. Kita sekarang bisa menikmati air. Tapi jika sumber air mati, anak-cucu kita kelak yang terancam,” kata Teguh kala menemani tim Ekspedisi Tirtamuria ke Air Tiga Rasa Rejenu di hari yang sama.
Teguh secara pribadi juga berpegang pada sebuah tembang Kinanthi berbunyi:
Mangka kanthining tumuwuh (Padahal bekal hidup)
Salami mung awas eling (Selamanya waspada dan ingat)
Eling lukitaning alam (Ingat akan pertanda yang ada di alam ini)
Dadi wiryaning dumadi (Menjadi kekuatannya asal-usul)
Supadi nir ing sangsaya (Supaya lepas dari sengsara)
Yeku pangreksaning urip (Begitulah memelihara hidup)
Tembang itu digubah oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adhipati Arya (K.G.P.A.A) Mangkunegara IV pada 3 Maret 1811 di Surakarta.
Jika dikaji, ada beragam tafsir atas tembang tersebut. Namun, dalam pemahaman Teguh, tembang itu menunjukkan bahwa alam bisa menjadi bekal dan kekuatan hidup bagi manusia. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa waspada dan ingat untuk tidak merusaknya, melainkan memeliharanya.
“Karena memeliharanya berarti memelihara hidup kita sendiri. Kalau tak ingin hidup sengsara, maka alam harus dijaga,” papar Teguh.
#E. Manusia akan selalu butuh air
Selepas dari Colo, saya dan tim Ekspedisi Tirtamuria sempat singgah di kediaman Wijanarko—pertani muda—di Rahtawu. Di belakang rumah Narko, panggilan akrabnya, ada sungai dengan air bening dan debit stabil mengalir.
“Kalau kekeringan, belum pernah,” kata Narko menjelaskan kondisi sungai di belakang rumahnya.

Di bawah terik matahari, saya iseng menyelupkan kaki di bawah aliran sungai itu. Terasa segar. Maka, saya putuskan untuk membasuh sebagian badan saya. Berkali-kali saya membenamkan kepala di bawah aliran air yang melintasi bebatuan. Byuh, segar sekali rasanya.
“Upaya penghijauan di sini, menjaga hutan, salah satu tujuannya ya menjaga debit air ini agar terus ada,” jelas Narko.
“Karena bagaimanapun, manusia akan selalu butuh air,” pungkasnya.
“Ketika pohon terakhir ditebang. Ketika sungai terakhir dikosongkan. Ketika ikan terakhir ditangkap. Barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang.” ― Eric Weiner, The Geography of Bliss: One Grump’s Search for the Happiest Places in the World
Tulisan ini merupakan serial Ekspedisi Tirtamuria untuk edisi Oktober 2025
Reporter: Ahmad Effendi dan Muchamad Aly Reza
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA: Mangrove, Garda Terdepan Ketahanan Pangan Pesisir Semarang yang Masih Diabaikan atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan