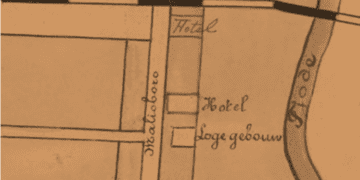Pagi tadi, saya menjemput istri saya di bandara. Ia baru pulang dari Jakarta setelah sebelumnya selama empat hari penuh mengikuti semacam kelas pelatihan yang saya tak tahu apa judulnya dan temanya. Pokoknya pelatihan, gitu aja.
Empat hari ditinggal istri, bagi seorang lelaki yang belum genap tiga bulan menikah adalah hal yang, tentu saja tak ubahnya siksa dunia.
Maka, ketika istri saya mengirim pesan wasap minta dijemput di bandara, saya, dengan segenap kerinduan yang menyala-nyala, tentu saja langsung girang bukan kepalang.
Motor saya siapkan, pakaian terbaik saya pakai, semuanya demi menyambut kedatangan istri yang terkasih.
Sampai bandara, di tempat kami biasa saling bertemu, saya menyambutnya. Ia tampak cantik dan sentosa. ia tampak serupa wanita karier dengan masa depan yang begitu cerah. Dari penampilannya, saya begitu yakin kelak ia bisa menafkahi saya, bukan sebaliknya.
Ia tersenyum, tampak manis, entah ini karena faktor kangen atau memang dia memang manis dari sononya.
Kami berpelukan sebentar. Saya angkat koper yang dia bawa, saya taruh di ruang depan jok. Tas yang saya bawa saya puter ke depan, semata biar ia, kalau mau, leluasa bisa memeluk saya.
Kami berdua melaju membelah jalanan Jogja. Laju motor kami tentu saja tidak impresif dan kencang, sebab memang banyak muatan yang kami bawa.
Laju yang agak lambat ini sedikit banyak menyiksa batin saya. Saya keburu ingin cepat-cepat sampai di rumah agar bisa segera memeluk lama dan mencium pipi istri saya.
Sampai di salah satu ruas jalan, tak jauh dari ring road, arus tampak macet merayap. Batin saya makin tersiksa. Maklum, macet tentu saja membuat saya semakin lama untuk sampai rumah untuk menuntaskan kerinduan saya.
Saya lantas penasaran, apa gerangan sebab kemacetan yang menyebabkan batin saya tersiksa itu. Ingin sekali saya maki apa saja yang menjadi penyebab kemacetan terlaknat di waktu yang “genting” ini.
Setelah sekitar seratus meter, barulah saya tahu apa penyebab kemacetan. Tak lain dan tak bukan adalah pekerjaan galian. Bangsat.
Emosi saya karena kemacetan, ditambah dengan rindu yang terkoyak, ditambah dengan kepayahan membawa barang-barang serasa bikin saya muntab.
Saya masih ingat betul, baru setahun yang lalu jalan itu kena pekerjaan galian. Sekarang sudah digali lagi. Apa mau mereka ini? Kemacetan kali ini semakin membuat rasa benci saya terhadap proyek galian jalan semakin membuncah.
Jalan aspal yang tadinya mulus bak karier politik Jokowi itu pasti selalu jadi bopeng tiap kali kena proyek galian.
Maklum, bekas galian jalan itu nantinya memang bakal ditutup kembali, tapi tentu saja dengan kualitas aspal yang tidak sebaik aspal sebelum digali. Tidak semulus sebelumnya. Semacam hanya formalitas bahwa galian itu ditutup kembali.
Ia bakal menyisakan pinggiran jalan dengan kontur yang tidak semulus bagian aspal yang tidak kena gali. Dan bagi pengendara motor seperti saya, itu adalah satu dari sekian banyak hal yang menyebalkan di jalan raya.
Sungguh, kendati saya begitu membenci banyaknya orang-orang yang menganggur di negeri ini, namun saya juga tak pernah suka dengan papan pengumuman bertuliskan “Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu, ada pekerjaan” yang kerap terpasang hampir di banyak ruas jalan.
“Sabar, Mas,” kata istri saya, “Mungkin memang galian itu diperlukan, biar nggak banjir,” terangnya.
Entah kenapa, pernyataan dari istri saya itu malah membikin saya agak mangkel. Berasa emosi saya tidak diredakan, tapi malah ditambah sebab ia jadi kelihatan membenarkan proyek galian tersebut.
“Ooo, Jadi kamu lebih memilih membela proyek pekerjaan itu ketimbang membela suamimu sendiri?” Kata saya agak sinis.
“Ya bukan begitu juga, keles!” jawabnya sambil merengut. Saya ikut merengut.
Tuh, kan. Proyek pekerjaan galian itu bukan hanya mengganggu perjalanan saya, tapi juga menganggu hubungan komunikasi rumah tangga saya.
Memang bedebah betul itu proyek.