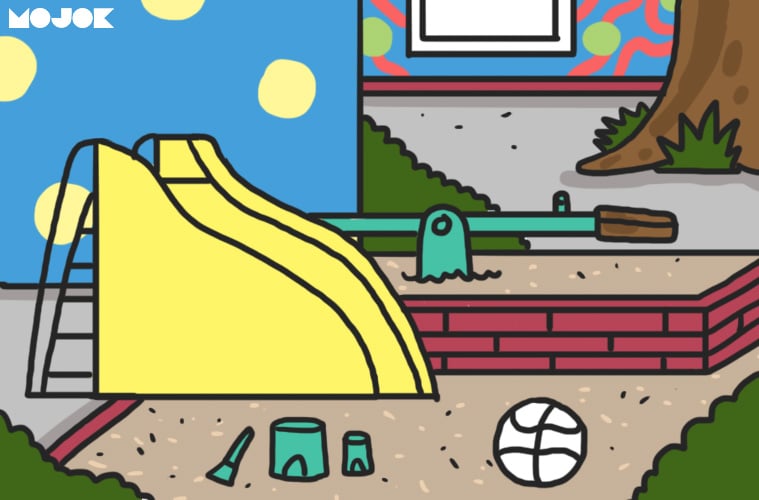Matahari sore terasa menyengat di sebuah lapangan sepak bola berdebu di kabupaten bagian selatan Pulau Jawa, Jumat (2/1/2026). Ribuan pasang mata tertuju ke tengah lapangan, menantikan hiburan rakyat yang paling dinanti: turnamen antarkampung alias tarkam.
Dari kejauhan, suasana tampak riuh dan penuh gairah selayaknya pesta rakyat. Namun, sore itu, saya tidak sekadar datang sebagai penonton. Saya datang dengan membawa keraguan dan pulang dengan sebuah kesadaran yang mengerikan: sepak bola di tingkat paling akar rumput ini ternyata menyimpan kegelapan yang setara dengan skandal pengaturan skor level internasional.
***
Di atas kertas, pertandingan hari itu seharusnya berat sebelah. Sebuah tim tamu yang bertabur bintang, ditantang oleh tim tuan rumah yang bermaterikan pemuda desa setempat. Jangan bayangkan “bintang” ini hanya sekadar pemain terbaik kecamatan sebelah.
Di sana, saya menyaksikan setidaknya ada tiga pemain yang masih aktif merumput di Liga 1 Indonesia–kompetisi kasta tertinggi di negeri ini–serta barisan pemain yang wajahnya kerap wara-wiri di Liga 2 dan Liga 3. Mereka bermain di lapangan yang tak rata, melawan anak-anak lokal yang sehari-hari mungkin bekerja di ladang atau pabrik.
Pertandingan tarkam digelar dengan durasi 2×35 menit. Dan, benar saja, baru 15 menit peluit dibunyikan, papan skor manual di pinggir lapangan sudah berubah angka menjadi 3-0 untuk keunggulan tim bertabur bintang. Kualitas memang tidak bisa bohong.
Penonton pun bersorak. Sebagian besar memprediksi ini akan menjadi pesta gol. Dalam benak saya, dengan sisa waktu yang panjang, skor akhir bisa menyentuh angka 7-0 atau bahkan lebih.
Namun, keanehan mulai terjadi. Memasuki pertengahan babak pertama hingga babak kedua berjalan, mesin gol tim bintang itu mendadak macet. Bukan karena tim desa tiba-tiba jago bertahan, melainkan karena tim bertabur bintang terlihat sengaja “menginjak rem”.
Bola yang sudah dialirkan rapi hingga depan gawang, tiba-tiba dioper kembali ke belakang. Peluang emas yang 99 persen seharusnya gol, dieksekusi dengan asal-asalan, seolah “disengaja” agar melenceng. Bahkan, beberapa pemain profesional itu terlihat bermain kasar tanpa alasan jelas, seakan-akan memburu kartu kuning dari wasit.
Atmosfer di tribun penonton berubah. Dari sorak sorai kekaguman menjadi umpatan kekesalan. Penonton di sebelah saya mulai gemas, marah, bahkan tak henti-hentinya misuh-misuh.
“Main kok ngono! [mainnya kok begitu?]’“ teriaknya. Mereka merasa dicurangi, hiburan mereka dirusak. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 3-0 tetap bertahan. Bagi penonton awam, mungkin ini hanya nasib sial atau kelelahan pemain. Tapi bagi saya yang curiga, ini adalah “pertanda”.
Bagi saya yang kerap menyaksikan pertandingan sepak bola level Eropa, sekilas memang tak ada yang terlalu aneh. Filosofi sepak bola selalu mengajarkan: bola itu bundar, apapun bisa terjadi di lapangan. Tim hebat bisa saja tumpul mendadak. Itu yang selalu saya pelajari. Namun, semua asumsi lugu itu runtuh ketika saya bertemu dengan Habib (bukan nama sebenarnya) seusai laga.
Habib dikenal luas di lingkungan tersebut sebagai “agen”. Dialah sosok yang mendatangkan pemain-pemain nasional untuk bermain di lapangan becek desa ini. Namun, setelah mengobrol lebih dalam, terkuak bahwa ia sejatinya adalah bandar lokal yang mengatur skema perjudian hingga menentukan voor-vooran (odds/handicap).
Dengan santai ia mengakui satu hal tentang pertandingan aneh tadi: laga sudah “dipesan”. Sebuah eufemisme untuk “sudah diatur”. Pendeknya, kesimpulan saya hari itu adalah bola tak sepenuhnya lagi bulat di sini.
Pengakuan I: “Bos” tarkam ingin main under, jangan sampai ada 4 gol
Pengakuan Habib membuka mata saya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik skor 3-0 yang “macet” itu. Menurut sang bandar lokal, dalam laga tersebut, tim bertabur bintang memang diunggulkan mutlak di pasar taruhan. Pasaran atau odds utama yang dibuka adalah tim tersebut diunggulkan menang dengan margin 4 gol.
“Nggak disangka, baru sebentar laga berjalan sudah 3-0. Satu gol lagi target tercapai dong,” ujar Habib, menjelaskan dinamika di lapangan.
Situasi ini berbahaya bagi sang bandar. Jika satu gol lagi tercipta, maka skor menjadi 4-0, dan para petaruh yang memegang tim unggulan akan menang atau setidaknya draw (balik modal) tergantung detail pasaran saat itu. Jika lebih dari 4 gol, bandar akan rugi besar.
Di sinilah intervensi “tangan tuhan” versi mafia tarkam bekerja. Sang “Bos”–pemilik modal di balik tim bintang tersebut–menginstruksikan agar laga berjalan under (di bawah target pasar).
“Bos minta laga berjalan under saja karena banyak penjudi atau bos lain main sesuai pasaran (4 gol). Makanya, di sisa laga, laga dipaksakan jangan ada gol lagi,” ungkap Habib.
Dengan menahan skor tetap 3-0, Bos menang besar karena petaruh yang memasang voor 4 gol kalah telak. Cuan besar pun masuk kantong, sementara penonton hanya bisa misuh-misuh melihat tontonan yang tidak logis.
Pengakuan II: Uang yang berputar ratusan juta per laga, tak masuk akal
Logika ekonomi tarkam memang membingungkan jika dilihat dari kacamata olahraga profesional. Hadiah turnamen tarkam biasanya tidak seberapa. Paling mentok, juara satu mendapatkan seekor kambing. Atau, jika dikonversi ke bentuk uang tunai, hadiah utama turnamen tarkam paling besar berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta saja.
Sementara itu, biaya operasional sebuah tim “sultan” sangatlah jomplang. Habib menuturkan, ada tim yang rela menyewa pemain nasional atau nama top yang tarif per laganya (sekali main) bisa dihargai Rp20 juta hingga Rp25 juta.
Mari berhitung sejenak: jika sebuah tim menyewa lima pemain top saja, mereka sudah harus mengeluarkan uang Rp100 juta untuk satu pertandingan. Jumlah ini lima kali lipat lebih besar dari total hadiah juara pertama.
“Artinya, kalau ada 5 pemain top saja, sudah ada uang 100 juta yang akan dikeluarkan klub tarkam. Tidak sebanding hadiah,” ujar saya saat itu. Namun, Habib tertawa melihat kebingungan saya. Ia kemudian membeberkan rahasia dapur perjudian ini.
Pertama, Bos yang memegang tim tidak mengincar hadiah panitia. Mereka mengincar uang taruhan. “Sekali memenangkan laga, taruhannya bisa mencapai ratusan juta. Uang miliaran juga bisa didapat kalau bisa juara,” kata Habib.
Maka, mendatangkan nama-nama top seperti pemain Liga 1 bukan semata-mata untuk gengsi, melainkan “investasi modal” untuk memenangkan taruhan.
Kedua, ini yang lebih mengerikan. Semakin kuat tim kamu, semakin leluasa kamu mengatur pasar taruhan. Jika tim kamu diisi pemain amatir, ya cuma bisa pasrah pada nasib. Namun, jika tim kamu diisi pemain profesional, kamu bisa memegang “kendali penuh”.
“Kamu bisa atur sendiri kapan mau under, kapan mau over, mau menang berapa juga bisa, karena sumber daya manusianya tersedia. Beda kalau timmu lemah,” tambahnya.
Inilah alasan mengapa laga sore tadi bisa berhenti mencetak gol di menit ke-15. Para pemain profesional itu adalah “karyawan” yang patuh pada instruksi bos, bukan atlet yang mengejar kemenangan semata.
Pengakuan III: Banyak pejabat terlibat di level tarkam
Pertanyaan selanjutnya yang menghantui saya adalah: Siapa orang-orang yang memiliki uang dingin sebanyak itu untuk diputar di lapangan desa? Saya menyaksikan sendiri warga lokal ikut bertaruh di pinggir lapangan, tapi nominalnya “receh”, hanya ratusan ribu rupiah. Tidak mungkin perputaran uang mereka bisa menutup biaya sewa pemain hingga Rp100 juta.
Habib kembali membuka tabir gelap ini. Menurut pengakuannya, uang besar itu datang dari orang-orang terpandang.
“Banyak pejabat ikut main (terlibat). Yang dari pejabat pemerintahan, tingkat kabupaten, kecamatan, desa. Ormas juga penegak hukum,” ungkapnya.
Tentu saja, mereka tidak akan terlihat mencolok berdiri di pinggir lapangan sambil memegang uang tunai. Mereka bermain cantik.
“Mereka nggak bakal langsung datang ke lapangan, biasanya diwakilkan. Tapi ya duit tetap berputar,” jelas Habib. Bagi saya, sistemnya sangat rapi dan terstruktur.
Sebagai ilustrasi, dalam sebuah turnamen tarkam dengan sistem gugur yang diikuti 16 tim, peta kekuatan sebenarnya sudah terbaca sejak awal. Kompetisi ini sudah ada pasar taruhannya. Namun, tetap ada “bos besar” yang ingin memastikan kemenangan.
“Makanya, dia rela ‘invest’ di satu tim dengan mendatangkan banyak nama top lewat agen pemain kayak saya,” kata Habib. Tujuannya ada dua: memenangkan kompetisi (dan taruhan besar di akhir) serta memiliki kemampuan untuk mengatur skor (match-fixing) di setiap pertandingan yang dilalui.
Investasi ratusan juta untuk mendatangkan pemain bintang adalah “biaya operasional” untuk mengeruk keuntungan miliaran dari pasar taruhan yang tidak terlihat oleh mata telanjang penonton biasa.
Kekuatan IV: kuat-kuatan backingan
Mendengar betapa masif dan terbukanya praktik ini, pertanyaan krusial pun terlontar dari mulut saya: Mengapa tak pernah diciduk polisi? Bukankah perjudian adalah tindak pidana?
Habib menjawab dengan sebuah analogi sederhana, tapi menohok: “Mana ada orang yang mematikan sumber rezeki mereka sendiri”.
Saya terdiam, tak mau menyimpulkan secara gegabah apa makna implisit dari kalimat itu. Namun, faktanya berbicara sendiri. Meski portal berita daring kerap memberitakan penangkapan bandar judi bola–mulai dari kelas kakap seperti Vigit Waluyo (VW) hingga nama-nama lokal–praktik di level tarkam seolah tak tersentuh. Fenomena penangkapan itu hanyalah puncak gunung es, sementara di bawah permukaan, di desa-desa, judi bola masih menjamur dengan subur.
Sebagai penutup perbincangan kami, sang bandar lokal mengungkapkan paradoks mengapa tarkam justru menjadi lahan yang lebih basah dan disukai para mafia bola dibandingkan liga resmi. Ada dua alasan utama.
Pertama, “Exposure-nya minim, jarang disorot, nggak seperti liga profesional yang selalu disorot media,” ujarnya.
Di Liga 1 atau Timnas, kontroversi sedikit saja akan langsung viral, dibedah oleh pengamat, dan dicurigai oleh Satgas Anti-Mafia Bola. Di tarkam? Tidak ada kamera televisi, tidak ada VAR, dan tidak ada wartawan investigasi yang rutin meliput. Semuanya terjadi dalam keremangan.
Kedua, “Laga-laganya mudah diatur,” tambah Habib. Tanpa pengawasan ketat, dengan wasit yang mungkin juga bagian dari “sistem”, dan pemain yang dibayar per pertandingan, skenario drama di lapangan bisa ditulis semudah membalikkan telapak tangan.
Sore itu, saya meninggalkan lapangan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya kagum dengan bakat-bakat sepak bola yang masih mau berkeringat di tanah desa. Namun di sisi lain, saya sadar bahwa sorak-sorai penonton hanyalah latar suara bagi perputaran uang haram yang dikendalikan oleh segelintir elite.
Sepak bola tarkam, yang seharusnya menjadi hiburan murni rakyat, ternyata telah menjadi mesin uang raksasa yang mengerikan, di mana bola tidak lagi bundar, melainkan lonjong mengikuti keinginan sang bandar dan bos besar.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Cerita dari Wasit Sepak Bola: Tarkam, Suap, dan Lisensi atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan