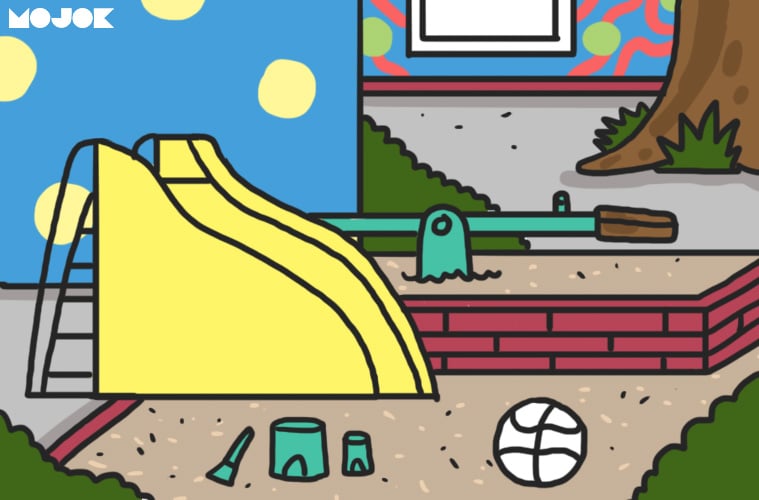Budaya “jatah ciu” kepada pemuda desa, biasanya diberikan ketika seorang warga menggelar hajatan, dianggap sebagai manifestasi dari srawung. Namun, ia tak selalu cocok bagi semua orang. Penuh pro dan kontra.
***
Di banyak desa, ada sebuah tradisi unik (atau nyeleneh): ketika seorang warga menggelar hajatan, baik khitan atau nikahan, mereka wajib memberi jatah miras kepada para pemuda. Tradisi ini tak diketahui kapan pertama kali muncul.
Yang jelas, memberi miras dianggap sebagai ungkapan “terima kasih” kepada pemuda desa yang secara sukarela telah membantu acara hajatan dalam bentuk sinoman. Pendeknya, ia disebut sebagai manifestasi srawung seorang warga.
Saya sendiri menyaksikan tradisi ini ketika pernikahan adik perempuan saya akhir 2024 lalu. Saat itu, pihak keluarga telah “mengalokasikan” dana hingga Rp2 juta untuk membeli beberapa botol ciu, miras versi murah di desa.
Nantinya, ciu-ciu bakal dinikmati oleh para sinoman, yang umumnya terdiri dari para pemuda desa anggota karang taruna. Meski dalam hati terasa agak janggal, saya tak bisa menolak keputusan ini karena sudah dianggap sebagai tradisi.
“Kalau nggak dijalani, takutnya dipandang buruk sama pemuda desa, karena umumnya memang begini,” kira-kira begitu jawaban yang saya dapatkan ketika coba menanyakan mengapa kami harus keukeuh menjalankan tradisi ini.
Habis Rp3 juta buat jatah ciu, pemuda desa merasa dipalak
Hal serupa dialami Eka (28) pada 2023 lalu. Saat itu, ia akan menjalani pernikahan. Sebagaimana umumnya di desa, saat mengadakan hajatan pernikahan, warga lain bakal bondong-bondong membantu. Dalam istilah Jawa, tradisi ini disebut rewang.
Tugas mereka biasanya dibagi rata. Kalangan ibu-bu biasanya memasak, bapak-bapak mengurus distribusi minuman, snack, dan bahan makanan, sementara para kejatah bagian nyinom, menyajikan makanan bagi para tamu.
“Senangnya hidup di desa begini, semua membantu memberikan tenaganya,” kata perempuan yang pernah berkuliah di Jogja itu, Senin (5/1/2026).
Namun, beberapa hari sebelum hari H pernikahan, kakak laki-lakinya memperingatkannya untuk mengalokasikan sedikit anggaran untuk “jatah ciu”. Mendengar itu, ia pun kaget. Sebab, jatah ciu dianggap sebagai hal yang tak masuk akal.
“Ya aku kalau ada tetangga hajatan ikut rewang, nyinom. Tapi nggak tahu kalau ada tradisi begini-begini sebelumnya,” ungkapnya.
Lebih kaget lagi ketika ia tahu nominal yang harus dikeluarkan. Setelah berhitung bersama keluarganya, dengan mempertimbangkan harga “miras yang pantas” dan jumlah sinoman yang mencapai 30-an orang, angkanya bisa mencapai Rp3 juta.
Baginya, ini angka yang besar. Daripada untuk membeli minuman keras, kata Eka, akan lebih bermanfaat kalau biayanya dialokasikan untuk kebutuhan lain.
“Aku malah lebih ikhlas kalau uangnya buat membayar ibu-ibu yang bantu masak,” ujarnya. Namun, uang itu harus tetap ia keluarkan karena dianggap sudah menjadi tradisi.
Apalagi, Eka berasal dari keluarga terpandang. Kakeknya dulu mantan lurah, sementara kedua orang tuanya PNS. Ada kekhawatiran, jika tradisi ini tidak dijalankan, takut mencoreng nama baik keluarga.
“Ya rasanya dipalak sih.”
Bikin mahasiswa KKN alami culture shock
Cerita lain juga dituturkan Reza (24), mahasiswa salah satu PTN di Jogja yang pernah menjalani KKN di sebuah desa di selatan Jawa Tengah. Kala itu, di desa tempatnya KKN terdapat warga yang menggelar acara pernikahan.
Sebagai mahasiswa dari Jakarta, yang terbiasa hidup dalam gaya individualis, ia terkejut dengan perilaku warganya yang penuh gotong royong. Sama seperti yang diungkapkan Eka, warga desa membagi peran masing-masing, membantu apa yang bisa dibantu, tanpa pamrih.
“Ngelihat itu, keren banget sih. Di kota, mana ada gotong royong begini,” ujar Reza.
Karena ingin merasakan budaya srawung ini, Reza bersama satu mahasiswa lain memutuskan untuk ikut nyinom. Ia membaurkan diri dengan pemuda desa lain. Dalam sinoman tersebut, Reza belajar cara menyajikan makanan dan minuman bagi para tamu yang datang.
Awalnya, tak ada yang aneh. Sebelum akhirnya, pada malam hari, ketika hendak kembali ke basecamp KKN, ia dicegat oleh ketua karang taruna. Pria yang mencegatnya itu mengajak “minum” Reza dan temannya. Kata dia, sebagai bentuk ungkapan terima kasih karena sudah seharian membantu nyinom.
Sebagai seorang peminum, Reza pun mengiyakan. Masalahnya, teman yang ikut dengannya itu seorang mahasiswa yang alim. Merokok saja tidak, apalagi minum. Situasi itu bikin dia awkward. Ingin menolak tak enak ke warga, kalau mengiyakan pun tak enak dengan temannya.
Reza pun punya jalan tengah. Berdalih masih ada banyak tugas kuliah yang harus dikerjakan, ia pun dengan halus menolak ajakan itu. Ia bilang, “kapan-kapan saja kalau lagi free”.
Meski akhirnya tidak jadi minum bersama, Reza mempelajari satu hal bahwa di desa-desa tradisi seperti ini telah mengakar. Ia tak mau bilang ini tradisi baik atau buruk, tak ingin terjebak hitam-putih. Yang jelas, bagi Reza, ini tradisi unik karena baru pertama kali ia jumpai.
“Ya jujur aja shock. Di balik warga desa yang selama ini kulihat alim-alim, ternyata demen party juga,” katanya, terkekeh.
Kalau bisa diubah, mengapa tidak?
Tradisi jatah ciu sudah mendarah daging bagi masyarakat desa. Boleh dibilang, ia telah bertransformasi menjadi sebuah budaya. Kalau membaca literatur sejarah lokal pun, tradisi ini sudah menjadi bagian dari masyarakat rural. Terutama dengan kearifan lokal mirasnya, seperti arak di Bali atau tuak di budaya masyarakat Batak.
Namun, bagi Eka yang pernah menjalankan tradisi ini, ia menilai budaya ini harus ada penyesuaian. Ia tak mau menyebut ini sebagai budaya yang baik atau buruk. Hanya saja, ia tak bisa selalu “cocok” dengan setiap orang.
“Terutama ya, kalau ngomongin uang. Bagi aku yang alhamdulillah mampu, mungkin bukan masalah. Tapi buat orang lain yang pas-pasan, pasti memberatkan banget,” kata Eka.
“Kalau bisa dialokasiin buat biaya lain, kenapa harus buat miras?” imbuhnya.
Penyesuaian yang ia maksud, adalah kembali ke masing-masing warga desa. Yang mampu, dan dengan sadar ingin memberi jatah ciu, ya silakan. Namun, buat yang tak berkenan, kata Eka, juga dipersilakan tanpa perlu ada kekhawatiran bakal dianggap beda.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Meninggal di Desa Itu Sebenarnya Mahal, Menjadi Murah karena Guyub Warganya atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan