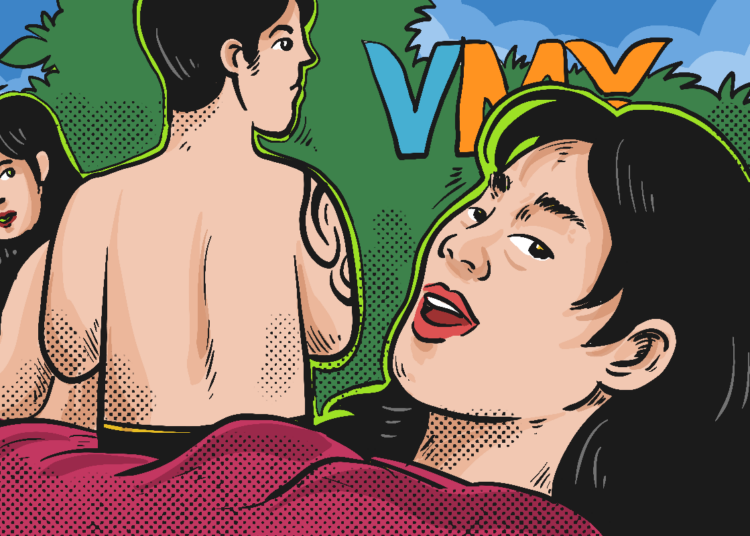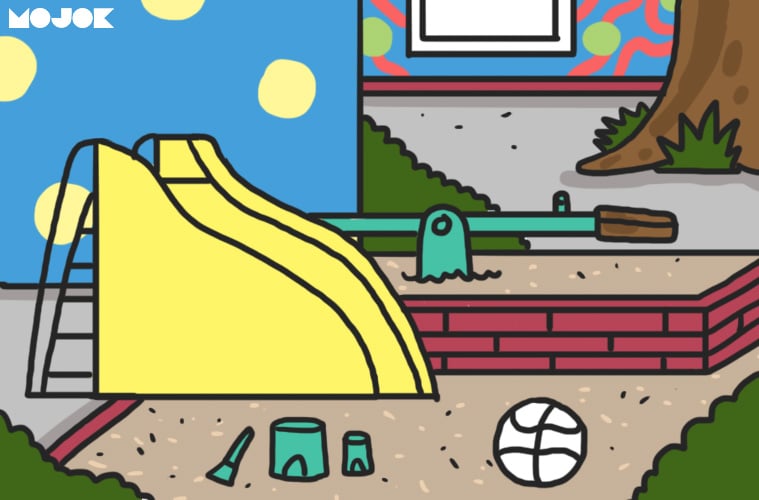- Sebelum Vivamax meledak, film erotis Filipina memiliki sejarah yang panjang. Berakar dari era bomba 1960-an, masa darurat militer, hingga masuk ke rumah tangga melalui VCD dan platform streaming.
- Uhaw (1970) diperkirakan menjadi film pertama yang menandai era “bomba” dalam skena film erotis Filipina. Film ini meledak, dan formulanya mulai ditiru.
- Beberapa pakar seperti Lanot, Lumbera, dan Tolentino, menilai film erotis di Filipina seperti katarsis atau obat penenang yang membuat masyarakat lupa atas krisis ekonomi dan represi politik. Terutama di masa darurat militer Ferdinand Marcos.
***
Filipina adalah negara yang unik. Di negeri yang menaruh patung Maria di hampir setiap rumah, dosa dan ibadah seperti dinegosiasikan. Hampir 80 persen penduduknya memeluk Katolik. Setiap Januari, jutaan peziarah berdesakan dalam prosesi Black Nazarene di Manila.
Namun, pada malam yang sama, di gang-gang gelap kota, atau di layar ponsel warganya, tubuh lain sedang “disembah”. Unik, bukan? Di negara yang secara keras menolak aborsi dan melarang perceraian, industri film erotis tumbuh subur. Bahkan, hari ini, menjadi yang paling produktif di Asia Tenggara.
Jujur saja, kapan terakhir kali kalian mengakses Vivamax? Atau, seberapa banyak orang yang tidak mengenal Angeli Khang dan Rob Guinto?
Namun, yang perlu kalian tahu, Vivamax atau Angeli Khang cuma nama baru yang lagi naik daun. Sebab film erotis di Filipina tak pernah benar-benar mati. Ia cuma berganti bentuk: dari layar bioskop berasap rokok di tahun 1970-an, ke cakram VCD di 1990-an, lalu ke platform streaming Vivamax hari ini.
Sejarahnya panjang, dan setiap babnya menceritakan satu hal yang sama: bagaimana bangsa yang saleh ini tak pernah benar-benar berdamai dengan tubuhnya sendiri.
Bomba, titik awal yang memunculkan sinema erotis di Filipina
Industri film erotik Filipina tak terlepas dari kemunculan istilah bomba di penghujung 1960-an. Istilah bomba mula-mula bukan berasal dari dunia film, melainkan dari bahasa Tagalog yang menyerap kata Spanyol “bomba”–artinya berarti bom, ledakan, atau sesuatu yang mengejutkan, mengguncang.
Dalam wacana publik Filipina akhir 1960-an, media mulai menggunakan kata itu untuk menyebut berita skandal atau pengungkapan “sesuatu yang meledak”. Kalau di Indonesia, kira-kira “bombastis”.
Ketika film-film dengan adegan telanjang pertama kali muncul di layar, para jurnalis hiburan menyebutnya bomba films, karena “meledakkan moral publik” dan “mengguncang sensor negara.”
Saat itu, perfilman Filipina memang sedang loyo. Genre melodrama dan aksi, yang sempat menguasai pasar, mulai kehabisan tenaga. Sementara penonton muda di Manila mulai mencari tontonan yang lebih jujur terhadap hasrat dan realitas tubuh.
Maka pada tahun 1970, muncullah film Uhaw (dalam bahasa Indonesia artinya “Haus”) karya Ruben Arthur. Film ini kemudian dianggap sebagai film bomba pertama yang sukses secara komersial dan kultural.
Uhaw mengisahkan seorang istri muda di pedesaan yang hidup kesepian karena suaminya sibuk bekerja jauh dari rumah. Dalam kesunyian, ia perlahan tergoda oleh lelaki lain.
Ceritanya memang sederhana, hampir template. Namun, di situlah letak kekuatannya. Film ini menampilkan ketelanjangan frontal untuk pertama kalinya di layar Filipina; bukan sekadar sebagai sensasi, melainkan sebagai metafora atas dahaga emosional dan sosial.
Dalam hitungan bulan, Uhaw meladak. Bioskop di Cubao, Avenida Rizal, hingga Davao penuh sesak. Produser-produser lain segera meniru rumusnya, sehingga melahirkan gelombang film bomba yang diproduksi cepat, murah, dan laris manis.
Cerita-cerita pun template: perempuan miskin, laki-laki kaya, dan godaan kota. Namun, di balik repetisi itu, muncul juga semacam alegori sosial. Seks menjadi bentuk perlawanan dan keputusasaan dalam masyarakat yang terjepit oleh kemiskinan dan patriarki. Tokoh-tokohnya jarang datang dari kelas atas, bisanya perempuan pekerja, mahasiswa miskin, atau janda muda, karena lebih familiar bagi penonton umum–sekaligus memancing fantasi.
Kritikus film seperti Nick Deocampo bahkan menulis bahwa bomba adalah “produk dari kegelisahan urban”. Ia lahir di tengah kota yang berubah cepat, di mana kemiskinan dan modernitas berdampingan secara brutal. Tubuh perempuan, kata Deocampo, menjadi mata uang baru dari ekonomi-moral yang sedang goyah. Bagi banyak penonton kelas bawah, menonton film semacam ini bukan sekadar mencari birahi, tapi mencari refleksi.
Film esek-esek cuma “pembebasan semu”
Dalam esainya yang berjudul “Liberation and Exploitation: On Sex-Flicks and the Filipino, Before, During, and After Martial Law” (1977), jurnalis Marra P. L. Lanot menulis dengan nada getir. Katanya, bomba films bukanlah bentuk kebebasan, melainkan “pembebasan semu” (false liberation).
Tubuh perempuan di layar tampak merdeka dari sensor, tapi sesungguhnya hanya berpindah dari satu bentuk penguasaan ke bentuk lain. Ia bukan lagi dikekang oleh moral Katolik dan kolonialisme, melainkan oleh logika pasar dan tatapan laki-laki.
Dalam kalimat Lanot yang paling jelas: “tubuh perempuan tidak sedang dibebaskan, melainkan dijual atas nama kebebasan.”
Lanot membaca fenomena bomba dalam konteks sosial yang lebih luas. Di masa ketika sensor politik begitu ketat dan ekonomi makin timpang, seks menjadi satu-satunya wilayah “kebebasan” yang diizinkan negara. Namun, kebebasan ini justru bekerja sebagai alat pengalih perhatian; rakyat dibuat sibuk menikmati tubuh, bukan mempersoalkan kekuasaan.
Dalam dunia yang dibungkam oleh darurat militer, hasrat menjadi katarsis publik: film erotik berfungsi seperti injeksi kecil kebebasan yang aman, karena tidak mengancam rezim. Bagi Lanot, inilah wajah baru dari kolonialisme kultural: tubuh perempuan dijadikan “koloni internal,” tempat negara dan pasar bersama-sama memetik keuntungan.
Ia juga mencatat ironi sosial yang lebih dalam. Para aktris bomba, kebanyakan perempuan muda dari keluarga miskin, datang ke Manila dengan mimpi menjadi bintang. Namun, yang mereka temui adalah sistem yang memanfaatkan tubuh mereka, lalu membuangnya begitu sensasi berakhir.
“Mereka dipuja di layar, tetapi dihakimi di gereja,” tulis Lanot.
Dalam paradoks itulah, bomba films menjadi cermin masyarakat Filipina: bangsa yang religius, tapi tak pernah berdamai dengan tubuhnya sendiri.
Obat lupa atas krisis ekonomi dan represi politik
Ketika Ferdinand Marcos menetapkan darurat militer pada 1972, banyak yang mengira film bomba akan dibungkam. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Rezim menutup mulut para sutradara politik, tapi tetap membiarkan film erotis beredar luas. Seks dijadikan alat distraksi nasional.
Film-film seperti Hubad na Bayani (1977) karya Celso Ad. Castillo atau Bomba Star (1978) menampilkan tubuh-tubuh telanjang yang memikat penonton, tapi pesan sosialnya samar. Di ruang bioskop yang gelap, rakyat bisa melupakan krisis ekonomi, korupsi, dan represi. Tubuh perempuan di layar menjadi semacam katarsis kolektif. Ia adalah obat lupa dari krisis ekonomi dan represi politik.
Bienvenido Lumbera, kritikus terkemuka dalam esai berjudul “Revaluation“ (1984), menyebut strategi Marcos ini sebagai “pengalihan budaya”. Rakyat diarahkan untuk menatap tubuh, bukan negara. Tesis ini, punya nada yang sama dengan gagasan Lanot sebelumnya.
Sementara itu, Rolando B. Tolentino dalam Sine Patriyotiko (2001) menafsirkan tubuh perempuan dalam film era Marcos sebagai metafora bangsa. Ia indah, tapi dikontrol; sensual, tapi tunduk pada sensor. Seks menjadi wajah lain dari hegemoni, di mana negara tak hanya mengatur politik, tapi juga hasrat.
Proyek nasional ke proyek komersial
Empat dekade kemudian, dalam buku The End of National Cinema (2016), Patrick F. Campos melihat fenomena bomba dari sisi lain. Ia menempatkannya dalam konteks yang lebih historis: sebagai titik balik sinema Filipina dari proyek nasionalis menjadi proyek komersial.
Di era 1950–60-an, film masih dianggap bagian dari “proyek bangsa”–alat untuk membangun identitas nasional pascakolonial, sebagaimana dilakukan oleh sutradara seperti Lamberto Avellana atau Gerardo de León. Tapi bomba mengubah segalanya. Sejak saat itu, film tak lagi bicara soal “bangsa,” melainkan soal “pasar.”
Campos menyebut bomba films sebagai “simptom dari transisi ekonomi dan ideologi”. Dalam pandangannya, tubuh perempuan menjadi “layar bangsa” tempat Filipina menonton dirinya sendiri. Dengan menonton tubuh-tubuh itu, imbuhnya, masyarakat Filipina seperti sedang menonton hasrat dan dosa mereka sendiri, sekaligus menertawakannya.
“Bomba adalah hiburan sekaligus pengakuan dosa massal, dan bioskop menjadi ruang pengampunan yang gelap dan anonim,” tulisnya.
Tubuh perempuan menjadi pusat narasi, bukan karena kuasa naratifnya, tapi karena daya jualnya.
“Dalam bomba, bangsa berhenti bermimpi tentang kemerdekaan, dan mulai bermimpi tentang kepemilikan,” tegasnya.
Dalam konteks itu, tulisan Lanot, Lumbera, hingga Campos membentuk satu garis pemikiran yang saling melengkapi. Mereka sama-sama melihat bahwa di balik setiap adegan sensual, tersimpan narasi yang jauh lebih serius: tentang negara yang kehilangan arah, masyarakat yang mencari pelarian, dan industri yang menjadikan hasrat sebagai strategi bertahan hidup.
Dari bioskop ke rumah tangga
Ketika Marcos tumbang, sensor negara longgar, tapi industri menghadapi krisis baru: banjir film impor dan turunnya jumlah penonton. Maka bomba berevolusi menjadi bold film–lebih modern, lebih sinematik, tapi esensinya sama.
Film seperti Sibak: Midnight Dancers (1994) atau Scorpio Nights 2 (1999) mengangkat realisme urban seperti pekerja malam, buruh pabrik, mahasiswa miskin. Seksualitas tampil dalam warna kemiskinan dan kapitalisme kota. Istilah “bold” menandai pergeseran dari skandal menjadi gaya. Tubuh tak lagi tabu, tapi komoditas normal.
Teknologi VCD dan DVD memperluas pasar. Film erotis Filipina tak lagi harus diputar di bioskop murahan, tapi ia bisa ditonton diam-diam di ruang tamu. Ironisnya, inilah masa ketika bomba benar-benar “masuk rumah tangga”, dihidupkan oleh para ayah keluarga Katolik yang menontonnya saat anak dan istri tertidur.
Pasar bawah tanah film VCD di Quiapo dan Tondo menciptakan ekonomi alternatif. Produksi murah, distribusi cepat, keuntungan langsung. Bagi banyak pekerja miskin kota, industri bold menjadi bentuk kerja informal.
Sementara pandemi Covid-19 membuka babak baru. Saat bioskop tutup, Viva Entertainment meluncurkan platform streaming lokal bernama Vivamax. Formatnya sederhana: cerita template, durasi wajar (90 menit), dan selalu menyelipkan adegan sensual yang frontal.
Dalam waktu singkat, Vivamax menjadi fenomena sosial. Filmnya diunduh jutaan kali, terutama oleh penonton laki-laki dari provinsi dan buruh migran di luar negeri.
Film-film seperti Kinsenas, Katapusan, Palitan, atau Scorpio Nights 3 menghidupkan kembali estetika klasik bomba dengan kamera digital dan narasi urban.
Mengapa tak pernah mati, padahal di tengah masyarakat religius-konservatif?
Bagaimana mungkin industri semacam ini bertahan di tengah masyarakat Katolik yang konservatif? Jawabannya ada pada paradoks Filipina itu sendiri. Gereja memang mengutuk dosa, tapi tidak bisa menghapus kemiskinan yang melahirkannya. Negara menolak pornografi, tapi menikmati pajak dari industri hiburan sensual. Masyarakat menonton dengan rasa bersalah, tapi terus menontonnya juga.
Sosiolog Jayeel Cornelio dalam Being Catholic in the Contemporary Philippines (2016) menulis bahwa generasi muda Katolik Filipina menegosiasikan iman dan seksualitas secara pragmatis. Seksualitas bukan lagi tabu mutlak, tapi bagian dari hidup urban yang mereka terima dengan ambivalen.
Bahkan, dalam kerangka yang lebih luas, Neferti Tadiar dalam Things Fall Away (2009) melihat tubuh di dunia pascakolonial sebagai arena globalisasi. Yakni tempat di mana ekonomi, agama, dan hasrat berkelindan tanpa akhir.
Maka, selama kemiskinan, patriarki, dan hipokrisi moral tetap hidup, industri ini akan terus menemukan napas baru. Setiap kali negara menindas, ekonomi runtuh, atau publik tertekan, film erotis muncul kembali sebagai cermin buram: bukan sekadar pornografi, tapi catatan sosial tentang bagaimana bangsa ini bernegosiasi dengan tubuhnya sendiri.
Kini, film erotis Filipina beredar di layar enam inci, bukan di bioskop. Vivamax hanyalah nama baru bagi sesuatu yang sudah lama hidup di bawah kulit masyarakat.
Penulis: Ahmad Effendi
Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Main Serong di Sinema Indonesia: Mengapa Kamu Menyukai Film Bertema Perselingkuhan? atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan