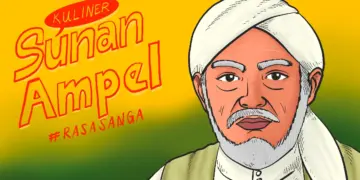Film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah (2025) mengajarkan bahwa KDRT tidak selalu datang dalam bentuk kekerasan fisik, tamparan di wajah, atau makian. Ia juga bisa hadir dari ketidakpedulian.
***
Jujur saja, saya memiliki aturan tak tertulis dalam memilih tontonan: hindari drama keluarga, terutama yang mengeksploitasi hubungan ibu dan anak.
Bagi saya, genre ini sering kali terasa manipulatif. Ia memaksa air mata menetes dengan cara yang cengeng.
Referensi terakhir saya untuk tema serupa adalah film Korea Selatan, Mother (2009). Itu pun saya tonton karena film ini sejatinya adalah thriller balas dendam yang intens, bukan sekadar etalase kesedihan.
Prinsip itulah yang membuat saya menolak ajakan seorang anak magang di kantor pada September 2025 lalu. Ia, dengan antusiasme khas sinefil, mengajak saya menonton Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah yang sedang tayang di bioskop.
Saya menolak, meski judul dan premisnya sangat menarik. Film ini mengisahkan Alin (Amanda Rawles), mahasiswi kedokteran yang kembali ke rumah saat beasiswanya terancam. Di rumah, ia menemukan kenyataan pahit perjuangan ibunya, Wulan (Sha Ine Febriyanti), yang menjadi tulang punggung keluarga akibat ayahnya, Tio (Bucek Depp), tidak bertanggung jawab.
Alin menemukan buku harian ibunya yang mengungkap kisah cinta pertama, mimpi yang dikorbankan, hingga pilihan hidup Wulan, yang pada akhirnya memunculkan pertanyaan reflektif dalam benaknya: “Andai ibu tidak menikah dengan ayah, apakah hidupnya akan lebih bahagia?”.
Premisnya sederhana, cukup umum, tapi menarik.
Dan, keengganan saya itu akhirnya runtuh pada awal tahun baru 2026. Ketika film ini mendarat di katalog Netflix, saya memutuskan untuk menekan tombol play. Saya menontonnya dalam keadaan “buta”, tanpa membaca sinopsis mendalam atau menonton ulasan apa pun di media sosial.
Saya pikir saya akan aman. Ternyata, saya salah besar.
Spoiler alert! Film ini tidak sekadar membuat saya tersentuh. Ia bahkan menghajar saya telak dalam tiga babak. Tangis pertama saya pecah saat melihat Ibu mengoleskan salep gatal di kakinya sambil terisak. Bagi saya, ini adalah sebuah momen sunyi yang menyuarakan kepedihan lebih lantang dari teriakan mana pun.
Pertahanan saya makin hancur di babak kedua, saat terjadi dialog antara Ibu dan anak keduanya, Alin. Kalimat itu meluncur tajam: “Aku nggak apa-apa nggak dilahirin asalkan Ibu bisa hidup lebih bahagia.” Itu adalah jenis kalimat yang membuat Anda harus menekan tombol pause untuk bernapas sejenak.
Dan, puncaknya, di babak ketiga, saat Ibu yang sudah kritis memutuskan tidur bersama anak-anaknya di ruang tengah. Ia menciumi mereka satu per satu di tengah malam, sebuah pamitan sunyi sebelum pagi merenggutnya selamanya.
Film ini bukan sekadar drama keluarga
Setelah menyeka air mata dan mencoba berpikir jernih, saya menyadari bahwa label “drama keluarga” mungkin terlalu lunak untuk film ini. Meminjam istilah yang tepat dari ulasan kanal YouTube Cine Crib, film ini sejatinya adalah sebuah “horor kehidupan”.
Ya, tidak ada hantu yang melompat dari balik lemari. Tidak ada juga musik jumpscare yang memekakkan telinga. Namun, teror di dalamnya terasa jauh lebih nyata dan mencekik karena ia begitu dekat dengan realitas banyak keluarga di Indonesia.
Bagi saya, kekuatan utama sang sutradara, Kuntz Agus, dalam film ini adalah kemampuannya membangun dunia yang believable. Rumah keluarga ini tidak ditampilkan seperti rumah sinetron yang “steril dan kaku”. Ini adalah rumah yang “aut-autan,” berantakan, tapi tetap hidup.
Misalnya, sesederhana mata saya dimanjakan–sekaligus diiris–oleh detail-detail artistik yang presisi. Mulai dari talenan dapur yang sudah butut dan hitam, mangkok ayam jago jadul yang mungkin dimiliki oleh kita semua, hingga termos air panas plastik berwarna biru yang ikonik.
Bahkan, riasan wajah para pemainnya dibuat natural. Wajah berminyak dan rambut lepek saat di rumah memberikan tekstur realisme yang jarang kita temui.

Di tengah set yang begitu membumi inilah, cerita bergulir. Amanda Rawles, yang berperan sebagai Alin, berfungsi sebagai mata penonton. Sebagai anak yang sempat “keluar” dari rumah (karena ngekos), ia pulang dan melihat kondisi keluarganya dengan kacamata yang lebih objektif dibandingkan saudara-saudaranya yang terjebak di sana setiap hari.
Melalui tatapan Alin, kita diajak menelusuri setiap sudut rumah yang menyimpan bom waktu emosional. Mulai dari kipas angin rusak, hingga adegan atap ambrol, di mana ibunya harus rela naik genteng di tengah hujan untuk memperbaiki.
“Kok ibu yang di atas. Memangnya ayah kemana?” tanya Alin kepada kakaknya, Anis (Eva Celia), saat menyaksikan ibunya memanjat genteng.
“Memangnya kapan sih kita bisa ngandelin ayah?” jawab Anis. Kalimat ini singkat, tapi menohok. Membuka mata Alin tentang situasi yang sebenarnya di rumah.
Di balik segala kekacauan itu, memang ada sosok yang menjadi sumber dari segala “horor” di film ini: sang ayah. Ibu, Anis, dan adiknya, Asya (Nayla Purnama) setiap hari menyaksikan horor ini. Namun, ini adalah kenyataan baru yang disaksikan Alin karena memang dia jarang pulang.
Tak perlu melakukan kekerasan untuk menjadi penindas
Jika ada satu hal yang membuat dada saya sesak sepanjang film, itu adalah karakter ayah yang diperankan oleh Bucek Depp. Betul, karakter ini menurut saya memang terlalu “di-antagonize“, dibikin terlalu hitam-putih, tanpa sisi baik sedikit pun. Meski pun, di dunia nyata, memang ada banyak sosok seperti si ayah ini.
Dan, dari sikap antagonize-nya inilah kebencian penonton bisa sangat mudah tersulut. Termasuk saya.
Bayangkan, di pagi hari yang sibuk saat Ibu “membelah diri”–harus menyiapkan sarapan, membenarkan kipas angin yang rusak, menyiapkan seragam sekolah Asya, hingga ngongkel motor Anis yang macet–si ayah baru bangun tidur, duduk santai, dan merokok dengan dalih “mengumpulkan nyawa”.
Boro-boro bekerja. Kalimat pertama yang ia ucapkan adalah “bikinkan kopi!” Secara harafiah, ia adalah “beban”. Karena nggak cuma suka bangun siang; ia juga hobi judol dan terlilit utang sampai si ibu dikejar-kejar debt collector.
Namun, jika kita membedah karakter menyebalkan ini dengan pisau sosiologi, saya jadi teringat dengan teori patriarki-domestik yang digagas Sylvia Walby dalam bukunya, Theorizing Patriarchy (1990). Teori ini mengajukan pertanyaan krusial: “Bagaimana kekuasaan bekerja di dalam rumah tanpa kekerasan langsung?”. Jawabannya ada pada sosok Tio, sang ayah, di film ini.
Bagi saya, kalau boleh meminjam istilah Walby, si ayah ini adalah sosok yang parasitik dan destruktif, tapi ia tetap memegang otoritas tertinggi di rumah. Maksudnya, ia tidak perlu menjadi kompeten atau menjadi pencari nafkah untuk tetap dianggap sebagai “kepala keluarga”.

Inilah yang disebut Walby sebagai legitimasi gender. Sistem sosial patriarki memungkinkan eksploitasi ini terlihat “normal”. Ayah tidak perlu memukul untuk menindas. Ia cukup tak berperan apa-apa, bangun siang, dan membiarkan struktur keluarga melindunginya.
Bahkan, ketika anak-anaknya membencinya, mereka tetap terjebak dalam kewajiban melayaninya–seperti adegan membuatkan kopi. Ini menunjukkan bahwa patriarki mereproduksi dirinya bukan lewat kekerasan fisik, melainkan lewat “kewajaran” yang dipaksakan.
Lantas, mengapa ibu bertahan?
Banyak penonton–dan mungkin sebagian karakter di film–menganggap sikap Ibu sebagai bentuk kesabaran atau kesetiaan. Namun, kalau meminjam kacamata Martin Seligman lewat teori Learned-Helplessness (ketidakberdayaan-yang-dipelajari), apa yang dialami Ibu bukanlah kesabaran, melainkan kelumpuhan harapan.
Teori ini menjelaskan, bagaimana seseorang belajar untuk menerima penderitaan sebagai kondisi normal setelah mengalami kegagalan berulang kali untuk mengubah situasi. Situasi di rumah itu kronis: utang yang terus menumpuk, dan perilaku suami yang tidak pernah berubah.
Secara fisik, ibu memang aktif. Misalnya, ini ditunjukkan dengan fakta bahwa ia punya usaha laundry–dengan detail mesin cuci dan lantai beceknya. Namun, secara psikologis, ia pasif. Ibu tidak lagi memiliki harapan spesifik bahwa ia bisa mengubah suaminya atau keluar dari pernikahan itu.
Di masyarakat sendiri, kalimat yang sering kita dengar, seperti “yang penting dia tidak selingkuh” atau “setidaknya dia baik”, sekali lagi saya tegaskan bukan tanda kebahagiaan. Dalam teori Seligman, itu adalah rasionalisasi kognitif. Ibu menurunkan standar kebahagiaannya serendah mungkin hanya agar ia bisa tetap waras menjalani hari demi hari.

Bayangkan saja, dalam satu adegan, di mana si ayah dengan enteng mencuri uang hasil jerih payang ibu untuk membayar tagihan utang, tak ada kemarahan. Tak ada konfrontasi. Tak ada adu mulut. Ibu malah terkesan mengalah, meskipun wajahnya menunjukkan kekecewaan.
Meminjam teori Seligman, dalam adegan itu–dan sebagian besar adegan di film ini–menunjukkan kalau ibu telah menggeser makna hidup dari “mencari kebahagiaan” menjadi sekadar “bertahan hidup”.
Tangisan Ibu saat mengoles salep bukan sekadar karena sakit fisik, tapi manifestasi dari jiwa yang tahu bahwa ia terjebak, dan ia telah “belajar” bahwa tidak ada jalan keluar. Cuma bisa sabar.
“Kenapa nggak ayah saja yang mati? Kenapa harus Ibu?”
Tentu, film ini tidak lepas dari kekurangan teknis. Misalnya, ada beberapa lubang logika yang mengganggu, misalnya, karakter mahasiswa kedokteran yang mengenakan celana jins sobek-sobek saat di laboratorium–sebuah detail kostum yang menurut saya kurang riset.
Selain itu, penyelesaian cerita (closure) terasa agak bertele-tele (draggy), terutama pada subplot hubungan asmara Alin dan pacarnya yang terasa repetitif dan membosankan di babak akhir.
Juga, pacar Alin yang sudah lima tahun berhubungan tapi masih kaku dan canggung saat berkunjung ke rumah juga menjadi catatan kecil yang mengurangi “kesempurnaan” naskah.
Namun, kekurangan-kekurangan tersebut tertutupi oleh kekuatan emosional yang dibangunnya. Transisi visual kondisi Ibu yang makin memburuk, dengan efek kulit yang menguning akibat kanker pankreas yang menyebar ke hati, ditampilkan dengan detail medis yang cukup akurat dan mengerikan,.
Pada akhirnya, Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah adalah sebuah pengalaman sinematik yang menguras energi. Ia bukan film yang sempurna; naskahnya kadang terasa terlalu hitam-putih dalam menggambarkan antagonisme sang Ayah, membuat kita bertanya-tanya, “Apa yang dulu dilihat Ibu dari pria ini?”.
Namun, sebagai potret sosial, film ini berhasil menangkap realitas banyak rumah tangga di Indonesia dengan kejujuran yang brutal.
Film ini mengajarkan kita bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berupa pukulan lebam di wajah. Kadang, kekerasan itu berupa ketidakpedulian yang kronis, tumpukan utang yang tak berujung, dan hilangnya kemampuan seorang ibu untuk membayangkan masa depan yang berbeda.
Adegan Alin yang meledak marah dan berteriak, “Kenapa nggak ayah aja yang mati?”, adalah kulminasi dari semua rasa frustrasi yang dibangun sepanjang durasi film. Itu adalah teriakan perwakilan dari penonton, sekaligus teriakan dari anak-anak yang menjadi pewaris trauma sistem patriarki yang rusak.
Bagi saya, film ini layak ditonton, bukan untuk mencari hiburan, melainkan untuk merenung. Judul film ini sendiri adalah sebuah pengandaian yang menyakitkan–sebuah pertanyaan “what if” yang tak pernah bisa dijawab oleh Ibu, karena seumur hidupnya ia terlalu sibuk bertahan dari satu hari ke hari lainnya.
Dan, bagi kita yang menonton, film ini meninggalkan jejak horor yang lebih sunyi: ketakutan bahwa mungkin, di suatu tempat di luar sana, atau bahkan di dekat kita, ada seorang ibu yang sedang mengoleskan salep di kakinya sambil menangis, sendirian.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Film “Tinggal Meninggal” Bukan Fiksi Biasa, tapi Realitas Sosial Orang Dewasa yang Caper agar Diakui di Lingkaran Pertemanan atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan