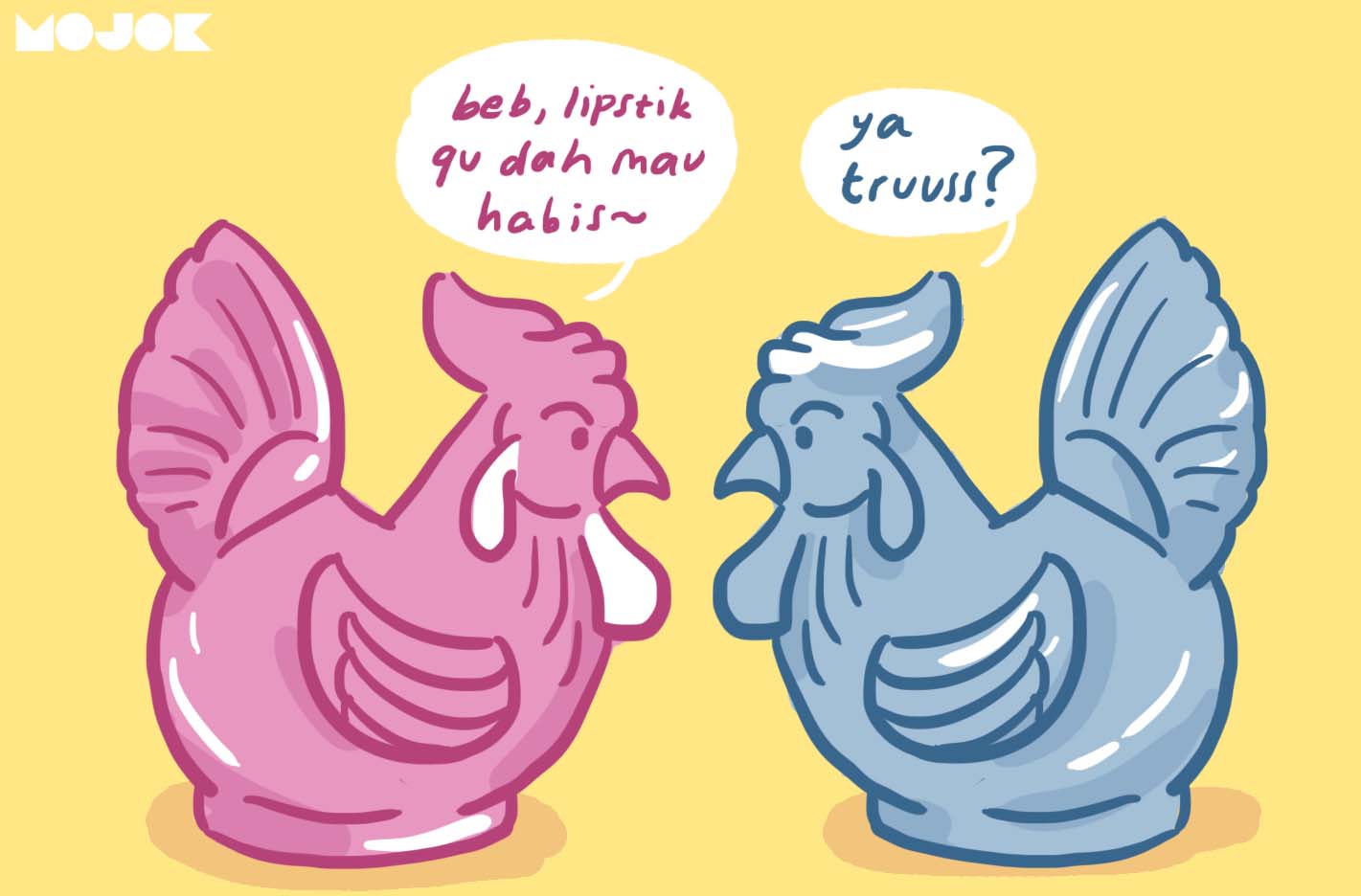MOJOK.CO – Pada akhirnya, keputusan saya adalah “hijrah”. Ketimbang saya terjebak di situasi yang beracun, di sebuah kampus yang berdiri di Malang, Jawa Timur.
Kira-kira, apa yang dipikirkan seorang mahasiswa baru saat hendak pergi ke kampus untuk pertama kalinya? Jika itu saya, maka saya sudah memikirkan beberapa rencana aktivitas keseharian yang indah. Seperti misalnya setiap hari ke perpustakaan, ngopi sambil nugas bareng teman, mengadakan diskusi ilmiah yang renyah.
Selain itu, sesekali mengkritik negara boleh dong, ikut gerakan mahasiswa, riset bareng dosen, dan menulis makalah ilmiah di kampus dari pagi sampai sore jika tidak ada mata kuliah. Naif, bukan? Tidak masalah. Saya percaya pada organisasi masyarakat yang menaungi sebuah kampus di Malang.
Imajinasi inilah yang saya bawa saat menjadi mahasiswa baru di sebuah kampus di Malang. Saat ospek berlangsung, saat kali pertama menginjakkan kaki di kampus, ada narasi gagah “Generasi Indonesia Emas 2045” yang digemakan dengan bangganya.
Tidak ada yang salah dengan narasi itu. Cuma, adalah suatu keanehan bagi saya apabila narasi optimis itu digemakan secara lantang di tengah krisis nasional dalam berbagai bidang. Mulai dari merajalelanya korupsi, krisis kepercayaan masyarakat, sampai ekonomi yang timpang. Krisis tersebut membuat saya resah dan bertanya dalam batin, “Ini orang-orang pada membicarakan ‘Indonesia Emas 2045’. Lha memang di tahun segitu Indonesia masih ada?”
Selain narasi heroik itu, ada beberapa agenda janggal seperti tugas ospek untuk membuat video TikTok, alih-alih menulis esai akademik. Banyak acara konser ketimbang agenda ilmiah. Tidak ada agenda diskusi untuk membahas masalah-masalah yang sedang terjadi.
Ketika sebuah kampus di Malang mengabaikan saya
Saat salah satu dekan menjelaskan perihal kehidupan di kampus beserta narasi Indonesia Emas. Saya menyiapkan beberapa pertanyaan untuk merespons sang dekan. Saya siap bertanya soal krisis nasional di mana sang dekan luput menjelaskan. Untuk itu, saya sudah mengumpulkan berbagai referensi di dalam kepala. Saya juga berharap ospek yang janggal bagi saya itu mendapatkan jawaban secara tuntas.
Seorang moderator membuka sesi tanya-jawab. Saya menjadi mahasiswa pertama yang angkat tangan sembari berdiri. Alih-alih mendapat kesempatan, moderator mengabaikan angkat tangan saya. Dia pura-pura tidak melihat dan menunjuk peserta lain. Tidak terima, saya maju ke depan untuk menuntaskan rasa ingin tahu. Nahasnya lagi, saya masih diabaikan.
Pengabaian itu memantik emosi dalam batin ini. Jelas, ini merupakan suatu sikap otoriter dalam dunia akademik. Sudah sangat mengganggu kebebasan berekspresi. Barangkali pihak kampus di Malang itu tahu bahwa saya sering melontarkan kritik sehingga mereka melarang saya berbicara.
Baca halaman selanjutnya….