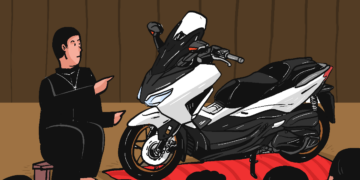MOJOK.CO – Perda Manokwari Kota Injil berpotensi melahirkan konflik. Apakah pemeluk Islam, Kristen, dan Katolik tidak bisa menjadi makhluk penuh tenggang rasa dan saling memahami selamanya?
Pada 8 Januari 2019, tirto.id memuat sebuah berita yang judulnya cukup membuat cemas. Berita itu diberi judul: “Perda Manokwari Kota Injil Berpotensi Melahirkan Konflik”.
Membaca judul di atas saja kamu pasti sudah mendapatkan sari pati berita yang ingin diangkat. Kamu bisa membacanya lewat tautan yang saya sertakan di artikel. Klik saja kata “tirto.id”. Setelah membaca sampai tuntas, pikiran apa yang terbentuk di dalam kepala kamu masing-masing? Biasa saja? Khawatir? Menyambut dengan suka cita?
Kalau saya sudah jelas: cemas. Bagian “berpotensi melahirkan konflik” adalah sebuah kalimat yang tidak seharusnya ada di kehidupan kita. Siapa sih yang mau berkonflik? Siapa sih yang begitu bahagia menghabiskan waktunya untuk membenci orang lain? Pada dasarnya jelas, tidak ada yang mau kesejahteraannya terganggu karena urusan konflik.
Membaca dinamika Perda Manokwati Kota Injil, seperti dikelaskan oleh judul Tirto, berpotensi merepotkan masyarakat yang tidak tahu atau tidak mau tahu. Bukankah menyeret orang banyak yang ingin hidup tenang juga salah satu bentuk intoleransi? Kamu tidak setuju? Ya tidak apa-apa. Begini lho masalahnya…
Ada dua hal yang perlu dipahami. Pertama, sejarah Manokwari yang diklaim sebagai tempat masuk injil di Papua Barat. Atas sejarah ini, memang masuk akal apabila Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) mengusulkan dibentuknya Perda Manokwati Kota Injil. Konon, supaya tidak hanya sebatas menjadi slogan “kota injil”, sebuah perda perlu disusun supaya pemeluk Kristen betul-betul mengimani status tersebut.
Sampai di sini masih masuk akal tidak terlihat potensi konflik. Namun, ketika membaca beberapa pasal di dalam perda tersebut, masuk akal juga apabila MUI Papua menyampaikan keberatan. Lewat ketuanya, Ahmad Nausrau, MUI menilai ada tiga pasal yang “rancu” di dalam perda yang bahkan sudah disahkan DPRD Manokwati sejak 28 Oktober 2018 yang lalu.
Dari tiga pasal “rancu” tersebut, Ahmad Nausrau menyoroti pasal 14 yang mengatur aktivitas publik. Ahmad Nausrau merasa pasal ini merupakan bentuk pemaksaan umat Islam untuk tidak beraktivitas di hari Minggu.
“Lalu kenapa harus semua orang pada hari Minggu atau hari raya orang Kristen harus menghentikan kegiatan? Orang lain, kan, tidak ada hubungannya dengan hari raya orang Kristen,” ungkap Ahmad Nausrau.
Menurut kamu, apakah pernyataan Ahmad Nausrau masuk akal? Bagi saya, pemeluk Katolik, pernyataan tersebut sangat masuk akal. Seperti yang saya sebutkan di atas pada bagian “Bukankah menyeret orang banyak yang ingin hidup tenang juga salah satu bentuk intoleransi?”, memaksa pemeluk agama lain untuk melakukan perintah agamamu itu sudah bentuk intoleransi. Bukan sikap tenggang rasa, justru pengkhianatan kepada taklid manusia makhluk sosial.
PGGP berpendapat bahwa mereka hanya ingin seperti Aceh. Kalau ada Serambi Mekkah di Aceh, mengapa tidak bisa ada di Papua untuk pemeluk Kristen, khususnya di Mansinam?
Logika ini sebetulnya juga masuk akal karena menjadi bentuk “pemerataan kepercayaan” dan diakui oleh negara dan masyarakat di dalamnya. Namun, sesuatu yang baik secara logika, juga perlu mempertimbangkan dinamika sosial yang terjadi di dalamnya. Kalau idenya bagus, tetapi bentuk nyata di masyarakat justru merugikan pemeluk agama tertentu, ide yang bagus itu tidak berbuah baik.
Pemeluk Islam, berhak beraktivitas kapan saja mereka mau. Mau hari Senin, Rabu, Jumat, atau Minggu. Islam punya pandangan bagus, yaitu lakum dinukum waliyadin yang artinya “bagimu agamamu, bagiku agamaku”. Perda Manokwari Kota Injil baik adanya, asal pasal di dalamnya tidak membatasi pemeluk agama lain.
Cukup mengatur kehidupan iman Kristen (dan Katolik). Buah Kristus paling paripurna adalah cinta kasih. Kalau melewati batasan tenggang rasa, jatuhnya menjadi intoleran. Ingat, intoleran tidak terjadi hanya dari mayoritas kepada minoritas. Intoleransi juga berlaku sebaliknya. Lha wong pelakunya sama: manusia yang penuh kelemahan dan ego. Tak akan ada lagi cinta kasih di situ.
Lagipula, mengapa kudu jauh-jauh studi banding ke Aceh ketika di dekat Manokwari ada sebuah fenomena kasih antara Islam, Kristen, dan Katolik?
Coba tengok ke Fakfak, di mana warga muslim, kristiani, dan katolik bisa hidup rukun, berdampingan, tenggang rasa, kalau kata orang Jawa: tepa selira.
Saya tidak akan capai untuk terus mengingatkan bahwa Indonesia punya penawar paling indah untuk masalah intoleransi. Tidak jauh, kok penawar itu berada. Fakfak, masih satu pulau dengan Manokwari. Di sana hidup sebuah pandangan hidup bernama “satu tungku tiga batu”.
Konsep “tiga batu” merujuk pada pemeluk agama (Islam, Kristen, dan Katolik) yang sama-sama menunjukkan niat menjaga kerukukan beragama dan kehidupan sehari-hari. Konsep ini sifatnya harga mati dan begitu dihayati.
Sebagai gambaran, selama bulan Ramadan, angka kejahatan di Fakfak hampir nol. Semua menghormati bulan penuh berkah ini. Jika kamu tak percaya, silakan berkunjung ketika bulan Ramadan tiba. Kamu akan mendapati budaya sungkan yang begitu dalam.
Ketika bulan Ramadan, orang Kristen tidak akan pernah makan, minum, atau merokok di depan orang Islam. Mereka akan menyingkir, misalnya masuk ke dalam rumah apabila ingin minum atau makan. Warung-warung akan tutup dengan iklas dan sendirinya tanpa ada paksaan dan razia yang kekanan-kananakan.
Ketika Lebaran tiba, orang-orang Kristen akan datang ke tempat salat Ied dilaksanakan. Mereka akan mengenakan peci dan sarung, jadi kamu akan susah membedakan mana yang Muslim, mana yang Kristiani. Mereka akan duduk mendengarkan khotbah, lalu memberi salam, bersalam-salaman selepas salat Ied usai.
Begitu pula ketika Natal menjelang. Saudara-saudara Muslim akan menjadi panitia gelaran Natal, mulai dari mengurus keamanan hingga berpartisipasi ketika misa atau kebaktian berlangsung. Mereka akan duduk di dalam gereja dan mengikuti ibadah dengan iklas, tanpa mempermasalahkan soal iman.
Bahkan tak jarang pula, saudara Kristiani akan menjadi panitia pembangunan masjid. Pada intinya, kesadaran akan perbedaan begitu tinggi, namun semuanya itu adalah bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang perlu dirayakan. Saling menghormati adalah perkara mudah.
Tiga agama merupakan “tiga batu” yang menopang “satu tungku”. Sebuah analogi manis bahwa semua manusia yang hidup beranak-pinak di tengah masyarakat memerlukan suasana damai dan kondusif.
Supaya tungku tersebut mengasilkan masakan yang lezat, dibutuhkan bumbu yang tepat, dan terutama penyangga yang kokoh. Masalah iman adalah masalah sepele. Kekerasan dengan latar belakang agama dan dinamika sosial di Pulau Jawa menjadi terlihat seperti masalah anak kecil saja.
Masyarakat di Fakfak juga dengan sadar harus meredam potensi konflik yang disebabkan oleh biang eksternal. Misalnya ketika pecah kerusuhan Ambon, ada beberapa usaha provokasi untuk membuat Fakfak menjadi medan perang selanjutnya.
Namun, para tokoh agama dan adat bersatu padu, saling meneguhkan dan menjaga. Hasilnya, provokasi brengsek tersebut berhasil ditepis. Fakfak tetap aman, dan “tungku” tersebut terus mengepulkan aroma masakan yang tak hanya lezat, namun juga bergizi.
Saya berharap kamu bisa membayangkan betapa enaknya hidup dalam nuansa damai lewat penjelasan di atas. Sebuah daerah boleh saja punya status yang menggambarkan iman tertentu. Bahkan sangat boleh karena itu menggambarkan kedewasaan iman semua pemeluk agama.
Namun, seyogyanya, jangan pernah memaksakan kehendak kepada pemeluk agama lain untuk taat dengan peraturan agamamu.
Shirley Parinussa, ketua PGGP kepada suaramandiri.co pernah berujar bahwa, “Agama harus menjadi sarana pemersatu dan pemberi terang untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat.”
Naaahh, kalau Ibu Pendeta Shirley saja sudah begitu bijak menyampaikan tugas agama, mengapa kita masih mau merawat intoleransi itu? Mengapa masih “memaksa” pemeluk agama lain untuk “tunduk”? Mari ingat selalu makna “satu tungku tiga batu” supaya kita tidak menjadi manusia intoleran. Gampang banget begitu kok kamu ndak bisa.
Katanya makhluk sosial. Atau kamu-kamu semua itu makhluk egois?