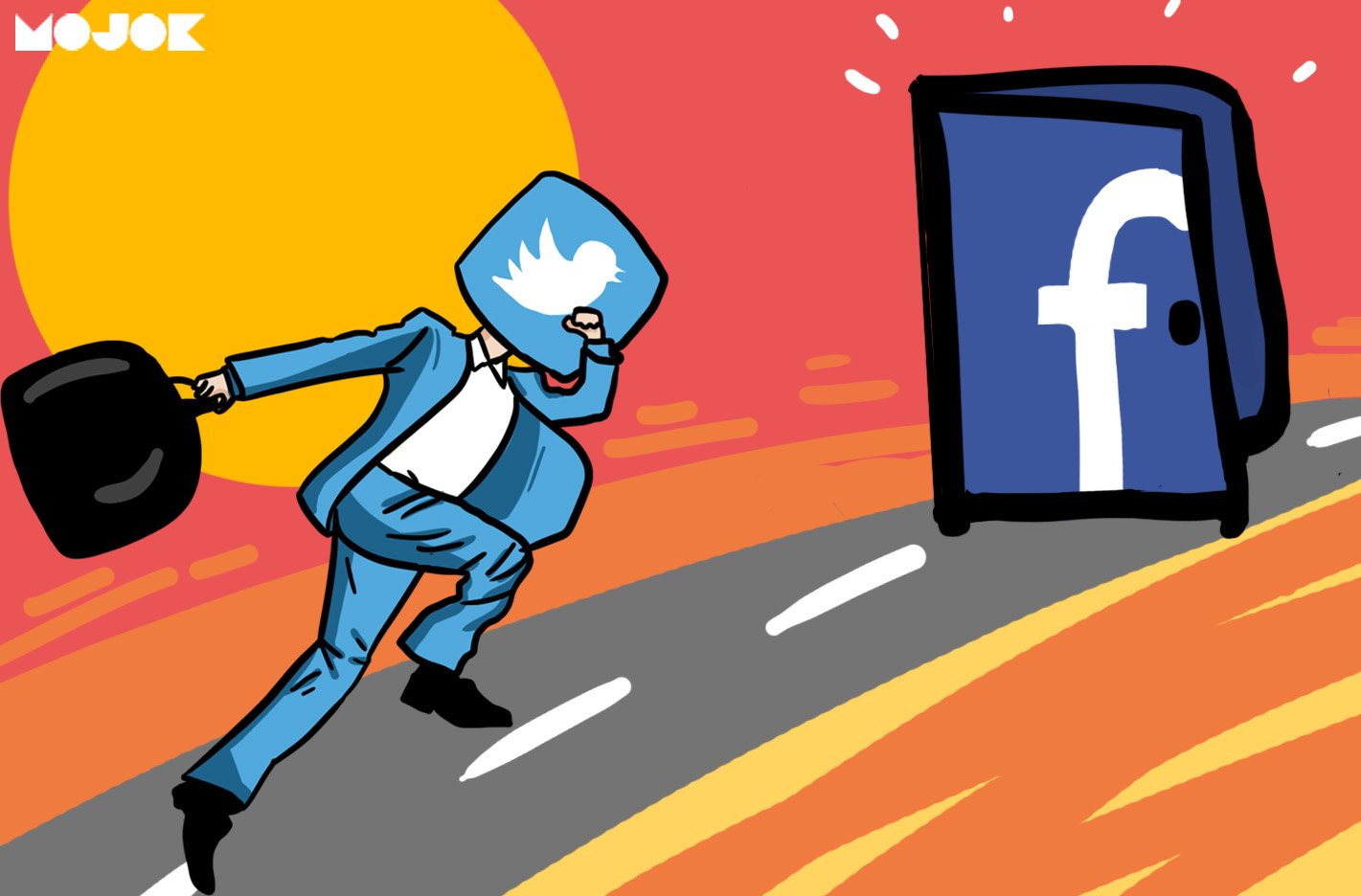Dulu kala, selama dua atau tiga tahun, saya seorang pencandu Twiter. Saya punya akun dengan follower terakhir cuma 1200. Tapi selain akun resmi itu, ada beberapa akun rahasia lain yang saya pegang. Tenang saja, bukan akun Jokowi atau Fahri Hamzah atau apa. Cuma akun-akun iseng, tapi cukup kriuk buat amunisi sepak kiri sepak kanan haha.
Dengan kehidupan saya yang berkutat antara ngetwit, kultwit, twitwar, dan kekhusyukan mantengi timeline, saya terkejut sendiri ketika pada sebuah malam yang penuh keagungan akhirnya saya memutuskan pensiun dari Twitter. Saya pun hijrah ke Facebook, sebuah hijrah yang kaffah.
Peristiwa sakral hijrahnya saya meninggalkan Twitter itu tentu dilandasi hidayah Tuhan. Dia Yang Maha Menguasai Dunia Nyata, Dunia Gaib, dan Dunia Cyber itu telah menunjukkan, betapa Twitter membawa mudarat bertumpuk-tumpuk. Nah, ini saya tuliskan sebagian kecil di antaranya.
Twitter memantik obrolan dangkal yang jauh lebih banyak dibanding Facebook!
Begini, Twips. Twitter berlanggam rock, sementara Facebook berlanggam keroncong. Sundari Sukotjo dan Mus Mulyadi jelas terasa lebih kontemplatif ketimbang para personil Deep Purple, misalnya.
Maka kita bisa melihat sendiri, betapa obrolan di Twitter adalah obrolan yang terlalu rancak, saling bersahut, dengan ritme yang sangat cepat penuh dentuman. Irama semacam itu merampas kesempatan kita untuk berpikir matang sebelum mencuitkan sesuatu. Lebih-lebih ketika twitwar. Twitwar pun tumbuh menjadi semacam Cerdas Cermat P4 tapi dalam format tarung bebas ala UFC.
Bandingkan dengan Facebook. Di Facebook, sebuah perdebatan bisa berlangsung berhari-hari. Bukan karena berkepanjangan, tapi lebih karena para ‘panelis’ masih memungkinkan untuk pergi makan siang dulu, atau mandi dulu, atau ngerokok dulu, atau sembahyang dulu, sebelum menjawab lawan debatnya. Itu mustahil terjadi di twitwar. Pergi sebentar saja dari twitwar bisa-bisa langsung di-nomensyen: “Aduh, dia ngilang…”.
Memahami gagasan yang utuh lebih enak di Facebook
Twitter memberikan kesempatan yang jauh lebih terbatas ketimbang Facebook untuk merunut suatu gagasan. Sebuah runtutan ide di Twitter akan dengan sangat gampang tertimbun celetukan-celetukan lainnya. Akibatnya, sangat sering terjadi munculnya tanggapan alias reply yang sepotong-sepotong, atas pemahaman teks yang juga sepotong-sepotong. Kebiasaan inilah yang secara signifikan membentuk mental generasi alay dengan kebiasaan memotong-motong. Apanya yang dipotong? Nah, itu kau pikir sendiri lah.
Delusi imam-makmum
Twitter adalah penipu paling ulung, karena dia menenggelamkan kita dalam kubangan delusi, dalam comberan halusinasi. Seorang twip akan mengkhayalkan dirinya setara imam sekte keagamaan, hanya karena dia punya follower 20.000, misalnya. Seolah ke-20 ribu akun itu adalah manusia semua, dan seluruhnya jemaat taat belaka.
Padahal yang terjadi sesungguhnya, ada sekian ribu akun yang mem-follow cuma untuk mencari sisi bolong si ‘imam’. Cuma biar bisa terus stand by, agar selalu siap mem-buli dia. Sekian ribu follower yang lain mem-follow cuma karena politik transaksional. Lihat saja pesan klise ini: “Folbek dong!”. Ya, si follower baru tersebut ngeklik fitur follow cuma karena mau cari follower juga! Lalu setelah terjadi saling follow, sebenarnya siapakah yang jadi imam, siapakah yang jadi makmum? Tak jelas. Tapi masing-masing terus mengimajinasikan diri tengah diikuti barisan prajurit yang setia dan penuh jiwa corsa.
Bandingkan dengan di Facebook. Follower yang asli bisa dipantau dengan simpel lewat jumlah klik jempol pada postingan-postingan. Kalau nggak mau jadi jemaat, ya nggak perlu nge-like. Simpel. Lah, fitur follow di Facebook bagaimana? Ah, itu kan fitur iseng aja. Waktu bikin itu Zuckerberg lagi PMS.
Menjunjung tinggi bahasa persatuan
Twitter adalah musuh besar guru pelajaran Bahasa Indonesia. Bayangkan saja, betapa tak berguna lelah-letih Bu Guru yang mengajarkan penulisan kata yang baik dan benar, ketika dengan alibi keterbatasan karakter lantas kalian dengan semena-mena ngetik “Ksini aj, q lg sndri nie.”
Iya sih, itu sisa-sisa peninggalan tradisi SMS purba. Tapi sejak munculnya hape qwerty, cuma Twitter yang masih secara konservatif menetapkan batasan jumlah karakter. Jadi.. masih ngerasa gahul jadi pasukan Twitter? Plis deeeh..
Tambahan lagi, Twitter pun memporak-porandakan hasil keterampilan mengarang yang telah diajarkan guru Bahasa Indonesia sejak SD hingga SMA. Sebabnya jelas, yaitu karena kalian lebih suka “mengarang” dengan urutan angka-angka di kala kultwit, alih-alih dengan paragraf! Mungkin para selebtwit sudah merasa menulis dengan baik, cuma dengan menyajikan kultwit sehari dua kali. Padahal silakan periksa, mana ada di antara mereka yang masih mengingat teknik organisasi gagasan berupa pemilahan paragraf, kohesi antara satu paragraf dengan paragraf yang lain? Tidak, tidak pernah ada paragraf di Twitter. Menangislah, Bu Guru…
***
Demikianlah. Dengan memahami empat poin saja di antara puluhan kesesatan Twitter, kita dapat langsung menyadari bahwa satu-satunya kelebihan Twitter hanyalah karena suksesnya gelar kopdar paling spektakuler abad ini, antara @redinparis dan @panca666 di Istora Senayan dua pekan lalu.
Maka tinggalkanlah Twitter sekarang juga, hai orang-orang yang menginginkan jalan kebenaran.