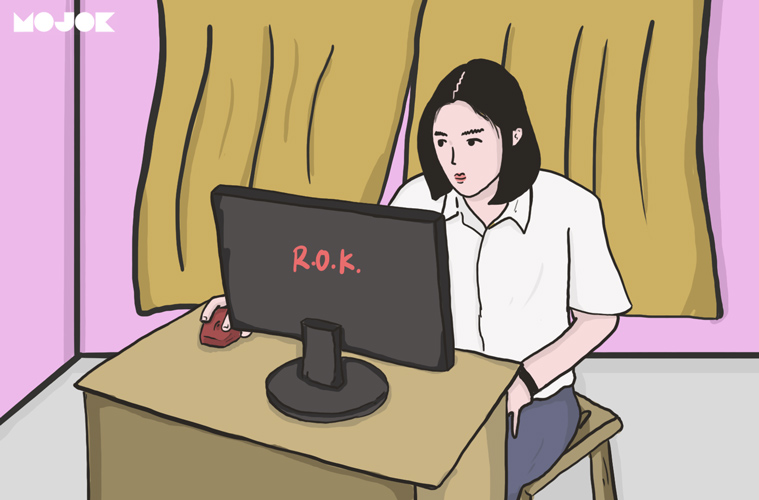MOJOK.CO – Soal kelakuan emak-emak yang gelantungan di MRT, polarisasi terjadi lagi. Ada SJW yang malu luar biasa sebagai orang Indonesia, ada juga yang memaklumi.
“Malu aku jadi orang Indonesia!” kata seorang teman SMA di status facebooknya.
Sekilas, saya mengira ia sedang menulis ulang judul buku Taufik Ismail. Padahal setahu saya, ia tidak suka dengan penulis itu. Dua kali kilas, rupa-rupanya ia sedang meriuhkan perdebatan online seputar kelakuan emak-emak penumpang Mass Rapid Transportation (MRT). Media-media pun belakangan sudah menggembor-gemborkan keramaian tersebut.
Mau tak mau saya yang suka telat update pun turut mengikuti pro kontranya. Dan dari pengamatan sementara, saya ingin bilang, “Luar biasa.”
Tak disangka bahwa emak-emak berhijab yang gelantungan atau ibu-ibu yang plesir sambil makan di stasiun MRT itu bisa menggegerkan jagat persosmedan.
Teman saya itu menekankan lagi rasa malunya di kolom komentar.
Katanya, “Bandingin deh kelakuan orang Indonesia sama orang dari negara maju. Gimana caranya negara ini bisa maju kalau kelakuan warganya kayak begini?” Komentar itu ditambahi dengan emotikon nangis bombay dan marah.
Saya ingin membalas komentar tersebut, “Anu, jangan salah, banyak lho orang dari negara maju yang tak punya etika sama sekali. Tapi negaranya tetap maju tuh. Amerika malah pernah seenaknya ngebom sama perang. Tapi tetap maju negaranya.”
Cuma, saya urungkan jawaban itu karena rasanya kok terlalu OOT (out of topic). Saya tahu bahwa inti yang ingin dia sampaikan adalah kondisi bahwa ia sedang merasa malu dengan kelakuan orang senegaranya. Super duper malu.
Untuk beberapa saat saya heran sendiri kenapa saya tidak merasakan kedalaman perasaan malu yang sama.
Apa saya ini kurang nasionalis? Kurang patriotik? Kurang bermental maju? Kurang berkeadilan? Kurang terpelajar? Atau saya ini kurang beradab? Saya kok… biasa aja ya?
Alasan saya merasa biasa sebetulnya sangat sederhana. Begini lho, menurut saya yang namanya masalah etika adalah sesuatu yang bukan runtuh dari langit. Bukan given. Etika adalah sesuatu yang perlu diajarkan.
Sama kok dengan etika kita saat melakukan kebiasaan lainnya. Etika saat bertamu, etika saat ke rumah ibadah, etika saat makan, etika saat bicara dengan orang tua, dan lain sebagainya adalah hal yang perlu diajarkan.
Seorang anak tidak lahir lalu tumbuh dengan satu set etika sempurna. Dan pengajaran etika ini berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Tergantung budayanya. Jadi sifatnya pun kadangkala tidak mutlak.
Etika orang Indonesia saat ke rumah ibadah, misalnya, bisa dibilang sudah baik. Jauh “kelasnya” dibanding beberapa bule dari negara sekuler. Terus, apa si bule perlu malu luar biasa ketika etikanya lebih rendah dari orang Indonesia saat ke tempat ibadah? Kan tidak.
Asalkan tidak sampai seperti Logan Paul yang melewati batas (masalah menghormati orang mati itu kan universal ya toh?), saya kira masih bisa dimaklumi.
Yang menurut saya penting dan bermanfaat adalah mendukung pemerintah untuk mengajarkan bagaimana etika yang tepat di MRT. Tak usahlah sampai ngatain emak-emak itu “monyet” dan “terbelakang”. Wajar kok mereka tidak paham sebetulnya.
Lah wong punya MRT pun baru sekali ini. Belum lagi media juga menggembar-gemborkan bahwa kehadiran MRT ini adalah capaian besar buat Indonesia. Makanya rakyat pun jadi ikut antusias luar biasa.
Kalau saat ini fenomenanya menunjukkan masyarakat kita ini tak paham etika di MRT, ya sekali lagi, kita bisa menuntut pemerintah mengajarkannya. Kalau kelak masih bandel setelah diajari ya denda. Dikatain pun wajar kalau sudah diajarkan masih membandel. Tapi kalau belum diajari ya jangan dikata-katain dulu.
Ealah, ketika memberikan komentar itu, ada teman yang berkata, “Duh kamu kok jadi kayak SJW-SJW itu!”
Eits? Maksudnya “SJW itu” SJW yang mana, ya?
Dari situ, teman saya kemudian mengarahkan saya ke postingan orang yang dianggapnya SJW. Sebab postingan tersebut dianggapnya membela kelakuan emak-emak yang gelantungan di MRT.
Beberapa akun yang dia sebut SJW ada juga yang membenarkan kelakuan itu karena pengguna MRT diasumsikan dari kelas sosial bawah. Sedangkan penghujatnya dari kelas menengah dan atas yang mengagumi perilaku pengguna MRT dari negara maju yang pernah mereka kunjungi.
Whoa. Saya jadi bingung. Saya kira, kelakuan SJW lebih tepat ditujukan buat si penghujat kelakuan warga MRT yang dianggap norak. SJW kan Social Justice Warrior. Sepemahaman saya mereka ini bertindak bagai penegak keadilan dan kebenaran.
Oleh karena itu, mereka mendapatkan julukan slur “SJW”. Dalam kasus ini, mereka yang mencoba menegakkan “kebenaran” cara beretika di MRT, saya kira cocok dengan istilah SJW.
Kok aneh jadi kebolak-balik gini ya? Atau saya yang salah?
Terus kalau mereka itu bukan SJW, lantas harusnya disebut apa? Penderita inferiority complex?
Bukannya apa-apa, cuma menurut saya, ada beberapa di antara mereka yang rasa malunya terlampau dalam. Siapa tahu, “dalamnya” rasa malu tersebut bersumber dari perasaan rendah diri karena standar negaranya jauh dari standar negara maju.
Bahkan, ada satu komentar yang sampai bilang bahwa, “Mendingan Indonesia dijajah Belanda saja.” Komentar itu pun mendapat banyak liker.
Saya jadi bertanya-tanya, apa mereka itu ingin merasakan sensasi geli-geli emosi ketika membaca plang “Verboden voor honden en inlander” alias “Dilarang masuk bagi anjing dan pribumi”? Asalkan MRT tertib, jadi inlander yang dipersamakan dengan anjing pun tak mengapa ya?
Ah, sudahlah. Saya cuma ingin berpesan bereaksi lah yang wajar aja. Fenomena seperti ini sungguh sangat bisa diperbaiki. Beberapa negara maju pun juga mengalami masalah serupa.
Kita sebagai masyarakat memang perlu menilai gelantungan di MRT dan sejenisnya itu salah. Tapi tak perlu menganggap ini sebagai masalah besar yang mengerikan sampai bikin sama-sama emosian.
Bangsa ini udah terpolarisasi dengan cebong dan kampret, bahkan udah nambah pro-golput dengan kontra-golput. Masa iya sekarang harus tambah lagi dengan yang beginian juga? Kayak pengangguran aja sih kita ini?