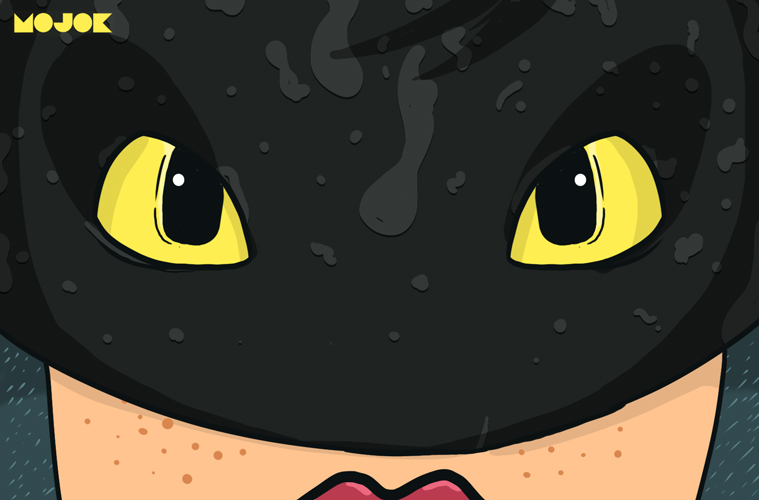MOJOK.CO – Katanya, perempuan yang suka pulang malam adalah contoh pamali. Ah, kamu cuma nggak tahu enaknya pulang malam itu gimana, kan?
Sekitar enam bulan yang lalu, seorang teman perempuan pernah mengajak saya pergi menonton Stars and Rabbit karena mendapat dua tiket gratis. Saya mengiyakan, lalu bertanya jam berapa acaranya mulai.
“Jam 11 mulai, tapi Stars and Rabbit-nya baru naik jam 12 atau jam 1,” jawabnya.
“Wah, jam segitu aku kerja.”
Teman saya memandang tak percaya, “Li, ini konsernya malem. Kamu tengah malem masih kerja?”
Gantian saya yang kaget setengah mati. Loh, loh, ini dia sedang mengajak saya keluar tengah malam???
Setelah menempuh perdebatan yang cukup panjang, saya akhirnya mengerti bahwa konser ini memang lebih afdol dilaksanakan malam hari. Masalahnya, saya belum pernah berangkat keluar kosan menjelang tengah malam. Bukan apa-apa, nih, tapi saya nggak kebayang kalau nanti bapak saya menelepon dari rumah di kampung halaman: bisa-bisa saya dikira main terus di perantauan!
Saya yakin ada banyak perempuan yang punya kepanikan yang sama: diberi tekanan oleh lingkungan sekitarnya soal “perempuan-seharusnya-tidak-pulang-malam-malam” atau malah “berangkat-malam-malam” seperti kasus saya yang mau nonton konser. Saya sendiri butuh waktu dua hari untuk memutuskan saya bakal ikut nonton dengan si teman.
Oh, dan dia sendiri tidak perlu ambil pusing. Teman saya ini adalah perempuan yang suka pulang malam—ibunya memercayainya 100% dan tidak mempermasalahkan jam berapa dia pergi dan pulang ke rumah. Enak betul~
Di sepanjang jalan ke dan dari acara konser, ada banyak orang berlalu lalang, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya terasa normal dan baik-baik saja—ternyata tengah malam dan dini hari tidak selamanya mengerikan seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya.
Selama duduk di jok belakang motor, saya jadi ingat kejadian semasa kuliah. Waktu itu, ada tugas kelompok yang harusnya saya selesaikan berdua. Namun, karena satu dan lain hal, saya dan teman satu kelompok ini hanya bisa berkomunikasi lewat WhatsApp. Menjelang pukul 12 malam, si teman membalas:
“Bentar, ya, Li, aku diajak keluar sama temen. Mau refreshing sebentar, sekalian cari makan.”
Cari makan??? Menjelang tengah malam???
“Kamu nggak ditelepon bapakmu?” tanya saya otomatis. Teman saya menjawab, “Kalau ditelepon, aku diemin. Biar dikira udah tidur. Hehe.”
Saya ingat saya ngakak membaca balasannya. Teman saya itu penampilannya jauuuh lebih tertutup daripada saya—kerudungnya panjang dan ia rajin ikut kajian. Tapi, perkara pergi keluar malam hari, ia jauh lebih fasih daripada saya yang udah ngetem di kosan selepas azan Magrib dan harus siap angkat telepon malam dari orang tua yang ingin memastikan saya nggak kelayapan di perantauan. Katanya, “Perempuan nggak usah pulang malem-malem, bahaya!”
Teman saya yang lain tinggal di kota yang bukan perantauan. Pekerjaan mengharuskannya pulang pukul 9 malam, padahal jarak kantor dengan rumahnya bakal menghabiskan waktu hingga 45 menit. Ia tidak bisa ikut “nongkrong-selepas-kerja” karena hapenya bakal berbunyi terus, berisi pesan dari orang tuanya yang menanyakan kapan ia akan pulang.
Saya pikir, ia merasakan hal yang sama dengan saya. Namun ternyata, masalahnya lebih dari sekadar “orang-tuaku-agak-sedikit-konvensional”.
“Orang tuaku paham akan pekerjaanku, tapi mereka risih karena harus menjawab pertanyaan tetangga soal kenapa aku selalu pulang malam. Tetanggaku sering bertanya sebenarnya pekerjaanku apa.”
Wow. Wow. Wow.
Seorang teman yang lain (iya, saya punya banyak narasumber) juga tidak tinggal di perantauan. Ia hanya tinggal berdua dengan ibunya dan sering sekali mengeluh karena dilarang bermain sampai malam. Selepas kerja, ia harus kembali ke rumah dengan segera. Alasannya: “Buat apa perempuan keluar malam-malam? Pamali!”
“Kalau aku nggak ikut nongkrong,” keluh teman saya, “gimana bisa aku kenal sama teman-temanku selain dari kantor?”
Saya cuma manggut-manggut mendengar keluhannya. Saya nggak punya saran lain selain “Komunikasiin lagi aja” karena saya pun mengalami hal serupa.
Saya masih merasa bahwa perempuan yang suka pulang malam adalah sesuatu yang tidak bakal diterima oleh lingkungan keluarga saya, tapi kini saya melihatnya dari sisi yang berbeda: bahwa dengan beberapa alasan tertentu , seorang perempuan—termasuk saya—memang wajar-wajar saja pulang malam, sebenarnya.
Belakangan, saya suka sekali menyepi di sebuah working space 24 jam di dekat kosan. Kadang, saya baru pulang tengah malam—kadang-kadang lebih cepat kalau tiba-tiba bapak saya telepon dan menyuruh saya pulang. Apakah rasanya mengerikan menjadi perempuan yang suka pulang malam?
Pulang malam hari—atau tengah malam, atau dini hari—bagi saya selalu terasa mengerikan, tapi sekaligus normal tanpa ada bedanya dengan siang hari. Jalanan lebih sepi dan itu bagus karena saya tidak perlu terjebak macet. Yang saya perlukan hanyalah jaket untuk melindungi diri dari udara yang terasa lebih dingin dan kewaspadaan yang lebih tinggi.
Rasanya memang sedikit aneh—kalau perlu saya tambahkan—karena selama bertahun-tahun saya telah terbiasa pulang cepat dan merasa takut dimarahi. Tapi nyatanya, saya toh tidak sedang membuang-buang waktu: saya mengerjakan kerjaan saya di working space tadi, atau menghibur diri saya di konser Stars and Rabbit.
Saya melakukannya demi diri saya sendiri.
Dan kadang-kadang, memikirkan apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri itu memang perlu, bahkan kalau kita jadi harus pulang malam.
Bahkan—ingat—kalau kita adalah perempuan.