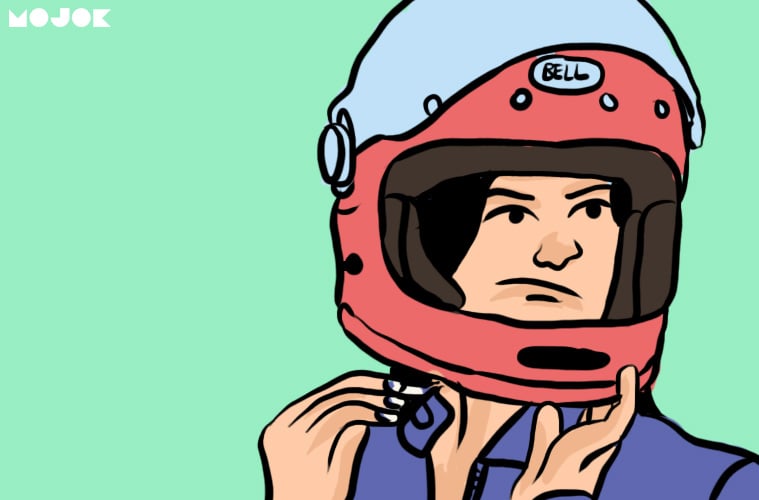Malam kemarin, di beranda Indomaret Point Jalan Kaliurang, saya sedang duduk santai sambil sekrol-sekrol temlen Twitter saat lelaki bermotor besar itu datang dan kemudian memarkirkan motornya. Prejengannya tampak sangat gagah. Lha gimana, motornya gedhe, helm-nya bak pembalap, jaketnya kulit sporty. Benar-benar mengingatkan saya pada sosok Boy dalam sinetron Anak Jalanan itu. Ingatan yang belakangan harus saya koreksi sebab setelah helm-nya dibuka, ternyata tampang si pengendara blas nggak ada persis-persisnya dengan Stefan William si pemeran Boy itu.
Lelaki itu kemudian masuk ke Indomaret dengan menenteng helm-nya. Ya, helm-nya tidak ia taruh di motor, tapi ia bawa masuk ke Indomaret. Untung helm-nya ditenteng, bukan dipakai, sehingga saya tak punya kesempatan untuk membatin “Masuk Indomaret kok masih pakai helm, memangnya kasir Indomaret-nya nyambil jadi polantas po?”
Lelaki itu tampak sangat kerepotan. Sudahlah memanggul tas, masih pula menentang helm.
Apa yang ia lakukan saya pikir memang beralasan. Helm yang ia pakai tampak betul adalah helm mahal. Helm full face yang bukan sekadar full face. Helm yang dari tampilannya saja bisa ditaksir bahwa harganya pasti lebih dari satu juta rupiah.
Pemandangan sekelebat itu kemudian membuat saya sedikit berpikir. Betapa kadang barang mahal itu bukan hanya memunculkan kepuasan dan kebanggaan, namun juga kekhawatiran.
Saya hakul yakin, si Boy yang sangat tidak Boy itu pasti menenteng helm-nya karena takut helm-nya bakal digasak maling kalau ia taruh di atas motor atau digantungkan di spion motornya.
Membawa helm masuk Indomaret mungkin masih terlalu biasa. Namun pikiran saya menerawang lebih jauh. Saya membayangkan, bagaimana jika suatu saat ia harus menonton film di bioskop di dalam mall? Atau menonton pertandingan sepakbola di stadion? Atau menonton konser di GOR dan lapangan kampung? Apakah ia masih akan tetap menenteng helm-nya, maka semakin terbayang betapa repotnya dirinya.
Kalau ternyata ia meletakkan helm-nya di atas motor dan meninggalkannya di parkiran, saya menebak, betapa dirinya bakal dipenuhi dengan perasaan khawatir sebab helm-nya yang mahal itu berpotensi bakal digasak maling.
Mahal memang kerap sejalan dengan kemewahan. Dan kita semua paham, bahwa semakin mewah, semakin ia membuat gelisah. Itu berlaku sepaket.
Konsep tersebut tentu saja tidak hanya berlaku pada helm, melainkan juga berlaku untuk barang-barang lain. Bisa sepatu, tas, laptop, atau sejenisnya.
Saya beberapa kali mengalami kegelisahan tersebut. Di kafelangganan saya, tempat saya biasa menulis, saya hampir selalu khawatir kalau laptop saya bakal diambil orang saat saya tinggal ke toilet atau salat di musala kafe. Lebih berabe lagi sebab kalau saya ke toilet, utamanya kalau berak, saya sering lama, yang mana tentu saja membuat saya semakin tidak tenang.
Salat saya pun begitu, kerap tak jenak dan khusyuk sebab selalu terpikir akan laptop saya yang saya tinggal di meja.
Seiring berjalannya waktu, saya mulai sadar, bahwa kekhawatiran saya tersebut seringnya hanyalah kekhawatiran semu belaka. Toh, sudah hampir dua tahun ini saya nongkrong di kafe tersebut dan belum pernah sekali pun saya kehilangan laptop. Agaknya saya memang berpikir terlalu paranoid.
Pada titik tertentu, kesadaran saya soal kekhawatiran ini kemudian menemukan kuncinya: Ikhlas.
Saya pernah sama sekali tidak merasa khawatir laptop saya diambil orang. Gara-garanya simpel, saya mencoba untuk santai dan menyiapkan diri kalau memang laptop itu hilang.
“Halah, cuma laptop doang, kalau hilang ya nanti kerja lagi, beli lagi,” batin saya waktu itu. Dan ajaib, perasaan semacam rela kehilangan itu benar-benar ampuh membuat saya tenang. Saya jadi bisa leluasa berak lebih lama dan salat lebih tenang. Saat berak, saya jadi bisa lebih menikmati dan meresapi setiap feses yang keluar. Saat salat, saya jadi lebih tenang saat membaca Al-Fatihah. Sedaaaap.
Sikap tersebut tentu saja terbangun melalui kontemplasi yang panjang (Hahaha). Tidak semua orang serta-merta punya sifat kerelaan sedemikian rupa. Ibu saya salah satunya.
Sudah setahun lebih saya meletakkan sepatu saya di teras rumah tiap kali saya pulang. Ibu saya tak pernah peduli dengan sepatu saya. Sampai suatu ketika, saya bercerita tentang sepatu tersebut. Bahwa sepatu tersebut adalah oleh-oleh dari Kalis saat ia bervakansi ke Jepang. Saya ceritakan pada ibu saya bahwa sepatu itu harganya satu setengah juta rupiah.
Begitu tahu kalau harga sepatu tersebut satu setengah juta, maka mulai malam itu pula, ibu saya selalu memindahkan sepatu saya ke dalam rumah.
“Lha kok dipindahkan, Mak?”
“Lha katamu harganya satu setengah juta, nanti kalau diambil maling gimana?”
“Lha kemarin-kemarin kenapa nggak dipindahin?”
“Kan kemarin Makmu nggak tahu kalau harga sepatu itu satu setengah juta, jadi ya Emak tenang-tenang saja. Karena sekarang Emakmu ini sudah tahu kalau sepatumu mahal, ya Emak pindahin ke dalam, biar nggak dimaling.”
Saya tertawa mendengar jawaban Ibu saya. Maklum, saya yakin, tidak ada maling yang percaya kalau sepatu itu harganya sejuta, sebab ia diletakkan di teras rumah saya yang kecil dan tampak kumuh itu.
Sembari melihat ibu saya memasukkan sepatu saya ke dalam rumah, saya mengatakan sesuatu pada Ibu saya, tentu saja saya mengatakannya di dalam hati: “Kuncinya ikhlas, Mak. Ikhlas.”