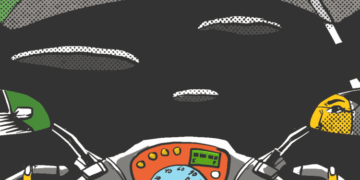MOJOK.CO – Ada kenangan tersendiri ketika melintasi Pantura dari atas roda-roda lusuh bus Sinar Mandiri. Serasa naik kapal membelah ombak jalanan rusak.
Tahun 2006, Terminal Tuban.
Azan Magrib berkumandang. Perasaan hendak melintasi Pantura mulai membuncah.
Terminal Tuban sudah lengang selayaknya pemakaman. Pencahayaan yang temaram membuat suasana semakin suram. Tampak bus-bus tiga perempat yang kebanyakan Puspa Indah terparkir perpal berurutan menanti keberangkatan esok hari.
Bus Puspa Indah yang saya tumpangi merupakan bus terakhir yang berangkat dari Jombang menuju Tuban di hari itu. Selanjutnya, dari Terminal Tuban, saya akan melanjutkan perjalanan menuju Demak, Jawa Tengah. Menumpang bus apa saja yang menuju ke arah barat, jurusan Semarang, bahkan Jakarta tidak jadi masalah. Asalkan ngetem dan berhenti di Terminal Tuban. Bus yang sudah pasti melewati trayek itu adalah Sinar Mandiri, Indonesia, Jaya Utama, Restu, dan yang jurusan Jakarta ada Harapan Kita.
Jujur saja, saya agak pemilih perihal naik bus. Apalagi di masa-masa itu, saya semacam punya feeling, “Bus ini mantep, nih.”
Mantap dalam kepala saya adalah, pertama, belum pernah saya tumpangi. Kedua, bus ini kayaknya enak. Ketiga, bus ini kayaknya kencang banget.
Namun, bus jurusan arah barat, terutama jurusan Surabaya-Semarang, interval jarak dan waktunya lumayan berjauhan dan lama. Jika saya melewatkan satu bus yang ngetem hanya karena menuruti feeling dan sikap pemilih tadi, justru bikin saya mengeluarkan ongkos nongkrong dan jajan yang lebih banyak.
Meskipun, jujur saja, saya juga senang nongkrong di pinggir terminal hanya sekadar menonton kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bus yang balapan beradu skill dan kecepatan. Namun, nongkrong seperti itu juga butuh beberapa gelas es teh dan camilan. Artinya, saya perlu mengeluarkan uang lebih untuk itu.
Saya memang tidak begitu ingin bus yang akan saya tumpangi segera tiba, apalagi yang biasa melintasi Pantura. Saya suka berlama-lama di terminal. Di warung sederhana, di seberang terminal, sebelah barat terminal persisnya, tempat di mana bus dari timur (Surabaya), ngetem menunggu penumpang, di situlah saya beristirahat sekaligus makan malam. Bus-bus yang melintas tidak ada yang mau masuk terminal. Semacam sudah menjadi kebiasaan, kalau terminal sudah sepi, bus-bus AKAP lebih senang ngetem di luar terminal.
Warung sederhana namun menyediakan menu istimewa. Berbagai olahan makanan hasil laut seperti ikan, udang, cumi-cumi, digelar dengan baskom seng bercorak belang-belang dan bakul sudah tertata rapi dan cantik di atas dipan bambu. Semua tampak begitu menggelitik selera.
Pengunjung yang datang untuk makan, duduk dengan posisi setengah jongkok, sejajar, dan sama tinggi. Saya memesan nasi dengan lauk beberapa ekor udang goreng, sepotong ikan goreng, dengan sambal terasi yang pedasnya membuat tumbuh ketombe di kepala. Bikin gatal. Yang sudah pasti tidak akan saya lupakan, tentu saja segelas es teh Pantura yang memiliki racikan segar sempurna.
Selesai makan, perut kenyang, es teh tersisa setengah gelas. Sebentuk bus warna abu-abu lusuh dan kumuh, dengan sentuhan garis biru bergradasi hijau, dengan logo Batman Hino persis di tengah tampak dari kejauhan. Di bagian atas kaca bus, tertempel stiker bertuliskan Surabaya – Kudus – Semarang, dan di bawahnya bertulis Bungurasih. Sementara badan samping bus berkelir sama, bertuliskan Sinar Mandiri berukuran besar dengan dwi warna merah dan kuning.
Bagian jendela dibagi menjadi dua sekat atas dan bawah, dengan perbandingan 20:80. Bagian bawah berupa kaca tempered glass permanen, sementara bagian atas kaca yang bisa digeser ke depan dan belakang, dan hanya ditutup saat hujan. Ketika dibuka, jendela bagian atas merupakan lubang ventilasi tempat sirkulasi udara masuk dan keluar. Udara yang bercampur debu, asap, serta aroma laut sepanjang jalan pantai utara.
Kru bus Sinar Mandiri itu turun, memesan kopi, dan makan. Mereka makan dengan lahap, cenderung terburu-buru. Mereka dikejar waktu. Dikejar bus yang berada di belakang mereka. Selesai makan, mereka menyalakan rokok dan menghisapnya dalam-dalam.
Tidak sampai 30 menit, mereka bertiga, sopir, kernet, dan kondektur saling berpandangan.
“Wis, budal?” Tanya sopir.
“Ayo!” Jawab si Kernet.
Kondektur hanya mengangguk sembari menenggak kopi yang tersisa seperempat cangkir. Semua penumpang kemudian naik bersamaan.
Di saat bersamaan, saya memesan beberapa potong ikan goreng untuk diganyang di dalam bus saat perjalanan. Tidak ketinggalan sebotol air mineral untuk menghidrasi tubuh selama perjalanan panjang Tuban menuju Demak.
Saya naik bus Sinar Mandiri melalui pintu belakang. Daun pintu bus masih menggunakan model lama. Daun pintu model lipat baik pintu depan maupun pintu sisi belakang. Pintu seperti ini memudahkan dan mempercepat penumpang naik dan turun dengan rumus naik kaki kanan, turun kaki kiri, dan badan hadap ke depan.
Pada bus-bus jaman dulu masih bisa ditemui peringatan besar yang kalau dibaca serasa bernada tinggi:
“DILARANG MENGELUARKAN ANGGOTA BADAN”, “TURUN KAKI KIRI”.
Kemudian masih dipertegas (baca: diteriaki) kernet saat akan menurunkan penumpang:
“HADAP DEPAN, KAKI KIRI DULU” dengan kondisi bus yang masih setengah berjalan.
Saat kaki penumpang menginjakkan tanah, sopir akan langsung menginjak gas dan memaksa penumpang untuk setengah berlari. Bus pun ngacir. Menjadi penumpang bus pada masa itu memang harus punya skill responsif, dan sudah pasti sehat lahir dan batin.
Belum ada hal istimewa yang saya temui dari bus ekonomi Sinar Mandiri yang saya tumpangi ini. Semua tampak sederhana. Tidak ada bagasi kabin yang berada di bagian atas plafon bus. Penumpang harus mengamankan barang bawaannya masing-masing.
Bagian tengah langit-langit bus Sinar Mandiri terdapat tiga buah lampu neon putih redup yang hanya cukup untuk mata melihat lorong bus, kursi, juga wujud manusia. Yang paling penting cukup untuk melihat huruf dan angka bagi kondektur mencoret dan menulis angka pada bundelan karcis yang dia bawa. Namun tak cukup mengganggu penumpang yang ingin tidur selama perjalanan.
Sementara di sisi tepi plafon ada enam buah speaker yang diam membisu. Memang, bus tanpa bagasi kabin lebih minim getaran. Apalagi bagi penumpang yang telinganya risih mendengar suara getaran seperti getaran bagasi.
Jok bus Sinar Mandiri ini terbuat dari busa yang lumayan keras, dibalut kulit sintetis yang agak licin berwarna abu-abu gelap. Meski sedikit keras, namun posisi jok tetap bisa menopang bentuk punggung untuk berada pada posisi yang nyaman. Jarak dengkul dengan bangku depan juga masih lega, tidak akan membuat dengkulmu yang kopong itu jadi lecet apalagi sampai retak.
Sedangkan bagian lantai bus ini terbuat dari board desk stainless yang warnanya sudah mulai pudar, mulai berubah cokelat, sebagian sudah jadi cokelat gelap. Lantai seperti ini cocok untuk bus yang lebih banyak berisi penumpang meteran. Sebab tidak gampang membuat penumpang kehilangan cengkeraman saat menapakkan kaki dan melangkah dalam keadaan bus melaju. Kencang tentu saja.
Tempat duduk favorit saya di dalam bus ekonomi Sinar Mandiri macam ini adalah bagian tengah sisi kanan. Ada dua hal yang menjadi alasan saya memilih posisi ini.
Pertama, bagian tengah bus merupakan bagian yang minim guncangan sehingga lebih nyaman dibanding sisi yang lain. Apalagi, ini lewat jalur Pantura. Sepanjang perjalanan serasa berada di atas gelombang, melalui jalanan penuh gronjalan.
Kedua, bus ini berformasi bangku kiri dua kanan tiga. Sisi kanan lebih nyaman saat bus tidak begitu penuh, apalagi mendapat bangku isi tiga yang kosong. Bisa duduk selonjoran, dengan punggung bersandar pada dinding bus, kepala ditaruh di sandaran kursi. Sebuah posisi yang nikmat untuk tidur sambil melaju di jalur Pantura yang penuh gelombang dan gronjalan.
Bus mulai bergerak perlahan, semakin kencang, seiring pedal gas yang mulai diinjak dalam-dalam. Saya sudah mendapatkan tempat duduk sesuai harapan.
Duduk di bangku sisi kanan dekat jendela, memandang laut Pantura yang sudah gelap. Di kejauhan tampak kerlap-kerlip lampu nelayan berjejer melengkapi garis laut yang pekat.
Aroma laut masuk dari jendela sisi atas yang terbuka seperempat. Angin dingin bercampur debu serta sisa-sisa panas asap yang keluar dari knalpot truk, bus, dan kendaraan lain, juga asap rokok penumpang berputar-putar di dalam bus dan keluar lewat mana saja yang ia suka; jendela sisi lain, dan pintu belakang bus.
Bus mulai meninggalkan Tuban. Melewati jalan aspal Pantura yang penuh dengan tambalan tidak rata. Ditambah jalan bergelombang yang disebabkan truk-truk bermuatan berlebihan, atau bisa saja karena pembangunan jalan yang kualitasnya sudah dipenggal.
Kondektur mulai menagih ongkos karcis kepada saya dan beberapa penumpang lain yang bersamaan naik dari Tuban.
“Mau turun mana?”
“Demak.”
Saya menyodorkan uang lima puluh ribuan. Beliau mencoret karcis yang bertuliskan “Halte” dari dan ke mana saya akan turun. Sret, sret, begitu bunyinya.
“Kembaliannya nanti, ya,” kata kondektur dengan ramah dalam Bahasa Jawa, sambil menulis angka di balik karcis sebagai catatan berapa uang kembalian yang harus saya terima.
Di situ tertulis angka Rp38.000. Saya sedikit bingung. Kok murah? Masa cuma Rp11 ribu tarif Tuban-Demak. Seingat saya, tarif Tuban-Demak adalah Rp22 ribu. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu hanya saya ucapkan di kepala saja. Saya lipat dan saya taruh karcis di dalam tas.
Sinar Mandiri bermesin Hino AK ini mulai mosak-masik di jalur yang mulai ada belokan setelah meninggalkan Tuban. Ia mendahului truk-truk gandeng, truk trailer, dan, truk bermuatan kayu gelondongan dari sisi kanan.
Bus meliuk ke kiri, lalu ke kanan dengan cepat untuk mengambil space menghindari kres di depan. Sopir kembali menginjak gas lebih dalam hingga menemukan torsi yang pas lalu mengoper gigi untuk menambah kecepatan, mendahului truk-truk di sebelah kirinya.
Lampu dim selalu berkedip sebagai pertanda bus yang saya tumpangi meminta jalan dan ruang untuk mendahului. Mendahului dengan kecepatan tinggi melalui jalan bergelombang dan sempit di Pantura bukan perkara mudah. Butuh pengalaman, keahlian, nyali, serta jam mengaspal yang tinggi.
Kernet melakukan escorting, dengan kondisi pintu terbuka. Seperti yang sudah saya ceritakan di atas, bus Sinar Mandiri ini menggunakan pintu lipat. Pintu selalu dalam keadaan terbuka.
Kernet hanya berpegangan pada pintu lipat dan gantungan yang terbuat dari tali tambang yang diikat pada pengait di dinding bus. Bagian tali yang dijadikan genggaman berbentuk lingkaran dilapisi spons dan digulung dengan kain agar menyerap keringat dan keset saat digenggam.
Saat melakukan pengawalan memantau kondisi “lawan”, kernet akan bergelantungan seperti monyet. Ngeri? Tentu saja.
Dibutuhkan keberanian untuk menaklukkan kepadatan lalu lintas di jalur Pantura yang penuh dengan kendaraan besar, ketidaktahuan, dan ketidakberpengalamannya pengendara lain. Penumpang hanya tahu beres. Duduk nyaman, tidur, dan sampai tujuan dengan selamat.
Perjalanan yang melintas sepanjang pesisir pantai di Tuban, hingga masuk Rembang di Jawa Tengah tidak pernah ada kata mulus dan pelan. Sinar Mandiri tetap melaju kencang menerjang jalan bergelombang.
Ketika melintasi jalur Pantura pada siang hari, saya sedikit menenggelamkan posisi duduk. Sejauh mata saya bisa memandang, hanya terlihat air laut berwarna biru. Sudah serasa naik kapal cepat yang sedang menerjang ombak. Hanya kurang suara benturan kapal yang membelah ombak. Saya kerap melakukan itu jika naik bus dari arah barat ke timur (Demak menuju Tuban). Berkhayal seolah-olah sedang berada di kapal cepat.
Ketika melintasi jalur Pantura, ada aroma sangat khas yang bisa diperkirakan kita sampai di wilayah mana. Iya, Rembang!
Sisi timur kabupaten Rembang, di sepanjang kiri dan kanan jalan, terdiri dari tambak garam. Aroma lautnya begitu asin terasa. Tidak terasa bus ini sudah masuk Jawa Tengah. Menghirup aroma garam seperti itu, tiba-tiba membuat saya mengantuk, dan meringkuk di bangku yang seharusnya untuk tiga orang.
Beberapa sata kemudian, saat terbangun. Saya melihat dari jendela, mencari informasi berupa baliho toko, Bank BRI, atau apa saja yang memberikan petunjuk sudah sampai kota mana.
Oh, bus sudah masuk kota Juwana.
Bangun tidur, perasaan ingin mengunyah tiba-tiba muncul. Saya mengganyang beberapa potong ikan goreng yang tadi saya beli di warung seberang Terminal Tuban. Setelah habis dan kenyang, saya kembali tidur.
Bangun tidur di babak kedua, tiba-tiba saja saya sudah sampai di Gajah, Demak. Saya perlu mengumpulkan nyawa agar tetap terjaga sampai turun.
Tiba-tiba dari arah belakang, kondektur mendatangi saya. Mengembalikan uang sebesar Rp38.000, meminta karcis untuk dicoret bagian belakangnya, bukti bahwa kembalian sudah dilunasi. Karcis diserahkan kembali kepada saya. Saya masih berpikir kenapa tarifnya cuma Rp11 ribu?
Sampai di penghujung jalan lingkar Demak meninggalkan jalur Pantura, dini hari, saya turun. Kemudian saya jalan kaki menuju Masjid Agung Demak untuk beristirahat di sana hingga subuh. Setelah subuh, melanjutkan perjalanan naik angkutan menuju kampung Bu Lik saya.
Badan saya mulai terasa lengket oleh keringat yang semakin deras karena jalan kaki. Saya menurunkan restleting jaket yang saya gunakan. Kemudian saya sadar kenapa karcis busnya murah.
Ternyata saya melintasi Pantura sambil masih memakai seragam sekolah!
BACA JUGA Pandangan Baru Dunia setelah 202 Jam Naik Bus Lintas Sumatra-Jawa dan kisah menarik lainnya di rubrik OTOMOJOK.
Penulis: M. Mujib
Editor: Yamadipati Seno