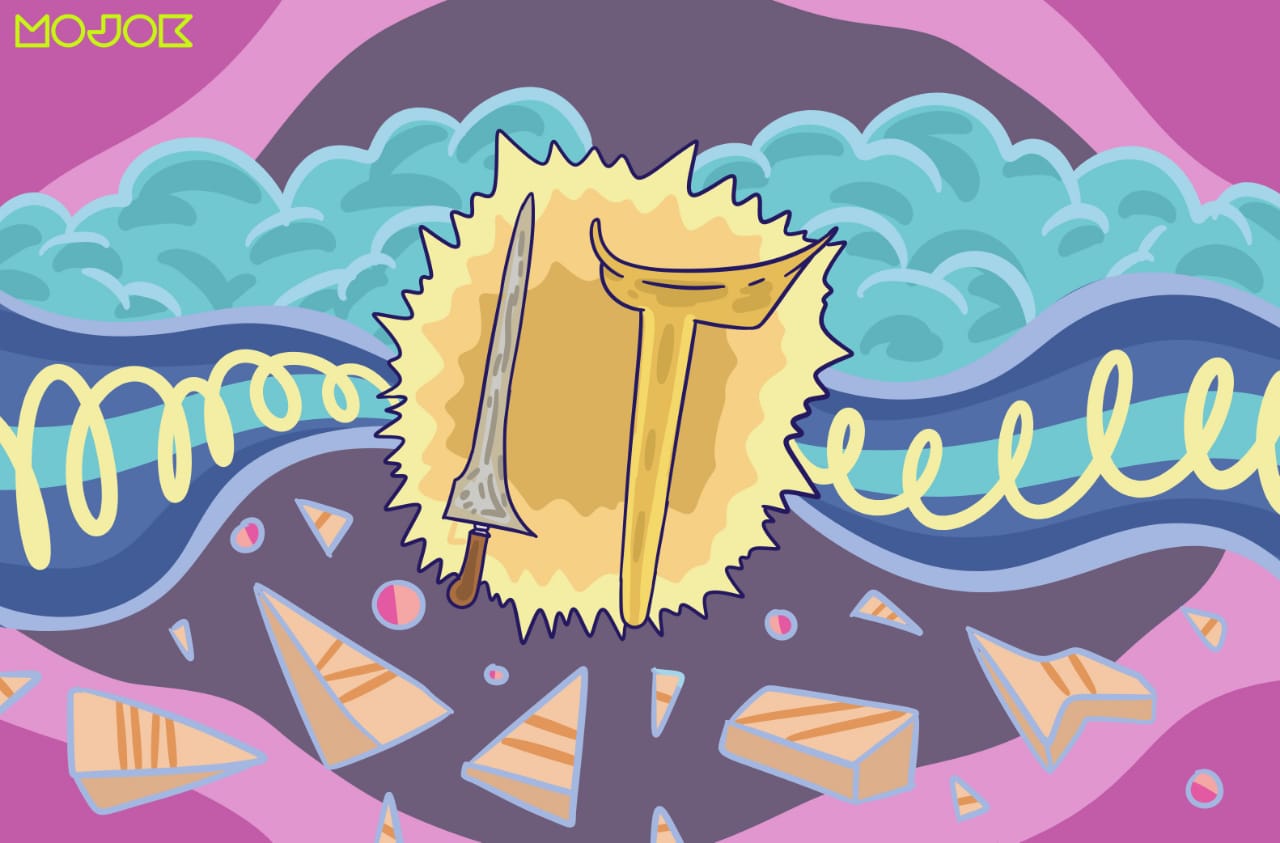Di awal peralihan kekuasan Ngayogyakarta, Sultan Hamengku Buwana Kaping IX—bukan Bawana—tidak pernah secara terbuka memasrahkan keris Ki Ageng Joko Piturun ke Sultan Hamengku Bawana Kaping X (sedasa atau sepuluh?)—yang kata para abdi dalem, sedikit menyalahi kebiasaan paugeran sebelumnya. Kita tahu, prosesi pewarisan keris Ki Ageng Joko Piturun ini biasanya merupakan simbol resmi penyerahan kekuasaan kepada raja baru yang segera bertahta.
27 Mei 2006 gempa bumi mengguncang Yogyakarta, juga keraton. Bangsal Prabayeksa, ruang pusaka itu jungkruk. Trajumas, simbol jejeba penegakan “keadilan” rontok. Mbah Marijan, saat Merapi njebluk di tahun 2010, “mbalela” untuk turun gunung. Ia, katanya, hanya “sendika dawuh” dengan Sultan kaping IX.
Para Sentana dan Abdi Dalem mengeluh. Sejak dikeluarkan Sabda Tama, para Abdi Dalem banyak yang undur diri. Jauh sebelum itu beberapa Empu mengaku tak lagi diakui oleh keraton. Bahkan ada Empu yang memutuskan pindah ke Keraton Solo. Selain itu, saya juga lamat-lamat pernah mendengar bahwa ada seorang pujangga keraton bernama Suryanto Suryatmaja yang terpaksa harus hijrah ke Solo di era Pakubuwana 12.
Ontran-ontran ini tak berhenti di sini. Ringin alun-alun kidul kobong tahun lalu. Keterampilan nembang macapatan dan sekar ageng mulai diabaikan dan macet secara regenerasi. Ada beberapa teman yang sinau macapatan di Keraton mengakui hal ini.
Kondisi “geger” ini diperparah dan memuncak sejak santernya isu penetapan Keistimewaan Yogyakarta. Sungguh, gelontoran dana setelah penetapan Keistimewaan Jogja dari Jakarta benar-benar tidak hanya memecah sedaya kawula alit Ngayogyakarta, melainkan juga membuyarkan darma “hangabekti” dan ketulusan para Abdi Dalem yang telah diwarisi berabad-abad dari leluhur mereka.
Saya tanya, apakah Anda pernah merasakan pujaan hati Anda “berpaling” dari Anda dengan alasan memilih orang lain karena alasan materi dan kemapanan? Ah… Sudahlah, ndak perlu saya lanjutkan.
Sebenarnya saya tidak terlalu weruh babakan geger Sabda Tama dan Sabda Raja. Saya hanya tahu bahwa sekarang Pembayun sudah bergelar Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Itu pangkat sekelas Ywaraja atau Pangeran Pati, dan seorang yg bergelar Mangkubumi atau sekelas Pangeran Pati tidak mungkin tidak diangkat Sultan(ah). Sebuah tahap yang mungkin tidak bisa dicegah lagi.
Namun, saya juga tahu, meskipun penghilangan gelar khalifatullah dianggap bisa sedikit memantaskan melenggangnya Pembayun untuk Jumeneng Nata, saya sangat ragu apakah seorang perempuan pantas menerima keris, apalagi kerisnya bernama Kyai Ageng Kopek dan Kyai Ageng Joko Piturun. Tidakkah ia lebih pas menerima wedung ataupun patrem—semacam belati? Atau jangan-jangan, penyempurnaan keris Ki Ageng Kopek seperti tertera dalam Sabda Raja—menurut tafsir ngawur saya—merupakan sanepa dari kata “Mengko Pek’en” (baca: Nanti ambillah) seperti yang diujarkan Prabu Darma Kusuma sang Raja Amarta kepada Sunan Kalijaga sebagai ungkapan terima kasihnya karena dibantu membaca Jamus Kalimasada yang telah lama membuatnya tak bisa mati. Maksudnya, ya kekuasan ini “Mengko Pek’en, Nduk, Anakku.”
Para kawula alit, termasuk saya, selalu membayangkan bahwa satu-satunya raja di Indonesia yang masih jumeneng, bisa menjadi raja yang gung binathara. Seorang raja besar yang mewarisi kemulyaan sifat-sifat Bathara Dewa. Ya, seorang Raja yang selalu aweh tongkat untuk orang-orang yang mudah terpeleset, mendermakan boga/makanan kepada mereka yang kelaparan, dan menyediakan air bagi rakyat yang kehausan—alias selalu wening penggalih, rasa, pikirannya untuk tak sebatas mementingkan keluarganya, melainkan sumrambah kepada rakyat Ngayogyakarta pada umumnya.
Saya sebatas rasan-rasan, jangan sampai harapan-harapan kawula alit akan rajanya justru malah luput dari kudangan dan mrucut dari embanan. Mungkin itu, dugaan saya, makna Manunggaling Kawula Gusti seperti yang disiratkan dalam konsep khalifatullah.
Lalu?
Saya jadi ingat Suwargi Prof. Damardjati Supajar akan sanepanya, bahwa pada suatu hari nanti mata para kawula alit Ngayogyakarta berubah menjadi sebesar kenong, alias mata terbelalak membesar karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi, sekali lagi, ontran-ontran apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu. Yang jelas, mata saya sekarang terbelalak. Anda?