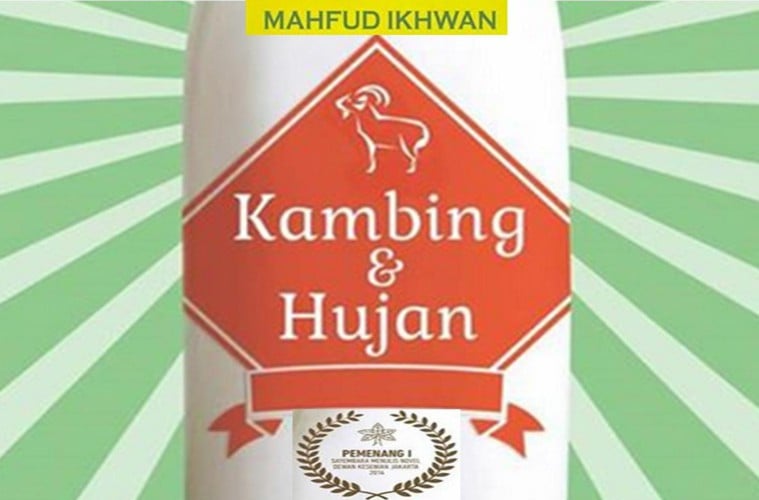Ia termasuk orang pertama yang saya kenal di sebuah padepokan, sebuah rumah kumuh di bilangan Bulaksumur, tempat sejumlah anak muda angkuh dan aneh dari berbagai fakultas di Universitas Gajah Mada biasa berkumpul untuk sekadar bertukar mimpi dan omong kosong, pada masa itu.
Ada sejumlah hal yang mempertemukan kami berdua. Dua di antaranya adalah dangdut dan film India. Bedanya, ia memiliki intensi berlipat-lipat lebih besar terhadap dua hal itu. Jika saya hanya menikmati dangdut secara sambil lalu, tak benar-benar intens, maka lelaki mungil itu selalu membicarakan dangdut dengan penuh berahi. Jika saya sekadar menyukai Sanjay Dutt dan Mithun Chakraborty, maka dia bisa mengupas film India hingga sisik-meliknya yang tak pernah saya pikirkan.
Anda pernah membaca blognya, Dushman Duniya Ka? Bacalah. Saat ini ia mungkin satu-satunya orang Indonesia yang bisa disebut sebagai “ensiklopedia berjalan film-film India”. Dan ia adalah pengamat yang tangguh.
Ya, lelaki itu tak lain adalah Mahfud Ikhwan. Waktu itu ia masih mahasiswa Sastra Indonesia. Ketika kami berkenalan, belasan tahun silam, Mahfud sudah menulis banyak cerpen. Cerpen-cerpennya telah dimuat di sejumlah media, baik yang terbit di daerah maupun ibukota. Saya masih ingat pada sebuah petang, di halaman belakang rumah itu, ia menyodori saya sebuah majalah.
“Baca, Tar, cerpenku dimuat,” ujarnya. Senyumnya mengembang.
“Lho, kamu nulis di majalah ini juga?” tanya saya, sembari mengamati majalah yang disodorkannya.
“Kenapa?! Kamu juga baca majalah ini?”
“Lho, lha iya. Waktu SMA saya rutin membelikan majalah ini untuk pacar saya. Dan sebelum saya kasihkan, mesti saya baca dulu, biar nggak rugi,” ujar saya.
“Ah, pendekatanmu konvensional, memikat gadis berjilbab dengan Majalah ANNIDA,” ledeknya.
“Lho, bukan hanya ANNIDA. Saya juga selalu membelikannya Majalah UMMI,” tukas saya, tanpa rasa malu, atau bersalah.
Ia tertawa mendengarnya.
Ya, majalah yang disodorkannya petang itu adalah Majalah ANNIDA, yang dulu diasuh oleh Helvy Tiana Rosa. Saya lupa judul cerpennya, tapi masih ingat ia menggunakan nama pena “Lee Ma Hwan”.
Saya tak pernah menyangka jika persahabatan kami akan berumur panjang. Meski memiliki sejumlah kesamaan, sebetulnya ada banyak perbedaan antara saya dengannya. Dalam banyak hal, Mahfud adalah seorang oposan yang kejam. Saya menyebutnya sebagai seorang yang “terlalu skeptis”, pada saat yang bersamaan dia menyebut saya “terlalu optimis”. Ya, dia selalu mengambil sikap skeptis terhadap banyak hal. Bahkan mungkin terhadap apapun. Dan itu berlaku untuk siapapun.
Tapi karena sikapnya itu saya justru merasa membutuhkannya. Skeptisisme Mahfud adalah sebentuk tantangan. Percayalah, tak ada hal matang yang pernah kamu miliki jika gagal menghadapi skeptisisme seseorang seperti Mahfud. Bagi saya, dia adalah seorang “tester”. Karena ikatan aneh itulah persahabatan kami terus memanjang.
Sejak awal berkenalan dan mengikuti perkembangannya, saya memiliki keyakinan bahwa Mahfud akan menjadi salah satu sastrawan terkemuka dari generasi saya. Dia bukan hanya bisa menulis sastra, tapi juga menguasai literatur kesusastraan. Dan bacaannya memang sangat luas. Jangan lupa, tak setiap mereka yang bisa menggambar bisa disebut pelukis, dan tak setiap mereka yang bisa menulis bisa disebut pengarang. Dalam lima belas atau dua puluh tahun terakhir, memang ada banyak orang telah menulis karya sastra. Tapi, hanya beberapa saja dari mereka yang kini atau kelak akan dikenangkan sebagai “sastrawan”. Dan menurut saya, Mahfud Ikhwan akan menjadi salah satunya.
Novel pertamanya, “Ulid” (2009), yang diapresiasi bagus oleh kritikus sastra kenamaan, Katrin Bandel, ditulisnya tak kurang dari lima tahun. Tentu saja, lamanya proses penulisan sebuah karya tak otomatis menunjukkan karya itu telah digarap dengan serius, atau hasilnya pasti bagus. Namun, lamanya penggarapan “Ulid” menunjukkan bahwa Mahfud tidak instan dalam menuliskan karya. Ia bukan tipikal “sastrawan partikelir”, yang sekadar menulis karya sastra atau kritik sastra untuk menyambung hidup. Saya tahu persis, Mahfud menulis sastra untuk menghidupi berahinya pada sastra. Sementara untuk hidup, dia menulis karya-karya lain, seperti biografi, buku pelajaran, menulis sepak bola, serta buku-buku komersial lainnya.
Sayang, novel pertamanya “dibunuh” oleh penerbitnya sendiri, sebuah penerbit besar di Yogya. Novel itu terbit ketika novel “Laskar Pelangi” sedang booming, sehingga oleh penerbitnya novel itu dikemas seolah epigon yang hendak mengais rezeki di belakang popularitas karya Andrea Hirata. Itu jelas sebuah keputusan yang salah. Sangat salah.
Saya ikut berdebat dengan editornya ketika desain tampilan novel itu hendak dieksekusi, karena kebetulan Mahfud, yang tak pernah mau belajar untuk naik sepeda motor itu, meminta saya untuk mengantarkan ke penerbitnya. Kami sampaikan, dengan kemasan yang dirancang penerbit, novel itu tak akan dilirik oleh para pembaca sastra serius yang seharusnya membaca karya itu, dan sebaliknya, juga tak akan sanggup menarik perhatian para pembaca populer yang disasar, karena isinya memang bukanlah fiksi populer. Sayang, meski sudah ngotot, penerbit kukuh pada keyakinannya.
Saya bisa menyaksikan kekecewaan Mahfud. Anak rohaninya, yang ditulisnya bertahun-tahun, sedang dipecundangi oleh penerbitnya sendiri. Tapi Mahfud tak putus asa. Ia segera menyiapkan karya berikutnya, sebuah novel berlatar keagamaan dengan setting 1965. Itu juga karya yang disiapkan menahun. Dia menyelesaikan novel kedua pada kuartal pertama 2013 silam, dan sebuah penerbit sastra ternama sudah memintanya untuk diterbitkan. Kini novel itu sedang antre cetak.
Sejak beberapa bulan yang lalu, Mahfud juga sudah mulai menuliskan novel ketiganya. Dia menuliskan draf novel itu dalam sebuah buku tulis tebal yang selalu dibawanya ke mana-mana. Sungguh klasik. Dalam sebuah kesempatan berbincang, dia sempat bercerita mengenai garis besar ceritanya. Saya yakin, itu akan menjadi sebuah novel yang menarik dan berbeda dengan dua novel yang sudah diselesaikannya.
Kemarin pagi saya mendapat kabar gembira bahwa novel keduanya, “Kambing dan Hujan”, yang akan diterbitkan oleh penerbit terkemuka tadi, memenangi hadiah sastra Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).
Ya, sejak lama saya sudah memiliki keyakinan bahwa Mahfud Ikhwan memang akan menjadi salah satu sastrawan terkemuka dari generasi saya. Dan penghargaan itu hanyalah sebuah awalan untuknya.
Selamat, Kawan. Jangan lupa janjimu untuk belajar dan beli sepeda motor dahulu sebelum beristeri tahun depan. Seorang lelaki yang tak becus menyetir motor, memang pantas diragukan kemampuannya untuk bisa menyetir isteri, ha ha ha.
Dan seorang lelaki yang tak punya motor, kisah asmaranya mudah disabot orang lain.