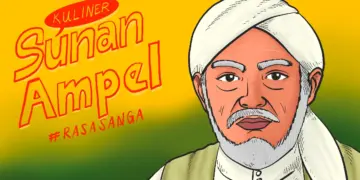Di salah satu adegan awal Ratu-Ratu Queens: The Series (2025), empat perempuan Indonesia: Party (Nirina Zubir), Chinta (Happy Salma), Ance (Tika Panggabean), dan Biyah (Asri Welas), berkumpul di dapur apartemen kecil mereka di Queens, New York.
Panci bergemerincing. Aroma tumis memenuhi udara. Tawa mereka pecah, menutupi dinginnya udara New York yang menyelinap lewat jendela.
Tak ada latar kemewahan. Tak ada gedung pencakar langit. Hanya empat ada perempuan yang berusaha membuat sesuatu yang hangat di tengah keterasingan.
Di ruang itulah “rumah” lahir. Bukan dari bata dan semen, tetapi dari kebersamaan yang mereka rajut di perantauan.
Serial terbaru Netflix garapan Lucky Kuswandi ini–prekuel dari film Ali & Ratu-Ratu Queens (2021)–menawarkan potret langka dalam sinema Indonesia: perempuan-perempuan kelas pekerja di luar negeri yang tidak digambarkan tragis, meski hidup dengan kegetiran (dan kelucuannya).
Dalam enam episode pendek, Kuswandi merangkai kisah kompleks soal isu diaspora, persahabatan, dan identitas. Namun, di balik kehangatan komedinya, serial ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam: siapa yang punya hak untuk merasa di rumah?
Homeplace, ruang domestik yang menjadi “panggung perlawanan”
Rumah, dalam serial ini, bukan sekadar bangunan fisik, tetapi ruang batin yang mereka perjuangkan. Queens digambarkan bukan sebagai kota impian, melainkan ruang liminal–ruang “antara” yang tidak sepenuhnya Amerika, tapi juga bukan Indonesia.
Di situlah mereka menanam akar baru, menciptakan versi mereka sendiri tentang kenyamanan dan kebersamaan. Kamera Kuswandi sering berlama-lama di dapur, ruang tamu, atau jendela kecil apartemen–ruang domestik yang dalam sinema arus utama sering diabaikan.

Bell Hooks dalam buku Feminist Theory: From Margin to Center (1984), memperkenalkan konsep homeplace sebagai ruang yang memungkinkan perempuan, khususnya perempuan kulit berwarna, membangun identitas dan melakukan perlawanan terhadap struktur patriarki yang menindas. Homeplace bukan sekadar rumah fisik. Melainkan ruang di mana perempuan dapat merasa aman, dihargai, dan memiliki kontrol atas lingkungan sosial mereka.
Hooks menekankan bahwa di dunia yang sering menyingkirkan suara perempuan, homeplace menjadi basis kekuatan, solidaritas, dan kreativitas. Ia adalah tempat di mana perempuan memulihkan diri dari tekanan eksternal.
Dalam konteks Ratu-Ratu Queens, apartemen kecil yang dihuni Party, Chinta, Ance, dan Biyah secara konseptual berfungsi sebagai homeplace. Dapur yang tampak sederhana, meja makan yang sempit, dan jendela yang menampilkan pemandangan kota yang dingin, bukan hanya latar fisik. Namun, ia adalah panggung di mana karakter membangun kehidupan bersama, saling menopang, dan mengukir identitas mereka di tengah keterasingan.
Dapur adalah arena menjaga identitas budaya
Dalam serial ini, dapur menjadi laboratorium kehidupan, di mana solidaritas dihasilkan melalui aktivitas sehari-hari yang tampak biasa. Memasak tumis, menanak nasi, atau menyiapkan teh bukan sekadar rutinitas domestik, melainkan ritual yang memperkuat ikatan emosional di antara para perempuan.
Hooks berargumen bahwa tindakan-tindakan ini–yang mungkin tampak sepele bagi pandangan luar–adalah bentuk perlawanan terhadap struktur sosial dan budaya yang menempatkan perempuan di pinggiran.
Dalam adegan di mana Party memotong bawang sambil bercanda dengan Chinta, misalnya, terlihat bagaimana mereka menggunakan ruang ini untuk menegaskan eksistensi, mengekspresikan emosi, dan menciptakan komunitas kecil yang aman.
Dapur menjadi arena di mana mereka bisa menyalurkan kreativitas, humor, dan kehangatan yang tidak mereka dapatkan di dunia luar.
Selain itu, kegiatan memasak dan berbagi makanan Indonesia juga dapat dibaca sebagai strategi resistensi terhadap kehilangan identitas budaya di tengah diaspora. Hooks menekankan bahwa homeplace memungkinkan perempuan untuk melawan isolasi sosial dan mengukir narasi mereka sendiri.
Dalam Ratu-Ratu Queens, Party, Chinta, Ance, dan Biyah menggunakan masakan sebagai simbol kontinuitas budaya, sekaligus cara mempertahankan diri dari arus globalisasi yang sering mengabaikan sejarah, bahasa, dan tradisi mereka. Dalam sendok sambal yang mereka aduk atau nasi yang mereka sajikan, terdapat perlawanan halus: penegasan bahwa mereka hadir, mereka berhak merasa di rumah, dan mereka menolak hilang di antara hiruk-pikuk negeri yang asing.
Ruang domestik yang tampak sederhana ini, menurut pandangan Hooks, menunjukkan bagaimana homeplace dapat menjadi sumber kekuatan, ketahanan, dan kreativitas bagi perempuan diaspora.
Ratu-Ratu Queens mengajarkan untuk merawat diri satu sama lain
Dari gagasan homeplace Bell Hooks, saya juga bisa merasakan bagaimana ruang domestik bukan hanya tempat perlindungan, tetapi juga arena di mana perempuan mengelola dan mengekspresikan emosi mereka. Dalam konteks Ratu-Ratu Queens, dapur dan ruang apartemen yang kecil tidak hanya menjadi panggung solidaritas, tetapi juga medium bagi para tokoh untuk menyalurkan lelah, cemas, rindu, dan kegembiraan yang mereka alami sebagai migran.
Di sinilah gagasan Sara Ahmed dalam The Cultural Politics of Emotion (2004) relevan. Menurutnya, emosi dan tubuh tidak dapat dipisahkan dari pengalaman sosial dan politik.

“Dengan kata lain, pengalaman emosional menjadi politik sehari-hari, di mana ketahanan, solidaritas, dan identitas perempuan diuji dan dikuatkan,” kata Sara Ahmed.
Dalam Ratu-Ratu Queens, banyak adegan menunjukkan bagaimana perempuan menanggung beban emotional labor yang sering tak terlihat. Party tersenyum saat video call dengan keluarga di Indonesia, meski jelas ia lelah dan rindu rumah, atau Chinta yang menahan kekesalan agar tidak mengganggu suasana bersama teman serumah.
Ahmed menekankan bahwa emosi yang tampak personal atau privat ini sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi yang lebih besar. Seperti diskriminasi, ketimpangan kerja, dan tekanan hidup di diaspora.
Dengan demikian, setiap senyum, tawa, atau pelukan menjadi bentuk negosiasi dan resistensi. Yakni, perempuan memilih bagaimana menampilkan diri mereka, mempertahankan hubungan dengan orang-orang terkasih, dan menegaskan hak mereka untuk “merasa di rumah” di dunia yang tidak selalu ramah.
Kamera Kuswandi menangkap tubuh dan gerak ini dengan intim: tangan yang menyiapkan teh, bahu yang bersandar satu sama lain, langkah ringan menari di dapur setelah hari panjang. Semua tindakan ini, meski sederhana, menjadi ekspresi kekuatan kolektif.
Sara Ahmed menekankan bahwa emosi kolektif ini bukan hanya reaksi pribadi, melainkan medium keterlibatan sosial yang membangun komunitas dan solidaritas. Dengan memperhatikan tubuh dan emosi, Ratu-Ratu Queens menunjukkan bahwa menjadi migran perempuan bukan hanya soal bekerja atau bertahan hidup, tetapi juga tentang bagaimana mereka merawat diri sendiri dan satu sama lain.
Konsep “diaspora space” dalam Ratu-Ratu Quuens
Serial ini juga menyoroti pertanyaan kepemilikan rumah dalam konteks budaya dan bahasa. Dalam Ratu-Ratu Queens, penggunaan bahasa campuran (Indonesia, Inggris, dan logat Betawi) menjadi indikator utama identitas hibrida para tokoh.
Stuart Hall, dalam esainya berjudul “Cultural Identity and Diaspora“, menekankan bahwa identitas diaspora tidak pernah statis. Ia selalu dalam proses negosiasi; dibentuk oleh pengalaman sejarah, budaya, dan interaksi sosial.
Dalam konteks Ratu-Ratu Quuens, kode bahasa yang berganti-ganti mencerminkan proses itu. Para tokoh menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, tetapi juga mempertahankan koneksi dengan akar budaya mereka. Identitas mereka terbentuk bukan dari satu budaya saja, tetapi dari interaksi berkelanjutan antara yang-lama dan yang-baru.
Sementara itu, Avtar Brah, dalam Cartographies of Diaspora (1996) menekankan pentingnya konsep “diaspora space”, yakni ruang sosial dan geografis di mana identitas diaspora terbentuk, dinegosiasikan, dan terus berkembang. Ruang ini tidak statis, melainkan bersifat “liminal” atau berada di antara budaya asal dan budaya baru.
Dalam konteks Ratu-Ratu Queens, apartemen kecil para tokoh di Queens, pasar lokal tempat mereka bekerja, atau komunitas Indonesia di kota besar bukan sekadar latar fisik. Semua itu merupakan diaspora space yang memungkinkan para tokoh merasakan keterhubungan, sekaligus menghadapi ketegangan budaya.
Mereka harus menyeimbangkan antara adaptasi terhadap norma dan kebiasaan baru, serta mempertahankan ikatan dan identitas budaya mereka sendiri. Ruang liminal ini membentuk karakter mereka, memaksa mereka bernegosiasi secara terus-menerus dengan dunia baru.

Selain itu, diaspora space juga menekankan interaksi sosial sebagai medium pembentukan identitas. Dalam serial ini, interaksi sehari-hari antara Party, Chinta, Ance, dan Biyah (mulai dari berbagi makanan, bercanda, hingga menyelesaikan konflik kecil) merupakan praktik sosial yang membangun identitas kolektif mereka.
Ruang apartemen menjadi lebih dari tempat tinggal. Ia adalah arena di mana norma-norma sosial baru diuji dan solidaritas dibangun. Adegan ketika mereka menata apartemen bersama, memasak, dan saling menasihati menunjukkan bagaimana diaspora space memungkinkan identitas hibrida (hybrid identity) berkembang melalui aktivitas yang tampak sepele, tetapi sarat makna budaya dan emosional.
Terakhir, Brah menekankan bahwa diaspora space bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis dan simbolik. Di Queens, para tokoh sering menghadapi rasa keterasingan dan kerinduan akan tanah air. Namun, ruang liminal ini memberi mereka kesempatan untuk membangun “rumah baru” versi mereka sendiri.
Misalnya, ketika mereka merayakan ulang tahun atau menyiapkan hidangan khas Indonesia di tengah kota yang asing, apartemen kecil itu berubah menjadi panggung resistensi budaya. Mereka menciptakan ruang yang aman, menegaskan identitas, dan mempertahankan rasa memiliki.
Dengan cara ini, diaspora space menjadi medium bagi perempuan migran untuk menegosiasikan identitas, menjaga budaya, dan membangun rumah batin, meskipun secara geografis mereka berada jauh dari tanah air.
Dalam Ratu-Ratu Queens, “solidaritas adalah rumah”
Ratu-Ratu Queens juga menolak stereotipe umum tentang perempuan migran, baik sebagai korban yang lemah maupun sebagai perempuan diaspora glamor yang jauh dari realitas. Keempat tokoh, bukan hanya subjek cerita, tapi juga manusia yang aktif menentukan hidup mereka sendiri.
Mereka bekerja, tertawa, berkonflik, dan menegosiasikan ruang sosial dan emosional mereka di negeri yang asing. Dalam perspektif feminis, hal ini penting. Bell Hooks, sekali lagi, menekankan bahwa perempuan perlu memiliki ruang untuk membangun identitas dan kekuatan sendiri–bukan hanya direpresentasikan oleh orang lain.
Serial ini menempatkan perempuan migran di pusat narasi, menunjukkan bahwa mereka mampu berpikir, memutuskan, dan bertindak secara mandiri, sekaligus mempertahankan budaya dan solidaritas di tengah dunia yang tidak selalu ramah.
Solidaritas menjadi napas utama serial ini. Tidak ada pahlawan tunggal yang menyelamatkan orang lain secara heroik. Yang ada hanyalah tokoh-tokoh saling menopang. Ketika Party pulang lelah dari kerja malam, Chinta sudah menyiapkan teh hangat; ketika Biyah menghadapi dilema hukum, Ance menemaninya dengan sabar.
Persahabatan dan solidaritas ini bukan hanya penghiburan, tetapi strategi bertahan hidup. Mereka membangun “rumah” dalam arti sosial dan emosional, di luar konsep rumah sebagai bangunan fisik.
Ruang domestik–apartemen kecil dan dapur yang mereka huni–pun pada akhirnya menjadi arena politik. Aktivitas sehari-hari seperti memasak, menata ruang, atau sekadar bercanda bukan hanya rutinitas. Ia adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, kesepian, dan tekanan ekonomi yang dihadapi perempuan migran.
Dengan memperhatikan ruang, emosi, dan interaksi sosial, serial ini menunjukkan bahwa feminisme tidak selalu harus monumental atau dramatis. Ia juga dapat hadir dalam tawa, pelukan, dan perhatian kecil yang menopang satu sama lain.
Ratu-Ratu Quuens memperlihatkan bahwa membangun rumah adalah proses dinamis. Karakter-karakter perempuan terus bernegosiasi dengan lingkungan, pekerjaan, budaya, dan identitas mereka sendiri. Mereka menciptakan “ritual”, kebiasaan, dan jaringan dukungan yang memungkinkan mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga menemukan kebahagiaan dan kebebasan.
Dalam konteks feminis, hal ini menegaskan pentingnya ruang yang memungkinkan perempuan mengontrol narasi dan kehidupan mereka sendiri, meskipun berada jauh dari tanah air.
Bagi saya pribadi, serial ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menegaskan bahwa politik feminis dan politik diaspora bisa hadir dalam hal-hal sederhana: memasak, menertawakan diri sendiri, merawat teman serumah. Itu semua membentuk fondasi rumah yang nyata, hangat, dan berarti di tengah globalisasi yang sering membuat manusia merasa tercerabut.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Main Serong di Sinema Indonesia: Mengapa Kamu Menyukai Film Bertema Perselingkuhan? atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan