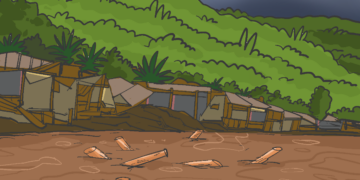Bagi para perempuan Aceh, merantau ke daerah lain menjadi tantangan yang berat. Selain harus meninggalkan daerah asalnya, ada banyak konsekuensi nggak mengenakkan yang biasanya mereka dapatkan.
Saya sendiri adalah satu dari banyak perempuan Aceh yang merasakan hal tersebut. Sekitar Juni 2021 lalu, saya mendarat di Jakarta. Ini merupakan pengalaman pertama saya meninggalkan kota kelahiran untuk merantau.
Sebenarnya, tibanya saya di Jakarta hanya untuk kebutuhan transit. Sebab, dua minggu berselang, saya akan terbang lagi ke Surabaya untuk mengikuti Seleksi Mandiri di Unair–tempat saya kini berkuliah.
Meskipun cuma sebentar tinggal di Jakarta, ada banyak hal tak mengenakkan yang saya dapatkan cuma karena identitas sebagai perempuan Aceh.
Misalnya, saat sedang nongkrong di sebuah kafe Jakarta Timur, saya bersama teman-teman iseng melakukan Live Instagram. Tak ada yang aneh dari obrolan di siaran langsung itu.
Namun, yang bikin saya kaget, saya mendapatkan komentar negatif di Live Instagram tadi.
“Jam segini perempuan kok masih nongkrong-nongkrong di cafe? Bareng cowo cowo lagi. Pantes pengen banget kuliah di Jawa, ternyata pengen hidup bebas dan liar gitu. Wkwkwk.”
Kira-kira demikian komentar salah satu teman SMA yang menyakiti hati saya.
Perempuan Aceh ini dapat nyinyiran gara-gara berkunjung ke tempat ibadah agama lain
Hate comment yang saya dapatkan saat sedang Live Instagram belum seberapa. Keysa (20), perempuan Aceh lain yang kini berkuliah di UNY, pernah mendapatkan perlakuan serupa. Bahkan lebih parah.
Ceritanya, pada Juni 2024 lalu, ia melakukan kegiatan Pertukaran Pelajar Merdeka (PPM) ke Sulawesi Utara. Kegiatan ini semacam KKN, yang diikuti mahasiswa lintas kampus.
Mayoritas penduduk di Sulawesi Utara, tempat Keysa PPM, beragama Katolik dan Kristen. Hal ini ditandai dengan cukup banyaknya bangunan gereja yang membentang tiap 100 meter.
Menurut Keysa, meskipun mereka terbilang mayoritas, toleransi antaragama mereka junjung tinggi. Kegiatan PPM ia dan teman-temannya pun tak bisa terlepas dari aktivitas para jemaat gereja.
“Saya pernah melakukan kontribusi sosial di Gereja GMIM Minahasa untuk sosialisasi pernikahan dini pada remaja sekitar, atas saran dan permintaan dari tetua desa tersebut” ujarnya, Minggu (21/7/2024).
Kegiatan tersebut ia abadikan ke Instagram Story.
“Tapi ketika saya meng-upload foto dalam gereja tersebut, muncullah berbagai komentar kebencian terhadap saya,” jelas perempuan Aceh ini.
Beragam pertanyaan intimidatif terlontar jelas kepadanya. Mulai dari pertanyaan mengenai keislamannya sampai tuduhan ia pindah agama.
“Kesya pindah agama ya?”
“Ih semenjak pindah dari Aceh, sudah pindah agama aja, lupa ya sama agama sendiri”,
“Ngeri ya pergaulannya, sampe masuk masuk gereja gitu, diajak pindah agama kah?”
Kira-kira komentar tersebut yang dilontarkan teman-teman SMA-nya kepada Keysa. Ia pun merasa prihatin karena sekadar berkunjung ke tempat ibadah agama lain saja dianggap tabu.
Nongkrong sampai larut malam dikata-katai “jual diri”
Pengalaman tak mengenakan juga pernah dialami Aliza (22). Ia merupakan perempuan Aceh yang kini menimba ilmu di Unair Surabaya.
Sama seperti saya dan Keysa, Aliza juga mendapat hate comment di Instagram. Alasannya sangat sepele, gara-gara ia nonton konser di Surabaya.
“Pernah sih waktu itu aku lagi ngonser bareng temen temen aku, terus aku upload di Instagram Story ku, eh malah dihujat,” ujar Aliza, Selasa (23/7/2024) lalu.
“Katanya ‘perempuan apaan malem-malem ngonser bareng cowok, loncat-loncat gitu, dempet-dempetan sama yang bukan muhrim, entah sudah dipegang apa-apa itu’,” imbuh perempuan Aceh, mengingat kata-kata menyakitkan tadi.
Soal perempuan keluar malam, aturan Aceh memang sangat rigid. Jika ada perempuan keluar rumah di atas jam 10, pasti bakal dapat kecaman dari masyarakat.
Keysa sendiri punya pengalaman pahit soal aturan tak tertulis ini.
“Ibu saya dulu pernah pulang sekitar jam 10 Malam, namun langsung dicap oleh warga ‘abis pulang menjual diri’,” kenangnya. “Padahal saat itu ibu saya terpaksa pulang malam karena harus mencari nafkah buat keluarga.”
“Keluarga saya pernah lagi kesusahan, minta bantuan sama tetangga, tapi tidak ada yang mau bantu, malah nanya emang ayahnya kemana? kita ngga bisa bantu istri orang kalo suaminya ngga ada,” timpa Keysa lagi.
Walau bagaimana pun, bagi Kesya hal buruk tadi tak perlu dijadikan alasan untuk membenci pihak manapun. Aturan yang diterapkan di Aceh, menurutnya, juga memiliki dampak positif tersendiri, khususnya bagi warga asli.
“Nggak ada yang salah sih sebenarnya, hanya saja perlu perbaikan atas sumber daya manusia yang ada di Aceh supaya lebih toleran dan tidak menyudutkan salah satu pihak dengan kesalahan yang kecil,” pungkasnya.
Catatan:
Liputan ini diproduksi oleh mahasiswa Program Kompetisi Kampus Merdeka-Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PKKM-MBKM) Unair Surabaya di Mojok periode Juli-September 2024.
Penulis: Adelia Melati Putri
Editor: Ahmad Effendi
Ikuti artikel dan berita Mojok lainnya di Google News