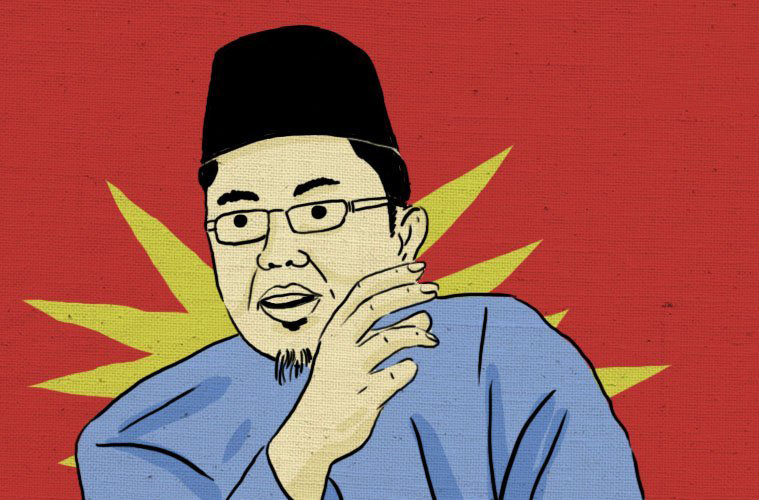Sayangnya, menurut Gigih, program ini terlalu berat sebelah. Pemerintah selalu berfokus pada kebijakan yang bersifat terapan ketimbang riset dasar. Padahal, riset dasar bisa membantu pengembangan hingga menciptakan ilmu pengetahuan baru.
“Arah pendidikan kita cenderung bagaimana memenuhi kebutuhan dunia kerja dan bagaimana bisa meraih peringkat kampus yang sangat prestise,” kata dia.
“Narasi bagaimana agar Indonesia menjadi kiblat ilmu pengetahuan dengan terobosan-terobosan penemuan dalam teori baru untuk mengimbangi peradaban barat bukan menjadi arah prioritas,” lanjutnya.
Riset tak hanya soal kuantitas
Oleh karena itu, Gigih mengimbau kapitalisme dan feodalisme dalam praktik pembuatan riset seharusnya diberantas, jika ingin Indonesia Emas 2045 terwujud. Apalah arti memenuhi kebutuhan dunia kerja serta mengejar peringkat kampus dunia, jika moral dari sumber daya manusianya rusak.
“Untuk mencerdaskan bangsa, syaratnya tentu perlu ada keseimbangan untuk memajukan riset dasar dan riset terapan yang berdampak langsung bagi kehidupan,” ucapnya.
Jika memilih riset dasar maka yang ia peroleh adalah top achievement penemuan hingga muncul penciptaan teori baru. Jika riset terapan, hasilnya adalah inovasi teknologi. Tujuan itu yang seharusnya jadi motivasi para peneliti maupun dosen. Sementara, kenaikan pangkat hanyalah bonus dari kadar kebaruan riset yang mereka buat.
Dengan orientasi dosen yang berubah, maka target pendidikan kampus di Indonesia seharusnya ikut berubah. Di mana, dosen tidak terlalu dibebani dengan jumlah riset yang banyak atau kuantitas semata, tapi juga kualitas ilmiah yang menunjukkan kebaruan.
“Dengan begitu, kontribusi maksimal para dosen di kampus Indonesia dapat meningkat secara kumulatif. Hal tersebut bisa mengurangi persepsi bahwa publikasi riset atau jurnal hanya sekadar gugur kewajiban atau mengejar jumlah dalam tiap semester dan tahunan,” ujar Gigih.
Pola sistemik yang perlu diterapkan kampus di Indonesia
Menurut alumni UIN Surabaya Jurusan Filsafat tersebut, doktor seharusnya tidak dipahami sebagai gelar akademik tertinggi saja. Tapi seseorang yang mampu menemukan teori baru. Masalahnya, dalam pengelolaan studi doktoral di kampus Indonesia saat ini, gelar doktor hanya dijadikan sebagai standar sukses pendidikan seseorang.
Orang yang punya gelar doktor, dianggap mampu menerbitkan jurnal internasional bereputasi, sekolah lama dan lulus tepat waktu dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang bagus. Tidak ada yang salah memang, tapi pengelolaan studi doktoral ini, kata Gigih, seharusnya dapat mengarah pada penemuan dan penciptaan teori baru.
“Jika diperlukan, ada program khusus mahasiswa yang memiliki rencana untuk mengembangkan dan menemukan teori baru. Mahasiswa yang mengikuti program tersebut perlu menyiapkan setidaknya penelusuran kesenjangan teoritik yang akan ditindaklanjuti oleh pihak pascasarjana menjadi desain kesenjangan teoritik,” jelas Gigih.
Gigih berharap mahasiswa yang menempuh pendidikan S3 lebih banyak mendapatkan kelas diskusi hingga brainstorming soal desain konstruksi, maupun penataan ulang atau rekonstruksi teoritik. Selain itu, mereka juga dapat mengikuti kuliah tamu, studium generale, sampai colloqium, sehingga tema riset yang dihasilkan tidak hanya mainstream dan menarik.
Gigih tak menampik, untuk mewujudkan itu semua, perlu kesungguhan dari berbagai pihak dengan waktu yang relatif lama. Tapi, ia masih yakin kalau sistem pendidikan akan jauh lebih baik asal pemerintah jeli dalam melihat akar masalahnya.
“Tekad yang kuat sangat diperlukan untuk lepas dari jerat permasalahan klasik. Begitu fundamentalnya sistem pendidikan dan bisa berefek kepada sektor yang lain. Jika sistem pendidikan banyak permasalahan, maka itu akan berefek negatif pula,” kata Gigih.
Penulis: Aisyah Amira Wakang
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Riset Kampus di Indonesia Cuma Jadi Sampah Ilmiah, Alarm Serius buat Binus hingga Unair yang Masuk Daftar Red Flag atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan