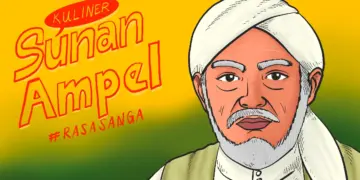Keresahan warga lokal akan citra yang tercoreng
Di sisi lain, warga asli Malang ternyata merasakan keresahan yang mendalam terkait fenomena kos LV dan kumpul kebo ini.
Salah satunya Siti (31), perempuan yang mengaku melanjutkan bisnis kos orang tuanya di lingkungan padat penduduk. Ia mengungkapkan perasaannya yang merasa “campur aduk” dan takut nama baik kota ini tercoreng.
Keresahan Siti berakar pada beberapa hal. Pertama, adanya pergeseran identitas kota.
“Dulu, kalau ada mahasiswa lewat, kami bangga. Sekarang, kadang mau negur saja sungkan, takut salah. Tapi kalau dibiarkan, rasanya mata ini perih melihat pemandangan yang tidak pantas di depan rumah,” ujarnya, Selasa (29/7/2025).
Malang, yang dikenal sebagai pendidikan, kini dikhawatirkan akan dikenal sebagai “kota bebas” karena perilaku segelintir oknum pendatang. Bagi Siti, ini adalah pukulan telak bagi citra kota kelahirannya itu.
Kedua, ancaman norma moral. Menurutnya, praktik kumpul kebo bertentangan langsung dengan nilai kesopanan, kekeluargaan, dan ajaran agama yang dipegang teguh masyarakat.
“Anak-anak saya mulai bertanya, ‘Bu, kok pacaran begitu boleh ya?’ Bagaimana saya menjelaskan?” Ada kekhawatiran perilaku ini “menular” atau memengaruhi generasi muda lokal,” jelasnya.
“Kami paham. Itu kan hak pribadi mereka. Kami nggak bisa ikut campur terlalu jauh. Tapi lama-lama, itu bisa bikin citra kota kami jadi buruk, Mas.”
Kumpul kebo berada di ruang abu-abu
Keresahan serupa juga dirasakan oleh Andri (30), seorang warga asli Malang yang kini bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di kota ini. Setelah menempuh pendidikan S1 dan S2 di luar Malang, ia merasakan betul perbedaan kota kelahirannya.
“Malang yang dulu saya kenal, beda sekali dengan yang sekarang,” ujarnya. “Dulu, kota ini identik dengan ketenangan dan nilai-nilai yang kuat. Sekarang, saya melihat sendiri bagaimana gaya hidup yang lebih ‘bebas’ semakin terang-terangan, terutama di lingkungan sekitar kampus.”
Meskipun ada rasa prihatin dengan kumpul kebo di Malang, Andri menjelaskan bahwa fenomena tak bisa dibicarakan sesederhana membahas nilai moral dan agama. Ada benturan nilai yang kompleks di dalamnya.
Misalnya, kebutuhan akan kebebasan dan privasi dari pendatang berhadapan langsung dengan norma moral dan sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat lokal.
“Ada area abu-abu hukum, di mana hukum positif mungkin tidak secara spesifik mengatur kumpul kebo tanpa unsur pidana lain. Seperti prostitusi, misalnya,” kata dia.
“Namun, praktik tersebut jelas melanggar hukum adat atau norma yang hidup di masyarakat,” imbuhnya.
Alhasil, benturan nilai ini bukan tanpa konsekuensi. Di balik setiap razia dan keluhan warga, ada harga yang harus dibayar. Bukan hanya citra kota yang terancam, tapi juga erosi kepercayaan antargenerasi.
“Anak-anak muda lokal mungkin mulai mempertanyakan nilai-nilai yang mereka anut. Sementara warga asli merasa asing di tanah sendiri,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Tak Mudah Jadi Orang dengan KTP Malang, Susah Payah Berbuat Baik tapi Sia-sia karena Cap Aremania atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.