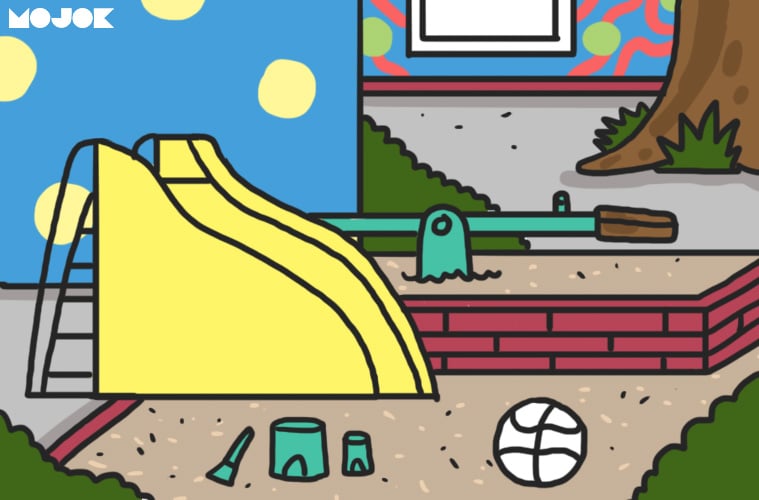Layar lebar Indonesia sedang keranjingan kisah perselingkuhan. Dari film Noktah Merah Perkawinan (2022), Ipar Adalah Maut (2024), hingga Lah Tahzan dan yang terbaru Norma (2025), sinema kita semakin berani mengusung cerita cinta terlarang.
Fenomena ini memunculkan tanya: mengapa publik begitu terpikat pada drama perselingkuhan, meski isu ini dalam kehidupan nyata sering dianggap tabu?
***
Rina (28), seorang karyawan swasta, masih ingat betul malam ketika ia menonton Noktah Merah Perkawinan di sebuah bioskop di Jogja. Lampu ruangan meredup, layar mulai menyala, dan popcorn yang ia beli mendadak tak lagi terasa gurih.
Setiap kali konflik antara Ambar, Gilang, dan Yuli memuncak, ia merasa jantungnya ikut berdegup cepat.
“Rasa-rasanya, kayak aku yang dikhianatin,” ujarnya, mengingat pengalamannya menonton itu kepada Mojok, Minggu (21/9/2025).
Pengalaman menonton itu bukan sekadar hiburan baginya. Rina dibesarkan di keluarga yang pernah retak akibat perselingkuhan. Ibunya harus menanggung perih karena ayahnya memilih perempuan lain.
Alhasil, adegan-adegan dalam film membuat kenangan pahit itu kembali menyeruak. Ia bahkan sempat menahan air mata, lalu duduk lama di lobi bioskop setelah film usai.
“Rasanya campur aduk. Marah, sedih, tapi juga anehnya lega, karena film itu seolah mewakili yang dulu tidak pernah bisa aku ucapkan,” katanya.
Bagaimana “cinta terlarang” direpresentasikan dalam sinema?
Kisah Rina mencerminkan bagaimana film tentang perselingkuhan bekerja pada penontonnya: membuka luka lama, menggugah empati, dan memantik perenungan. Uniknya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga punya sejarah panjang dalam sinema global.
Anthony Balducci dalam bukunya Unfaithful: The History of the Adultery Film (2010) menulis bahwa film tentang perselingkuhan telah menjadi salah satu genre penting sejak era Hollywood klasik. Ia menelusuri bagaimana kisah cinta terlarang di layar lebar selalu dipenuhi paradoks: menarik karena sensasional, tapi harus dibingkai dalam moralitas agar tidak dianggap “merusak tatanan”.
Balducci menunjukkan bahwa pada era Hays Code—pedoman moral dan etika yang diterapkan secara luas di industri film Hollywood pada 1930–1960-an, film perselingkuhan hanya bisa ditampilkan dengan syarat sang pelaku pada akhirnya menerima hukuman. Narasi ini menjaga “moral publik” sekaligus menyajikan bumbu dramatis bagi sebuah film.
Seiring waktu, terutama ketika kode sensor longgar pada 1960-an, representasi berubah drastis. Sebagai misal, Balducci mencontohkan The Graduate (1967), yang menampilkan perselingkuhan sebagai pencarian identitas dan makna hidup, bukan sekadar dosa.
Lalu pada 1980–1990-an, muncul gelombang erotic-thrillers seperti Fatal Attraction (1987), di mana kisah selingkuh dikaitkan dengan bahaya, obsesi, bahkan teror. Masuk 2000-an, film Unfaithful (2002) mengubah pendekatan: perselingkuhan digambarkan dengan intimitas emosional dan ambiguitas moral.
Balducci menandai pergeseran penting ini: adultery film tidak lagi sekadar memberi pelajaran moral, tetapi mengajak penonton larut dalam dilema tokoh. Pendeknya, audiens diajak lebih banyak memahami kompleksitas psikologis pelakunya, bukan sekadar mengutuk.
Beda film perselingkuhan era Orba dan sekarang
Dalam konteks Indonesia, dinamika serupa juga terjadi. Banyak penelitian menyebutkan bagaimana sinetron Orde Baru kerap menampilkan konflik rumah tangga secara hitam-putih.
Perselingkuhan nyaris selalu digambarkan sebagai dosa besar yang pantas dihukum, selaras dengan narasi moral negara tentang keluarga ideal. Namun, pasca-Reformasi, terutama pada dekade 2000-an, ruang representasi mulai longgar.
Misalnya, studi Maria Nugraheni Syafei berjudul “Representasi Konflik Pernikahan pada Film Noktah Merah Perkawinan” (2023) menunjukkan, film Noktah Merah Perkawinan (1981) sudah lebih dulu mengangkat kisah serupa. Bedanya, pada masa Orde Baru, narasi kerap ditutup dengan “penertiban moral”: si pelaku kembali ke keluarga, atau dihukum secara simbolis.
Kini, versi terbaru film yang sama jauh lebih berani menampilkan kompleksitas emosi dan pilihan individu, tanpa menyodorkan jawaban moral tunggal.
Remake film terbaru Noktah Merah Perkawinan (2022) menekankan pergeseran nilai dalam masyarakat urban. Dari sekadar menjaga “keutuhan rumah tangga” menuju pengakuan atas luka psikologis perempuan akibat pengkhianatan.
Ambar dan Gilang tidak lagi digambarkan hitam-putih. Namun, penonton diajak memahami perasaan masing-masing, meski tetap merasa terusik.
“Film tersebut tidak hanya menyorot perselingkuhan sebagai pelanggaran moral, melainkan juga sebagai gejala komunikasi yang gagal dalam pernikahan,” tulis Maria.
Film perselingkuhan, tabu tapi dinikmati
Alhasil, analisis Maria membantu menjelaskan mengapa film Noktah Merah Perkawinan begitu kuat menggugah audiens seperti Rina. Sebab, ia memberi ruang empati pada semua pihak, bukan sekadar menunjuk siapa yang salah.
Chingching Chang dalam risetnya “Enjoyment of Love-Related Dramas and the Implications of Perspective Taking” (2023) menguatkan argumen ini.
Menurutnya, penonton sering kali terlibat secara emosional dalam drama cinta terlarang karena mereka melakukan perspective taking alias “membayangkan diri berada di posisi karakter”.
Rina, misalnya, ikut merasakan luka Ambar, tetapi juga memahami dilema Gilang. Di sinilah daya tarik utama film perselingkuhan: ia menjadi laboratorium emosional, tempat penonton menguji simpati dan moral mereka.
Alhasil, melalui keterlibatan emosional ini, audiens tidak hanya menonton untuk hiburan, melainkan juga untuk “menegosiasikan moralitas pribadi” melalui narasi di layar.
Penonton boleh jadi mengutuk karakter yang berselingkuh, tetapi diam-diam terpesona pada romansa terlarang itu. Paradoks inilah yang membuat genre ini tak pernah basi.
Uniknya, fenomena ini tak cuma berlaku di Indonesia. Shoma A. Chatterji dalam esai panjangnya “Adultery in Indian Cinema” menunjukkan bahwa di India, film-film perselingkuhan sering menghadapi sensor ketat. Namun, ia tetap populer karena audiens menganggapnya “realistis” dan “berhubungan dengan kehidupan sehari-hari”.
Perbandingan ini menarik: di dua negara Asia yang sama-sama menjunjung nilai keluarga, sinema justru menemukan ruang subur untuk mengisahkan pelanggaran terhadap nilai itu.
Menghadapi kemungkinan terburuk dalam hidup
Yang menjadi pertanyaan: Mengapa tema perselingkuhan ini begitu kuat resonansinya? Dari sisi psikologi, Scott M. Stanley dan Howard Markman dalam Fighting for Your Marriage (2002) menyebut bahwa perselingkuhan adalah salah satu ancaman paling besar terhadap pernikahan modern—sekaligus salah satu ketakutan universal pasangan.
Maka, menonton film bertema ini bisa jadi cara “aman” untuk menghadapi ketakutan tersebut. Seolah-olah mereka berlatih menghadapi kemungkinan terburuk tanpa harus benar-benar mengalaminya.
Dedi (27), seorang ayah satu anak yang saya temui di sebuah kafe di Sleman, punya pengalaman berbeda dengan Rina. Ia menonton Noktah Merah Perkawinan bukan karena trauma pribadi, melainkan karena rasa penasaran.
“Awalnya saya ikut-ikutan istri. Tapi lama-lama saya sadar, film ini bikin saya mikir ulang tentang rumah tangga,” katanya.
Dedi mengaku, ada kalanya ia “merasa jenuh” dalam pernikahan. Namun, setelah menonton, ia justru jadi lebih menghargai batas-batas yang harus dijaga.
“Kalau sampai kepleset, yang rugi bukan cuma diri sendiri, tapi keluarga besar.”
Kisah Rina dan Dedi menggambarkan dua sisi penerimaan penonton: yang satu merasa film membuka luka lama, yang lain menjadikannya cermin preventif. Keduanya menunjukkan bahwa film perselingkuhan bekerja bukan hanya sebagai hiburan, melainkan juga sebagai ruang refleksi sosial.
Di sinilah analisis Balducci kembali relevan. Ia menegaskan bahwa film perselingkuhan selalu menjadi “zona liminal” di mana moralitas publik diuji. Penonton boleh marah, kecewa, bahkan jijik, tetapi tetap tak bisa berpaling dari kisahnya.
Perselingkuhan di layar barangkali tabu, tetapi justru di situlah daya tariknya. Ia menyodorkan pertanyaan yang sulit dijawab, tetapi perlu dihadapi: apa arti setia, dan sejauh mana kita bisa memahami rapuhnya cinta?
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Film SORE: Istri dari Masa Depan Lebih Cocok Disebut Film Horor daripada Drama Romantis atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.