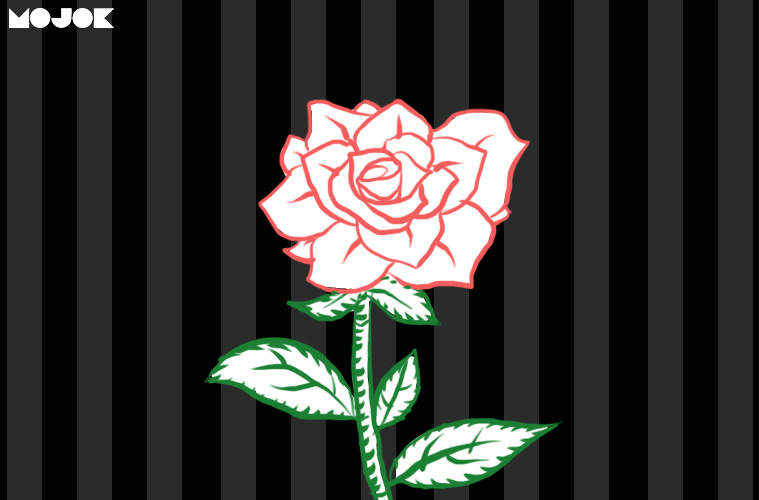MOJOK.CO – Rasa-rasanya untuk memperoleh keadilan itu, selain mahal juga bisa rugi berlipat ganda. Akhirnya, Tuhan yang dibawa-bawa.
Bertahun lalu saya membaca anonymous quotes: Kalau dunia adil, tidak akan ada yang namanya lembaga peradilan. Saat itu umur saya baru beranjak remaja dan nggak tahu betul apa maksud dari ungkapan tersebut.
Namun yang saya ingat, zaman itu, untuk memperoleh keadilan biayanya sangat mahal. Mungkin, sebagian orang zaman itu masih ingat ungkapan: kehilangan ayam, kalau lapor malah akan kehilangan kambing. Prosedur formal zaman itu mengharuskan keluar biaya ekstra bahkan meski Anda adalah korban.
Kehilangan nggak seberapa, kalau lapor masih harus kehilangan waktu, pikiran, tenaga, dan tentu saja biaya untuk proses laporan. Sederhananya, kalau (zaman itu) Anda kehilangan KTP, bikin surat kehilangan saja harus bayar ongkos ketik.
Karena rumitnya birokrasi dan biaya “kenakalannya” yang luar biasa. Pernah suatu ketika, kenalan saya bawa mobil, mobilnya lagi diparkir. Eh, terus ditabrak dari samping sama anak SMP yang lagi belajar naik motor. Hadeeeh, bikin kaget saja!
Hebatnya, teman saya ini malah harus menanggung biaya rumah sakit sekalian dengan biaya perbaikan motor. Abi situ, mobilnya masih ditahan. Dan untuk “nebus” mobilnya tersebut, dia masih harus mengeluarkan biaya lagi. Yang tentu saja pas bayar nggak pakai nota.
Segala kesulitan yang dialaminya terjadi, karena sebelumnya dia memutuskan untuk bikin laporan kalau mobilnya habis ditabrak motor. Mungkin inilah yang disebut dengan apes. Udah jatuh, tertimpa tangga, masih kejatuhan genteng pula!!11!!1
Dengan pengalaman yang panjang dan berliku, sebagian masyarakat akhirnya berusaha memperoleh keadilan tanpa melalui proses formal. Dari bayar preman, aksi main hakim sendiri, sampai pergi ke tukang santet pun dilakukan untuk memperoleh keadilan yang diinginkan.
Kalau orang zaman itu bener-bener sadar, ketidakadilan juga terjadi dalam skenario film. Bagi Anda penggemar film Susana, pasti tahu entah berapa kali dia harus mati dan jadi hantu hanya untuk membalaskan dendamnya demi memperoleh keadilan.
Aktivis perempuan zaman itu sampai bilang: di Indonesia, perempuan kalau mau memperoleh keadilan, kenapa harus mati dulu terus jadi setan? Bila diamat-amati, memang nggak cuma Susana dan Katemi yang mengalaminya. Si Manis Jembatan Ancol, juga bernasib serupa. Sedih jadinya.
Di dunia nyata, yang tertindas dan disakiti tapi nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya pasrah dan (sebagian) terpaksa melakukan aksi ikhlas. Tunggu, memangnya bisa ya, ikhlas tapi terpaksa? Ya, mau bagaimana lagi? Mau ngotot juga tetap saja nggak dapat apa-apa.
Mungkin, ada juga sih yang betul-betul ikhlas. Akan tetapi, ketika yang menyakitinya dulu tertimpa musibah, kemudian akan teringat dengan luka-luka lama. Sembari bilang, “dia memang orangnya gitu, sekarang baru tahu rasa”, seolah petaka adalah obat untuk luka lama yang dimiliki.
Jadi, sebenarnya dia itu ikhlas apa nggak, ya? Jangan-jangan ingin membalas tapi nggak mampu? Yang akhirnya, menyimpan dendam membara. Terkadang, memaafkan memang sekadar basa-basi doang untuk kebutuhan sosial. Di dalam hati sih, masih terasa panas nggak ketulungan.
Tidak sedikit orang yang terkadang akhirnya meremehkan kata “maaf”. Seolah-olah, setelah minta maaf semua jadi beres. Padahal, maaf bukan sekadar jadi prosedur untuk menggugurkan dosa karena berbuat salah. Tentu saja, maaf jadi kata yang diobral murah.
Bahkan sering kali orang meminta maaf meski tidak merasa bersalah. Untuk memperpendek urusan, orang bakal bilang: ya sudah, saya minta maaf. Lalu biasanya, di belakangnya akan ada embel-embel, “padahal kalau…”, yang menunjukkan dia tidak merasa betul-betul bersalah apalagi menyesalinya.
Akan menjadi semakin menyebalkan, jika kemudian ditambah kata, “gitu doang aja, marah.” Meskipun, orang lain kalau melakukan hal yang “gitu doang”, dia bisa berang minta ampun. Ngomong ke sana ke mari, terus ditambah-tambahin biar lebih dramatis supaya merasa jadi orang yang teramat sangat terzalimi.
Pertengkaran antara pihak yang “setara” pun terkadang bisa berakhir dengan saling mengacuhkan, meski tidak bermusuhan. Akan tetapi, ya nggak masalah. Dengan saling tidak acuh, setidaknya mereka akan berhenti saling menyakiti.
Yang menyebalkan, kalau yang terjadi adalah pertengkaran yang “tidak adil”. Sudah salah, ngotot, menang lagi. Tentu saja, hanya akan bikin korban kelara-lara (tersakiti). Sebel nggak, sih? Dia yang salah, kok malah gue yang disalah-salahin orang sekampung?!
Lebih sebel lagi malah kita (Hah? Kita??) yang disuruh minta maaf. Mungkin inilah yang disebut kalau dunia itu kejam. Di sini mungkin orang akan lebih memilih untuk berhenti jadi makhluk sosial. Nggak penting banget, cuma bikin sakit hati.
Yang lebih seru lagi, ada yang ngedem-demi (mendinginkan/menenangkan). “Udah, tenang saja, biar nanti Tuhan yang balas”, terus ditambah lagi, “Tuhan akan balas berkali lipat dari perbuatan yang dia lakukan. Tuhan nggak tidur.” Gitu katanya.
Hadeeeh, ini orang pede banget bawa-bawa Tuhan untuk “kepentingan” pribadi. Emangnya kalau dia celaka itu (((hanya gara-gara))) Tuhan membalas karena dia sudah menganggu hidupmu, po? Lagian, darimana dia tahu kalau itu balasan dari Tuhan? Bukankah bisa jadi, dikira cobaan karena ia terlalu beriman?
Saya paling sebel, kalau Tuhan sudah dibawa-bawa untuk mengancam. “Lah, saya kan sudah minta maaf, kalau kamu nggak maafin, kamu yang dosa.” Tentu saja ngomongnya nggak ada nada menyesal sama sekali. Seolah-olah, pokoknya Tuhan harus nurut sama dia, buat mengancam maupun doa yang jelek-jelek.
Ujung-ujungnya, Tuhan diancam, “Kalau tidak mengabulkan doaku, aku takut tidak akan ada lagi yang menyembahmu.”
Hadeeeh, gini amat ya kalau pengin memperoleh keadilan ke manusia. Saking mahal, ribet, dan budrek-nya, Tuhan harus dibawa-bawa~