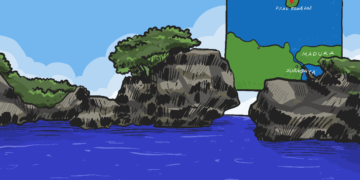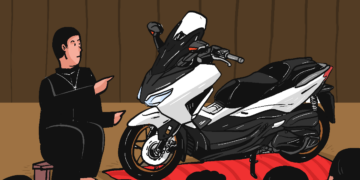MOJOK.CO – Suku presiden Indonesia dalam beberapa kasus dianggap “Jawa” saja atau “Bugis” saja. Padahal bapak-ibu mereka sudah campur-campur sukunya. Aneh? Ini lagi-lagi soal patriarki.
Waktu masih kecil dulu, saya pernah heran dengan tetangga saya yang namanya Bu Sarjono. Anda juga mungkin heran dengan saya. Kenapa kok sama Bu Sarjono saja heran? Ada apakah dengan ibu-ibu itu? Apa dia semacam mutan? Wonder Woman? Atau namboru Panjaitan?
Ah, tidak, tidak! Bu Sarjono ini ibu-ibu yang tipikal di kampung saya. Dia seperti emak-emak pada umumnya, suka memakai daster bolong-bolong di rumah tapi menjadi penuh gaya di acara resepsi. Yang membikin saya heran cuma satu, yaitu namanya.
Masak ada ibu-ibu namanya Sarjono? Pikiran bocah saya sulit mencerna bahwa ada seorang ibu-ibu bernama Sarjono.
Kronologinya bermula saat kakak sepupu saya ditugaskan mengantarkan undangan rapat PKI PKK ke tiap rumah warga. Waktu itu, saya sedang bermain ke rumahnya, dan saya terpaku lama sekali dengan nama Bu Sarjono di salah satu kertas undangan.
Bayangan saya mengenai Bu Sarjono adalah seorang bapak-bapak yang berdandan ala ibu-ibu. Saya makin kaget saat membaca undangan lain yang namanya bapak-bapak semua padahal panggilannya “Bu”.
Rasa penasaran saya tak terbendung lagi. Meski pemalu, saya memberanikan diri bertanya ke bude mengenai siapa itu Bu Sarjono dan ibu-ibu “macho” yang lain. Bude saya menjelaskan bahwa Bu Sarjono itu istrinya Pak Sarjono. Begitu pula dengan Bu Bagyo yang ternyata istrinya Pak Bagyo dan Bu Sukir yang istrinya Pak Sukir.
“La, terus kenapa namanya jadi Bu Sarjono? Kok bukan Bu Sumi aja?” tanya saya heran. By the way, ternyata yang dimaksud Bu Sarjono itu De Sumi, penjual pengananan langganan saya. Tampilannya nggak ada macho-machonya sama sekali, tuh! Tega sekali society menamainya dengan nama laki, pikir saya.
Bude saya menjelaskan lagi bahwa setelah seorang perempuan menikah namanya akan ngikut nama suaminya. Waktu itu, saya jelas tidak paham. Saya masih terlalu kecil untuk memahami adat kebiasaan seperti ini. Saya malah tanya dengan polos ke bude saya kenapa tidak Pak Sarjono saja yang ganti nama menjadi Pak Sumi? Atau Pak Bagyo menjadi Pak Ratih? Hayo, hayo!
Bude saya menjawab pertanyaan saya dengan jawaban ala Kim Jong Un. “Ya memang dari dulu begitu. Titik. Awas tanya lagi!” Karena takut kena senjata nuklir berupa omelannya, saya pun diam saja.
Mengingat kejadian itu, sekarang saya jadi suka senyum-senyum sendiri. Apalagi, kini saya sering dipanggil dengan nama suami saya di kertas-kertas undangan kampung. Padahal nama suami saya ya macho banget kayak namanya Pak Sarjono, Pak Bagyo, dan Pak Sukir.
Tapi untungnya saya sudah tidak kaget lagi. Pikiran kanak-kanak saya sudah berevolusi sehingga sudah bisa maklum dengan kerumitan norma adat orang dewasa. Kadang adat istiadat begini memang unik. Tapi suka tidak suka, we live in society, in this patriarchal society.
Cuma, seberapa pun nrimo-nya kita dengan society, kadang yang bikin sedih, adat seperti ini bisa membuat seseorang tertutupi identitasnya, terutama identitas perempuan. Selain perkara remeh-temeh soal Bu Sarjono vs Pak Sumi, masalah suku presiden di Indonesia pun kena imbasnya.
Presiden pertama Indonesia adalah Sukarno. Ia setengah Jawa dan setengah Bali. Bapaknya orang Jawa, sedangkan ibunya orang Bali. Tapi ia sering dianggap sebagai presiden bersuku Jawa saja.
Lalu Presiden Megawati yang notabene anak Bung Karno. Bapaknya setengah Jawa dan Bali, lalu ibunya punya darah Minang. Tapi Megawati dianggap sebagai presiden Jawa saja. Belum pernah tuh saya denger ada orang ngomong kalau Megawati adalah presiden Minang atau Bali.
Kasus Habibie malah lebih unik. Ia sering didapuk sebagai satu-satunya presiden non-Jawa di Indonesia. Padahal, Pak Habibie ini meski bapaknya memang orang Bugis, namun sebetulnya ibunya Jawa. Unik sekali karena Habibie ini diangga less javanese dibanding Megawati dan Sukarno!
Presiden Indonesia yang darahnya mungkin murni Jawa adalah Soeharto, Gus Dur (meski Gus Dur pernah bilang ia punya darah Tionghoa), SBY, dan Jokowi. Yang lainnya berdarah campuran. Jadi dari 7 presiden Indonesia, yang 100% Jawa kemungkinan ada 4, yang lainnya berdarah campur aduk dari berbagai suku di negeri ini.
Kita bisa lihat, ada suatu pola konspiratif di sini. Ehem, bukan maksud sa ngikutin bli Jrx atau Yonglex, tapi memang aroma konspirasi tercium nyata benar di kasus ini!
Serius!
Jadi, ketika darah suatu suku mengalir dari pihak ibu, identitas suku tersebut menjadi kurang diakui. Sebaliknya, ketika darah suku tersebut mengalir dari pihak bapak, pasti ia langsung dicap dari suku terkait.
Padahal, yang namanya anak itu terbentuk dari “darah” ibu serta bapaknya. Malah pengaruh ibu lebih kuat, karena janin berkembang di perut ibu dan disusui ibu! Bapaknya mah jadi cheerleader aja.
Coba kalau bapaknya Habibie orang Jawa, pasti dia disebut presiden dari suku Jawa. Kebalikannya kalau bapaknya Megawati yang berdarah Minang, pasti dia bakal disebut presiden dari suku Minang.
Kasus ini mirip sekali dengan penamaan nama ibu-ibu dengan nama suaminya: Bu Sumi jadi Pak Sarjono dan Bu Ratih jadi Pak Bagyo. Di Barat sana, kasusnya juga mirip-mirip. Nama keluarga pihak ibu tidak dipakai buat anaknya, sampai kemudian ada beberapa yang protes lalu memadukan nama keluarga bapak dan ibu.
Tapi kita bisa apa? We live in society, kan? Kalau protes nanti dikira kurang kerjaan. Nanti dikira feminis galak blablabla. Padahal sebetulnya yang nulis ini pun nggak ngerti blas sama feminis-feminisan. Wong cuma dibutuhkan pikiran seorang bocah kok untuk bertanya kenapa Bu Sumi yang harus berganti nama menjadi Bu Sarjono, dan bukannya Pak Sarjono menjadi Pak Sumi.
Ya toh? Kan seru gitu lho kalau sekali-kali kita nyebut bapak-bapak pakai nama istrinya. Apa kabar Pak Iriana? Apa kabar Pak Hartinah? Apa kabar bapak-bapak feminim nan girly lainnya?
BACA JUGA Soeharto, Satu-Satunya Presiden Indonesia yang Pernah Kena Gebuk