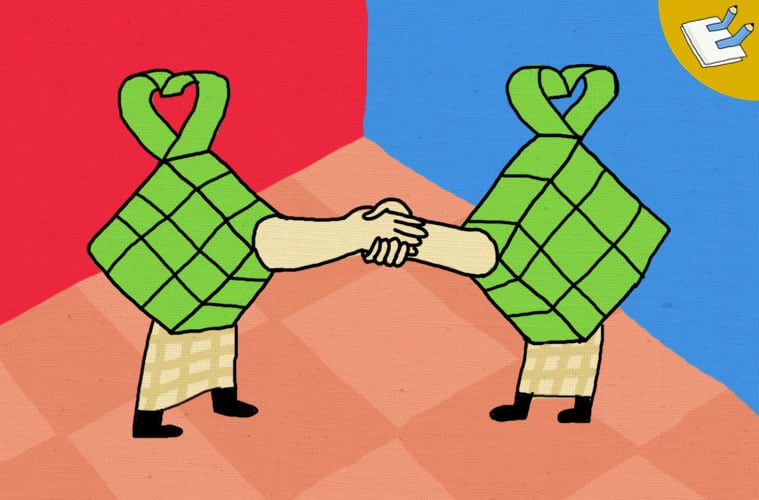Lebaran telah tiba. Tak terasa ada banyak hal yang telah kita lalui selama setahun ini.
Permasalahan kita yang paling membekas tentu adalah perselisihan dan pertengkaran kita di medsos. Apalagi jika Anda jomblo; perselisihan, pertengkaran, dan saling bully di kolom komentar itu benar-benar menguras tenaga dan pikiran.
Dalam suasana hati yang penuh tekanan karena ketiadaaan pasangan kencan, kecenderungan hati para Jomblo sebenarnya ingin “merengkuh” dan “menyatukan”. Tapi, apa boleh buat, suasana linimasa menuntut untuk melampiaskan hasrat “pertengkaran” yang membelah kita sebagai bangsa. Dan pada akhirnya membelah hati mereka.
Pertengkaran-pertengkaran itu, nyaris tak lepas dari bingkai dua kubu politik yang terus membuat kita “melas” dan “trenyuh”. Apalagi jika ditinjau dari perspektif jomblo. Ada isu bumi-datar vs bumi bundar, Islam Nusantara, rasisme dan sektarianisme dalam kasus penistaan agama dan ulama, pengerahan “massa actie” dalam politik dukung-mendukung, Aksi Bela Islam, Gaj Ahmada yang muslim, Full Day School, “Saya Pancasila, Saya Indonesia”, dll.
Nah, lebaran ini adalah momen yang tepat untuk merenung. Apakah kita memang benar-benar berbeda? Tidakkah ada—meminjam istilah seorang Jomblo teman saya—sesuatu yang “menyatukan” atau “merengkuh”? Tak bisakah kita yang daif ini mengakui, bahwa pertengkaran-pertengkaran itu tak lebih adalah usaha sebuah bangsa untuk saling bertegur sapa, kencan, dan selanjutnya “penyatuan”?
Kondisi penyatuan itu relatif sudah kita praktikkan di masa “retreat” 30 hari selama berpuasa. Terbukti dengan berkurangnya aktivitas penyebaran hoax dan aksi sweeping warung makan di bulan Ramadan. Dugaan aksi sweeping warung makan selama bulan puasa akan menjadi bahan pertengkaran kita ternyata tidak terjadi, kan? Ini kondisi baik.
Mari kita deret, apa saja yang sebenarnya bisa menyatukan, atau sebenarnya tak benar-benar perlu dibentur-benturkan, antara dua kubu politik yang saling bertengkar. Bingkai pemihakan politik yang selama ini menubuh dengan kita, bisa kita kurangi. Dan sebagai hasil olah jiwa dari puasa, semoga fakta-fakta yang saya suguhkan di bawah ini bisa ditanggapi dengan suasana “sumeleh”, santai, dan syukur-syukur kocak.
Bumi Datar Vs Bumi Bundar
Menurut penelitian ngawur saya, teori bumi datar dan teori bumi bundar sungguh tidak mempunyai nilai relevansi apa-apa bagi Anda yang harus mudik ke kampung halaman. Baik Anda tim datar maupun tim bundar, Anda akan segera merasakan bahwa hanya aspal yang Anda lewati yang bisa disebut datar atau rata. Tentu dengan selingan fakta “gronjalan”, tanjakan, dan turunan.
Fakta ini memang seolah sedikit membela teori bumi datar. Namun, ada fakta yang bisa kita terima dari perspektif kedua belah pihak: aspal itulah yang sebenarnya rata, bukan bumi kita. Jadi kaum bumi datar maupun kami Bumi bundar tak perlu saling bersitegang.
Ingatlah, saat mengendarai motor, entah Anda kaum bundar atau kaum datar, jangan terlalu sering melirik kaca spion untuk memastikan bahwa aspal yang telah Anda lalui masih datar atau cenderung melengkung ke bawah (bundar). Tindakan ini salah-salah bisa menyebakan kecelakaan. Dalam kamus perjombloan, jika Anda terlalu sering menengok masa lalu, Anda akan sulit move on.
Jika bulan-bulan kemarin Anda ngotot mengolok-olok Islam Nusantara sebagai produk liberalisme Islam yang ingin mengubah “assalamualaikum” dengan “sampurasun”, saya sarankan Anda mengurangi tensi ketegangan otot. Karena lebaran kita di Indonesia, dengan tradisi mudik massal, tradisi ziarah ke makam leluhur, tradisi sungkeman, saling mengunjungi dan salam-salaman antar saudara dan tetangga, halalbihalal, apalagi “lebaran ketupat” yang kita praktikkan, ternyata adalah manifestasi “Islam Nusantara” tanpa terkatakan. Disetujui atau tidak disetujui.
Kalau tak percaya, silakan Anda berlebaran di Arab Saudi atau negara lain di Timur Tengah. Tak ada tradisi-tradisi seperti yang saya sebut di atas.
Setelah salat Id di Masjidil Haram, orang-orang Mekkah segera pulang ke rumah masing-masing. Acara selesai. Tak ada tradisi salam-salaman melingkar yang melibatkan seluruh jamaah salat. Dalam kamus salafi, apa yang kita selenggarakan terkait tradisi-tradisi di atas “tidak ada dalilnya” alias bid’ah. Dan kitalah para pelaku bid’ah itu. Orang Indonesia. Islamnya orang Indonesia ya Islam Nusantara.
Ini belum termasuk jika kita menengok tradisi puasa yang dipenuhi kekhasan “Islam Nusantara”, yang sekaligus membedakan puasa kita dengan saudara-saudara kita di Arab, yakni tradisi “takjil(an)”, penabuhan bedug, pengumuman suara imsak di TOA langgar dan masjid, ngabuburit, upacara mercon/petasan, juga acara takbir keliling dengan oncor bambu atau parade motor. Saya jamin, acara-acara tersebut tak ada di Arab.
Kita, orang Indonesia, baik yang menggugat konsep Islam Nusantara maupun yang mendukungnya, sebenarnya telah menjalankan “Islam Nusantara” secara murni dan konsekuen.
Tidakkah oncor yang kita gunakan untuk takbir keliling itu sebenarnya adalah “lilin” yang kita nyinyiri sebagai simbol aksi dukungan Ahok? Tidakkah takbir yang dipekikkan kelompok Habib Rizieq dan Aksi Bela Islam-nya juga kita gemakan bersama-sama sejak malam lebaran?
Jika Anda terheran-heran dengan postingan viral tentang Patih Gadjah Mada yang telah memeluk Islam dan berganti nama menjadi Syeikh Gaj Ahmada, Anda perlu sedikit relaks. Karena saya yakin-seyakinnya, Universitas Gadjah Mada(UGM) tidak akan mengubah namanya menjadi Universitas Gaj Ahmada (UGA). Keyakinan saya ini tidak ingin membela bahwa Gajah Mada itu penganut Siwa-Budha ataupun sebaliknya. Bukan. Sama sekali bukan.
Saya tidak ingin memperkeruh suasana. Entah Gadjah Mada itu pemeluk Islam atau Siwa-Budha, tetap saja, menurut survei pemandangan mata saya, mahasiswi-mahasiswi UGM saat ini sebagian besar telah berjilbab. Bahkan jilbab dan hijabnya lebih besar daripada mahasiswi UIN Sunan Kalijaga di sebelah selatannya. Dan Saya yakin-seyakinnya, sebentar lagi akan diadakan “halalbihalal” di UGM.
Anda bisa menambah daftar yang telah saya sebut.
Bukan apa-apa. Para jomblo lebih mengharapkan suasana yang “menyatukan” daripada yang “membelah”.
Lebaran kita yang khas Indonesia, bisa juga kita pandang sebagai peristiwa “Full-Day School” tanpa perlu ruang peresmian dan perselisihan yang menguras energi. Ia mengajarkan karakter khas kita, sebagai penguatan jati diri bangsa dalam mengelola keragaman—layaknya mengelola perbedaaan penentuan hari raya idul fitri yang sudah kita akrabi.
Lebaran kita yang khas ini tentu adalah lebaran Indonesia. Dan saya harap, sesuai sila ketiga Pancasila, semoga lebaran kita ini menyatukan. Lebaran kita adalah Indonesia. Lebaran kita adalah Pancasila.
Lebar puasanya, luber makanannya, lebur dosa-dosa kita.
Allahu akbar, wa lillahil hamd.
Kapan kawin, Mblo?