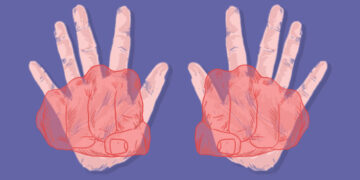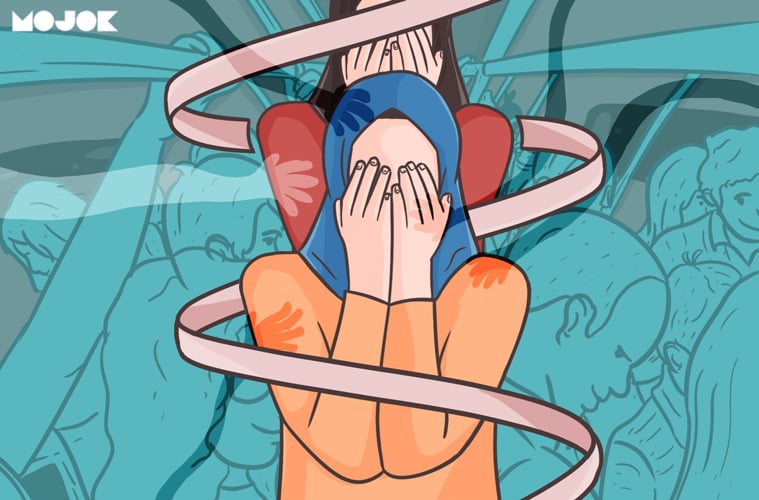Sebelumnya, saya ingatkan di awal tulisan bahwa contoh cerita yang saya tulis ini bersifat TW alias Triggered Warning. Bagi kalian yang nggak kuat, boleh mundur dulu ya.
Seorang ayah tiri memperkosa anak perempuannya selama sembilan tahun. Si anak baru melaporkan kejadian yang dialaminya karena ia baru menyadari apa yang terjadi padanya sejak usia 9 tahun itu merupakan pemerkosaan. Kok bisa?
Dulu, ia sama sekali tak memahami itu. Pelaku pemerkosaan, sang ayah tiri, selalu meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Termasuk ketika ada sentuhan yang tak diinginkan pada tubuhnya, si ayah selalu mengulang bahwa itu adalah wujud kasih sayang.
Korban baru menyadari setelah memproses segala hal yang terjadi kepada dirinya sebagai kekerasan seksual setelah remaja, bahwa ia telah dimanipulasi selama bertahun-tahun. Manipulasi tidak selalu datang dengan kata kasar atau senjata tajam, melainkan tipuan kalimat yang amat halus dan menjebak.
Ia sempat jijik kepada diri sendiri untuk waktu yang lama, memproses peristiwa demi peristiwa yang pernah ia lewati hingga akhirnya menyadari dirinya adalah korban yang boleh melawan dan mencari keadilan.
Setiap kali membaca pengalaman perempuan korban kekerasan, saya selalu berpikir jika sampai hari ini saya lebih beruntung karena tak mengalami hal yang menyedihkan itu, sepertinya itu benar-benar karena takdir semata.
Pengetahuan tentang otoritas tubuh adalah sesuatu yang tak pernah saya dapatkan secara cuma-cuma, baik lewat keluarga maupun lewat sekolah.
Saat belajar di madrasah, saya pernah kebingungan menerima penjelasan salah satu aktivitas yang membatalkan puasa, yang tertulis bersenggama pada siang hari.
Sampai rumah, saya bertanya dengan polos kepada Bapak, apa itu senggama? Tapi siang itu, Bapak menampar mulut saya dengan spontan dan marah mengapa saya bertanya demikian.
Saya belum paham bahwa membahas peristiwa reproduksi seksual secara terbuka merupakan hal yang tabu, apalagi oleh anak kecil usia SD yang masih sangat polos.
Setelah puluhan tahun sejak peristiwa itu, saya membaca pertanyaan dari seorang remaja usia 15 tahun di akun Menfess, apakah seseorang bisa hamil karena masturbasi?
Bagaikan berkaca pada diri saya yang lalu, penuh dengan pertanyaan yang tak bisa saya jawab sendiri saat belum ada mesin pencari. Bayangkan, betapa lembaga keluarga yang seharusnya bertugas memberi pendidikan perihal seksualitas justru absen hadir, sehingga seorang anak mesti lari ke akun base demi menjawab rasa penasarannya.
Saya juga teringat cerita remaja yang mengadu ke lembaga layanan bahwa ia hamil karena percaya bahwa ngeseks satu kali saja tidak akan membuat hamil. Maka iseng saja, katanya.
Orang tua dan lembaga pendidikan lebih memilih untuk menabukan seks sampai hari ini. Negara tidak memberikan hak dasar anak untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang tubuh, kesehatan reproduksi dan seksualitas.
Consent atau persetujuan seksual adalah sebagian pengetahuan dalam kurikulum Comprehensive Sexuality Education. Ketika kamu paham bahwa tubuhmu adalah hakmu, kamu akan membuat batas-batas privasimu sendiri.
Kamu lah yang memberi batasan ruang aman dan nyaman untuk tubuhmu. Kamu akan diajarkan bagaimana keterampilan berkomunikasi asertif ketika batasan yang kamu buat untuk dirimu itu dilanggar. Yang paling penting, kamu tahu kamu boleh melawan ketika orang lain tidak menghormati otoritas tubuhmu.
Demikian jelasnya konsep consent untuk memberikan hak atas rasa aman buat tubuh, saya selalu mempertanyakan, “Kok bisa orang mikir kalau persetujuan seksual itu akan membuat semua orang rajin mantap-mantap sembarangan?”
Parah bener sih imajinasi itu. Dipikir orang-orang nggak punya nalar kritis, nggak punya value untuk dirinya sendiri.
Lha wong berbagai riset tentang Comprehensive Sex Education di level global justru terbukti efektif pada beberapa indikator, antara lain untuk meningkatkan awareness soal HIV, menolak ajakan seks, penundaan seks pertama sebelum usia legal dan jumlah pasangan seks jeh.
Dipepet orang lalu berujung mantap-mantap sembarangan itu kan imajinasi cerbung dewasa saja. Jika imajinasi kalian masih sebatas itu, tolong dibersihkan dulu pikiran kotor yang demikian.
Saya punya pengalaman tidak menyenangkan soal catcalling. Apa ya padanannya dalam bahasa Indonesia, emm…sebut saja aktivitas bersiul kepada pengguna jalan dengan tujuan membuatnya tak nyaman.
Dulu, saya memilih memutar jauh sekali setiap kali pulang les sore semata agar tak berjumpa dengan segerombolan laki-laki yang gemar catcalling di perempatan. Keputusan itu merepotkan sekali, sebab seharusnya saya bisa menghemat waktu lima belas menit jika lewat jalur biasanya.
Seandainya pada masa itu saya sudah paham konsep consent, saya mungkin tak akan memutar jalan sebab bukan saya yang seharusnya merasa ketakutan. Saya bisa mendatangi para penganggur di jalan kampung itu untuk mengingatkan jika aktivitasnya itu primitif dan melanggar hak tubuh seseorang akan rasa aman.
Itu consent. Itulah persetujuan seksual.
Entah bersumber dari tradisi mana, perempuan yang diam dianggap bersetuju. Anggapan ini sepertinya membuat sebagian laki-laki memilih asal sentuh, asal cium dan asal-asalan lainnya.
Padahal, ketika perempuan terdiam, bisa saja ia tengah mengalami tonic immobility. Ia terkejut dengan sentuhan yang tiba-tiba, respons tubuhnya tidak bisa memproses dengan baik apa yang ia alami selain dengan menjadi kaku, gagal lari alias diam saja.
Consent mengajarkan seseorang untuk memahami bahwa “no means no“, tidak artinya tidak, dan “yes means yes“, iya artinya iya. Semua keputusan mesti diutarakan dengan jelas dan antusias tanpa tekanan.
Dalam penyelesaian kasus hukum seperti pemerkosaan, konsep consent dihadirkan untuk melihat seberapa timpang relasi kuasa antara pelaku dan korban. Sebabnya, banyak alat penegak hukum tidak berperspektif korban yang gemar mengajukan pertanyaan tak masuk akal kepada korban pemerkosaan:
Kenapa kamu tidak lari? Kenapa kamu diam saja? Kamu menikmati kan?
Pertanyaan yang membuat korban menjadi korban dua kali itu diajukan tanpa memandang konteks bagaimana korban yang siswi kelas 6 SD berlari jika pelaku pemerkosaan adalah guru usia 40 tahun yang telah mengancamnya sejak lama?
Bagaimana korban yang disabilitas bisa melawan ketika ia tak bisa mendefinisikan apa yang ia alami sebagai kekerasan seksual?
Dengan demikian, membicarakan persetujuan seksual dengan melihat ketimpangan relasi kuasa akan membantu korban mencari keadilan. Melihat ketimpangan relasi kuasa mendidik penyidik agar tak mengajukan pertanyaan jahat kepada korban.
Sebab, consent tidak dianggap sebagai consent jika tidak freely given. Kekerasan seksual yang terjadi sebab pelakunya melancarkan abuse of power dari gelar, jabatan dan uang yang ia punya mesti diperberat hukumannya.
Consent membuat saya paham bahwa sebagai manusia yang setara dengan manusia lainnya, tubuh saya berhak atas hak paling dasar atas rasa aman. Sekalipun itu dalam relasi suami-istri, tubuhmu adalah milikmu dan berpasangan tak membuat pasanganmu bebas melakukan apa saja yang membuatmu tak nyaman atau membahayakan fungsi reproduksimu.
Kecuali kalau kamu menganggap dirimu nggak punya kedaulatan tubuh, pikiran dan keputusan karena percaya bahwa level kemanusiaanmu selamanya bersifat subordinate/second class subject, memang sulit sih memahami kedaulatan diri (consent).
Nggak papa, besok-besok juga kamu akan paham.
Kamu bisa baca kolom Kelas-Kalis lainnya di sini. Rutin diisi oleh Kalis Mardiasih, tayang saban hari Minggu.