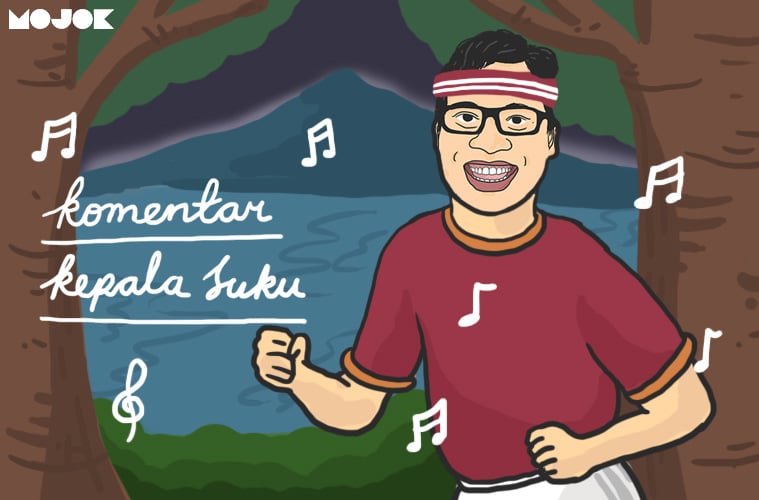MOJOK.CO – Kerusuhan terjadi. Ketegangan politik mengintai. Polarisasi dua kubu tak terelakkan. Lantas, semua saling menyalahkan, lalu mengungkit-ungkit persatuan.
Kerusuhan skala kecil meletus di Jakarta. Tapi kita semua tahu, ini mungkin hanya letusan awal yang mungkin akan menjadi babak baru di wajah sosial kita.
Letusan ini tentu tidak turun dari langit seketika tanpa pertanda. Atau, meledak tanpa musabab. Pasti ada sekian variabel yang mendukungnya. Ada sejumlah item yang jadi onggokan kayu bakar kering, lalu satu percik api, terbakar sudah.
Mari kita mulai dari hal yang paling mudah. Setidaknya, diam-diam kita semua telah menyaksikannya, atau malah jangan-jangan menjadi pelakunya, walaupun tidak sadar.
Selama kurang lebih 5 tahun, kita ada dalam ketegangan politik. Ada polarisasi dua kubu. Kedua kubu menggunakan cara yang serupa, mirip satu sama lain. Kreatif dalam melakukan merencanakan dan menyebarkan fitnah, fasih dalam soal perundungan, dan hiperaktif dalam menghujat lawan.
Dari situ saja kita tahu bahwa ongkos apa yang sering kita sebut “pesta demokrasi” dan persatuan begitu mahal. Dan bukan hanya itu: memadamkan baranya, menyurutkan pertikaiannya, mendinginkan suasananya, akan butuh waktu lama.
Tapi ada pertanyaan yang terselip di pikiran saya: apakah benar persoalan pokok kita hanya itu? Apakah cuma gara-gara politik elektoral saja, suasana bisa terjaga begitu panas sampai 5 tahun?
Banyak orang bilang, itu karena pengaruh media sosial dan dunia digital. Ya, mungkin ada benarnya. Tapi sebagai sebuah peranti yang diproses dan ditemukan oleh peradaban, media sosial dan dunia digital sebagaimana hal lain: dia hanya medium. Dia teknologi. Dia seperti surat kabar atau barang cetak, dia seperti kendaraan bermotor. Memang, kalau dipakai untuk serampangan, ugal-ugalan, sesuka hati, bisa memiliki dampak negatif. Tapi, jika digunakan untuk menyebarkan informasi yang baik, menyampaikan pengetahuan, medium bagi diseminasi keilmuan, tentu berdampak positif.
Namun sebentar—bukankah sejarah luka kita, kerusuhan dan konflik sosial yang selalu ada dalam wajah kita, terjadi sebelum era digital dan maraknya media sosial?
Sebetulnya inilah tugas para intelektual, cerdik pandai, budayawan, dan seniman. Merekalah yang diberi perangkat keilmuan, serta kemampuan menilai dan menakar, memindai apa yang tidak terucapkan oleh publik.
Tapi sayang, pesta demokrasi kita pun telah merebut mereka semua untuk masuk ke gelanggang pertarungan. Ketika para elite politik berebut kekuasaan, para cendekiawan, budayawan, seniman, mestinya bersama masyarakat. Tujuannya, untuk menjaga agar benturan tak terjadi dengan keras. Memagari dengan rambu-rambu etik, mengingatkan ada batas yang tak boleh dilanggar.
Tapi kita semua tahu, berduyun-duyun, para intelektual, budayawan, dan seniman menjadi tukang sorak mereka yang berebut kekuasaan. Menjadi alas kaki dan tameng elite politik kita.
Pagar yang membatasi panggung kekuasaan dengan masyarakat begitu rapuh. Bantalan yang membuat gesekan antarmasyarakat, yang mestinya membat dan empuk sehingga tak melukai siapa pun, malah kosong. Siapa yang tidak berada di 01, dianggap 02. Siapa yang tak terlihat di 02 adalah 01. Semua harus berpihak. Berpihak pun harus dengan keras kepala. Politik elektoral menjadi agenda yang seakan lebih penting dari kedamaian negeri ini, kenyamanan berwarga negara, serta kemanusiaan yang terawat dan terjaga.
Panggung kekuasaan begitu menyilaukan mata sehingga mata batin para seniman tak lagi bisa menembus keresahan rakyat kecil yang terpinggirkan. Seniman yang konon dianugerahi kemampuan untuk setia kepada hati nurani dan kepekaan perasaan kini berlomba menghasilkan karya untuk sebuah pesta yang, kita tahu, tak butuh-butuh amat diglorifikasi sedemikian rupa.
Para cendekiawan, cerdik pandai, ilmuwan, dan budayawan, memeras pikiran mereka bukan untuk agenda kemaslahatan umat dan persatuan, tapi untuk menemukan argumen yang adekuat menangkis serangan lawan, menyusun desain kampanye yang bisa efektif melumpuhkan lawan.
Semua tiba-tiba menjadi binatang buas politik yang tak lagi dikendalikan oleh kadar moral dan kebijaksanaan.
Lalu ketika letusan ini terjadi, semua seolah cuci tangan. Saling menyalahkan. Naik ke mimbar dan berkhotbah tentang pentingnya menjaga persatuan, menjaga kedamaian, menjaga kemanusiaan. Persatuan yang ikut mereka cabik-cabik, persatuan yang ikut mereka bikin rantas, kemanusiaan yang sudah mereka tinggalkan sejak lama.
Sudah terlalu banyak orang hebat dan baik di negeri ini yang menjual integritas, bakat, dan hati nurani mereka, hanya untuk menjadi alas kekuasaan.
Sudah lama mereka meninggalkan rakyat dan persatuan. Tidak ada lagi yang menemani orang-orang biasa. Warga negara yang tulus dan ikhlas hidup di negeri ini. Bekerja menggerakkan roda perekonomian. Saling berbagi dalam kenestapaan.
Sudah saatnya kita semua menyadari ini. Lalu kembali. Politik itu penting, tapi ada batasnya. Semua yang tak punya batas, pasti melakukan sesuatu yang tak pantas.
Kembalilah wahai para intelektual, budayawan, seniman, dan para aktivis sosial, ke haribaan rakyat jelata. Tempat di mana kasih sayang Tuhan ditanamkan dalam-dalam!