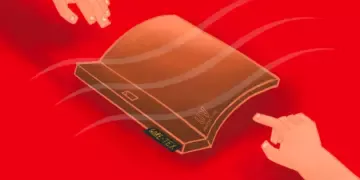Eddward Samadyo Kennedy…
Aku tahu, dini hari seperti ini kamu ada pada situasi yang tak menentu. Memang begitu takdir sebagai redaktur Mojok, sebagaimana yang satu tahun dialami oleh Arlian Buana, tandemmu.
Ketika ada naskah bagus, rasanya tak sabar untuk segera mengunggah ke situsweb kesayangan kita semua ini, tapi kalau tak ada naskah yang bagus, detik yang berlalu seperti pukulan palu. Mengejar beberapa penulis yang punya pengalaman dan jam terbang, sadar bahwa mereka belum tentu punya ide dan waktu, tapi tetap diminta menulis, sembari menunggu karomah, siapa tahu ada naskah bagus terkirim usai azan Subuh, sesaat sebelum fajar pecah.
Samadyo yang baik…
Juga sudah menjadi takdirku, setiap kali tidak ada naskah yang bagus menurut kalian, maka aku harus menjalankan dharma sebagai kepala suku: melahirkan tulisan. Mengisi apa yang tak boleh kosong. Sebab kita sadar betul, ada banyak orang yang begitu bangun tidur, belum sempat mencuci muka dan mencium anak istri, membuka terlebih dahulu laman kesayangan mereka ini.
Mungkin banyak orang berpikir betapa menterengnya jabatan Kepala Suku ini, Samadyo. Tapi kamu pasti tahu, ketika habis memimpin sekian rapat di hari yang meletihkan, aku harus mencadangkan energiku untuk menulis. Terkadang aku pengen sesekali menambah keterangan jabatan Kepala Suku dengan kalimat: ‘sekaligus ban serep tulisan’.
Sekalipun Kepala Suku adalah jabatan tertinggi di Mojok, tapi aku harus taat azas. Bukan begitu, Samadyo? Seperti potongan namamu yang menurutku berarti ‘orang yang harus selalu siap sedia’. Tapi aku bisa salah. Karena aku sedang malas menguji pikiranku lewat Google. Jangan-jangan ‘Samadyo’ yang dimaksud dalam namamu berarti: sekadarnya, secukupnya.
Jadi, pada menjelang Subuh ini, aku harus menulis tentang Pemerintahan Jokowi-JK. Tulisan yang tak lagi penting apakah bakal bagus atau buruk. Sebab bagus dan buruk itu untuk kasta para penulis Mojok. Kalau untuk Kepala Suku, semua lenyap. Cuma ada dua yang tertinggal: kewajiban dan tanggungjawab.
Baiklah, Samadyo…
Mari kita lanjutkan ke tema kita. Semua orang tahu, makin hari makin banyak orang yang mengritik pemerintahan ini. Kebanyakan dari mereka tentu kecewa. Tapi kenapa mereka kecewa? Sebab pernah punya harapan. Kenapa punya harapan? Sebab mereka pernah punya pengalaman dikecewakan. Kekecewaan yang terus-menerus terjadi, seperti perahu mati mesin di tengah lautan. Ada awan sedikit, dikira pulau. Ada batang kayu kemampul, dipikir perahu lain.
Kekecewaan kepada sesuatu, cenderung membuat banyak orang, menganggap beling dari pantat botol bir terlihat seperti zamrud. Jokowi-JK menurutku berada dalam posisi sebagai beling dari pantat botol bir. Kata kuncinya ‘posisi’ ya, bukan ‘beling dari pantat botol bir’. Aku tegaskan ini supaya tidak mudah dipelintir.
Jadi, sumber kekecewaan itu terletak bukan pada Pemerintahan Jokowi-JK, melainkan karena terlalu tingginya harapan kita. Dan harapan kita yang membubung tinggi seperti itu, bukan hanya monopoli persoalan Jokowi. Kita juga mendadak suka pemimpin yang gemar mengumpat, sebab terlalu lama kita dikecewakan oleh ilusi kesantunan dan kelembekan, sehingga ketegasan yang kita impikan seakan identik dengan kemarahan dan umpatan. Jadilah kemudian kita takjub dengan pemimpin yang suka marah dan gemar memaki.
Demikian juga dengan Pemerintah saat ini. Karena dulu yang memimpin selama sepuluh tahun bergerak dengan lambat dan gradual, sementara kita menginginkan perubahan yang cepat, lalu kita tumpukan harapan kita pada sosok yang melipat baju putih lengan panjangnya, sebagai simbol kecepatan dalam bekerja.
Sigap. Cepat. Kerja. Kerja. Kerja.
Sialnya, harapan punya kecepatannya sendiri yang melenting jauh ke depan. Jauh meninggalkan figur berbaju putih, berlengan panjang yang dilipat.
Kisah ini memang mirip dengan persoalan asmara. Kalau ada orang yang terus ditolak cintanya, siapapun orang yang mau dengannya terlihat mempesona. Kalau tidak percaya, silakan tanya ke Arman Dhani atau Agus Mulyadi. Begitu putus asanya mereka di bidang asmara, melihat ada tiang listrik pun seakan gadis jelita. Sehingga ditembaklah tiang listrik itu. Karena tiang listrik tak punya mulut, maka dia diam. Lalu lantaran Arman Dhani dan Agus Mulyadi punya prinsip ‘cewek yang ditembak diam berarti mengiyakan’, maka mereka bersorak girang. Menganggap sudah punya pacar. Esok harinya mereka berdua baru sadar bahwa pacar mereka yang semalam diam ketika ditembak, ternyata tiang listrik.
Kisah asmara mereka berdua memang mengenaskan, Samadyo. Kamu boleh tertawa. Tapi sesungguhnya kisah kita sebagai warganegara Indonesia kurang-lebih sama dengan kisah asmara mereka berdua.
Pengen punya Presiden yang bekerja cepat, akhirnya kita pilih yang baju putihnya terlipat. Suka ketegasan, akhirnya mengidolakan Gubernur yang suka ngamukan.
Tapi apakah kita salah? Apakah kita keliru kalau punya harapan?
Arman Dhani dan Agus Mulyadi juga punya hati. Apakah mereka salah kalau jatuh cinta? Apakah mereka keliru kalau berharap punya kekasih yang mempesona?
Samadyo yang baik…
Kelak di pemilihan umum yang akan datang, aku yakin kita bakal terus seperti ini. Ada dalam siklus kecewa-harapan-kecewa-harapan demikian terus. Tapi mungkin itulah bumbu kehidupan. Ya, mungkin kita ini hanyalah bumbu untuk menu besar yang terus dimasak, yang biasa disebut sebagai ‘politik’.
Jadi sebetulnya kepada siapa kita kecewa? Benarkah kepada Jokowi? Jangan-jangan sebetulnya kita kecewa kepada diri kita sendiri. Diri yang terus mengulang ketololan berkali-kali.
Samadyo, tolong diedit tulisan ini ya…
Karena kalau aku menulis banyak sekali terjadi salah ketik. Tapi setidaknya aku tak seperti Arman Dhani dan Agus Mulyadi yang punya potensi menembak tiang listrik.
Sudah ya, Samadyo…
Saatnya kamu mengunggah tulisan, lalu tidur. Jangan lupa pintu kantor dikunci. Tapi mengunci pintunya dari dalam kantor, jangan dari luar ya…
Salam.