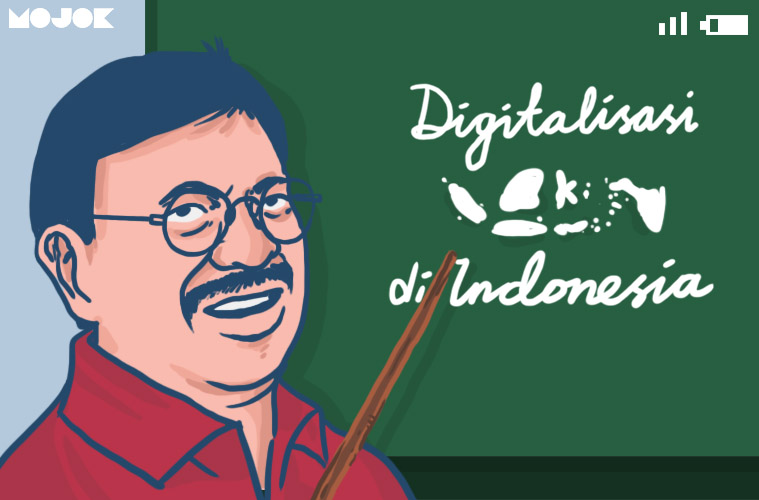Ketika Yang Terhormat Bapak Menkominfo berbekal rekomendasi dari BNPT memblokir 22 situs bertema Islam, tampaknya beliau tidak menyadari bahwa setidaknya ada dua implikasi yang mungkin di luar perhitungannya.
Pertama, beliau tidak sadar sedang menabrak misi penting Presiden Jokowi untuk membuka 10 juta lapangan kerja.
Sekarang zamannya online. Untuk bisnis informasi (juga bisnis dis-informasi?), jagat internet memegang tampuk kekuasaan. Mendulang nafkah lewat situs-situs online sudah menjadi mata pencaharian banyak orang. Satu jenis pekerjaan yang 20 tahun silam belum masuk ke imajinasi anak-anak akan cita-cita saat dewasa, apalagi masuk ke tayangan iklan susu formula.
Situs-situs “islami” yang diblokir tersebut bukan perkecualian. Saya amati, hingga dua tahun lalu situs-situs begituan sepi-sepi saja. Paling-paling yang agak dibaca orang ya Eramuslim, karena banyak kisah Freemason dan Novus Ordo Seclorum di sana. Namun belakangan, pating jrudul situs-situs beraroma Islam yang terkerek naik ke panggung secara cepat. Bahkan sangat cepat. Tren itu nge-boom, menemukan titik terpanasnya, di sekitaran Pilpres 2014. Betul, kan? Hehe. Kenapa bisa begitu?
Simpel saja. Pada musim Pilpres kemarin, agama menemukan revitalisasi fungsinya dalam peradaban, yakni sebagai alat marketing politik. Bahkan akhirnya terbukti agama menjadi mata dagangan yang mega-bestseller. Konkret sekali peran agama pada bulan-bulan itu. Situs-situs yang semula hanya mengabarkan ajaran agama pada posisi dasarnya, tiba-tiba riuh bicara politik dalam bingkai “agama”. Fokusnya pun jelas, tak henti mengabarkan adanya kekuatan-kekuatan politik yang mengancam agama. Secara marketing, ini memang sangat cerdas. Taktis luar biasa.
Pada titik itu, saya jadi ingat sebuah iklan suplemen untuk ibu hamil, yang memproklamirkan bahwa produknya bisa mencegah cacat fisik pada bayi di kandungan. Bayangkan, ibaratnya begini: “Ibu, kalau Anda nggak minum produk saya, anak Ibu bisa cacat lho!” Edan. Maka, produk itu pun laris manis. Barang tentu, penyebabnya satu hal: ketakutan. Rasa terancam. Dengan menyebarkan rasa takut, para ibu cemas akan nasib anaknya, lantas mengkonsumsi produk yang diklaim bisa menyelamatkannya. Produsen suplemen tadi sedang menjalankan industri rasa takut.
Terbukti, dengan pola marketing yang sama, yakni marketing ala industri penjual rasa takut, situs-situs “islami” tertentu juga berhasil mendulang rating. Sebuah situs yang semula hanya mengabarkan kegiatan-kegiatan partai politiknya, sebagai contoh, lantas berubah menjadi etalase kabar-kabar ancaman dari kelompok politik yang ia lawan. Hasilnya gimana? Tentu saja: laris manis tanjung kimpul.
Dari sini pasar pun terbentuk secara sempurna. Ceruk pasar potensial ini terus digali, dikelola sebagai mesin pendulang dolar, dan di-maintain secara berkelanjutan. Cara me-maintain-nya ya apa lagi, selain dengan terus-menerus memelihara kecemasan, perasaaan terancam, yang berujung pada kapitalisasi kebencian. Lantas bagaimana nasib pencerdasan masyarakat dengan berita-berita panas yang digoreng tanpa henti oleh situs-situs tersebut? Walah, Sampeyan itu kalau tanya mbok ya jangan muluk-muluk gitu to…
Nah, ketika Menkominfo memblokir ke-22 situs yang dipandang bermasalah, bayangkan saja, ada berapa manusia yang terjungkal periuk nasinya? Banyak sekali. Ada berapa duit yang lenyap karena tutupnya situs-situs itu? Buanyaaaaaak sekali. Salah satu situs begituan bisa mendulang hingga 4 juta rupiah per hari! Hanya dengan mengandalkan Ad Sense, belum lagi iklan banner dan lain-lain. Coba, bisakah Pak Menteri mengganti periuk-periuk yang hilang itu? Enggak bakal bisa. Dan kalau soal itu, Pak Menkominfo boleh menjawab: “Bukan urusan saya.” Hehe.
“Lho! Situs-situs dakwah kok kamu bilang cuma cari duit to Bal?? Fitnah! Mereka itu berjuang demi kejayaan Islam!! Ah, dasar kamu liberal sesat antek Jokowi!!”
Eit, mbok sabar to. Lugunya disudahin dulu. Saya percaya kok, banyak di antara mereka yang tulus memperjuangkan apa yang mereka yakini. Tapi takdir alam fana dunia sudah bersabda: “Di hadapan Tuhan, semua manusia sama derajatnya. Di hadapan uang, semua manusia sama agamanya.” Buktinya, saya pernah mengkonfrontir langsung ke salah satu “redaktur” situs begituan (Duh, mereka bukan lembaga pers, apa layak disebut redaktur?). Saya tanya kenapa mereka tetap mengunggah berita Anu yang jelas-jelas hoax? Ternyata akhi yang satu itu diam tanpa jawaban. Hening. Hanya terdengar suara jengkerik yang sayup-sayup menemani malam. Huhuhu.
Itu implikasi yang pertama. Yang kedua, Bapak Menkominfo mungkin tidak sadar, bahwa pemblokiran itu merupakan bentuk pelecehan serius pada mayoritas kaum muslimin yang cinta damai. Dikiranya efek berita-berita provokatif, fitnah, dan gorengan-gorengan berita penyembah rating, tidak dapat diimbangi oleh para penulis cerdas dan islami, yang saya yakin sebenarnya jauh lebih banyak dibanding penulis berita-berita sampah berlabel halal.
Nah, dalam era demokrasi informasi (kalau memang Pak Menteri bukan pendukung khilafah informasi), kenapa tidak memotivasi saja para penulis islami cinta damai agar secara serentak menebarkan anti-virus ekstremisme? Itu memang tugas maha-berat. Toh nyatanya Pak Tifatul pada masanya juga nggak bisa melakukan itu, dan lebih memilih memblokir juga 300 situs radikal. (Bedanya, waktu itu presidennya Pak SBY. Dan Pak SBY bukan musuh Islam to? Nguik.) Tapi seberat apa pun, tetap wajib dilaksanakan.
Jangan salah paham, saya tidak sedang mengatakan bahwa penulis-penulis baik hanya ada di luar situs-situs islami yang diblokir itu. Gara-gara prahara ini, saya jadi membaca juga beberapa tulisan yang ditayangkan di situs-situs tersebut. Boleh saya katakan bahwa secara kuantitas, sebenarnya lebih banyak materi yang baik daripada yang “jahat”. Misalnya tulisan-tulisan Mbak Ria Fariana di Dakwatuna dan VOA-Islam, ‘ainul yaqin, saya bersaksi bahwa buah-buah pikirannyan sangat bermanfaat bagi kemaslahatan semesta. Repotnya, kodrat media telanjur berkata: bad news is good news. Lebih gampang menyebarkan kabar buruk—entah fakta entah hoax—ketimbang kabar baik. Jadilah konten situs yang ngehek jauh lebih ngangkat ketimbang yang cakep-cakep.
Tapi apa pun itu, saya yakin Pak Menteri Rudiantara butuh piknik. Pasti bakalan lebih cantik cara main Bapak, kalau yang disikat bukan situsnya, melainkan konten-konten spesifik di dalamnya yang memang berbahaya menurut kacamata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jika memang ketemu situs dengan materi-materi brengsek yang dominan, cokok saja adminnya, seret ke pengadilan, suruh push up dulu bila perlu. Kalau ada situs lain yang masih jualan api tapi dengan porsi yang minimalis, cukup ajak adminnya ngopi-ngopi. Percayalah, kafein akan menurunkan kadar kebencian dan prasangka dalam aliran darah kita.
Lah, kalau nggak ketemu redaktur atau pengurus situsnya, gimana? Bukannya situs-situs itu sebenarnya memang cuma sekelas blog dan sama sekali tidak layak untuk disebut sebagai lembaga pers? Sebagian malah nggak jelas siapa pengelolanya dan di mana kantornya lho!
Ah, itu mah gampang. Bilang saja ke Pak Tedjo Edi. Masak cuma buat cari siapa admin-admin situs ngehek itu Pak Tedjo nggak bisa? Atau… mesti ngadu ke Pak Hendro lagi? Aduhdek.