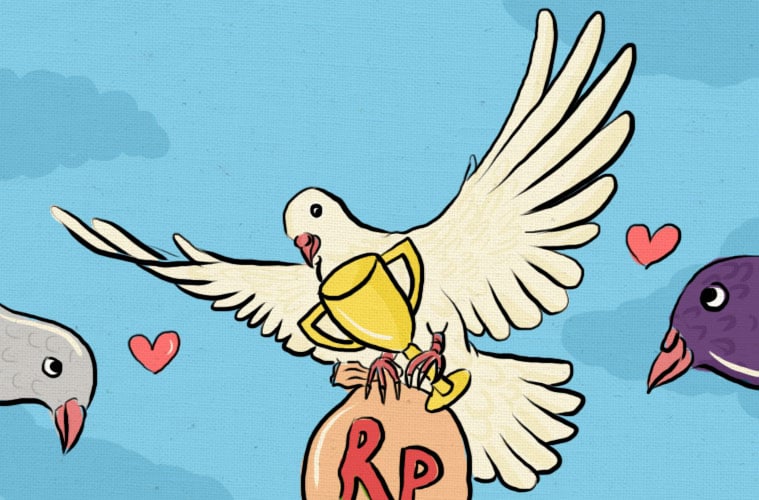Almaghfurlah K.H. Maimun Zubair pernah memberikan petuah. Beliau bilang bahwa uang mahar itu mengandung berkah kalau dijadikan modal usaha.
Demi mengamalkan petuah Mbah Maimun Zubair, dengan uang mahar, ditambah uang hasil menjual sepeda motor, plus uang pinjaman dari seorang kawan yang waktu itu bekerja sebagai asisten mantan ketua partai politik, usaha sayuran menjadi lembaran baru setelah saya menamatkan studi S2. Sedihnya, uang mahar tersebut tidak lain adalah uang yang ditransfer via ATM oleh mantan calon mertua yang membatalkan pernikahan saya dengan putrinya.
Perlu saya jelaskan di awal. Alasan banting setir ini bukan disebabkan rasa enggan menjadi budak korporat, demi mencapai kemerdekaan finansial, atau yang kata sebagian orang sebagai kapitalis kecil. Tidak! Jauh dari praduga semacam itu. Alasannya sederhana: dorongan mewujudkan petuah Mbah Maimun Zubair, utang di atas 10 juta, dan ekonomi keluarga saya sedang tidak baik-baik saja.
Sebelumnya, saya bekerja di sebuah NGO asal Swiss yang gajinya di atas UMR Jogja. Saya juga mengajar di salah satu Madrasah Aliyah di lingkungan pesantren tempat saya bermukim selama kuliah sebelum memutuskan untuk mengontrak rumah sederhana di daerah Kalasan, Jogja. Dengan pekerjaan itu dan nanti setelah lulus kuliah saya mulai meniti karier sebagai dosen, kiranya sudah masuk akal kalau saya memberanikan diri untuk menikah?
Walakin, semesta bukannya mengamini niat baik itu, melainkan membelokkan arah kompas hidup saya 180 derajat. Ibarat naik kereta api, saya bukannya berhenti di stasiun untuk menentukan arah berikutnya, tetapi diturunkan di tengah sawah pada malam hari yang gulita.
Dalam rentang waktu tidak sampai satu tahun, saya menjalani semacam antiklimaks dalam perjalanan hidup menuju usia 28 tahun. Pertama, saya kehilangan pemasukan utama karena pendanaan yang diberhentikan. Menjadi seorang guru, apalagi di pesantren, tentu tidak elok kalau saya mengharapkan gaji darinya. Wong saya ini siap mengajar karena saya sudah ada pemasukan utama dari NGO itu je.
Sebagaimana petuah Mbah Maimun Zubair yang populer lainnya bahwa seorang guru selayaknya memiliki usaha atau pekerjaan lain sehingga ketika mendidik dia tidak serta merta mengandalkan gaji dari mengajarnya. Begitu kira-kira.
Kedua, ibu saya yang berprofesi sebagai pedagang sayuran di sebuah pasar tradisional mulai jarang menjajakan dagangannya karena sepi. Padahal, dari hasil berjualan inilah saya dan adik-adik dibesarkan. Nampaknya, kondisi pailit ini disebabkan terutama oleh semakin menjamurnya para pedagang sayur keliling yang masuk ke gang-gang perumahan dan dusun-dusun. Mungkin kalau menggunakan istilah sekarang diistilahkan dengan “disrupsi bisnis sayuran”.
Sebenarnya ada satu peristiwa lagi yang memacu saya untuk segera lulus kuliah. Ibarat pecut yang disabetkan ke tubuh kerbau agar berjalan semakin kencang. Peristiwa yang saya maksud adalah sebuah panggilan telepon dari calon mertua. Sebuah percakapan singkat dan sangat berarti di mana beliau menyatakan untuk mengakhiri pertunangan saya dan putrinya, sekaligus membatalkan pernikahan yang tinggal dua bulan lagi.
“Ya Allah,” batin saya saat itu, “ini cobaan atau azab ya? Kok barengan kayak gini.”
Sudah tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak jadi menikah, kuliah pun belum selesai. Ini adalah tragedi terburuk yang menjadi salah satu pengalaman terbaik dalam hidup saya.
Mewujudkan petuah Mbah Maimun Zubair
Setelah ujian tesis, yang terlintas dalam benak saya adalah melunasi utang dan menormalkan ekonomi keluarga. Utang itu berasal dari tunggakan SPP, biaya sidang dan wisuda, dan ubo rampe selama menggarap tesis. Kira-kira sekitar 18 juta.
Idealnya, setelah lulus, berbekal ijazah ditambah pengalaman dan aktif ikut penelitian, saya bisa mengawali karier sebagai dosen. Namun, saat itu, saya melakukan riset kecil-kecilan. Saya menanyakan gaji seorang dosen di kampus Islam, baik negeri maupun swasta.
Untuk kampus swasta dengan spirit pengabdian, dan biasanya digunakan sebagai batu loncatan, gajinya antara Rp1 sampai Rp2 juta. Dosen tetap non-PNS antara Rp2 sampai Rp2,75 juta rupiah. Dosen luar biasa, tergantung jam ngajarnya yang hitungan per-SKS-nya sekitar Rp40.000. Seorang teman yang menjadi dosen luar biasa gajinya biasanya dirapel setiap semester yang kira-kira tidak sampai Rp5 juta rupiah.
Dengan gaji senilai Rp2 juta per bulan, dikurangi biaya kos, rokok, dan ongkos sosial, sungguh tidak masuk akal untuk mengurai masalah yang sedang saya hadapi. Kalau untuk diri sendiri dan dalam rangka sebagai batu loncatan sebenarnya tidak masalah. Namun, ketika memperhitungkan masalah keluarga, tentu saja saya tidak bisa sembrono mengambil keputusan.
Bertahan dengan status sebagai kepala sekolah di sebuah madrasah, yang sudah berjalan sekitar enam bulan, sambil berharap untuk diangkat jadi pegawai negeri atau mendapatkan gaji yang layak, misalnya, hanya akan mencederai jiwa pengabdian dan usaha mewujudkan petuah Mbah Maimun Zubair. Ekspektasi semacam itu lebih banyak membuat sakit hati ketimbang sebaliknya.
Saya memutuskan untuk melepaskan jabatan kepala sekolah. Meninggalkan madrasah dan pesantren tempat anak-anak yang saya bawa dari rumah untuk bisa mendapatkan pendidikan di sana. Saya mengalami semacam paradoks yang luar biasa: saya ini mendorong anak-anak di kampung dan sekitarnya untuk sekolah, mengusahakan agar mendapatkan keringanan biaya, sebagiannya juga sudah melanjutkan kuliah, malah saya sendiri mengambil keputusan untuk bisnis sayuran!
Pada titik itu saya mengakui belum bisa meneladani Gus Dur yang lebih mementingkan umat ketimbang keluarganya. Saya belum cukup kuat meneladani dawuh ulama, kiai, dan petuah Mbah Maimun Zubair yang mengatakan bahwa kalau kamu mengajar, rezekimu bakal dijamin dan datang dari arah tak disangka-sangka.
Bisa jadi saya yang kurang iman. Namun, dalam kondisi seperti itu, hitungan rasional dan kalkulasi hati saya benar-benar tidak sampai ke level semacam itu.
Dengan dukungan dan bantuan penuh dari orang tua dan teman-teman terdekat, saya mantap memulai bisnis sayuran ini. Kami menyewa ruko di belakang Hotel Quality dan beberapa kawan menghubungan saya dengan kafe dan penyetan yang masih berlangganan sampai hari ini.
Saya membuat akun Instagram dan bekerja sama dengan seorang fotografer dari Kaliangkrik yang menyuplai gambar-gambar sayuran dan pemandangan agar menarik pelanggan baru. Tahun pertama melalui perantara usaha ini saya bisa melunasi sebagian besar utang, membeli sepeda motor bekas, dan melanjutkan kontrak ruko untuk tahun berikutnya. Memasuki semester ketiga, ibu saya sudah pulang ke rumah dan usaha ini dijalankan bersama saudara dari rumah yang juga berprofesi sebagai driver ojek online.
Aslinya ya biasa saja menekuni bisnis sayuran. Hanya, dan ini di antara yang saya sukai, emosi saya relatif stabil. Saya jadi jarang mengeluh karena banyak administrasi yang harus dikerjakan, pemasukan atau gaji yang sedikit, atau banyaknya jam kerja yang membuat stres dan malas-malasan. Kayak gitu namanya bukan bekerja, tapi kurang pekerjaan.
Melalui usaha ini saya juga dipertemukan dengan lingkaran-lingkaran yang membuat saya tetap bisa menulis. Teman penulis di islami.co, kru Mojok, dan masih terhubung dengan kolega di kampus. Saya tetap menulis, baik dalam sebuah proyek riset, menerjemah, dan menulis artikel yang mana semua itu juga menjadi sumber pemasukan lain bagi saya.
Kuliah S2 saya tidak sia-sia, kok. Kalau ada kesempatan melanjutkan S3 dengan beasiswa penuh atau ada lowongan pekerjaan lain yang memungkinkan saya untuk terus berkembang, dengan tanpa ragu saya akan mencobanya.
Suatu hari, pada momen hari raya Idul Fitri, saya sowan ke salah satu kiai pesantren di tempat saya dididik, dibesarkan, dan disekolahkan. Saat ditawari untuk menjadi dosen. Dengan perasaan yang begitu berat, saya mengatakan “tidak”. Begitu juga dengan tawaran berikutnya yang datang dari dekan salah satu universitas negeri Islam di Indonesia.
Saya menolak bukan karena tidak mau, melainkan belum menjadi prioritas dalam hidup saya saat itu. Yah, meski saat itu, petuah Mbah Maimun Zubair selalu terbayang.
Soal kehidupan percintaan? Sungguh lucu. Pertama, sungguh beruntung perempuan yang tidak jadi saya nikahi waktu itu. Dia tidak perlu ikut berjuang merintis bisnis sayuran. Setelah itu, saya sempat dekat dengan perempuan lainnya.
Setelah dekat selama beberapa bulan, saya mendatangi keluarganya. Saya memperkenalkan diri sebagai mahasiswa lulusan S2 dan saat ini tengah merintis bisnis sayuran. Tidak lama kemudian, saya dapat kabar yang sedih tapi juga lucu setengah mati.
Saya dianggap bisa dekat dengan perempuan itu karena memakai guna-guna. Ya Allah, apakah wajah saya memang seterpuruk itu? Apakah bisnis sayuran itu sedemikian hina? Belum tahu saja itu keluarga. Bisa jadi, di setiap suapan sayur sop yang nikmat itu, wortelnya saya yang suplai. Nggak tahu aja mereka.
Yah, saat itu, saya hanya bisa tersenyum getir. Namun, di saat yang sama, saya menyadari satu hal: hati ini sudah tidak seringkih sebelumnya.
Merintis bisnis sayuran juga membantu saya menjadi sosok yang lebih tangguh menghadapi lucunya kehidupan. Dikira pakai guna-guna, misalnya. Mending keluarga itu saya kirimi satu truk sawi putih ketimbang guna-guna. Lebih sehat dan bermanfaat.
Saya mendapatkan kebermaknaan dalam pekerjaan ini. Dan kebermakaan itu, ternyata, tidak terletak pada apa pekerjaan kita, melainkan bagaimana kita memaknainya.
Cukuplah bagi saya kini, seperti nasehat Mark Manson, untuk sedikit bermimpi dan banyak bekerja. Menikmati pekerjaan yang sedang dijalani sembari menyiapkan sikap batin pada kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal datang di kemudian hari.
BACA JUGA Kamu Marah Petani Sayur dan Peternak Telur Buang Hasil Panen? Apalagi Mereka dan tulisan lainnya di rubrik ESAI.