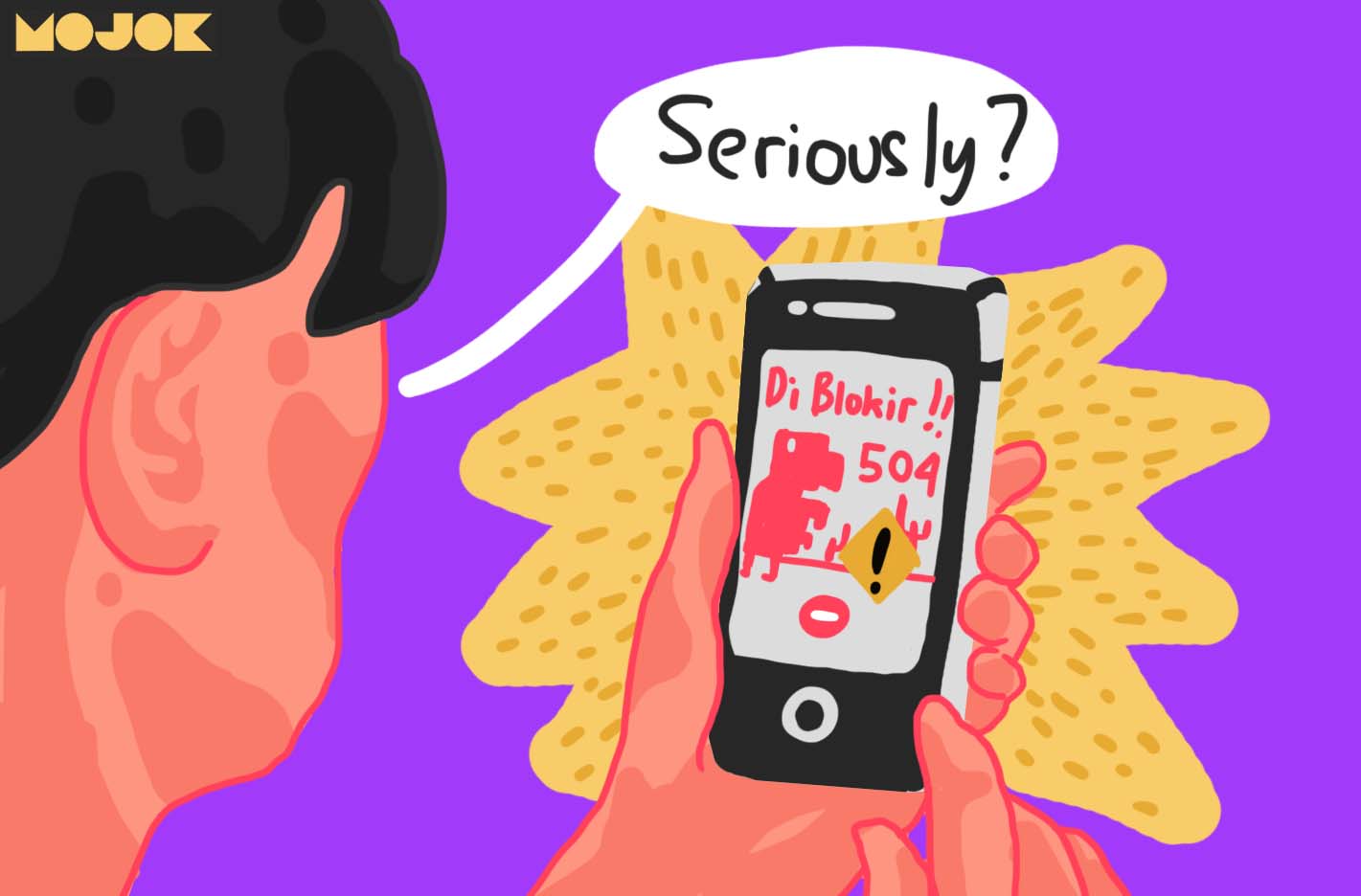Alamak, jejaring sosial Tumblr dan 477 situs lainnya resmi divonis sebagai agen laknat penyebar pornografi. Banyak orang bergegas memprotes. Tapi, ngaku saja, pasti tak sedikit yang buru-buru buka Tumblr lalu mengetikkan kata kunci saru. Mak plenyik, belum sempat netizen debat, kok kebijakan blokir itu dicabut Bos Rudiantara. Padahal kita kan seharusnya mengamalkan slogan rezim Jokowi untuk semua isu kontroversial: Kerja, kerja, kerja; Debat, debat, debat; Lupa, lupa, lupa.
Masalahnya bukan sekadar jenis situs yang diberangus. Tumblr disikat, walau akhirnya batal, berikutnya mungkin Instagram, Twitter atau malah Facebook terancam kena gebuk, wong semua medsos ini juga punya pojok remang-remang penuh lendir mirip jalur Pantura. Siapa tahu Kominfo di masa depan siap lahir batin dimaki-maki bakul online se-nusantara toh?
Lepas dari semua itu, saya yakin satu isu penting tetap terabaikan kendati ontran-ontran Tumblr berakhir: kesediaan menerima fakta bangsa kita bisa tergila-gila sekaligus jijik pada seks, seks, dan seks. Bangsa ini berbeda-beda sukunya, namun ujungnya, bersatu di selangkangan jua. Kita cepat heboh dengan isu seputar kelamin, mengucap istighfar, buru-buru memblokir atau meringkus pelaku bisnis lendir, hanya demi heboh lagi di lain waktu.
Patut diingat, kegemaran pemerintah Indonesia memaksa semua anak bangsa mengamalkan dasadarma kesepuluh – dari zaman Orde Lama, Orde Bau, sampai Orde Panasbung – sejauh ini belum berubah. Kalau bisa blokir, kenapa harus pakai cara lainnya?
Sudah banyak tulisan bernas yang mengulas mubazirnya sensor, di bidang film, musik, hingga akses Internet, terserak di dunia maya bagi mereka yang bersedia meluangkan waktu.
Sekadar contoh, sila membaca analisis Bosqu Damar Juniarto yang jernih membelejeti lemahnya kebijakan Kominfo selama ini menghadapi banjir bah informasi, termasuk yang negatif, dari sebuah teknologi bernama Internet. Sayangnya mengharapkan birokrasi cepat belajar menghadapi perkembangan zaman, lalu tak mudah mengambil jalan gampangan semacam sensor, adalah sejenis optimisme timnas bisa lolos Piala Dunia 2018.
Intinya, kebijakan blokir walau tolol dan menyebalkan, menjadi sangat tidak mengherankan. Selalu lebih mudah bagi pemerintah menuding sebuah situs menimbulkan mudharat, merusak moral, dan macam-macam alasan mulia lainnya, dibanding mengakui bahwa masyarakat kita menggandrungi seks (sampeyan termasuk salah satunya tho? halah, ngaku saja)
Justru yang mengherankan, bagi saya, adalah tetap tingginya kemunafikan bangsa kita setiap ketanggor wacana seksualitas di ruang publik. Padahal netizen Indonesia menggemari hal-hal menyerempet cabul, melalui saluran apapun.
Pernahkah anda menemui meme cabul, broadcast message menyinggung kelamin dan lendir yang tidak lucu, copas daftar harga panti pijat ++ yang sedang diskon di Jabodetabek, atau tautan video pendek adegan senggama melalui Whatsapp atau BBM?
Saya tak jarang mendapati konten seperti itu, seringkali dibungkus sebagai candaan. Nyaris setiap hari malah. Di grup WA kantor, alumni sekolah, dan banyak percakapan medsos lainnya. Saya tidak nyaman, tapi saya menghormati teman-teman, yang saya tahu rata-rata berasal dari keluarga baik-baik juga. Barangkali mereka memang menyukai pembicaraan selangkangan itu, sepenuh hati. Walau saya sering beprasangka buruk, teman-teman yang hobi membahas isu-isu nyerempet lendir itu termasuk golongan yang ciut nyalinya ketika ditodong anak mereka dengan pertanyaan “adek kenapa sih dulu bisa lahir?”.
Dengan keterpukauan bangsa kita pada seks, apa masuk akal menganggap Vimeo atau Tumblr atau ratusan situs yang fokus menyajikan pornografi lebih nista dari Twitter, Facebook, atau Google? Padahal semua situs dan medsos itu sama-sama membuka peluang kita jumpa konten ah-uh (tolong dikoreksi, yang bener “ah-uh”, atau “uh-ah” ya?).
Tentu pendukung sensor bisa berkomentar seperti ini: kalau supply dibatasi, demand akan turun dong. Betul, tapi sampai kiamat tidak akan menghapuskan gairah sebagian manusia pada hal-hal lucah. Toh, semua pihak harus mengakui, syahwat dan keingintahuan manusia pada selangkangan itu nyata di luar sana, menimpa orang dewasa sampai bocah yang bulu jembutnya saja sehelaipun belum tumbuh.
Teknologi tak memandang apakah anda remaja masjid, atheis, atau anak alay yang suka cenglu naik motor di jalanan kampung. You minta esek-esek, Internet pasti memberi tanpa berharap kembali.
Argumen supply-demand sama lemahnya dengan pendapat birokrat Kominfo yang dengan begitu mulia berkata, “yang dilindungi itu adalah masyarakat kita yang nggak ngerti apa-apa. Apalagi anak-anak yang melihat.”
Betapa naifnya pola pikir semacam itu, ketika sekarang begitu banyak orang tua membebaskan anak-anak memakai gawai terhubung ke Internet sejak balita. Peralihan akses anak-anak imut itu dari video-video lucu Thomas si kereta berwajah manusia ke video-video Fake Taxi sekadar tunggu waktu dan kesempatan.
Izinkan saya menceritakan pengalaman seorang anak di Jawa Tengah sana, 16 tahun lalu. Bocah ini beruntung lahir di keluarga kelas menengah, lalu mendapat akses internet di rumah. Seperti bocah tolol di manapun, dia yang baru saja disunat begitu penasaran sama seks. Teman di sekolahnya, pernah membawakan gambar-gambar orang bersenggama, lalu diberitahu bahwa yang semacam itu ada banyak sekali di Internet. Kelojotan dia melihat penis dan vagina bertebaran, hanya dengan mengetik kata-kata seperti ‘sex’ atau ‘fuck’.
Hanya dua hari pesta kecabulan itu berlangsung. Di hari ketiga, si bocah dipanggil oleh sang ayah, diberitahu tak ada lagi Internet. “Kamu belum siap memahami yang saru-saru. Paham tubuhmu saja belum. Bapak akan pasang lagi Internet, bahkan membolehkan kamu buka situs porno, kalau kamu sudah dewasa, minimal pas kamu sudah SMA.”
Ayah dan anak itu kemudian banyak membahas soal seks. Apa yang terjadi kemudian? Bocah itu patuh pada perintah si ayah. Dia tetap penasaran dengan selangkangan, dengan adegan ah-uh (sekali lagi tolong dikoreksi, yang bener “ah-uh”, atau “uh-ah” ya?) dan lain sebagainya, namanya juga remaja. Tapi selama empat tahun kemudian, sampai akhirnya Internet terpasang lagi di rumah, dia tak pernah main ke warnet sekadar mencari bahan coli. Dia sudah tak tertarik lagi memakai Internet sekadar mencari adegan senggama lalu kebelet mempraktikkannya dengan teman sekolah di semak-semak dekat kuburan kampung. Dia pun sadar orang tuanya ternyata selalu peduli dengan apa yang dia lakukan walau mereka tak sedang di rumah sekalipun.
Bocah itu adalah saya sendiri. Dan saya akan memakai cara yang sama menghadapi anak saya kelak. Saya berani memberi mereka akses Internet, maka saya bertanggung jawab pula menerima segala risikonya.
Anda berhak memakai perspektif apapun. Agama, moral, atau malah ajaran leluhur, untuk menjelaskan kenapa pornografi tak layak dikonsumsi anak kita sebelum jiwanya benar-benar dewasa. Tapi, demi sejuta topan badai, jelaskan itu semua, tatap mata mereka langsung. Luangkan waktu mendampingi mereka beranjak dewasa di dunia yang dihuni lumayan banyak bajingan. Pendekatan ini tentu lebih mudah diadopsi kelas terdidik, untuk kemudian, wajib disebar juga kepada tetangga dan saudara yang belum ngeh pada sisi gelap teknologi. Jangan bisanya nyebar BC hoax melulu.
Solusi semacam itu tentu makan waktu, kalah cepat daripada sensor. Ya iya lah Maliiiih. Dipikirnya bangsa Jepang jadi disiplin cuma dalam semalam hah? Jangan lupa, bangsa Nippon yang kalian puja-puji itu secara tertib mengatur bisnis film ah-uh lho demi kemaslahatan masyarakat yang mesum maupun yang lurus-lurus saja. Sedangkan kita selama ini kan cuma mau kimochi-nya saja tanpa pikir panjang.
Lebih baik jika kita belajar menerima bangsa ini terlanjur mesum dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita kecanduan semua yang serba cabul. Dan sebagian dari kita senang membagikannya di jejaring sosial.
Arus budaya negatif dari Internet, seakan-akan netizen di Jakarta atau Polewali Mandar hanya korban siasat jahat Illuminati yang ingin merusak moral generasi penerus NKRI, sepenuhnya omong kosong.
Kitalah arus yang membandang itu, menerabas semua penghalang, menihilkan semua jenis pemblokiran.