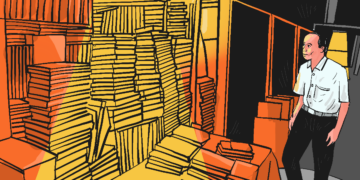Yang paling menyebalkan dari usaha untuk melawan pembajakan buku adalah kita dipaksa untuk berhadapan dengan narasi kemiskinan.
Masih banyak (dan mungkin akan terus banyak) orang-orang yang menganggap pembajakan sebagai hal yang sah sebab itu adalah salah satu jalan untuk bertahan hidup, mencari makan, mencari penghidupan. Dengan demikian, melawan pembajakan adalah menutup jalan rezeki. Para pegiat anti pembajakan menjadi tampak seperti orang bengis, orang jahat yang menutup rezeki orang.
Para pembajak seolah menjadi pihak yang lemah, yang tertindas, yang paling menderita. Sedangkan yang melawannya adalah barisan para tiran.
Narasi tersebut tentu saja sungguh-sungguh jahat, selain tentu saja memuakkan.
“Kalau pembajakan tidak diperbolehkan, lantas bagaimana rakyat miskin bisa pintar? Sedangkan buku mahal harganya. Hanya orang kaya yang kuat beli buku. Rakyat miskin dilarang pintar.”
Sebagai salah satu orang yang kebetulan bergiat dalam dunia perbukuan (penulis, penjual buku, dan sesekali jadi tukang nglayout), sungguh saya memohon maaf dengan kondisi yang demikian. Namun, sungguh, kemiskinan bukanlah pembenaran untuk membajak.
Kalau memang merasa tidak punya uang, bisa pinjam buku di perpustakaan daerah atau taman-taman baca. Kalau memang masih punya modal hape android walau murahan, bisa install aplikasi iPusnas dan baca di sana, ada banyak koleksi buku yang bisa dibaca dengan kuota internet yang sangat minim. Kalau memang bener-bener hanya punya uang sedikit, tunggu beberapa tahun sampai buku tersebut dijual di pameran-pameran dengan harga yang sangat miring, atau beli versi bekasnya.
Pintar itu penting. Tapi mencari kepintaran dengan cara yang baik tentu adalah jauh lebih penting.
Apalah gunanya pintar jika ia diraih dengan cara menzalimi orang lain.
“Sejak awal berkeinginan berkarir sebagai penulis seharusnya sadar bahwa pembajakan adalah keniscayaan. Kalau niatnya berjuang untuk literasi dan menyebarluaskan ide sampeyan, ya sudah ikhlas saja bukunya dibajak. Kalau mau cari duit ya cari main job selain penulis.”
Berjuang untuk literasi adalah satu hal, dan mengikhlaskan buah karya pikir adalah hal yang lain.
Justru melawan pembajakan itu adalah bentuk perjuangan untuk literasi. Sebab tujuannya adalah menyejahterakan penulis, layouter, editor, dan orang-orang yang bergiat di dunia perbukuan.
Berjuang untuk literasi tentu tidak dengan memaklumi pembajakan.
Pramudya Ananda Toer itu kurang literasi apa lagi? Ia bahkan boleh bikin lebih literasi ketimbang literasi itu sendiri. Dan ia pernah sampai pecah berpisah dengan Hasta Mitra, juga Joesof Isak, editor andalan Pram, sebab mereka dianggap tidak mampu melindungi karya-karya Pram dari pembajakan.
Ingat, mesin tik, laptop, kopi di kafe, kuota internet, semuanya harus dibayar dengan uang, bukan dengan keikhlasan.
“Tapi kalau melarang pembajakan, itu artinya mematikan rezeki para pedagang buku bajakan, jangan serakah dong, masak nggak mau berbagi makanan.”
Berbagi makanan itu baik. Tapi tentu tidak dengan merebut makanan orang lain. Ya, melarang pembajakan memang mematikan rezeki para pembajak dan pedagang buku bajakan. Tapi perlu diingat, bahwa pembajakan itu sendiri mematikan rezeki jauh lebih banyak pihak. Dari penulis, editor, layouter, penerjemah, pemeriksa aksara, desainer, orang penerbitan, dll.
Para pembajak memang butuh makan. Tapi penulis, editor, layouter, dan sebangsanya itu juga butuh makan. Jangan dikira mereka bisa hidup karena berfotosintesis. Mereka juga manusia, bukan pohon trembesi.
“Tapi semua di dunia ini adalah dari Allah. Milik Allah. Termasuk ilmu yang ada di buku. Kenapa tidak boleh membajak? Harusnya boleh digunakan untuk kepentingan manusia.”
Oke, kalau begitu, mulutmu itu juga milik Allah. Sini tak kruwes. Kamu nggak boleh marah, kan mulutmu milik Allah. Bukan milikmu.