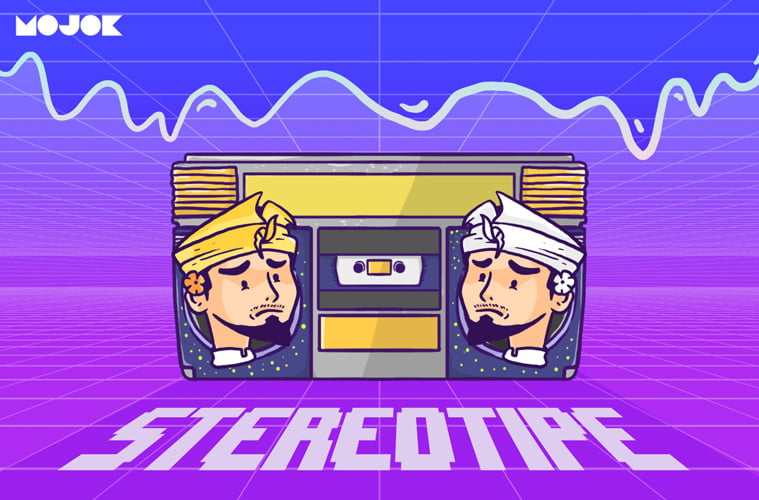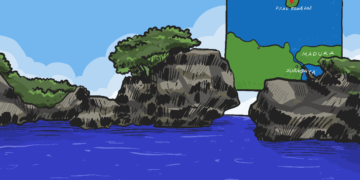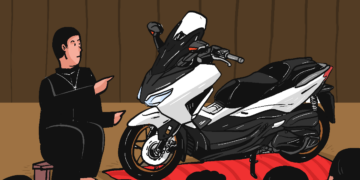MOJOK.CO – Sebagai orang Bali yang kuliah di perantauan, mahasiswa satu ini menceritakan stereotip demi stereotip yang diterimanya di Jogja.
Hanya karena saya orang yang lahir ceprot di Bali, lumayan banyak teman yang menganggap rumah di kampung halaman saya ibarat tempat pariwisata. Mungkin dalam bayangan mereka, rumah saya kayak hotel atau resort mewah.
Atau dipikir rumah saya ada puranya, terus di halamannya ada kemurunan orang lagi menari kecak sambil menikmati sunset di tebing-tebing pinggir laut. Ealah, padahal rumah saya di kampung ya kayak rumah-rumah normal. Biasa aja.
Selain rumah saya yang sering dianggap sebagai destinasi wisata, ada juga beberapa steorotipe yang kadang bikin saya aneh sendiri. Dan hal-hal itu semakin saya rasakan ketika saya kemudian merantau ke Pulau Jawa untuk kuliah di salah satu kampus di Jogja.
Sering saya ditanya kalau kenalan dengan orang Jogja, “Asli mana, Mas?” saya berpikir keras. Karena walaupun saya lahir ceprot di Denpasar, secara keturuan saya ini orang Batak. Tapi karena ditanya asli mana, ya saya jawab aja…
“Batak, Pak.”
“Oh, rumahnya di Medan ya?”
“Oh, bukan, Pak. Rumah saya di Bali.”
“Lah? Sampeyan ini gimana? Sampeyan itu asli Medan atau Bali sakjane? Kok mencla-mencle?”
“Asli Indonesia, Pak. Produk lokal!” jawab saya. Cuma dalam hati tentu saja, karena yang keluar dari mulut saya…
“Hehe, maaf, Pak,” sambil cengengesan.
Sebagai orang Bali yang merantau ke Jogja, tak jarang saya dianggap sebagai mahasiswa tajir dan hype. Pandangan ini berasal karena banyak kafe dan beachclub di daerah Seminyak, Legian, Kuta, dan Jimbaran yang harga makanan dan minumannya udah kayak harga makan sebulan di Jogja.
Padahal, meski kelihatannya Bali itu indah banget, ya nggak semua orang Bali itu tajir. Emang dikira di Bali nggak ada orang miskin apa?
Lagian kalau semua orang Bali tajir (hanya karena harga barang-barangnya dianggap mahal) ya orang Bali nggak perlu kerja di hotel sama tempat wisata lah. Justru karena orang Bali nggak tajir-tajir amat itu lah, orang-orang luar jadi datang ke Bali karena bisa “bayarin” orang Bali.
Nah, salah satu orang Bali yang nggak tajir itu ya saya ini. Makanya, saya suka sebel kalau dibilang…
“Hidup di Bali pasti mahal ya, Bro? Makanya orang-orang di sana harus punya banyak uang?”
Oh, tidak, Brader. Tidak seperti itu.
Sini saya kasih tahu ya. Yang bikin mahal hidup di Bali itu bukan harga makanan dan barang pokoknya, yang mahal di Bali itu gaya dan gengsinya. Sebenernya sih, hidup di Bali itu nggak mahal-mahal amat, khususnya di Kota Denpasar.
Hah, Denpasar? Iya, serius. Hidup di Denpasar itu nggak semahal yang kamu kira lho.
Di kota kelahiran saya itu, biaya hidup itu sebenarnya nggak jauh beda dengan Jogja. Masih bisa kok kamu temui nasi telor ditambah sayur dan es teh dengan harga 10 ribu. Ada juga pedagang nasi jingo yang cuma 5 ribu. Kenyang total lah itu.
Mau lebih murah lagi? Oh ada.
Di mana? Ya masak sendiri.
Kalau pengin tampil kece tapi low budget kamu tinggal ngeloyor aja ke Pasar Kreneng Denpasar atau Pasar Kodok (pasar yang menjual baju bekas) di daerah Tabanan. Nah, tempat-tempat kayak gitu sebenarnya menjawab, kalau Bali itu nggak semahal yang dikira.
Selain soal perkara fulus, orang Bali yang merantau ke Jogja juga sering dianggap jago-jago ngomong bahasa Inggris. Yaaah, nggak bisa disalahin juga sih. Mungkin karena Pulau Bali banyak bulenya, jadi orang Bali sering dianggap jago banget ngomong bahasa Inggris. Bahkan sering dianggap bisa segala aksen.
Ealah, padahal mah ya belum tentu.
Kayak saya misalnya, harus diakui sih Bahasa Inggris saya nggak bagus-bagus amat. Apalagi pronounciation-nya masih kental dengan logat Bali. Makanya Bahasa Inggris yang saya gunakan sering disebut Balinglish (Bahasa Inggris khas Bali). Emangnya cuma Singapura aja yang punya Singlish?
Yah, bisa dibilang banyaknya wisatawan asing di Bali, selain bikin banyak orang Bali bisa cas-cis-cus ngomong Inggris, juga bikin kami jadi terbiasa dengan bule. Ngobrol sama bule udah biasa, bahkan udah jadi makanan sehari-hari. Bule makan di warteg sebelah-sebelahan udah biasa, dan ibu-ibu warteg pun nggak histeris.
Itulah kenapa saya kadang heran ngeliat bule di Jogja kadang jadi artis dadakan. Diajak foto sana-sini atau diwawancarain ini-itu. Dan situasi yang berbeda itu pernah diceritakan oleh teman saya yang asli Australia.
Katanya, ketika lagi piknik ke Borobudur (iya saya tahu, itu di Magelang bukan di Jogja) teman saya ini agak heran ketika ada anak-anak sekolah pada minta foto. Kadang juga ada yang wawancara untuk tugas sekolah. Lantas, ketika ia main ke Bali, si teman saya ini makin heran karena nggak ada yang mengajak berfoto sama sekali. Hehe.
Selain soal bule dan bahasa Inggris, stereotip berikut yang saya terima sebagai orang Bali adalah—tentu saja—kefasihan saya berbahasa Bali. Wah, ini repot lagi. Soalnya, nggak semua orang yang tinggal di Bali itu bisa berbahasa Bali dengan baik dan benar. Apalagi saya, yang keluarga Batak tapi cuma numpang lahir, tumbuh, sampai SMA di Bali begini.
Hanya saja, karena sering ditodong untuk diminta ngajarin bahasa Bali, ya akhirnya dengan terpaksa saya ajarin, meskipun sebenarnya nggak bisa-bisa amat. Nah, kebetulan saya percaya dengan teori ngajarin bahasa baru ke orang, yakni: ajarin dulu kata-kata kasar atau makian. Pasti cepet ngerti.
Ya udah akhirnya saya ajarin dong teman-teman saya, naskleng, buduh, cicing ci nok, celeng ci nok. Penasaran artinya apa? Googling dong.
Selain soal bahasa, sebagai orang Bali saya juga sering ditanya, “Mas, mahasiswa dari Bali? Eh, Hindu di Bali itu gimana sih? Masnya Hindu kan?”
Pernyataan ini sebenarnya cukup sensitif dan personal, namun saya paham bahwa kadang cara basa-basi orang itu beda-beda, makanya saya tetap menjawab, “Nggak tahu, Pak. Saya bukan Hindu, saya Kristen Protestan.”
Dan wajah penuh keheranan akan muncul dari yang tanya. Kalau udah begitu, senyum penuh kebanggaan saya mengatakan bahwa Bali itu tidak hanya Hindu, tapi bermacam-macam agama, suku, ras dan etnis berdiam di dalamnya.
Barangkali itu yang dinamakan dengan konsep Menyama Braya, berbeda tapi tetap bersaudara. Dan bisa jadi Bali adalah salah satu daerah yang cukup selow sama urusan beginian. Nggak cuma terhadap yang beda agama, tapi juga yang beda negara.
BACA JUGA Mementahkan Stereotip Orang Ngapak Emosian atau tulisan Titanio Hasangapan Giovanni Sibarani lainnya.