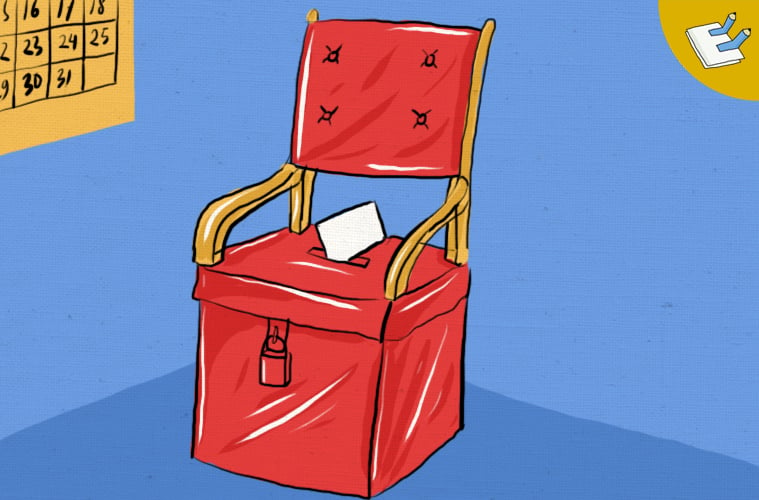Banyak orang berpikir dan menganalisis politik bukan berdasarkan faktor-faktor politik, melainkan dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga kebanyakan orang terpaksa gigit jempol kaki begitu yang dipikirkan dan diinginkan tidak terjadi.
Salah satu kekeliruan itu adalah analisis bahwa setiap Presiden (juga Gubernur dan Bupati/Walikota) yang berprestasi dengan otomatis akan menjabat lagi jika berlaga.
Di Indonesia, prestasi seorang pejabat publik tidak selalu berhubungan dengan keberlanjutan jabatannya. Faktor yang lebih dominan adalah politik itu sendiri. Soeharto berkali-kali menjabat sebagai Presiden bukan karena prestasinya. SBY menjabat Presiden untuk kedua kalinya, juga bukan karena prestasi yang diraihnya saat menunaikan jabatan tersebut sebelumnya.
Sebaliknya, pejabat publik tertendang dari kursi jabatannya juga bukan karena dia tidak berprestasi. Ahok, dengan segala kontroversinya, kalah dalam laga Pilgub DKI. Padahal dia relatif berprestasi. Sri Mulyani dipaksa hengkang dari jabatan Menteri Keuangan di era SBY juga bukan karena dia tidak berprestasi.
Jadi kalau Anda berpikir Jokowi akan menjadi Presiden lagi pada Pilpres 2019 karena dia berprestasi, sebaiknya Anda siap untuk kecewa.
Lalu faktor politik apakah yang bisa menjadi parameter Jokowi gagal menduduki jabatan yang sekarang diembannya untuk kali kedua nanti?
Prabowo-SBY
Banyak orang memandang sinis pertemuan politik Prabowo dan SBY. Ini kekeliruan pandangan politik. Apalagi jika semata hanya dilihat Prabowo sebagai kandidat yang selalu gagal menjadi Presiden, dan SBY sebagai mantan Presiden.
Prabowo mestinya diletakkan sebagai salah satu aktor politik yang berhasil membawa Partai Gerindra tumbuh pesat. Sampai sekarang, Gerindra termasuk salah satu partai yang nyaris tidak punya persoalan internal. Prabowo juga berhasil membuktikan diri mampu mengusung misi yang dulu dianggap tidak masuk akal: memenangkan Anies-Sandi sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI dalam situasi kompetisi yang sangat ketat.
Memandang SBY sebagai semata mantan Presiden, juga bukan cara menganalisis politik yang tepat. Dia punya pengalaman menjadi Presiden dua kali lewat pertarungan terbuka. Prestasi politiknya (bukan prestasinya sebagai Presiden) tidak bisa dianggap remeh. Dia mengandaskan Megawati yang kala itu merupakan inkamben.
Selain itu, SBY mampu membangun Partai Demokrat dengan relatif cepat. Tanpa kecakapan politik, hal tersebut nyaris tidak mungkin. Kemenangan SBY di Pilpres 2009 menunjukkan bagaimana kepiawaiannya dalam mengonsolidasikan partai-partai dan elite politik di Indonesia.
Pertemuan SBY-Prabowo jelas bukan reriungan dua jenderal pengidap ‘post power syndrome’, melainkan pertemuan dua politikus terlatih yang kaya pengalaman. Dan misi mereka jelas: menghadang Jokowi menjadi Presiden untuk kali kedua.
Jokowi Bukan Politikus
Menurut saya, Jokowi bukan politikus. Dia lebih sebagai seorang manajer hebat yang beruntung. Keterampilan yang dimilikinya adalah ketrampilan manajerial. Setidaknya kemampuan manajerialnya lebih menonjol dibanding kemampuan politiknya.
Maka dalam banyak hal, terlihat Jokowi sangat tertatih dan terbata dalam membuat strategi dan manuver politik. Dia tampaknya hanya mengandalkan dua kelompok besar: Luhut Pandjaitan dkk di satu sisi, dan para intelektual ilmu politik yang bercokol di Sekretariat Negara dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Luhut dkk tidak bisa dengan mudah mengonsolidasikan dukungan politik untuk Jokowi secara mantap dan permanen. Sementara orang-orang yang tahu ilmu politik, bukanlah politikus. Politik bagi mereka adalah apa yang ada dalam diktat politik, bukan apa yang ada dalam kenyataan politik.
Pergerakan Parpol
Semua parpol pendukung jelas punya keinginan tinggi untuk menjadikan orang di parpol mereka sebagai Cawapres pendamping Jokowi. Golkar sudah tentu. PKB sudah mulai mendorong nama Muhaimin Iskandar. Demikian juga partai-partai lain. Jika tokoh mereka gagal jadi Cawapres, mereka bisa punya peluang angkat kaki. Apalagi jika daya cium mereka yang terlatih mengendus makin kecilnya kemungkinan Jokowi menang, secepat mungkin mereka akan hengkang.
Makin mendekati perhelatan Pilpres, manuver partai-partai itu akan makin liar dan ganjen. Semua dalam rangka meningkatkan nilai tawar. Makin tinggi nilai tawar itu, posisi Jokowi akan rentan kalah jika ditinggalkan partai-partai pendukungnya.
PDIP Mudah Guncang
Sebagaian besar orang berpikir bahwa PDIP jelas akan memilih Jokowi sebagai Capres lagi. Anggaplah itu benar. Namun sebagai partai berkuasa, tampaknya PDIP gagal mengelola kekuasaannya. Hal ini mirip dengan ketika Pilpres 2004 digelar. PDIP dihukum oleh publik karena partai ini gagal mengambil hati rakyat ketika Megawati berkuasa.
Dan jangan lupa, PDIP bisa saja tidak mengusung Jokowi langsung. Apalagi jika partai-partai lain meninggalkan Jokowi, atau ketika PDIP merasa tidak bisa mengontrolnya lagi.
Mesin yang Utama
Figur politik itu penting. Tapi yang paling utama adalah kesiapan mesin politik. Dalam Pilpres 2014, figur Jokowi sangat kuat. Dan kala itu, mesin politiknya pun kuat. Partai-partai pendukungnya, terutama PDIP, dapat limpahan berkah dari keberaniannya menjadi oposisi pemerintahan SBY. Selain itu, karena antusiasme masyarakat yang berharap Jokowi bisa memperbaiki keadaan negeri ini lebih baik dari SBY.
Masalahnya, bisa saja mesin-mesin politik pendukung Jokowi dalam titik yang lemah. Golkar guncang. PDIP makin sering mengecewakan pemilihnya. Nasdem terlalu banyak permintaan. PKB memberi pilihan sulit. Dan Hanura belum ketahuan apakah akan membesar atau justru mengecil.
Kerinduan Akan Militer
Dalam psikologi masyarakat kita sekarang ini, ada semacam kerinduan atas institusi militer. Berbagai jajak pendapat menyatakan kalau institusi militer dianggap jauh lebih baik dibanding DPR, Kepolisian, dan lembaga negara lain.
Sementara itu, kita mafhum bahwa Prabowo dan SBY identik dengan militer sekalipun mereka sudah pensiun. Apalagi jika misalnya Prabowo nanti maju bersanding dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau dengan Gatot Nurmantyo.
Sentimen antimiliter makin mengecil dan sudah dianggap tidak signifikan lagi. Sebab semua orang militer yang berpolitik sudah dianggap sah berpolitik karena sudah pensiun.
Kerinduan ini begitu nyata adanya.
Penyingkiran Pendukung
Di Pilpres 2014, Jokowi banyak didukung oleh elemen masyarakat sipil, yang sebagian dari mereka kemudian bersikap kritis ketika Jokowi menjabat. Sikap kritis seperti ini tentu saja lumrah. Kalau Jokowi dianggap keliru, ya tentu saja harus dikritik. Pemimpin tidak boleh kebal kritik.
Sayang, kritik yang terlontar bukannya ditanggapi dengan baik, malah diserang oleh pendukung buta Jokowi. Strategi komunikasi politik seperti inilah yang kemudian membuat Jokowi mulai ditinggalkan oleh sebagian pendukungnya. Padahal, mestinya kritik dari pihak pendukung bisa dikelola dengan baik.
Jangan sampai kritik dianggap sebagai serangan. Sikap paranoid seperti itu menggerogoti kekuatan dukungan atas Jokowi.
Mari kita lihat respons para pendukung buta Jokowi atas tulisan ini. Kalau mereka membabi-buta dan menyangkal keras, berarti memang benar adanya: Jokowi belum tentu menjadi Presiden lagi.
Terakhir, kalau memang Tuhan memutuskan Jokowi tidak jadi Presiden lagi, terus kita bisa apa?
“Lho, Mas. Jangan bawa-bawa nama Tuhan dalam politik!” Mungkin Anda mau bilang begitu.
Saya dengan kalem akan menjawab, “Bukankah sudah lama Tuhan dilibatkan dalam dunia politik kita?”