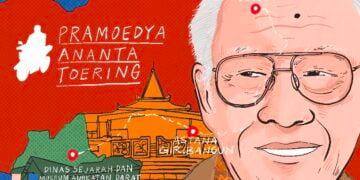Setelah menikah dan tinggal di rumah kontrakan, saya jadi sering bakar-bakar sampah di sore hari di halaman rumah. Saya menduga, ini semacam balas dendam masa lalu saya. Maklum, sebelum menikah dan tinggal di rumah sendiri (walau masih ngontrak), saya tidak pernah bisa bakar-bakaran di halaman karena rumah saya di Magelang sempitnya setengah mampus, atau bahkan nggak punya halaman sebab depan rumah saya langsung gang.
Di rumah kontrakan saya, yang alhamdulillah lumayan luas halamannya, saya terbiasa menyapu halaman untuk mengumpulkan daun-daun kering yang berguguran dari dua pohon rambutan yang tumbuh di depan rumah untuk kemudian membakarnya.
Ada sensasi yang menyenangkan tiap kali membakar sampah tersebut. Butuh daya dan upaya untuk menjaga agar api tetap menyala. Menikmati proses ketika api masih kecil dan hanya menyambar selembar dua lembar daun sampai kemudian membesar dan mampu membakar seluruh tumpukan daun yang ada adalah hal yang begitu menyenangkan.
Kebiasaan ini membuat saya sering berharap agar tiap sore, jumlah daun yang berguguran banyak dan melimpah.
Belakangan, saya semakin menyukai hobi bakar-bakar sampah ini setelah tahu bahwa ternyata sastrawan besar kita, Pramoedya Ananta Toer ternyata juga punya kegemaran serupa. Pram, menurut pengakuan anaknya, sangat suka menghabiskan waktu di sore hari dengan membakar sampah.
Saya seperti mendapatkan legitimasi. Kalau ada yang nanya kenapa saya suka bakar sampah, setidaknya saya bisa menjawab “Biar kayak Pram,” walau entah kenapa, sampai sekarang belum ada yang bertanya demikian.
Yah, siapa tahu, dengan mengikuti jejak tirakat Pram dalam perkara bakar-bakar sampah, saya bisa ikut sedikit ketularan kepiawaian beliau dalam menulis. Siapa tahu.
Kelak, aktivitas bakar-bakaran ini ternyata tak semulus yang saya bayangkan.
Dalam beberapa minggu terakhir ini, intensitas bakar-bakaran saya berkurang drastis. Alasannya begitu konyol: saya “dilabrak” secara halus oleh tetangga sebelah rumah saya.
Saya memang begitu suka bakar-bakaran, menyukai menjaga apinya, menyukai bau asapnya. Namun ternyata tidak demikian dengan tetangga saya.
Tetangga saya tak suka mencium bau asap yang mau tak mau memang sesekali mampir lewat ke beranda rumahnya. Maklum, kendati saya yang membakar sampahnya, namun saya bukanlah Avatar yang bisa mengendalikan arah asap.
Yah, asap hasil bakar-bakaran kita memang kerap seperti kentut. Kita enjoy saja menciumnya, namun orang lain eneg setengah mampus.
Kini, saya kalau mau bakar-bakar sampah, biasanya hanya saya lakukan di atas pukul sembilan malam ketika tetangga kiri-kanan sudah tidur. Itupun dengan api yang tak lagi besar dan sejahtera seperti sebelum-sebelumnya. Dan itu juga nggak setiap hari.
Hal tersebut tentu saja karena saya takut nanti tetangga saya nggak nyaman. Saya takut dia bakal lapor Pak RT, trus Pak RT laporan sama yang punya rumah yang saya kontrak, trus tahun depan saya nggak boleh lagi ngontrak di situ. Kan berabe.
Sejak saat itu, saya jadi merasa ada yang aneh dan kurang dalam hidup saya. Ada semacam sesal ketika melihat tumpukan daun-daun yang begitu banyak, namun tak bisa saya bakar semuanya sebab saya harus sadar diri dan sadar kondisi.
Sesekali, saya curhat tentang kegelisahan ini kepada istri saya. Namun tentu saja dengan curhatan yang biasa saja tanpa memperlihatkan rasa sesal saya. Hal ini karena istri saya orang yang unik. Saya yakin, kalau saya curhat dengan menumpahkan segenap rasa sesal saya karena saya nggak bisa lagi bakar-bakaran dan menikmati aktivitas menjaga api tetap menyala itu, maka istri saya, yang unik itu, pasti memberikan saran yang justru membikin sesal saya semakin besar.
“Ya sudah, kalau nggak bisa bakar-bakaran, nyalain kompor di dapur saja sana, trus lihat apinya sepuasnya. Simpel.”
Itu namanya berhenti membakar sampah dan memulai membakar emosi.