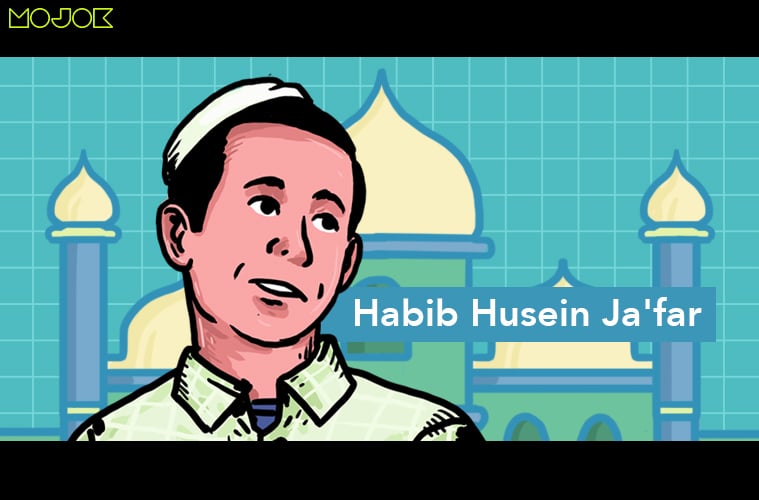MOJOK.CO – Ejekan untuk kaum hijrah yang cukup sering didengar. “Halah, baru tahu Islam kemarin udah sok suci,” atau, “dikit-dikit kok haram,” atau, “dasar, Onta.”
Pakar media sosial Mojok (sebut saja admin), Doni Iswara idola kawula muda, tiba-tiba memberi saya link sebuah tulisan di Terminal Mojok. Isinya sih berupa tulisan dengan judul lumayan provokatif, “Betapa Sulitnya Bergaul dengan Orang yang Baru Hijrah.”
Mas Doni lalu mancing-mancing agar saya mau nulis topik itu. Bagaimana respons saya atas tulisan tersebut. Isi tulisannya sih tidak baru-baru amat sebenarnya. Tentang kekhawatiran soal maraknya budaya hijrah belakangan ini. Termasuk yang terjadi di lingkungan si penulis artikel tersebut. Hal yang dimanifestasikan dengan “sulitnya” mengajak orang-orang baru hijrah ini berinteraksi.
Ketimbang langsung merespons permintaan Mas Doni, saya sebenarnya agak lumayan kaget dengan cara Mas Doni melihat tulisan tersebut. Bukannya gimana-gimana, tak semua orang bisa berpikir cukup “adil” seperti Mas Doni lho. Umumnya, orang liberal progresif kayak Mas Doni, akan merasa terancam dengan budaya hijrah. Tapi blio kelihatan selo-selo aja. Bahkan meminta perspektif tandingan dari narasi orang hijrah yang susah diajak bergaul.
Ya, saya pikir tak salah juga saya berpikir demikian. Sebab, saya kira narasi yang berkembang di lingkungan pertemanan saya (kalau Mas Doni menganggap saya sebagai temannya juga sih) hijrah sering bertautan dengan hal-hal negatif. Apapun bentuknya. Mirip seperti pandangan terhadap konservatisme dalam beragama. Dianggap kaku, nggak selo, nggak bisa lunak dengan keadaan.
Ejekan untuk mereka cukup lumrah. “Halah, baru tahu Islam kemarin sore aja udah sok suci,” atau, “Ealah, dikit-dikit kok haram,” atau, “balik aja lu ke Arab sana, Onta.”
Ya kalau mau jujur-jujuran, hal itu pernah menjadi stereotip saya juga sih. Paan sih, syor’a-syar’i mulu. Kok hidup kaku amat gitu?
Sampai kemudian pandangan itu luruh pelan-pelan seiring dengan intens-nya interaksi saya dengan mereka yang hijrah. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, lalu takdir mempertemukan saya dengan golongan hijrah.
Ada banyak interaksi yang mengubah cara pandang saya terhadap golongan hijrah di hidup saya. Interaksi saya dengan jamaahnya Felix Siauw misalnya. Itu terjadi di dekat rumah saya. Sangat dekat. Paling cuma selemparan tali kutang aja.
Di dekat rumah saya, berdiri auditorium yang berisi jamaah Felix Siauw yang digunakan pengajian sebulan sekali. Bagaimana saya tahu? Ya karena Felix Siauw juga pernah datang ke sana untuk mengisi pengajian secara langsung.
Sekarang bayangkan saja, di lingkungan kampung saya yang kental aroma Nahdliyin-nya, berdiri sebuah auditorium yang tiap sebulan sekali ada pengajian dari golongan lain. Lalu apakah terjadi penolakan warga atau gesekan sosial yang kencang? Oh, tidak saudara-saudara.
Ini terjadi karena pemilik gedung membuka dialog dulu dengan warga. Terutama kepada pengurus masjid yang lokasinya berada persis di belakang gedung auditorium mereka—kebetulan istri saya adalah salah satu pengurus masjid. Kalau dibilang tidak ada gesekan sosial sama sekali ya nggak juga, tapi hal-hal ini cenderung selesai dengan cara sederhana.
Seperti misalnya, kegiatan di masjid kampung saya udah penuh tiap harinya. Jadi golongan hijrah ini tidak bisa “masuk”. Kalau salat atau ikut ngaji juga monggo. Mau ikut nyumbang ya silakan. Tapi ya jangan coba-coba memasukkan agenda mereka ke masjid kampung kami. Dan untungnya, golongan hijrah ini mengerti.
Jadi kalau hari Jumat, kadang akan ada pemandangan yang aneh di kampung saya. Di auditorium depan masjid ada pengajian syar’i yang berisi golongan hijrah, di belakangnya (di masjid kampung) akan ada pengajian tafsir yang diisi warga kampung. Semua berjalan sendiri-sendiri, tapi baik-baik saja.
Lagian dari parkir pengajian di auditorium itu pula beberapa warga di kampung saya dapat pendapatan dadakan sebagai tukang parkir.
Poinnya, ya tidak apa-apa berbeda. Karena proses beragama masing-masing orang memang nggak pernah bisa sama. Nggak pernah bisa seragam. Ada yang dari pesantren, ada yang dari Youtube, ada yang dari Google, ada pula yang dari hijrah.
Dari pengalaman ini juga saya kemudian sadar. Selama ini, mungkin saya sering tidak adil memandang mereka. Hanya karena sebagian besar keluarga saya lahir dari kultur pesantren, hal itu tidak lantas membuat saya lebih berhak mencela cara mereka melihat Islam.
Pandangan yang sama juga sepertinya sedang dipraktikkan oleh orang-orang hijrah di kampung saya ini. Hampir lima tahun lebih ini warga kampung saya tidak ada tuh yang dibid’ah-bid’ahkan. Entah karena golongan hijrah ini nggak berani atau gimana, tapi yang jelas memang tak pernah ada gesekan sosial yang mengarah ke sana.
Kalaupun cara pandang beragama warga Nahdliyin di kampung saya dicela atau dibilang sesat (misalnya), ya suka-suka yang ngata-ngatain saja. Kalau kami membalas pakai cara yang sama, lalu bedanya kita dengan mereka yang suka sesat-sesatkan dan kofar-kafirkan apa coba?
Memang ada beberapa pandangan yang berbeda dengan Felix Siauw atau jamaahnya. Itu pun hanya sebatas pada perkara tafsir-tafsir agama. Baik secara kehidupan langsung maupun diskusi di media sosial, saya tetap menghormati mereka. Hal-hal yang saya dan warga kampung tidak sepakati pun hanya seputar ide-idenya, bukan orangnya.
Meski tak setuju dengan sebagian besar pendapat mereka tentang Islam, ya saya pikir kenapa juga harus sensi? Sama-sama belum tentu yang paling benar di muka bumi ini kok.
Misalnya, jamaah hijrah itu ada yang mendukung khilafah, ya saya dan warga sampai mati tidak akan setuju. Namun bukan berarti warga tidak bisa berteman dan hidup asyik bersama. Lha iya to? Kan katanya keberagaman? Katanya toleransi?
Ketimbang keluhan orang bahwa mereka yang hijrah cenderung menutup diri, interaksi sosialnya buruk (karena mungkin dibatasi soal mahram), saya sering berkaca kalau jangan-jangan justru orang seperti saya yang bikin akses mereka jadi serba terbatas sehingga mereka memilih hijrah betulan—dari yang awalnya cuma coba-coba.