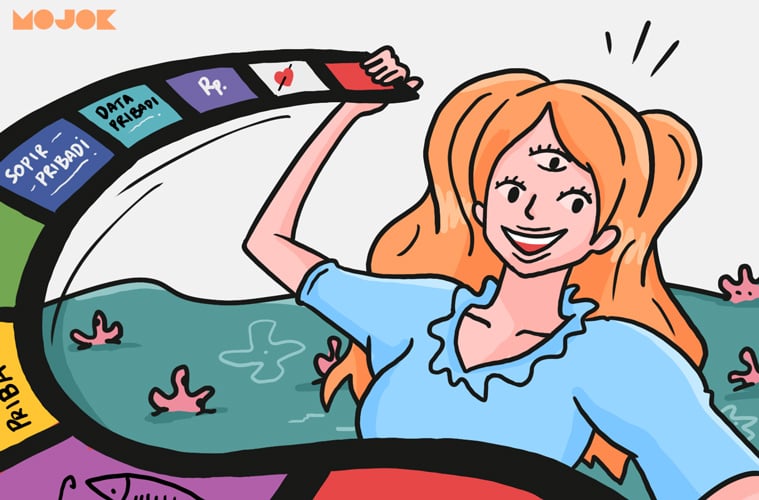MOJOK.CO – Tanpa saya sadari, saya membiarkan diri saya “telanjang” di hadapan Google dan selama ini saya merasa baik-baik saja. Padahal mereka dapat profit yang sangat banyak dari sana.
Suatu hari saya membicarakan keinginan saya untuk liburan ke Malang, saya membicarakan keinginan itu sambil menelepon seorang teman melalui telepon WhatsApp. Besoknya, saya menemukan iklan di halaman Facebook saya mengenai promo tiket masuk Jatim Park, tempat yang sebelumnya sempat kami bicarakan.
Di lain hari saya membicarakan ingin beli kulkas mini, membicarakannya dengan teman yang berbeda melalui chat WhatsApp. Besoknya iklan promo kulkas muncul di home Instagram saya.
Di hari lainnya lagi, saya membicarakan ingin membeli pen tablet, tapi saya tidak membicarakan keinginan ini di WhatsApp, saya membicarakannya dalam percakapan langsung dengan Lala (ilustrator Mojok). Besoknya, iklan Wacom (merek yang direkomendasikan ke saya) langsung muncul di Instagram saya….
Kejadian pertama dan kedua, sebenarnya bukan terjadi satu atau dua kali, beberapa teman juga pernah mengalami hal serupa. Tapi di kasus yang ketiga, saya mulai merasa aneh karena sebelumnya saya tidak pernah googling apa pun tentang produk itu, juga tidak pernah membicarakannya melalui aplikasi apa pun.
Untuk pertama kalinya saya merasa kalau saya sedang dimata-matai.
Saya kemudian mencari tahu mengenai bagaimana sebenarnya privasi saya dihargai di era digital. Sebelumnya saya memang tahu Google dan WhatsApp memang mengolah percakapan kita menjadi data yang berisi preferensi, keinginan, cita-cita, harapan, kejulidan, dst. dst. yang digunakan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan (((karakter))) saya.
Misal, ketika saya banyak menyukai video kocheng di Instagram, platform ini akan mengarahkan saya ke video-video sejenis. Pun kalau suka cari keributan di Twitter, algoritma mereka akan menampilkan seluruh keributan yang relevan dengan jenis keributan yang saya sukai meskipun sebenarnya saya nggak pernah follow akun-akun yang suka ribut itu.
Saya pikir, kegiatan merekam dan mengolah data aktivitas dan interaksi user di internet membuat Google dan layanan digital lainnya lebih mengenal saya dibanding orang tua saya sendiri.
Dan yang lebih canggih saya temui di Spotify. Saya bukan tipe yang suka mencari lagu-lagu baru, tapi Spotify selalu berhasil membuat saya menyukai lagu yang mereka rekomendasikan, seakan-akan Spotify lebih saya daripada saya sendiri. Mereka bisa mendeteksi selera musik saya padahal saya sendiri suka galau untuk menyebut saya ini sukanya genre apa.
Awalnya, saya tidak keberatan dengan semua ini. Maksud saya, apa yang Google lakukan malah membantu saya berinteraksi dengan hal-hal yang saya sukai saja. Saya juga tidak merasa dirugikan karena toh segala aktivitas yang saya lakukan di internet tidak berbayar.
Tapi sejak iklan-iklan mulai muncul, saya merasa cukup terganggu. Pas saya lagi pengin sesuatu, iklan produknya tiba-tiba muncul, biasanya dengan diskon pula. Kan jadi pengin. Mending kalau saat itu lagi kaya, coba kalo lagi tanggal tua. Wadidaw nelangsa.
Yang jadi masalah, saya nggak bisa mencegah dan menghentikan perubahan pembicaraan mengenai keinginan ini menjadi iklan-iklan. Ini tuh pelanggaran privasi nggak sih?
Daripada sotoy, saya kemudian nyari tahu. Dan jawabannya tidak. Sebab, saya sudah menyetujui tindakan-tindakan itu ketika (asal) klik dan (nggak pernah) baca terms and conditions Google maupun platform lain.
Saya membiarkan mereka mengakses kontak, kamera, lokasi, dan mikrofon tanpa memikirkan implikasinya. FYI, akses terhadap mikrofon ini yang bikin aplikasi bisa mencuri dengar pembicaraan saya–bahkan sesuatu yang tidak saya bicarakan lewat aplikasi, alias saat berbicara langsung dengan orang lain.
Saya jadi mikir: Tanpa saya sadari, saya membiarkan diri saya “telanjang” di hadapan Google dan selama ini saya merasa baik-baik saja. Padahal, gara-gara rekaman aktivitas yang saya punya, mereka dapat profit yang sangat banyak dari sana.
Sementara saya?
Malah rugi karena waktu saya habis dipakai rebahan dan main semua aplikasi yang membuat saya terus menaruh perhatian di sana karena kontennya sangat saya banget, dan sayang sekali kalau tidak dieksplorasi.
Ya betul. Tujuan Google atau layanan digital apa pun ialah bikin konten yang sesuai selera biar makin banyak dan makin lama kunjungan yang datang. Mereka dapet duit lebih banyak dengan lamanya kunjungan itu.
Di sinilah saya jadi tahu kalau ini tuh bentuk dari surveillance capitalism. Kalau kata Shoshana Zuboff, orang yang pertama kali mengenalkan terma itu, layanan digital seperti Google, Facebook, dll. mentranslasikan pengalaman kita menjadi data yang digunakan untuk mengembangkan produk mereka (sehingga kita makin betah mengakses platformnya) dan mengakumulasikannya untuk dijual supaya dapat profit.
Data-data kita hasil dari surveillance capitalism membuat Google mendapat uang iklan sampai 38 miliar dolar AS tiap tahunnya (Rp527,8 triliun). Dan ini semua menjadi masuk akal karena jika perusahaan ingin beriklan, mereka harus memastikan iklan mereka sampai di audiens yang tepat biar produknya laku. Google tentu saja tahu siapa saja audiens yang relevan untuk jadi sasaran calon kliennya.
Dan sekali lagi, data kita dijual, kita dijejali iklan-iklan, dan kita merasa baik-baik saja.
Oooh sekarang saya jadi mengerti, ini toh maksud dari kalimat, “If you’re not paying for it; you are the product.”
BACA JUGA Udahlah KPI, Nggak Usah Ikut Cawe-Cawe Ngurusin Platform Digital atau artikel lainnya di POJOKAN.