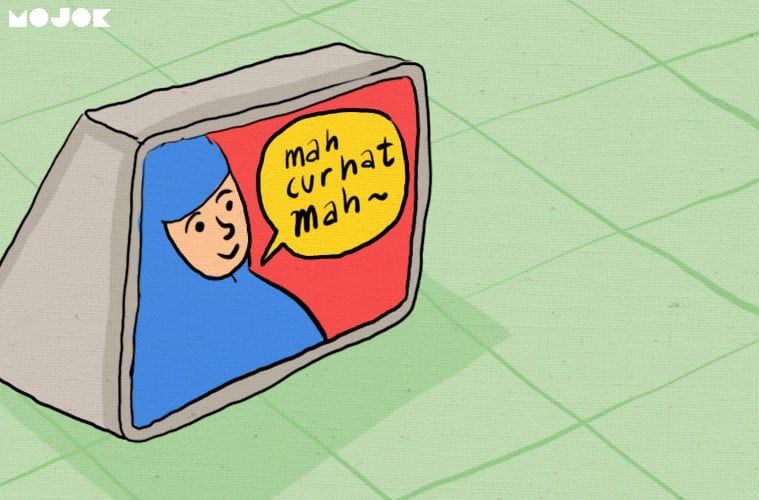[MOJOK.CO] “Mamah Dedeh selalu menjawab cepat, tampak tak kesulitan dengan pertanyaan jamaahnya. Tapi, apakah jawabannya menyelesaikan permasalahan?”
“Kalian ini hidupnya terlalu nyaman,” kata dosen saya suatu hari. Saat itu sebagian besar dari kami masih bingung mencari tema untuk menulis tugas akhir. Semua tema sepertinya sudah habis dibahas oleh kakak-kakak angkatan. Maka, ketika kami ditanya rencana judul, sebagian besar dari kami hanya bisa garuk-garuk kepala.
Lalu muncullah tuduhan bahwa hidup kami terlalu nyaman. “Hidup kalian kan hanya di situ-situ saja: kuliah, ke perpustakaan, pulang, makan, main hape, ngapel, tidur, bangun tidur nonton Mamah Dedeh, kuliah lagi….” Kami terpingkal-pingkal mendengarnya meski beberapa di antaranya memang agak tepat.
Tapi, saya kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal dalam pernyataan dosen saya, soal Mamah Dedeh. Mengapa nonton acara Mamah Dedeh bisa menjadi standar kenyamanan? Mengapa pula ia disebut sebagai faktor yang menghambat proses penulisan tugas akhir kami?
Barangkali perlu sedikit saya perjelas. Saya kuliah di Jurusan Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin, sebuah jurusan yang tidak begitu jelas alamat kerjanya. Saat KKN, anak ushuluddin biasanya kebagian urusan doa. Saking kaburnya, dalam sebuah wawancara kerja saya pernah ditanya mengapa tidak melamar kerja ke pegadaian. “Kan di sana ada tugas tafsir harga,” jelas si pewawancara setelah melihat saya terbengong-bengong. Pah poh.
Penasaran soal Mamah Dedeh, akhirnya untuk beberapa hari saya berjuang untuk bisa bangun pagi agar bisa menyimak acaranya di salah satu stasiun televisi. Perempuan kelahiran 1951 itu terlihat anggun di kursinya. Dia duduk tengah, didampingi Aa Abdel sebagai moderator. Para jamaah yang berseragam duduk rapi di sekeliling panggung. Mereka umumnya berasal dari kelompok-kelompok majelis taklim. Mamah Dedeh lalu berbicara tentang sebuah topik. Suaranya lantang dan sesekali diselingi humor dan tawa yang tak bisa saya lupakan. Sebagian besar jamaah menyimak tausiah dengan khidmat, beberapa tampak mengantuk.
Sampai beberapa hari saya belum bisa menemukan kaitan yang menghubungkan pernyataan dosen saya soal kenyamanan hidup dan Mamah Dedeh. Mungkin beliau hanya berkelakar. Pola acaranya sama belaka. Ceramah beberapa saat, musik, iklan, kemudian disambung dengan sesi tanya jawab (dalam acara tersebut diistilahkan “curhat”. Untuk curhat, seseorang terlebih dahulu harus mengucapkan kata sandi, “Curhat dong, Mah…” diikuti gerak tangan serempak para jamaah) tentang soal-soal elementer dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu, seperti pagi-pagi sebelumnya, seorang jamaah berdiri. Ia curhat tentang cara salah seorang tetangganya yang menjadi gay. Ia ingin Mamah memberi solusi.
Mendengar pertanyaaan itu Mamah Dedeh seperti tersengat. Ia langsung bangkit dari tempat duduknya dan dengan tangkas menyambarnya bahkan sebelum penanya sempat menyelesaikan kalimat terakhirnya.
“Itu setan.” Suaranya terdengar tegas. Ia menjelaskan perilaku gay adalah pengaruh setan. “Ia harus bertobat, memperbanyak istigfar, menyingkir dari komunitasnya… bla… bla….” Mamah lalu menyitir sebuah ayat. Selesai.
Saya melongo. Jangan-jangan inilah yang dimaksud oleh si dosen soal kenyamanan, pikir saya. Mamah Dedeh hampir selalu bisa menjawab pertanyaan apa pun yang diajukan dalam acara dengan mudah. Ia menjawab dengan cepat. Tak terdengar tinjauan mendalam. Ia tak perlu repot-repot menggali sumber masalah atau menelusuri variabel-varibel lain yang mungkin berkaitan. Semua beres dengan satu dua dalil.
Apakah jawabannya benar-benar membereskan masalah? Saya tidak tahu. Tapi, model jawaban ala Mamah kadang justru menimbulkan masalah. Seperti ketika Mamah Dedeh menjawab tentang kerumitan yang dialami seorang dokter hewan yang kadang harus mengoperasi anjing. Dalam fikih Islam, anjing bisa menjadi sebab najis mugaladhah. Untuk membersihkannya seseorang tidak cukup hanya dengan membasuh dengan air, tapi harus disertai debu pada salah satu basuhannya.
Mamah Dedeh kemudian mengusulkan agar orang Islam tidak perlu menjadi dokter hewan. Jawaban ini mendapatkan banyak protes.
Model semacam itu tidak hanya berlaku di acara Mamah Dedeh. Sebagian besar acara pengajian yang diselenggarakan oleh televisi menunjukkan pola yang sama. Seorang ustadz dengan gaya yang teatrikal, panggung yang menarik, memberikan tausiah. Beberapa saat kemudian pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya seharusnya bisa ditemukan di buku-buku, muncul di televisi.
Sebagaimana program acara televisi, pengajian keagamaan di televisi memang tidak bisa dilepaskan dari motif hiburan. Televisi punya kredo yang berbeda soal agama. Barangkali karena itulah dosen saya menyebut pola-pola sajian ala Mamah Dedeh sebagai bentuk kenyamanan yang justru dapat membuat seorang mahasiswa kesulitan merumuskan masalah untuk tugas akhirnya.
Tentu saja dosen saya bisa keliru. Tapi, kalau ia benar, saya jadi kepikiran temannya Tere Liye. Temannya bisa menyelesaikan skripsi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, pastilah ia tidak pernah nonton acara Mama Dedeh.