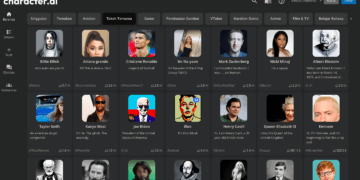Mungkin karena enggan ke mana-mana, teman yang biasa mengajak ngopi sedang ada urusan lain dan tak bisa diganggu, panas dan debu di desa yang nangkring di atas perbukitan kapur ini begitu memanggang kalau siang dan dingin menggigit saat malam, sementara pekerjaan yang saya bawa dari Jogja benar-benar tak ingin saya sentuh dulu, maka waktu nyaris seminggu di kampung lebih banyak saya habiskan dengan tiduran telentang dan layar ponsel telungkup menatap wajah. Ketika penerbit saya di Jogja akhirnya mengumumkan pra-cetak buku baru saya, tebersitlah pikiran itu: mungkin ini saatnya untuk mengunduh aplikasi Instagram. Setidaknya, dengan terbitnya buku baru, ketika saya menjelaskan dengan malu-malu kenapa akhirnya melakukan ini, saya punya sedikit alasan, meskipun ya… tak kuat-kuat amat.
Saya sudah diberi tahu beberapa kawan bahwa telah ada dua akun Instagram yang mengatasnamakan saya, bahkan lengkap dengan ratusan pengikut. Saya tak pernah menyentuh Instagram sebelumnya, jadi sudah saya pastikan akun-akun itu bukan saya yang buat. Maka, ketika memantapkan diri untuk membuat akun, yang saya pikirkan adalah apa nama akun baru ini, yang tak akan memakai nama saya secara langsung, sebab telah diambil oleh dua akun liar yang sudah ada.
Saya memikirkan beberapa karakter di novel-novel saya. Ulid, Is dan Mat, Dawuk, atau Warto, atau bagaimana kalau dirangkap jadi satu saja?
Anehnya, begitu membuka aplikasi tersebut, saya langsung masuk ke salah satu akun yang sudah ada, dengan pengikut yang telah mendekati 200 orang, meskipun tanpa satu pun postingan. Dan begitu akun itu saya masuki, saya menemukan semua data yang hanya saya dan Facebook yang tahu (email Yahoo 15 tahun lalu, tanggal lahir, nomor telepon, dst.). Bayangkan tentang rumah yang pertama kali kita lihat, yang bahkan di mimpi pun kita tak pernah memasukinya, kita dapati berplakat nama saya, bahkan bersertifikat atas nama kita, betapa bingungnya saya.
“Itu pasti kamu pernah bikin, tapi lupa,” kata seorang teman. Dan saya tiba-tiba merasa saya adalah tokoh di sinetron yang bangun dari koma dan menderita amnesia.
Ketika saya merasa tak perlu ribet-ribet lagi, lalu bisa menata ulang rumah sama sekali baru yang kesemuanya menandakan milik saya, dan memutuskan memakainya, sembari meminta seorang teman agar melaporkan akun satunya, saya memperingatkan kepada diri sendiri, juga kepada teman-teman paling awal yang mengetahui “akun baru” saya, bahwa bila dua-tiga hari ke depan ada yang tidak beres dengan akun itu, maka itu bukan saya.
Keanehan itu rupanya tak muncul, sementara lima postingan pertama saya terlihat normal-normal saja. Saya akhirnya menyimpulkan, seseorang atau sesuatu memang telah membuatkan akun itu untuk saya.
Dan, begitulah akhirnya saya “main IG”—setelah bertahun-tahun meremehkannya, menganggapnya sebagai media yang cocok bagi mereka yang hanya bisa menulis sebaris-dua baris kepsen foto berisi wajah mereka sendiri.
***
Saya terlambat untuk nyaris semua hal selain masuk sekolah (saya masuk TK sebelum berusia 3 tahun dan memulai kelas 1 sekolah dasar di usia 6 tahun). Keterlambatan-keterlambatan itu biasanya didasari oleh ketakpraktisan sikap yang melekat pada diri saya, keangkuhan-keangkuhan remeh-temeh yang agak sulit dijelaskan, sebagiannya tak penting-penting amat, dan biasanya pada akhirnya memang tak bisa dipertahankan.
Saya baru belajar naik sepeda di usia 11 tahun dan baru benar-benar “mau” mengendarainya ketika kelas dua SMP. Tahu alasannya? Karena saya tak mau pinjam punya orang. “Kalau punya sendiri pasti bisa,” begitu kata saya, mengkopi-paste kata-kata Bapak, yang tak pernah bisa naik sepeda seumur hidupnya.
Saya malas-malasan sikat gigi bahkan hingga melewati usia SMP. Alasannya, saya merasa semua remaja di desa saya tak benar-benar membutuhkannya—apalagi saat itu masih berlaku satu sikat gigi untuk satu keluarga, sebagaimana juga sabun batangan untuk ramai-ramai. Ketika masuk SMA dan hidup di pesantren, dan memutuskan untuk lebih teratur menyikat gigi, saya nyaris menyesalinya karena sejak itulah saya justru secara teratur dihajar sakit gigi. (Tentu saja dengan mengabaikan bahwa pada saat yang sama saya juga keranjingan permen Mentos.)
Meski tergolong lulus kuliah cepat (setidaknya di ukuran masa itu), saya tak tahu apa yang akan saya lakukan dan apa yang saya bisa di dunia kerja. Maka, bukan rahasia lagi, saya adalah penulis yang telat nongol. Saya baru menerbitkan novel di usia 29 tahun (itu pun baru dikenal sedikit luas sebagai penulis lima tahun kemudian), sementara banyak penulis sudah habis kariernya di usia 27. Dan, saya pikir-pikir, ini mungkin saja tak terlepas dari banyaknya keterlambatan saya untuk menyambut hal-hal yang memudahkan untuk mencapainya.
Ketika mulai bekerja di Jakarta, saat orang sudah mulai membayangkan akan ada teknologi yang lebih canggih dibanding telepon genggam, saya masih berkirim surat dengan ibu saya yang berada di perantauan. Sebulan sekali, setiap sehabis gajian, saya ke wartel dan menghabiskan seratusan ribu untuk menelepon Ibu selama lima hingga sepuluh menit lewat jaringan internasional. Ibu saya saat itu sudah memiliki telepon genggam sendiri dan ia marah dengan kekukuhan saya untuk tetap menghubunginya dengan cara lama. Saya baru tergerak untuk menebus Samsung bekas milik seorang teman kerja ketika ia mengancam akan membelikan saya telepon genggam.
Manakala teman-teman sekerja saya mengontak sebanyak-banyaknya “orang penting” di Jakarta untuk tetap bisa bertahan hidup di Ibu Kota, dengan telepon genggam baru saya yang bekas, saya justru dengan bersemangat mengumpulkan nomor-nomor teman lama di Jogja, dan dengan eksplisit menunjukkan bahwa saya merindukan mereka. Maka, saat beberapa teman sedang membabat jalan kariernya, benar-benar karier, mulai dari menjadi asisten penulis skenario sinetron, asisten komisioner lembaga negara tertentu, tim sukses calon anggota DPRD kabupaten A, saya malah balik ke kos lama saya di Jogja, menemui mahasiswa-mahasiswa tua yang bobrok nilai akademiknya, main 7 Sekop dengan orang-orang yang sama dengan saat saya masih mahasiswa, nongkrong pada jam tiga pagi di Burjo Ucil Klebengan, dan membahas hal-hal yang sama dengan saat usia saya masih 19.
Meski telah dibuatkan alamat email (mohon jangan diedit jadi “surel”) oleh seorang teman di awal usia 20-an, saya tak pernah benar-benar merasa nyaman mengirimkan cerita-cerita saya ke media lewat pos maya itu. Sebagaimana surat-surat saya untuk Ibu, saya masih terus mengirimkan cerpen-cerpen saya dalam amplop tebal dengan perangko berderet-deret, dan rela tak mendapat jawaban penolakan seperti di masa-masa sebelumnya. Ketika akhirnya saya pasrah dan menyerah, saya mungkin orang yang paling akhir memulai pakai email di dunia ini.
Tapi bahkan email tetap tak cukup membuat saya menjadi terlihat adaptif. Satu-satunya saat ketika saya mendapatkan honor dari Kompas, Rp75 ribu untuk resensi buku anak yang diterbitkan seorang teman di halaman “Kompas Anak”, saya mengambilnya di Kantor Pos lewat jasa wesel karena tak punya kartu ATM dan oleh karena itu tak merasa perlu menyertakan rekening bank. Tanpa punya ATM juga, selama dua tahun hidup di Jakarta saya mencairkan 200-300 ribu di depan teller bank dengan buku tabungan, mengantri di belakang nasabah yang membawa ransel penuh uang untuk melakukan pembayaran gaji karyawan.
Ketika menjadi buruh di penerbitan, saat email tak bisa lagi ditawar, pada akhirnya saya dipaksa bersinggungan dengan apa yang sudah sangat lama saya dengar: dunia milis (mailing list). Sekuat tenaga untuk tak terlibat, saya akhirnya masuk justru di masa mereka sedang sekarat dan media sosial telah mengintip. Tak paham pergaulan dunia maya, saya segera menjadi orang paling ceriwis dan paling menyebalkan dalam kelompok yang biasa ribut tanpa saling berhadap-hadapan itu. Di saat yang sama, dengan sangat telat saya baru memulai obsesi mengumpulkan kepingan film, ketika era pengunduhan sudah mulai menguat, dan akhirnya menghabisinya sama sekali sebelum dekade pertama tahun 2000 berakhir.
Hal yang sama saya alami dengan dunia blogging, komputer jinjing, modem internet, telepon pintar, dan kini, yang paling mutakhir, media sosial. Biasanya setelah saya menelan seluruh argumen ruwet yang selama bertahun-tahun membantu saya bertahan dan bahkan mencibir hal yang pada akhirnya dengan pasrah saya menjadi bagiannya.
***
Di film The Devil Wears Prada, saya selalu mengingat tatapan sengak dan ucapan datar namun tajam Miranda Priesly (dalam wajah dingin Meryl Streep) ke arah Andy Sachs (Anne Hathaway), asisten pribadinya, yang tersenyum meremehkan saat melihat keribetan di balik ruang editor sebuah majalah fashion. “Ada yang lucu?” Dan Miranda kemudian menceramahi Andy panjang lebar tentang sweater biru ketinggalan zaman yang dipakainya: bahwa orang-orang yang mengira tak berhubungan dengan dunia fashion, atau bahkan menganggapnya sebagai kekonyolan, biasanya adalah orang-orang yang paling akhir mengikutinya.
Saya adalah Andy Sachs berjenis kelamin laki-laki, dengan mulut lebih nyinyir, pakaian lebih dekil, dan kepala lebih keras. Dan, yang paling buruk, semua itu saya lakukan dengan sepenuhnya sadar diri: bahwa saya adalah orang yang pada akhirnya akan menyerah, mencerap semua yang saya ejek sebagai sesuatu yang telah sudah menjadi kenormalan, dan melakukan dengan sukarela apa yang sebelumnya saya pandang sia-sia.
Saya telah mengalaminya dengan Facebook. Dan kini Instagram. Setelah mengejeknya, telat mengikutinya, saya tinggal menunggu masa-masa keranjingan atasnya. Kalau tak percaya, silakan ikuti akun saya.
BACA JUGA Pola dan esai Mahfud Ikhwan lainnya di kolom REBAHAN.