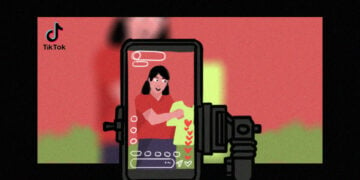Era post-truth telah membunuh kepakaran. Ia juga menyamarkan kebenaran. Hal inilah yang menjelaskan mengapa warganet lebih mudah percaya omon-omon Nikita Mirzani ketimbang argumen Najwa Shihab.
***
Nikita Mirzani mengambil alih panggung. Videonya yang berisi “surat terbuka” untuk Najwa Shihab ramai di berbagai kanal media sosial.
Di TikTok, misalnya, video itu FYP dan sudah ditonton jutaan kali. Di Instagram, penampakan sang influencer yang “menyerang” Najwa secara bertubi-tubi kerap muncul di fitur explore.
@ekspresiseleb88 Tanggapan NM soal Najwa Shihab bilang Jokowi nebeng 😩 #nikitamirzani #ekspresiseleb ♬ original sound – Bima_studio😳
Sebagai orang yang paham rekam jejak Nikita Mirzani, begitu juga Najwa Shihab, saya tak begitu mempermasalahkan video itu. Bagi saya, kebisingan adalah keniscayaan dari demokrasi. Namun, yang mengusik pikiran saya adalah respons warganet.
Bagaimana tidak, banyak netizen yang bersepakat dan bahkan mendukung pernyataan Nikita daripada Najwa Shihab. Padahal, argumen yang dibawa Nikita lebih banyak omon-omon, daripada Najwa yang bicara dengan berbasis data.
Sebagai informasi, Nikita Mirzani menyerang Najwa Shihab gara-gara sang jurnalis menyentil Presiden RI ke-7 Joko Widodo perihal “nebeng” pesawat TNI AU ke Solo saat purnajabatan.
Setelah menyaksikan berbagai respons warganet yang sepakat dengan Nikita–dan menyerang Najwa, sontak saya teringat dengan buku yang saya baca 2020 lalu. Judulnya Matinya Kepakaran (2019) karya Tom Nichols. Pendeknya, buku itu membahas soal fenomena post-truth yang bikin omongan influencer justru lebih didengar dan dipercaya ketimbang argumen para expert (ahli).
Era media sosial “membunuh” kepakaran
Saya ingat, dalam Matinya Kepakaran, Tom Nichols menyoroti betapa di era media sosial ini, audiens lebih mendengarkan suara para micro-celebrity alias influencer alih-alih mengacu para ahli yang jelas-jelas lebih punya kompetensi.
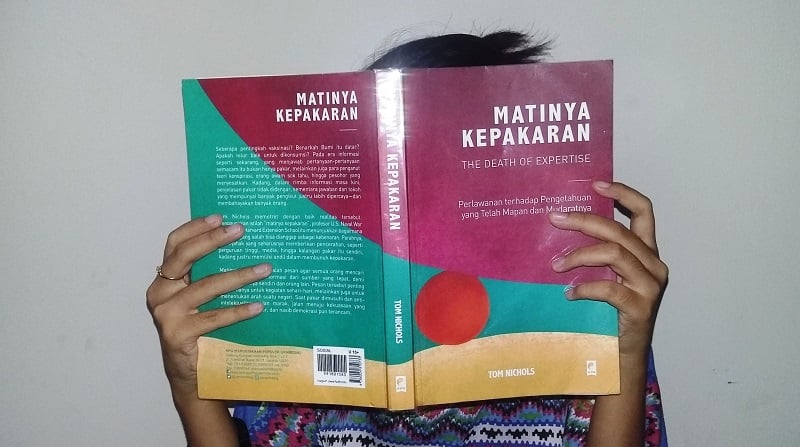
Dahulu, misalnya, untuk membicarakan sebuah isu, baik itu politik, kesehatan, dan lain sebagainya, dibutuhkan sebuah kepakaran. Artinya, untuk membicarakan suatu hal, dibutuhkan kompetensi. Sementara kompetensi sendiri diperoleh melalui pembelajaran.
Sementara saat ini, untuk berbicara soal isu tertentu, tak butuh yang namanya kepakaran. Cukup omon-omon saja. Fenomena ini jamak kita saksikan saat pandemi Covid-19. Kala itu, ada banyak influencer yang bersuara ngawur soal virus Corona. Celakanya, suara mereka lebih dipercaya daripada para ahli virus yang jelas-jelas lebih kompeten untuk membicarakannya.
Dosen Komunikasi Universitas Airlangga, Irfan Wahyudi, menyebut fenomena post-truth terjadi karena akses penggunaan teknologi semakin terbuka. Menurutnya, hal ini pun membawa perubahan lanskap yang cukup signifikan pada budaya manusia.
“Dahulu, tidak semua orang bisa berbicara. Setelah ada medsos, akses teknologi-informasi semakin bebas dan terbuka, semua orang bisa bicara apa saja,” jelas Irfan saat Mojok hubungi, Rabu (30/10/2024).
Alhasil, kata Irfan, dari gejala inilah yang disebut Tom Nichols sebagai “matinya kepakaran” tadi memasuki eranya. Di zaman sekaran, seseorang pada akhirnya dipercaya bukan karena keahlian atau kepakarannya, melainkan karena pengaruhnya yang besar di media sosial.
“Semakin banyak follower, semakin banyak subscriber, dan semakin lantang bicara di medsos, semakin dia disimak dan dipercaya,” ujarnya.
Rezim algoritma bikin warganet percaya pada kebenaran semu
Fenomena warganet yang lebih percaya pada omongan Nikita Mirzani alih-alih argumen berbasis data Najwa Shihab, bagi Irfan, adalah konsekuensi logis dari era post-truth.

Apalagi, hari ini masyarakat hidup di masa rezim algoritma. Preferensi kebenaran yang mereka percaya bukan lagi berdasarkan data-data valid, melainkan seberapa sering mereka terpapar oleh sebuah konten.
“Dalam bahasa komunikasi, ada yang nama echo chamber dan filter bubble. Di era media sosial, kita hidup dalam gelembung kita masing-masing,” jelas Irfan.
“Mudahnya begini, ketika kita like salah satu postingan, maka konten sejenis akan selalu muncul di algoritma kita, karena memang mesin membaca itulah preferensi kita. Nah, saking seringnya terpapar, pada akhirnya kita percaya bahwa itu adalah kebenaran.”
Apalagi, Irfan memahami bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah. Alhasil, mereka jadi sulit memfilter informasi mana yang valid dan mana yang bohong–karena minimnya kemampuan check dan recheck.
“Apalagi yang bicara influencer populer dan mereka senangi. Apapun yang yang dibicarakan, akan mudah bagi audiens untuk percaya,” kata Irfan.
Post-truth itu ancaman besar, tapi sekaligus keniscayaan
Irfan menjelaskan bahwa gejala post-truth yang membunuh kepakaran, akan berdampak negatif dalam konteks kehidupan sosial budaya. Bagi dia, dengan kecenderungan orang lebih mempercayai influencer ketimbang ahli, bakal mengaburkan sebuah fakta yang sebenarnya..
Lebih jauh, distribusi misinformasi dan berita bohong akan membanjiri warganet. Dampak lebih mengerikannya masyarakat akan mudah dipecah belah.
“Karena buta realitas, tak bisa membedakan kebenaran dan kebohongan, masyarakat akan mudah dipecah belah,” jelasnya.
“Makanya, hari ini siapa yang bisa menguasai dan memonopoli teknologi-informasi, dia yang akan menguasai kebenaran kita,” sambungnya.
Kendati punya dampak mengerikan, Irfan juga menggarisbawahi bahwa fenomena matinya kepakaran akibat post-truth tak cuma kejadian di Indonesia. Di belahan dunia lain, fenomena serupa juga terjadi meski dengan level yang berbeda. Artinya, apa yang terjadi dalam fenomena Nikita Mirzani vs Najwa Shihab hanyalah gambaran kecil dari besarnya kebenaran-yang-samar dan kepakaran-yang-mati.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA Iklan Judi Online Nikita Mirzani Itu Ganggu Banget, tapi Siapa yang Berani Melawan?
Ikuti artikel dan berita Mojok lainnya di Google News