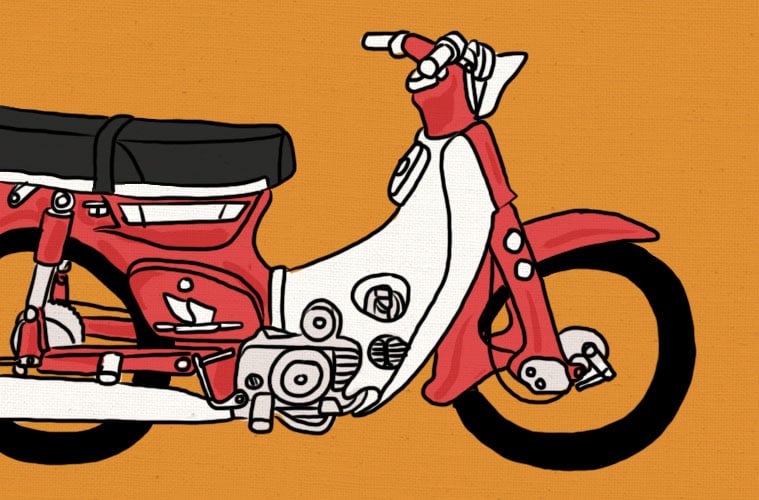Si pitung, demikian para penggemarnya menyebut motor antik ini. Lahir tahun ‘70-an, punya nama lengkap Honda C70, berkapasitas mesin 70 cc, nama apa lagi yang lebih layak selain “pitung”? Bukan si Pitung jagoan Betawi, melainkan kata Jawa pitung puluh (tujuh puluh) yang dipotong.
Desain moyangnya motor bebek ini sungguh memesona. Dari depan, setangnya manis menggoda, menimbulkan nostalgia di diri kids pemburu burung jaman old pada ketapel kayu. Dari samping, warna merah putih di bodinya memancarkan semangat tempur ’45. Kombinasi kedua aspek itu sungguh harmonis untuk diangkat di film Mad Max versi gondes insyaf yang sudah sadar betapa jahanamnya RX King.
Sekarang mari kita lihat dapur pacunya. Pitung memiliki kapasitas mesin 70 cc yang dengan spek demikian, melaju di kecepatan 80 kilo per jam menjadi kemewahan tersendiri. Tetapi, jangan lupa, pitung sudah menggunakan mesin 4 tak di zaman mesin 2 tak masih mendominasi motor-motor di Indonesia. Kesadaran bahan bakar fosil akan segera habis membuat irit menjadi jalan samurai bagi pitung.
Dan memang, bagi pitung, bensin senyatanya hanya aksesori. Kali ini, pengalaman saya sebagai eks-pemilik pitung yang akan bicara.
Saat kuliah dulu, tahun dua ribuan, kala harga bensin per liter masih dua ribuan juga, lima ribu rupiah berarti dua setengah liter bensin. Bahan bakar segitu cukup buat si pitung membawa saya jalan-jalan dari Kudus ke Demak, muter-muter ke sana kemari, dan pulang lagi ke Kudus. Cek tangki, bensin masih sisa seliteran. Padahal jarak Kudus ke Demak 25 kilo, PP 50 kilo, belum muter-muternya. Katakanlah saya muter-muter 20 kilo, artinya perjalanan 70 kilo tidak habis bensin satu liter.
Untuk menemani kuliah dengan jarak kos ke kampus hanya 2 kilo, saya biasa mengisi tangki seliter tiap 25 hari sekali. Bayangkan kalau saya isi dua liter, bisa sampai lupa sebenarnya motor ini butuh bensin atau tidak.
Tapi ya, namanya sempurna cuma punya Allah, Demian, dan cowok di drama Korea, pitung tetap punya kekurangan. Walau kalau dikenang-kenang, kekurangan ini bisa jadi karena saya saja yang sial beli pitung kurang waras.
Si pitung tersebut saya peroleh tahun 2004 dengan mahar 1,65 juta, dicicil dua kali. Saat itu saya masih mahasiswa baru yang nyambi serabutan sebagai tukang reparasi. Harga itu terhitung murah untuk motor antik dengan surat lengkap dan bodi masih bagus.
Penyakit pertama saya temukan ketika sedang asyik bermesraan dengannya di jalan raya dan tiba-tiba cuaca mendung lalu turun hujan. Sebagai pengendara yang memegang prinsip sedia jas hujan sebelum mendung, saya tenang-tenang saja. Saya menepi sejenak, memakai jas hujan, dan kemesraan dengan si pitung saya lanjutkan. Belum sampai 100 meter, tiba-tiba mesin si pitung meninggal dunia. Hujan deras, sendirian, motor mogok. Kata Bang Rhoma, “Sungguh derita di atas derita.”
Setelah hujan agak reda, si pitung saya beri pertolongan pertama pada permogokan. Semua hal tentang mesin yang saya ketahui langsung saya terapkan. Hasilnya nihil. Dengan sisa tenaga yang ada, si pitung saya dorong ke bengkel sembari berdoa semoga bengkel ini menerima titipan KTP kalau uang kurang.
Hasil diagnosis pak montir, karburator kemasukan air melalui saluran udara. Kalau saya perhatikan, memang posisi saringan udaranya rawan kemasukan air. Untuk memperbakinya karburator harus dibongkar dan dikeringkan terlebih dahulu. Perlu menunggu agak lama sampai si pitung mau hidup lagi.
Sejak saat itu saya akan berteduh jika kondisi hujan meskipun saya membawa jas hujan.
Penyakit kedua lebih parah. Lokasinya ada di dapur pacu alias pada sekernya. Sebagai motor tua, mesin si pitung mengalami oversize sehingga oli mesin merembes ke ruang pembakaran. Efek yang ditimbulkan ada tiga. Pertama, knalpot ngebul mengeluarkan asap mirip motor 2 tak. Kedua, busi akan cepet basah kena oli mesin. Ketiga, oli mesin cepat habis.
Efek pertama bisa saya ikhlaskan. Paling banter pengendara lain akan melotot saat berhenti di belakang saya dan saya kirimi asap tebal. Efek kedua sungguh menyusahkan, busi basah artinya motor mogok. Busi basah –> api tidak keluar –> tidak ada pembakaran –> mesin mati –> motor mogok. Mungkin kira-kira tiap jalan 5 kilo, dia akan mogok. Tiap kali mogok, saya harus mengambil kunci busi, melepas busi, mengeringkannya dengan kain, lalu memasangnya lagi. Hal serupa juga terjadi pada pengendara vespa antik, tapi minus solidaritas antarpemakai vespa yang biasanya selalu berhenti tiap melihat vespa lain mogok di jalan, haha. Jika orang lain mengukur lama perjalanan dengan rumus jarak dibagi kecepatan, saya harus menghitung dengan menambahkan durasi waktu bongkar pasang busi tiap 5 kilo.
Efek ketiga, yakni oli mesin cepat habis menghasilkan tragedi yang lebih tragis. Oli mesin habis –> mesin overheat alias terlalu panas –> mesin mati –> motor mogok. Entah tiap berapa kilometer sekali oli mesin si Pitung ini akan habis. Saya hanya mengingat, setiap kali melewati pom bensin saya harus mampir. Bukan untuk beli bensin, tetapi beli oli merk Mesran, oli Pertamina termurah dibanding oli-oli yang lain. Dan yang terpenting belinya boleh eceran. Mau beli seribu, dua ribu, tiga ribu, boleh-boleh saja.
Jika mogok motor karena busi basah hanya butuh waktu setengah jam, mogok mesin karena oli habis butuh waktu hampir satu jam. Sebab untuk menghidupkannya lagi butuh beberapa proses. Pertama, dorong si pitung ke pom bensin. Kedua, tunggu sampai mesin si pitung menjadi dingin. Ketiga, isikan oli ke mesin. Keempat, genjot starter sampai otot kaki mau putus agar mesin hidup lagi. Benar-benar alat fitness yang berpura-pura menjadi motor: membuat tubuh sehat dan kuat karena rajin bergerak dan jalan kaki.
Setelah hampir dua tahun berkencan dengan si pitung yang penuh duka lara, akhirnya kami berpisah juga. Bukan karena saya menjualnya, tetapi karena motor ini dipinjam oleh salah seorang saudara saya. Lama tidak dikembalikan, eee ternyata malah digadaikan ke temannya. Uangnya digunakan untuk sangu jadi TKI di Malaysia. Lengkap sudah penderitaan saya dengan si pitung.
Selamat tinggal Pitung, semoga engkau bahagia bersamanya.