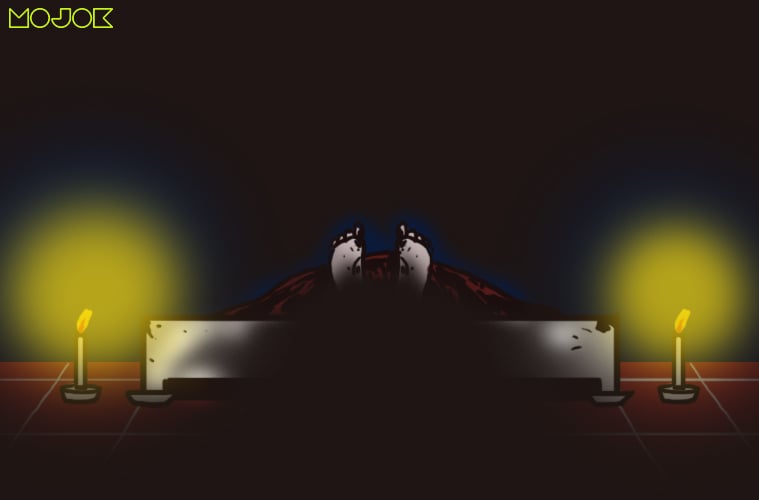MOJOK.CO – Di Indonesia pembunuhan yang dilakukan psikopat memang belum ditangani dengan proporsional. Dianggap kejahatan biasa aja gitu. Padahal kan….
Meski tetap tenang, pandangannya menunduk ketika masuk ruang penyidikan di Polres Surabaya Timur, 13 tahun lalu. Aura ruang kantor polisi yang seram, tak juga membuatnya takut. Bahkan, ia terkesan tak peduli. Ia juga tak mau menjawab apa-apa.
Perawakannya kecil. Pakai kacamata, kayak orang pintar. Selama tiga hari menjadi tersangka, tak banyak yang didapat penyidik. Ia hanya sebatas mengaku saja. Itu pun setelah kaki tangan pembunuhan yang disewanya tertangkap dan buka mulut.
Sebelum saya bertemu untuk wawancara dengannya, penyidik sudah mengeluhkan perempuan itu. “Atos, Mas, arek-e. Cuma jawab ya dan tidak,” kata penyidik itu.
Saya, yang saat itu masih jurnalis kriminal di lapangan, tertarik dengan kasus tersebut. Selain karena itu berita besar untuk ukuran Surabaya, saya merasa kasus ini agak berbeda dengan kasus-kasus pembunuhan sebelumnya.
Seorang pengusaha dibunuh oleh perempuan yang pernah ikut ngenger (numpang hidup) beberapa tahun lamanya—dengan sadis pula.
Menyewa dua orang pria untuk membantunya, perempuan itu dengan dingin membekap kepala pengusaha itu dengan bantal. Selama setengah jam lebih.
Detail pembunuhan memang terungkap. Tapi, motifnya belum. Tidak ada hubungan asmara (yang kerap jadi motif pembunuhan).
Hubungan antara pengusaha itu, istrinya, dan perempuan itu juga baik-baik saja. Tidak ada barang yang hilang. Tidak ada dendam. Perempuan itu keluar dari rumah pengusaha itu dengan baik-baik.
Lantas, ngapain membunuh kalau gitu?
Wawancara itu kemudian menjadi salah satu wawancara paling serius yang pernah saya lakukan selama jadi jurnalis.
Pada awalnya, seperti penyidik sebelumnya, ia bahkan menolak sama sekali berbicara. Ditanya diam saja. Selama setengah jam di depan, saya berusaha membuat dirinya nyaman. Mengurangi blocking pikirannya.
Setelah hampir dua jam berbincang, saya akhirnya mendapat pengakuannya. Bahwa ia membunuh karena “ingin” saja. Tiba-tiba merasa tak suka dengan pengusaha itu, dan berniat membunuhnya. Tidak ada penyesalan, hanya kelegaan.
Cerita selanjutnya, perempuan itu lalu diproses seperti kasus biasa. Meski penyidik tahu bahwa ada kemungkinan pelakunya ini psikopat, tak pernah ada pemeriksaan psikologi secara menyeluruh. Bergulir begitu saja.
Sependek pengetahuan saya, perempuan itu akhirnya divonis sekitar 15 tahun penjara.
Saya sempat bertemu penyidiknya di kemudan hari, dan menanyakan hal itu. Si penyidik mengakui bahwa perempuan itu memang “sakit”. Namun, dirinya juga dilematis.
Mau memeriksakan psikologi secara menyeluruh, selain prosesnya rumit, lama, dan membutuhkan biaya, juga nanti berisiko kasusnya gugur.
“Kalau dinyatakan gendheng, lak ucul, Bos,” katanya.
Kalau akhirnya dilepas dengan catatan harus diterapi, siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Siapa yang membiayainya?
“Juga berisiko berbahaya bagi masyarakat. Wis ngene ae, paling nggak selama belasan tahun kemudian dipenjara, masyarakat aman. Metu-metu wis tuwek, wis nggak iso opo-opo,” katanya.
***
Pembunuhan yang dilakukan psikopat memang jarang mendapat perlakuan yang “proporsional” di Indonesia.
Kita cenderung ngeri-ngeri aja ngelihat atau membaca beritanya, tapi tanpa sadar melihat kasus model begitu bak kasus pembunuhan biasa. Penyidik pun cenderung memperlakukannya seperti kasus kriminal pada umumnya.
Seperti kasus remaja perempuan 15 tahun yang membunuh bocah berusia 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta, baru-baru ini. Dari sejumlah berita, terlihat kecenderungan seperti itu. Penyidik, dan juga jurnalisnya, mencari gampangnya saja.
Ini muncul ketika Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus tanya ke pelaku pembunuhan ini, “Saya tanyakan lagi, ‘Pernah nggak kamu punya perasaan membunuh sebelumnya?’ Dia bilang, ‘ya pernah, tapi saya bisa tahan.’”
Sayangnya, ketika hari pembunuhan itu tiba pelaku ini mengaku sudah tak bisa tahan lagi buat ngebunuh orang. “Hari itu saya nggak bisa tahan (kepinginan membunuh orang),” kata si pelaku ditirukan oleh polisi.
Melihat pengakuannya yang ngeri begitu, belum dengan diary, dan status medsosnya yang sangar-sangar, tak perlu menjadi jenius psikolog untuk tahu ada yang salah dengan kejiwaan remaja 15 tahun tersebut.
Apalagi, muncul informasi-informasi “pelengkap” lainnya. Seperti, ayahnya galak, suka film-film sadis, suka menggambar adegan penyiksaan, suka menyiksa binatang pakai garpu, dan sebagainya.
Penjelasan gampang-gampangan ini kemudian ya kita ketahui akhirnya memunculkan reaksi yang tidak pernah menyentuh substansinya.
Dari perbaikan di sektor sensor, “Inilah pengaruh film yang buruk. Harus ada sensor yang lebih ketat,” atau perbaikan di pendidikan moral agama, “Kurangnya pendidikan agama,” dan hal-hal normatif lainnya yang belum tentu benar-benar menjawab problem tersebut.
Karena, pertanyaan pentingnya adalah harus diapakan remaja gadis ini? Celakanya, menelusuri jawaban dari pertanyaan itu tidak pernah mudah. Lah piye? Hawong, rumusan masalahnya saja sudah bermasalah.
Jika mau membaca sedikit saja, kita tahu bahwa remaja pembunuh bocah ini memang sakit secara kejiwaan. Seperti orang kena kanker, kena diabetes, tapi ini yang kena adalah pikirannya.
Dengan “penyakit” seperti ini, saya yakin betul kalau remaja pembunuh bocah ini ditangani pengacara andal, dia bakalan bisa lolos dari peradilan. Sebab, pasal KUHP jelas mengatur bahwa orang sakit jiwa atau masuk kategori gila tidak bisa dihukum begitu saja.
Di sisi lain, tentu saja perempuan muda ini berbahaya bagi masyarakat sekitarnya. Jika memang benar dia psikopat, maka membunuh baginya tidak ada masalah sama sekali.
Ada sejumlah ciri psikopat yang pernah saya baca. Seperti membunuh baginya adalah sebuah kewajaran. Sama seperti orang lain yang ketika lapar, lalu makan. Baginya, jika ada seseorang yang bisa dijadikan sarana, atau yang menghalangi jalannya, maka ya tinggal bunuh saja. Sesederhana seperti minum ketika haus. Gitu aja.
Namun, ketika kita kemudian meminta agar aparat menindak tegas, seperti menghukum mati, atau memenjarakannya di sel isolasi sampai remaja itu tua, maka itu akan bertabrakan dengan nurani sendiri.
Ya iya dong, bagaimana Anda bisa merekomendasikan hukuman mati bagi orang yang sakit? Saya percaya, tiap pikiran yang bertentangan dengan hati nurani akan membuat diri kita juga menjadi sakit.
***
Di sinilah, sistem hukum positif di Indonesia tidak punya alternatif untuk kasus-kasus nyeleneh begini.
Dalam dilema antara bertindak kejam (dan karenanya melindungi masyarakat) atau bersikap welas asih (tapi berpotensi membahayakan masyarakat), biasanya penyidik memilih untuk yaaa wis diserahkan ke hakim saja.
Pada gilirannya, hakim paling juga memutuskan untuk dipenjara dalam waktu yang lama. Karena memang tidak ada alternatifnya.
Indonesia belum punya fasilitas khusus untuk para psikopat. Seperti yang saya bayangkan di Arkham Asylum Gotham City dalam cerita Batman. Berharap, di dalam penjara, si pelakunya akan sembuh sendiri. Atau dipenjara dalam waktu yang lama, sehingga ketika keluar sudah tua renta dan tak bisa berbuat apa-apa lagi yang membahayakan.
Ini tentu saja bukan alternatif solusi yang baik pula. Tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi di penjara ketika psikopat campur dengan penjahat lainnya.
Mungkin saja sembuh. Tapi, mungkin saja penyakitnya juga makin bertambah buruk. Si pelaku mungkin akan lebih sadis, dan lebih membenci masyarakat di luaran yang mengurungnya.
Belum lagi kemungkinan dia bisa menularkan pemikiran psikopatnya ke yang lain. Sehingga, lahir psikopat-psikopat baru, yang siap menebar ancaman begitu keluar dari penjara.
Sebenarnya hampir semua dari kita yang mempunyai gangguan jiwanya sendiri-sendiri. Meski dengan tingkat yang berbeda-beda. Bapak psikologi modern, Sigmund Freud sendiri juga mengakui bahwa dia punya neurotis.
Tiap orang punya psikopatologinya sendiri-sendiri. Dan kerap muncul sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari.
Selip lidah, mimpi yang terasa tidak jelas, tiba-tiba galau sendiri, adalah tanda-tanda seperti itu. Meski memang, pada remaja berusia 15 tahun si pembunuh bocah itu, tingkat dan jenisnya sudah sangat ekstrem. Sampai-sampai membuatnya terobsesi untuk jadi karakter “blur” di komik Conan dan Kindaichi.
Sungguh, untuk kasus-kasus seperti ini, saya tidak pernah tahu solusi yang baik seperti apa. Tapi, mencari gampangnya dengan menyebut ini karena pengaruh tontonan, dan memperlakukan kasus ini seperti kasus biasa, maka itu sama saja menutup kemungkinan perbaikan sistem hukum di Indonesia.
Perbaikan sistem hukum ini rasanya sangat dibutuhkan. Sehingga, kita punya sistem hukum yang bisa menangani psikopat dengan baik, sekaligus di sisi lain juga bisa melindungi masyarakatnya.
Saya sih berharap banyak, dengan munculnya kasus semacam ini diskusi publik soal penderita psikopat dan cara penanganannya bisa muncul. Bukan cuma jadi obrolan “pemakluman” di warung kopi aja.
“Idih, pembunuhnya kejam banget ya? Bocah baru 5 tahun lho dibunuh.”
“Hm, psikopat ya?”
“Iya, psikopat.”
“Oalah, piskopat ya?”
“Hm, wajar sih. Psikopat kok ya?”
….
Wajar?
BACA JUGA Mengapa Orang Memutuskan Bunuh Diri? atau tulisan Cak Kardono Setyarokhmadi lainnya.