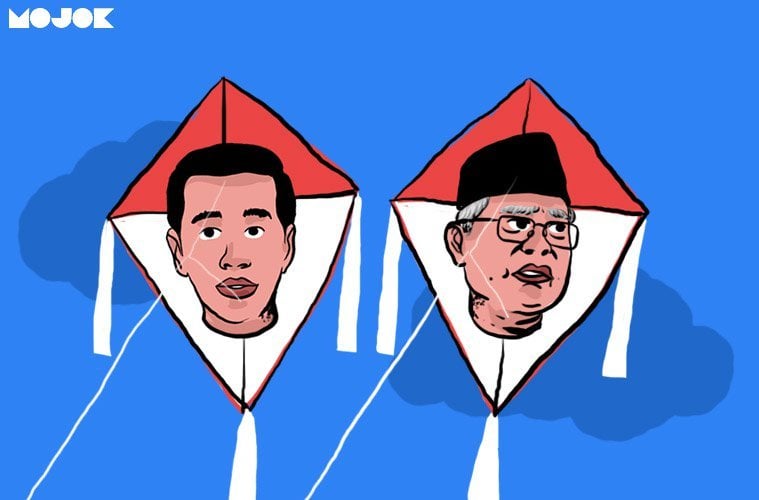Sore itu kopi saya betul-betul pahit selepas mendengar seorang tokoh nasional bicara definisi agama. Ia adalah Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah yang Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Mungkin saja beliau berbicara atas nama pribadi, mungkin juga mewakili sesuatu yang besar di belakangnya. Tapi, anggap saja tulisan ini tanggapan untuk Profesor Din sebagai pribadi—pribadi agung yang sudah malang melintang di dunia akademis, politik, maupun diplomasi internasional.
Alkisah, Ayah Mursid, tetua Selam Sunda Wiwitan yang selama ini diam didiskriminasi dan dianggap tidak beragama, baru-baru ini menyuarakan perlunya negara mengakui Selam Sunda Wiwitan sebagai agama dan dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk.
Ayah Mursid tidak sendirian. Sudah lima tahun terakhir pemeluk Kaharingan di Kalimantan, yang oleh Orde Baru dihindukan, menuntut negara untuk mengakuinya sebagai agama sendiri yang terpisah dari Hindu. Mereka tidak merasa Hindu dan tidak menganut ajaran Hindu.
Ayah Mursid tidak sendirian. Cobalah sesekali Profesor Din mengadakan semacam rihlah nusantariyah atau semacam ekspedisi mengunjungi kawan-kawan kita warga Kajang di Sulawesi, penganut Sapta Darma di Yogyakarta, Kejawen dan Kapribaden di Jawa Tengah, Parmalim di Sumatra, Wetu Telu di Lombok, Marapu di Sumba, Adat Lawas di Kalimantan Timur, dan ratusan lainnya di seantero nusantara.
Mereka adalah warga negara Indonesia yang memiliki sistem ketuhanan dan kemanusiaan sendiri-sendiri, yang satu sama lain berbeda, apalagi dibanding enam agama yang menurut Profesor Din diakui oleh negara. Entah apa pula maksud diakui di situ.
Apakah Ayah Mursid semata bicara tentang KTP? Tentu saja tidak.
Ayah Mursid sedang berbicara tentang hak warga negara yang selama puluhan tahun didiskriminasi sejak lahir hingga mereka meninggal. Sejak mengurus surat nikah, akta kelahiran, hingga menguburkan warganya yang meninggal. Diskriminasi adalah sesuatu yang menubuh pada mereka. Jutaan dari mereka. Sejak disebut dengan sangat peyoratif sebagai penganut animisme-dinamisme hingga disebut “lain-lain” dalam statistik populasi penduduk Indonesia di Badan Pusat Statistik maupun survei-survei akademis.
Apakah Ayah Mursid bicara tentang KTP? Tentu saja tidak.
Ayah Mursid bicara tentang tanah dan alam yang melahirkan mereka, yang mereka jaga dan rawat dengan segala kesantunan dan tata krama yang mereka miliki, yang perlahan dirongrong oleh para oligarch atas nama pembangunan dan peradaban. Juga atas nama agama yang diakui. Juga atas nama keniscayaan modernitas yang diagungkan oleh para perusak alam itu.
Dan Profesor Din Syamsuddin bicara tentang definisi agama secara ilmiah. Entah seperti apa yang disebut ilmiah itu.
Jika yang disebut ilmiah adalah memosisikan manusia yang memiliki sistem ketuhanannya sendiri sebagai bagian dari sub-agama orang lain; jika yang disebut ilmiah adalah mengakibatkan mereka-mereka penganut “agama yang tidak diakui” sebagai belum beragama, dan karena itu mereka adalah objek yang boleh menjadi sasaran kristenisasi, islamisasi, dan sejenisnya; jika yang disebut ilmiah adalah memaksa anak-anak mereka untuk mengikuti pelajaran agama yang bukan agamanya sendiri, atau diwajibkan mengaku Islam atau Kristen atau Hindu atau yang lain ketika mereka melakukan transaksi di bank; jika yang disebut ilmiah adalah sesama warga negara dirundung karena kolom agama dalam KTP-nya kosong, atau bahkan di-PKI-kan; jika yang disebut ilmiah artinya harus melarang mereka masuk menjadi anggota polisi dan TNI atau menjadi pegawai negeri sipil; lebih baik saya tidak ilmiah sama sekali. Sama sekali.
Ya, saya memilih untuk tidak ilmiah.
Dan Profesor Din Syamsuddin bicara tentang konsekuensi: jika Selam Sunda Wiwitan diakui sebagai agama, akan ada ribuan agama di Indonesia.
Adakah yang salah dengan tumbuh berkembangnya ribuan agama di Indonesia? Atau mungkin profesor satu ini memang lebih nyaman dengan model fusi partai ala Orde Baru? Cukup enam agama yang diakui, yang lain silakan menginduk. Peduli amat apakah si anak mirip dengan induknya, atau dimirip-miripkan, atau dipaksa mirip, atau yang penting halaman depannya saja yang mirip.
Lalu apa yang terjadi? 11 Oktober 2008, serombongan anggota Front Pembela Islam menyambangi salah satu sanggar Sapta Darma di Balecatur, Sleman, dan merusak beberapa barang di sana. FPI menganggap Sapta Darma aliran sesat karena beribadah menghadap ke timur sementara di kolom KTP mereka tercantum Islam sebagai agama.
Nah, loh! Meminta agamanya dicantumkan, ditolak. Menuliskan agamanya dengan menginduk ke agama lain, dilarang pula beribadah menurut agama aslinya.
Demikianlah. Semanis apa pun kopimu, tentu mengandung kepahitan.