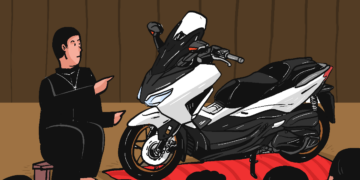MOJOK.CO – Pertanyaan kenapa Nabi Muhammad tak boleh digambar itu pertanyaan simpel sebenarnya, jadi rumit karena yang tanya Prof. Sumanto.
Baru saja di belantara Fesbuk saya menyimak rame-rame status Prof. Sumanto Al-Qurtuby. Dia mempertanyakan, kenapa umat Islam dilarang menggambar sosok Nabi Muhammad?
Padahal, kata Mas Manto, “umat agama lain biasa saja menggambar atau mengkarikaturkan nabi atau pendiri agama mereka. Bahkan sosok yang statusnya lebih tinggi dari sekadar ‘nabi’ atau ‘rasul’ pun mereka gambar dan karikaturkan.”
Kemudian Mas Manto mencontohkan bagaimana umat Hindu menggambar dewa-dewi, umat Kristen menggambar Yesus, dan sebagainya. Semua itu dijadikan landasan untuk menggugat “kebijakan teologis” Islam.
Antara Nabi Muhammad dan Lainnya
Oleh Sumanto Al Qurtuby
Hingga saat ini sayah itu terus bertakon-takon: kenapa Nabi…
Dikirim oleh Sumanto Al Qurtuby pada Senin, 26 April 2021
Sudah ada beberapa kritik yang saya baca terkait tulisan Prof. Sumanto itu. Kebanyakan nadanya menagih keislamannya. “Ngaku Islam tapi kok mengejek Islam? Islam beneran nggak tuh?” kira-kira begitu.
Ada juga yang lebih mendalam semacam junjungan saya Gus Rektor Rijal Mumazziq, yang memaparkan bahwa setiap agama punya sisi esoteris dan eksoteris yang dinikmati sendiri-sendiri.
Juga tentang wilayah toleransi, bagaimana setiap agama punya dimensi sakral masing-masing yang tak pantas diolok-olok.
Saya tidak cukup berminat memikirkan tipe kritik pertama, apalagi kalau isunya sudah ke penistaan dan semacamnya. Basi itu mah. Adapun tentang versi kritik Gus Rijal, saya termasuk warga Muhammadiyah yang selama ini taqlid buta kepada tokoh NU satu itu.
Cuma, saya ingin menambahkan sedikit, sambil melihat pertanyaan Mas Manto itu dari soal yang saya rasa lebih mendasar lagi. Yaitu tentang bagaimana Mas Manto lupa bahwa agama itu soal keyakinan, dan setiap keyakinan itu bersifat subjektif. Titik inilah sebenarnya bolong yang paling parah dalam gugatan Mas Manto.
Bukan tentang konsistensi iman personal Mas Manto, bukan pula tentang perkara toleransi. Tapi lebih pada pemahaman epistemologis bagaimana sebuah sistem keyakinan itu sama sekali berbeda dengan sistem pengetahuan objektif semisal sains.
Sains punya ukuran-ukuran umum, evidence based, dapat diverifikasi. Dan karena bisa diverifikasi dengan bukti-bukti terukur, ada standar-standar keumuman yang dapat diterapkan dalam segala kasus.
Ambil contoh, model penanganan virus Korona di Indonesia dan di Amerika itu semestinya sama, menurut standar-standar sains. Cara mengobati patah tulang untuk manusia penyembah Yahweh dan manusia penyembah UFO juga sama, sebab ada parameter standar medis yang juga sama.
Ringkasnya, sains sifatnya objektif, bisa dipertanggungjawabkan objektivitasnya, dan punya alat ukur yang seragam (meski tetap saja dinamis seiring perjalanan dialektika pengetahuan).
Tapi, agama jelas perkara beda. Agama itu subjektif. Itulah kenapa ia disebut “ke-yakin-an”. Orang percaya agama itu urusannya bukan soal keberadaan atau ketiadaan bukti empiris, melainkan soal yakin dan nggak yakin, percaya dan nggak percaya. Itu saja.
Dan karena sifat dasarnya sudah subjektif sesuai pengalaman personal-psikologis-spiritual orang per orang, lucu sekali kalau agama ditarik ke dalam ukuran-ukuran yang seragam seperti halnya rumus-rumus objektif sains.
Sikap mengukur dua atau tiga atau seribu agama dengan satu standar alias satu timbangan yang sama itu sudah cacat logika sedari titik pijak awalnya.
Nah, visualisasi Nabi Muhammad memang dilarang dalam Islam. Kenapa? Ya karena sistem keyakinan Islam melarangnya. Titik.
“Lho di agama lain boleh lho!”
Lha ya karena umat Islam memang tidak mempercayai ajaran agama lain, sebagaimana umat agama lain tidak mempercayai ajaran Islam.
“Trus kenapa orang yang tidak percaya Islam kok juga dilarang menggambar Muhammad?”
O, itu perbincangannya bukan lagi soal penimbangan validitas ajaran Islam sendiri, tetapi sudah ke perkara manajemen hidup bersama, demi harmoni sosial dan sebagainya. Obrolan lain kalau itu, Bund.
Saya ulangi. Agama itu perkara subjektif masing-masing dapur dan masing-masing penganutnya. Karenanya, mengukur secara “objektif” satu aspek dalam suatu keyakinan dengan menggunakan alat ukur keyakinan yang lain itu menggelikan.
Biar lebih enak, dan biar saya yang muslim tidak dikira cuma sedang menuruti sentimen keislaman saya, kita pakai contoh lain saja yang menempatkan muslim sebagai “pelaku”nya.
Tentang Trinitas dalam Kristen, misalnya. Itu menu yang paling sering dipakai sebagian orang Islam untuk mengukur ajaran Kristen.
“Tuhan kok tiga? Iya tahu, tiga yang satu, satu yang tiga, Tuhan adalah tiga pribadi yang sehakikat. Tapi kan semestinya yang namanya Tuhan itu ya satu secara mutlak!”
Lho lho lho. Ya suka-sukanya orang Kristen dong. Wong keyakinan Kristen seperti itu, kok mau diukur pakai konsep tauhid ala Islam.
Kalaulah ada orang Islam mau menerapkan pengukuran semacam itu sih monggo saja, tapi di lingkup internal masing-masing, untuk kepentingan keyakinan masing-masing.
Sebagaimana orang Kristen mau mengukur ajaran Islam dan menegaskan keyakinan Kristen bahwa Muhammad bukan nabi ya boleh-boleh aja, dalam lingkup internalnya.
Apa pentingnya internalitas ini ditekankan? Agar tidak terjadi pretensi objektivikasi, kan gitu.
“Lha itu Zakir Naik itu mengukur agama-agama lain di ranah publik, seolah standar keyakinan keislaman bisa diterapkan di semua agama. Hayooo!”
Yes, persisss! Persis di situlah, diam-diam sejak semula saya melihat gugatan Mas Sumanto itu pada hakikatnya tak beda dengan ceramah-ceramah Zakir Naik! Hahaha! Lho jangan merengut gitu, coba to renungkan lagi.
Oke, kita cari contoh lain di luar Islam. Orang Hindu tidak boleh makan daging sapi, misalnya. Tapi orang Konghucu boleh.
Trus apa orang Konghucu perlu bilang, “Kenapa umat Hindu dilarang makan sapi? Padahal umat Konghucu dan umat-umat lain biasa saja tuh makan sapi.”
Gitu? Ya nggak mashoook, Buoosss!
Lagi. Orang Sikh laki-laki harus pake turban (serban) dan dilarang memotong semua rambut di badannya. Orang Buddha boleh, bahkan biksu-biksunya malah harus gundul.
Masak orang Buddha mau bilang ala Mas Manto: “Kenapa umat Sikh dilarang potong rambut? Padahal umat agama lain biasa saja cukur. Ribet banget, jaman global warming panas gini kok nggak praktis.”
Gitu? Huuu!
Sekali lagi, agama itu keyakinan, dan keyakinan itu subjektif. Sama-sama subjektifnya, keyakinan itu pada sebagian sisi mirip dengan cinta, atau dengan selera. Cinta dan selera itu nggak bisa dan nggak perlu diuji secara objektif, nggak bisa dirembuk, nggak bisa dimusyawarahkan.
Kalau saya suka cappuccino dan Prof. Manto suka teh tarik, misalnya, saya tidak perlu bilang bahwa Prof. Manto aneh dan tidak masuk akal karena suka minuman yang tidak seenak cappuccino.
Atau kalau saya suka Chef Renatta dan Prof. Sumanto lebih suka Anya Geraldine, itu pun tidak perlu diuji dalam standar-standar ukuran pakem yang seolah-olah universal.
Ah, tapi saya khawatir, Prof. Sumanto Al-Qurtubi nanti juga mau menggugat, “Kenapa Iqbal bisa suka Chef Renatta? Bukannya followernya cuma dua juta? Padahal delapan setengah juta orang lebih memilih follow Anya Geraldine! Sikap Iqbal itu nggak kompatibel dengan perkembangan zaman! Helloooo!”
Mwuahahaha. Dyar.
BACA JUGA Yang Dibikin Karikatur Itu Bukan Nabi tapi Kelakuanmu Itu dan tulisan Iqbal Aji Daryono lainnya.