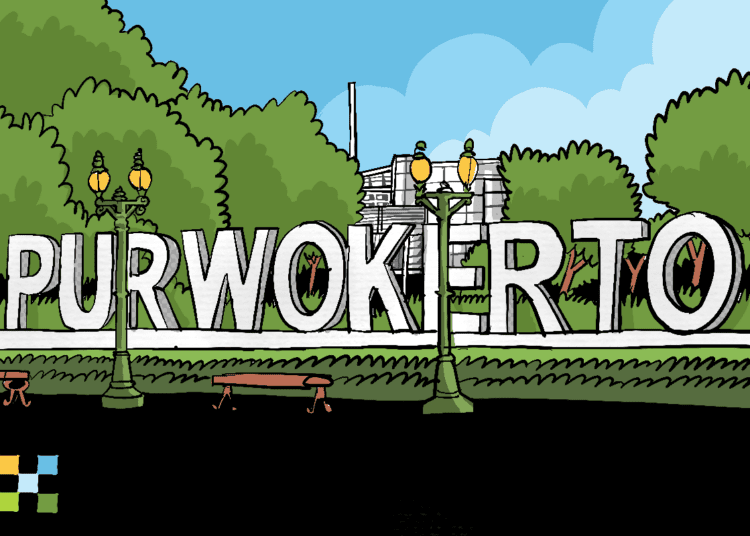Fenomena pungli ini sudah seterang lampu sorot stadion
Area kekuasaan jukir juga mencakup kawasan yang berada tepat di depan kantor pemerintahan. Lahan parkiran juga menjalar hingga depan kantor DPRD.
Sangat tidak masuk akal jika orang-orang Pemda Purwokerto tidak tahu masalah kronis ini. Oleh karenanya, tidak salah jika saya katakan bahwa Pemda memang sengaja tidak mau tahu.
Saya menduga di belakang para juru parkir liar itu ada “mafia” yang bermain dan mengendalikan arus uang. Jika Pemda terus saja bersikap apatis, bukan tidak mungkin, beberapa tahun mendatang Purwokerto akan mendapat “penghargaan anumerta” sebagai kota pungli terbaik se-Indonesia.
Saya rasa, pernyataan ini tidak berlebihan. Siapa saja yang tinggal di Purwokerto saya kira juga akan mengaminkan.
Sebab, polemik parkir memang sudah sampai di tahap yang sangat memprihatinkan. Di mana lahan dipijak, di sanalah pengendara dipalak. Tak peduli toko kecil atau besar, gerai ramai atau sepi, tukang parkir ada di mana-mana. Spot ATM, lokawisata, bahkan pedagang gerobak kaki lima pun ada tukang parkirnya.
Jika saya boleh menyarankan, kalau kalian hendak menjalani slow living di Purwokerto, siapkan juga budget parkir bulanan. Sebab, membayar parkir di Purwokerto adalah sebuah keniscayaan.
Parkir liar tak berkontribusi bagi PAD Purwokerto
Kalau parkir memberi pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur, saya mengiyakan. Tapi, kalau uang dari tarikan parkir turut menyumbang PAD, nanti dulu.
Pasalnya, parkir-parkir di Purwokerto lebih banyak berupa gembongan parkir liar yang sama sekali tidak terafiliasi dengan Pemda. Dan mereka seperti mendiamkan masalah ini. Maka jangan heran kalau ada warga yang curiga Pemda itu maunya cuci tangan dari masalah ini.
Kalimat “membuka lapangan kerja” dari parkir liar ini sangat mengganggu. Memang, hari ini, di Purwokerto, ada begitu banyak tukang parkir usia produktif. Makanya, saya tidak bisa 100% menyalahkan fenomena tersebut.
Sebab, logika tukang parkir itu sederhana saja. Kalau jadi tukang parkir saja sudah mencukupi kehidupan sehari-hari, buat apa mencari kerja di luar sana? Toh hasilnya sama saja, bahkan lebih.
Terlebih mereka juga bisa parkir dengan aman dan nyaman tanpa gangguan. Paling-paling cukup memberikan “uang keamanan”. Selebihnya beres! Jika logika semacam ini sudah menjadi mindset kolektif, apakah nantinya menjadi jukir bukan lagi pilihan terakhir?
Pada dasarnya, Purwokerto punya masalah serius dengan sempitnya lapangan pekerjaan. Tidak adanya industri besar, rendahnya standar gaji, dan minimnya upaya Pemda untuk mencari solusi menjadi sintesis masalah yang terakumulasi.
Tak mengherankan jika akhirnya banyak orang mengambil jalan lain. Menjadi jukir atau membuka angkringan kecil-kecilan di trotoar, misalnya. Cobalah sekali tempo berjalan-jalan malam ke Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di kawasan Menara Teratai.
Di sana, kita bisa menyaksikan para tukang angkringan menggelar dagangannya di trotoar. Di sepanjang jalan, puluhan tukang parkir hilir mudik mengurus motor yang datang dan pergi.
Tahu apa kesamaan antara si pedagang dan tukang parkir itu? Kesamaan dari keduanya adalah sama-sama liar. Pedagang liar dan tukang parkir liar. Kombinasi presisi untuk mengacaukan tata kota Purwokerto yang sudah diproyeksikan jauh-jauh hari.
Sebuah keresahan
Izinkan saya bertanya. Apakah keberadaan jukir dan preman memang sengaja dipelihara? Jika tidak, lantas mengapa belum ada tindakan nyata untuk membenahinya?
Saya kira, artikel semacam ini sudah bertaburan di banyak media. Di slip gaji anggota dewan juga ada tunjangan komunikasi yang bisa mereka gunakan untuk membeli kuota internet dan berselancar mencari artikel semacam ini.
Namun, sejauh ini, keresahan dan predikat kota pungli seakan menjadi angin lalu saja. Kalau saya boleh bertanya lagi, apa prestasi Purwokerto hingga hari ini?
Pada artikel sebelumnya, saya pernah menyatakan bahwa Pemda lebih tertarik dengan aspek-aspek pembangunan fisik. Pemda begitu mesra dengan pihak swasta sehingga kerap mengabaikan masalah-masalah fundamental yang sebenarnya harus segera dibenahi.
Saya hanya khawatir. Jika tidak ada tindakan yang serius berkaitan dengan fenomena jukir dan pungli ini, semakin lama Purwokerto benar-benar menjadi the city of pungli. Terlebih, oknum-oknum jukir merasa aman dan nyaman. Tidak pernah ada yang mengusik mereka, kecuali preman-preman lokal.
Purwokerto tidak bebas premanisne
Jika hendak head to head dengan Jogja, Purwokerto memang tidak ada gerombolan klitih, para begal tengik dan meresahkan. Meski begitu, bukan berarti kota ini bebas premanisme.
Premanisme tetap ada, hanya dalam bentuk yang lebih soft dan terselubung. Premanisme di Purwokerto biasanya terjadi di kawasan pasar dan tempat-tempat potensial untuk berjualan. Tarikan demi tarikan mengatasnamakan uang keamanan seakan menjadi hal biasa yang cukup untuk ditoleransi.
Apakah tulisan ini berusaha untuk menyudutkan? Bisa iya, bisa juga tidak. Tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Jika ada yang mengatakan apa solusi yang bisa ditawarkan, saya akan menjawabnya dengan sebuah banyolan.
Rakyat menggaji pemerintah melalui pajak agar mereka bekerja dengan cara memikirkan solusi atas sebuah permasalahan. Andaikan rakyat juga yang memberikan solusi atas masalah yang sedang terjadi, bukankah itu artinya pemerintah makan gaji buta? Apakah kita sebagai rakyat rela?
Kalau di artikel sebelumnya saya memberikan saran, di artikel ini saya justru ingin mendorong Pemda Purwokerto agar berpikir dan segera mengambil tindakan. Gunakan logika dan daya pikir untuk merumuskan solusi atas masalah ini.
Hal yang tak kalah pentingnya adalah adanya aksi, bukan hanya retorika semata. Jika mahasiswa semester akhir sibuk dan kebingungan mencari masalah yang hendak diteliti dan dipecahkan, Pemda justru sudah mengantongi masalah yang siap dikaji dan dicarikan solusi terbaiknya.
Tak perlu mencari-cari lagi. Kepada Pemda, selamat bekerja dan menemukan solusi paling baik untuk kita bersama. Tabik!
Penulis: Imam Safii
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Purwokerto Adalah Daerah Paling Aneh karena Bukan Kota, Kurang Pas Disebut Kabupaten, Apalagi Menjadi Kecamatan. Maunya Apa, sih? dan catatan meresahkan lainnya di rubrik ESAI.