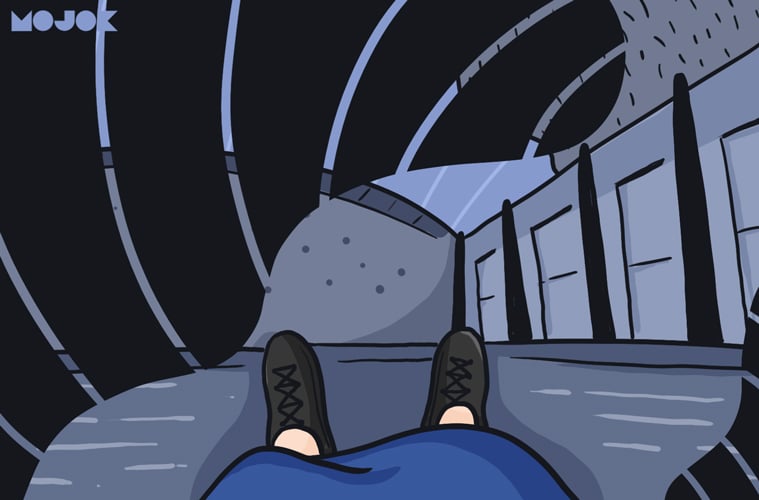MOJOK.CO – Ibu kos punya pengaruh besar membenamkan serentetan nilai, wacana, dan ideologi ke anak-anak yang numpang di kos-kosannya. Jangan meremehkan ya Anda.
“Di sini, nggak boleh telat bayar lebih dari dua hari, ya, Mas.”
Tiba-tiba perempuan paruh baya itu menghampiri saya, lalu menyuguhkan kunci kamar.
“Tentu, Bu. Hehe.”
Saya tersipu sekaligus membatin; akumulasi antara rasa takjub dan geram.
Takjub karena yang bersangkutan, saya yakin, punya kemahiran menebak gelagat dan kebiasaan buruk calon konsumennya—dan ini hanya bisa diraih dari pengalaman terjal selama belasan sampai puluhan tahun.
Geram, sebab alih-alih menghidangkan basa-basi khas Nusantara sebagai simbol perkenalan, yang bersangkutan justru membuat saya merasa tersindir. Padahal, kelak setiap awal bulan, saya akan jadi lumbung rupiahnya.
Itu adalah pengalaman pertama—sekaligus pengalaman kelam—saya berkenaan dengan cara kerja ibu kos. Dan bayangan itu tak bisa lenyap begitu saja di tempurung kepala. Ia terus berkelindan, saling-silang, terbayang-bayang, mengendap dan mencuri satu ruang parsial di benak saya, persis seperti lagu “Aisyah Istri Rasulullah” di benak ukhti–ukhti, atau Mars Perindo bagi penonton setia emensitivi.
Barulah, setelah berpindah-pindah kos sebanyak tujuh kali, saya sadar bahwa cara kerja ibu kos bukan semata berpijak pada SOP yang tak tersirat namun diam-diam juga menjadi tonggak lahirnya identitas suatu bangsa.
Heh? Coba ulangi, kamu ngomong apa barusan, bgzt?
Ini serius. Ngana pikir, kenapa sejauh ini Bangsa Indonesia begitu lekat dengan adagium gotong-royong? Ya, jelas, karena pada suatu masa, para penggagas republik ini pernah hidup di lingkungan kos yang kolektif.
Soekarno, Semaoen, Musso, dan Kartosoewirjo, seperti yang tercatat dalam lebar sejarah, pernah ditempa di tempat kos milik Tjokroaminoto, di JL. Paneleh Gang VII. Adalah RA Suharsikin, Sang Ibu Kos, yang secara teratur menagih uang sewa setiap bulannya kepada mereka.
Meski, diceritakan dalam Soekarno: Penyambung Lidah Rakyat, bahwa tempat kos ini “jelek dan sama buruknya” tetapi mereka tetap berkumpul dan konon saling berbagi lektur. Di sanalah embrio berjamaah bagi bangsa ini mulai muncul ke permukaan.
Tetapi “identitas”, apa pun embel-embel di belakangnya, tak pernah final. Ia terus bergejolak seturut laju zaman. Adalah keniscayaan bahwa “Identitas Bangsa” kita terus dipupuk—kalau bukan dicari.
Buktinya setiap semester, di kampus saya, bapak-bapak MPR sering mengadakan seminar Empat Pilar Kebangsaan, dan bagi-bagi tas untuk peserta. Sebuah usaha yang tak bisa dibilang gagal, cuma salah sasaran aja.
Ada baiknya para bapak pejabat yang terhormat mengalihkan anggaran untuk seminar-seminar-nggak-guna-itu untuk memberi pelatihan khusus untuk para ibu kos se-Indonesia. Karena dari mereka lah, masa depan Indonesia berada.
Apalagi menurut survei Property Watch, sekitar 47,4% generasi milenial memilih tinggal di kos alih-alih nyicil atau membeli rumah, dan persentase itu akan terus meningkat sebab harga properti yang kian hari kian tak masuk akal.
Dari angka itu, setidaknya ada kelompok intelektual (yang direpresentasikan oleh mahasiswa) dan kelompok para pekerja. Artinya, ada hampir setengah populasi warga usia produktif (dan calon produktif) di Indonesia yang tinggal di kos-kosan.
Kelompok Mahasiswa-Pekerja dan Ibu Kos ini, kita tahu, menciptakan satu relasi yang ambivalen, keduanya menyatu disebabkan kebutuhan masing-masing; uang di satu pihak dan tempat tinggal di pihak lain.
Keduanya tentu tak berdiri sejajar, meski juga tak saling gontok-gontokan. Tetapi sampai di sini, kita perlu mencatat satu hal, ibu kos punya kuasa lebih. Sehingga bukan tidak mungkin ia membenamkan serentetan nilai, wacana, dan ideologi ke anak-anak yang numpang di kos-kosannya.
Suatu kali, ketika mengerjakan tugas kelompok di tempat kawan, saya pernah pulang tunggang-langgang di malam gelap karena ditagih denda oleh ibu kos kawan saya. Kepada saya, si ibu kos mengatakan satu fakta; setiap yang bertamu hingga lewat tengah malam, numpang mandi dan cas handphone, akan dikenakan tarif istimewa.
Saya berani bertaruh dengan seluruh harta-benda, bahwa intelektual yang terikat kebijakan jenis ini akan tumbuh menjadi insan yang materialistik dan penuh itung-itungan. Mereka tidak hanya akan berkutat hidup pada corak kepemilikan pribadi, namun juga sensitif dengan perhitungan ekonomi. Dari urusan air panas di dispenser sampai colokan menanak nasi.
Saya yakin orang macam Sri Mulyani, Rizal Ramli, Faisal Basri sampai Kwik Kian Gie—paling tidak—dalam satu fase kehidupannya pernah ngekos di tempat ibu kos model begini. Sudah jadi serba-ekonomi(s) sejak dalam kamar sendiri.
Di sisi lain, saya juga pernah dapat pengalaman menginap di tempat kos kawan. Sebuah kos-kosan yang tidak terikat pada durasi dan jumlah pengunjung. Bahkan di sana juga dibebaskan untuk mengeksplorasi hal-ikhwal yang berkenaan dengan bakat dan hobi. Entah karena ibu kosnya kelihatan sangat paham arti kebebasan atau sebatas cuek saja.
Wajar kalau di dinding kamar penghuni kos-kosan terlukis pelbagai mural yang bentuknya mengenaskan, dan tempat ini terbebas dari segudang aturan yang menjemukan. Sudah jelas penghuni kos-kosannya akan berkembang menjadi pemuda yang bebas dengan cita-cita besar tanpa batas.
Saya yakin orang macam Mario Teguh sampai pemimpin Sunda Empire pasti berasal dari ibu kos model begini.
Bahkan hanya dari kunjungan ke dua tempat saja, perwakilan kinerja ibu kos sudah bisa mewakili apa yang saya maksud. Catatan ini bahkan belum memasukkan jenis ibu kos galak, judes, menggemaskan, lucu, seksi, layaknya cerita-cerita stensilan milik Enny Arrow.
Omong-omong, apakah ngana sekalian paham, alasan mengapa saya membuat tulisan ini? Agar kita semua bisa memecahkan satu teka-teki semesta, kira-kira ibu kos macam apa yang melahirkan insan adiluhung macam anggota staf khusus milenial sang multitalenta?
BACA JUGA Pindah Kos Itu Berat, Apalagi Jika Ibu/Bapak Kosnya Baik Setengah Mampus atau tulisan Muhammad Nanda Fauzan lainnya.