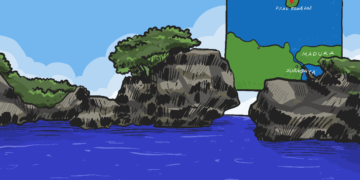MOJOK.CO – Mungkin yang lokal, yang tradisional itu memang tidak harus dipikir, mungkin realitas pawang hujan di Mandalika ini harus disikapi melalui pendekatan rasa.
Tulisan ini jelas merupakan reaksi atas fenomena pawang hujan Mandalika. Di sini bukan menjelaskan apakah pawang hujan itu halal atau haram, sah atau tidak sah, syirik atau tidak.
Bukan kompetensi saya untuk memberi stempel untuk pawang hujan di Mandalika. Tapi bagi pembaca, bisa saja tulisan ini dianggap sebagai pembelaan yang sudut pandangnya berat sebelah, dicap sebagai mekanisme buzzer front pembela klenik, musrik atau bid’ah. Biar saja. Saya tidak keberatan dituduh seperti itu.
Memang benar, latar belakang pendidikan dan pekerjaan saya berada di ranah yang akrab dengan kebudayaan dan tradisi lokal. Tulisan hanya akan mencoba menawarkan cara berpikir dalam menyikapi fenomena pawang hujan di Mandalika, bukan pula how to menjadi pawang hujan, menjabarkan mantranya, dan ritualnya. Meskipun, di kampus saya, memang ada kajian tentang hal-hal itu.
Di media sosial, kita sedang berantem mengomentari pawang hujan di Mandalika. Belum selesai debat panas tentang ritual penyatuan air dan tanah seluruh Indonesia di IKN yang belum lama dilakukan institusi resmi negara kita, eh sudah muncul kasus yang mirip. Media sosial memang tak pernah kehabisan gorengan meskipun minyak sedang mahal.
Perdebatan menjurus ke arah labelisasi ilmiah vs non ilmiah. Modern vs tradisional. Religius vs klenik. Tapi, sekali lagi. Sudut pandang agama tidak akan saya singgung.
Seru sekali menyaksikan pertarungan opini ilmiah vs tradisional tentang si pawang hujan di Mandalika. Kaum ilmiah menuntut penjelasan tertulis yang komprehensif dan empirik, mengenai teknologi modifikasi cuaca di Mandalika. Sementara kaum tradisi (yang lalu dianggap sebagai lokal dan lisan) agak kesulitan menjelaskan secara tertulis dan ilmiah apa yang dilakukan Mbak Rara. Ya, karena memang mereka tradisinya lisan. Tidak punya dan kadang tidak perlu referensi tertulis untuk menjelaskan kejadian di dunia ini.
Atas nama modernitas dan rasionalitas, kaum ilmiah selalu berada di atas angin. Keilmiahan menempati posisi yang hegemonik dalam pertarungan tersebut. Situasinya serba mendukung untuk itu.
Teknologi modern, literasi dan informasi yang melimpah, tingkat keterdidikan masyarakat yang semakin tinggi, adalah kondisi yang memosisikan bahwa keilmiahan seolah menjadi tolok ukur utama dalam pola pikir dan tatanan masyarakat guna menyikapi realitas-realitas yang ada di kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pawang hujan yang merupakan indigenous, kearifan lokal dari tradisi lisan, susah payah memosisikan diri dalam tatanan tersebut.
Tapi, fenomena Mandalika memutarbalikkan posisinya. Tradisi lokal sementara waktu mengungguli keilmiahan dalam hal teknologi, yakni rekayasa cuaca. Eksposure akan hal ini luar biasa di media. Bahkan akun resmi motoGP ikutan mengamini ini dengan postingannya—institusi yang semestinya sangat ilmiah karena memang sangat “barat” dan modern.
Mbak Rara, lewat praktiknya di sirkuit, berhasil menunjukkan bahwa ada kenyataan di dunia ini yang ternyata sukar dijelaskan secara ilmiah. Kearifan lokal berupa mantra, ritual, dan permainan bunyi (dari bejana yang menjadi instrumen performatifnya), yang merupakan hasil teknologi masyarakat tradisi lisan, dipertontonkan ke seluruh dunia.
Diakui atau tidak, di bangsa timur, khususnya Asia, apalagi Indonesia, tradisi pawang hujan ini masih tetap hidup, lestari, dan diwariskan hingga hari ini. Meskipun, hidup dalam kalangan atau komunitas tertentu, kadang pula teknologi ini hanya “disimpan” dalam ingatan “pemiliknya”, tidak ditulis, dibukukan, lalu dikaji. Teknologi yang bersifat sakral dan hanya ditransmisikan atau diwariskan secara turun-temurun dan tidak ke sembarang orang.
Hanya orang terpilih yang dianggap mampu yang akan memperoleh transfer pengetahuan ini dari pendahulunya. Sehingga muncul kesan eksklusif, minoritas, di mana tidak semua khalayak yang mayoritas ilmiah, punya akses untuk itu. Jadi dianggap tidak lumrah atau umum, dan dilabeli tradisionalitas. Padahal, pengetahuan ilmiah sebenarnya juga milik kalangan terbatas, diwariskan secara ekslusif pula.
Lihat saja seleksi ujian masuk perguruan tinggi. Bukankah kuliah juga bukan milik semua orang? Hanya, sekali lagi, kaum terseleksi secara ilmiah jumlahnya lebih banyak, mayoritas, jadi keilmiahan seolah-olah lumrah dan umum, yang pada akhirnya terlabeli dengan modernitas.
Kontestasi kedua ideologi tersebut, moderenitas dan tradisionalitas, berkelindan setiap waktu dalam kehidupan ini. Seringnya, modernitas memenangkan kontesnya. Lalu kita hidup dalam kultur berpikir seperti itu. Kita terbiasa dan terobsesi menjelaskan segala sesuatu secara ilmiah dan modern.
Tapi bukankah secara ilmiah (di kampus) kita diajari untuk berpikir kritis melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang? Kita dilatih untuk menelisik gejala-gejala realitas yang terjadi di sekitaran kita? Kita dibimbing untuk tidak terburu-buru menyimpulkan segala sesuatu sebelum melakukan penelitian dan memahaminya dengan benar?
Barangkali yang terjadi di Mandalika hanyalah sebuah gejala yang perlu kita kritisi dan teliti lebih lanjut (secara ilmiah jika memang dituntut untuk itu) di mana ternyata manusia mampu merekayasa cuaca. Bisa saja hal itu merupakan realitas di sekitar kita yang belum kita pahami. Kita tidak boleh menafikan kenyataan tersebut. Karena memang ada, dan diakui worked oleh orang barat yang modern.
Jika memang belum bisa dijabarkan secara ilmiah, barangkali pembacaan kita saja yang belum sampai ke situ. Atau malah keilmiahan belum mampu mendefiniskan pawang hujan, atau justru tidak perlu didefinisikan secara ilmiah? Mungkin dalam memahaminya, tidak butuh teori ilmiah dan akademis khas barat yang menjadi standar berpikir kita. Meskipun saya akui tulisan ini juga terjebak dalam hegemoni keilmiahan barat.
Penjabaran tentang tradisi lokal dan lisan di atas adalah risalah teori akademisi barat Walter J. Ong, Albert Lord, Homi K. Bhabha, J.J. Ras, Pierre Bourdieu. Huuft… bahkan untuk menjelaskan tentang timur saja butuh pemikiran orang barat.
Mengutip beberapa ceramah guru-guru timur:
“Tidak semua hal di dunia ini harus diukur dengan rasio. Otakmu ra bakal nyandhak mikirke iku.”
Serta ada nasihat untuk senantiasa rendah hati dalam menuntut ilmu, karena makin banyak yang kita pelajari, sebenarnya makin banyak yang tidak ketahui. Hidayah ilmu itu seperti jodoh, rejeki, dan kematian. Datangnya kapan kita tidak pernah tahu. Barangkali hari ini saja kita belum paham tentang pawang hujan di Mandalika. Siapa tahu besok lalu paham.
Mungkin yang lokal, yang tradisional itu memang tidak harus dipikir, mungkin realitas pawang hujan di Mandalika ini harus disikapi melalui pendekatan rasa. Kalau sudah begitu, ya sudah percaya saja. Seperti kamu percaya hal-hal di luar logika dalam praktik ritual agamamu.
BACA JUGA Teror Mistisisme Jawa Bikin Warga Jogja Selalu Narimo Ing Pandum dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.
Penulis: Paksi Raras Alit
Editor: Yamadipati Seno