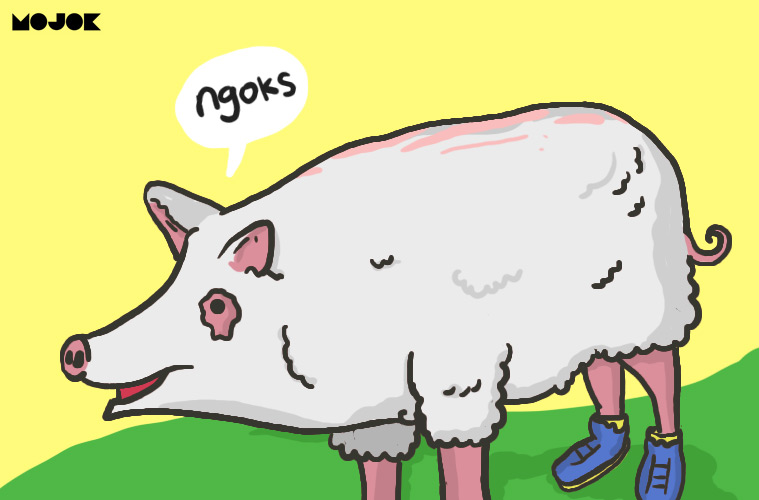Berkali-kali, saya dikatain banyak orang sebagai antek Islam liberal. Alih-alih ngambek, yang terjadi pada saya justru malah pusing kepala, karena tak begitu paham apa sebenarnya yang mereka maksud dengan liberal.
Mohon dimaklumi ketidakpahaman saya. Lha wong saya ini nyantri nggak pernah, sekolah agama nggak pernah. Belajar agama cuma dari bapak-ibu, dari pengajian di kampung, dari Majalah Suara Muhammadiyah, dan dari pelajaran sekolah.
Dengan bekal minim begitu, mana bisa saya paham apa itu muslim liberal? Tahunya ya Islam itu begini begini begini. Ada sekian ulama dan kelompok, dengan tafsir mereka masing-masing atas teks pegangan umat Islam. Itu saja.
Nah, begitu saya tanya kepada teman-teman yang menyebut saya liberal itu, “Eh, sakjane liberal ki opo to?”, pusing saya bukannya berkurang, malah kian berlipat.
“Nggak perlu penjelasan rumit tentang mana yang liberal dan mana yang tidak. Melihat orang liberal itu cukup dengan perasaan saja sudah ketahuan.” Begitu jawaban seorang sahabat saya, teman FB yang sekarang hijrah ke Instagram.
Waduh. Pakai perasaan? Lha menurut saya kok malah Abu Bakar al Baghdadi itu muslim yang liberal banget ya. Lho kok bisa? Lha iya, perasaan saya mengatakan demikian. Verifikasinya gimana? Ha embuh, kan katanya cukup pakai perasaan. Kyaaaaa.
Proses identifikasi berbasis metode perasaan tadi semakin lengkap ketika sahabat saya itu menindaklanjutinya dengan sikap politik. “Terkait konflik Suriah, cara kita bersikap gampang saja. Lihat di mana orang-orang liberal berada, kita berdiri di pihak seberangnya.”
Saya tertegun. Lalu dengan ragu-ragu saya bertanya. “Eh, Pak, orang liberal banyak yang membela Asaad. Di seberang Asaad, berdiri Zionis Israel. Berarti apakah secara prinsip lebih baik kita bergabung bersama Zionis ketimbang sama muslim liberal?”
Kali ini dia tidak menjawab. Mungkin dia sedang terbang ke Tel Aviv.
Maka saya pun mengadu kepada raksasa intelektual muslim masa depan, Azis Anwar Fachruddin. Saya pasrahkan kegalauan saya di pangkuannya.
“Kekeliruanmu adalah,” kata Azis, “mengira bahwa istilah liberal adalah istilah yang monolitik.”
Waduh. Lha kok malah tambah pusing begini? Tentu saya tidak nyantol dengan penjelasan Aziz selanjutnya yang amat sophisticated itu. Ada jurang kesenjangan intelektual yang terlampau lebar di antara diriku dan dirinya. Selamat tinggal, Propesor Azis.
Akhirnya saya merenung-renungkan saja tokoh-tokoh yang dicap liberal. Pak Quraish Shihab, itu contoh yang paling gampang. Beliau distempel liberal karena, konon, menyatakan jilbab tidak wajib.
Dari dua teman, saya dapat kopian halaman-halaman paparan atas jilbab dalam Tafsir al-Mishbah, magnum opus Pak Quraish. Tapi setelah saya baca, kok tidak ada pernyataan jilbab tidak wajib, ya? Isinya hanya beragam pandangan para ulama klasik tentang hukum jilbab. Pihak yang mewajibkan dikutip berikut penjelasan mereka, demikian pula yang tidak mewajibkan.
Salah satu yang tidak mewajibkan adalah Muhammad Thahir ibn Asyur, ulama besar dari Tunis. Bersama kutipan pandangan sang ulama, Pak QS juga memaparkan bagaimana sejarah jilbab sebagai penanda perbedaan status antara perempuan merdeka dan perempuan budak.
Di ujung rangkaian pemaparannya, Pak QS menyimpulkan bahwa mereka yang berjilbab sedang menjalankan “bunyi” ayat Al-Quran. Adapun yang tidak berjilbab, belum tentu mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama”.
Tuh, di mana pernyataan Pak QS yang menyatakan “Sesungguhnya jilbab tidak wajib!”, Jon?
Setelah Pak Quraish, ada Cak Nun. Tetangga saya se-Bantul ini dituding liberal karena, salah satunya, menggelar selawatan di gereja. Irama selawatannya pun ada yang pakai irama lagu gereja.
“Dasar kyai liberal! Agama dicampuradukkan!” Komentar jenis demikian sudah jadi bumbu sehari-hari kehidupan Cak Nun. Masih untung kalau yang komen nggak ketemu di jalan sama laskar Maiyah yang terkenal galak-galak itu.
Agama dicampuradukkan? Sebentar. Mari kita lihat prinsip-prinsipnya saja. Yang dilarang campur aduk itu dimensi akidah dan ibadah mahdhah, ibadah khusus. Padahal ini selawatan. Selawat jadi bagian ibadah khusus saat dibaca dalam salat. Tapi kalau selawatan di waktu-waktu lain, ia sekadar ekspresi cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan ibadah khusus.
Lalu ketika Cak Nun main ke gereja, itu juga perkara muamalah, hubungan sosial, bukan ibadah. Ketika di gereja nembang selawat, alias menyanyikan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi saat main ke tempat tetangga, so what? Wong si tetangga juga rela, kok.
Bakalan jadi pencampuradukan agama kalau yang dilakukan Cak Nun adalah, misalnya, salat sambil sengaja menghadap salib, atau umat Kristen di situ menjalankan kebaktian sambil mensyukuri kenabian Muhammad. Itu baru pencampuradukan, Denmas.
Dan kalau oplosan begituan yang terjadi, itu malah bukan liberal juga. Melainkan sudah bukan Islam, dan bukan juga Kristen. Ya to? Lalu liberal tuh yang seperti apa, Jon?
***
Saya kira, tarik ulur antara liberal dan ortodoks terjadi karena orang Islam berbantahan tentang garis batas. Ada yang meyakini masuk ke bangunan gereja bagian dari perkara ibadah, ada yang tidak. Lalu yang pertama menyebut yang kedua sebagai liberal.
Ada yang meyakini pakai celana anti-isbal alias celana cingkrang bagian dari syariat. Ada juga yang cuma melihatnya sebagai bahasa zaman, karena pada zaman Rasul pakaian yang melewati mata kaki merupakan simbol kesombongan. Lalu yang pertama menyebut yang kedua sebagai liberal, atau minimal bahwa dirinya lebih syar’i.
Ada yang melihat batasan penafsiran teks suci adalah bunyi kata-kata. Tapi ada pula yang memahaminya sebagai sistem simbol yang harus diserap spiritnya.
Maka kelompok pertama meyakini hukum potong tangan bagi pencuri adalah syariat sampai akhir zaman. Sementara yang kedua melihatnya sebagai spirit suci ajaran Islam, yakni agar pelaku kezaliman kepada sesama dihukum berat.
Maka kelompok pertama meyakini gambaran surga dengan bidadari dan sungai-sungai sebagai realitas faktual nantinya. Sementara yang kedua memandang bahwa itu semua cuma sanepa Tuhan atas keindahan tiada tara.
Oh, iya … ngomong-ngomong tentang surga, saya jadi ingat Dek Ustadz Syam dan ceramahnya tentang pesta seks. Dari kasus kemarin itu saya menyaksikan betapa banyak ulama Indonesia jadi liberal. Ini gejala bagus.
Meski apa yang disampaikan Dek Ustadz tidak secara mentahan mengacu pada dalil letterlijk dari kitab, sebenarnya ia masih berada dalam koridor tekstualisme. Kita tahu, ayat-ayat suci mengatakan bahwa janji kenikmatan surga adalah para bidadari cantik jelita, dan semua itu ditangkap Dek Ustadz sebagai pesta seks.
Itu jelas tekstualisme. Lha kalau para lelaki dikasih perempuan cantik bahenol pada situasi yang tidak lagi menetapkan verboden moral apa pun, emang trus pada mau ngapain? Main gaple?
Nah, ketika kaum muslimin lintas batas menolak paparan Dek Ustadz, artinya semua sudah bersepakat bahwa gambaran di kitab suci tentang surga hanyalah simbolisme semata! Lho, bukannya ini cara pandang liberal? Bahaya! Selamatkan akidah umat!
Pada ujung kebingungan saya tentang isu liberal ini, di Perth saya ketemu Ustadz Azizi. Beliau orang Malaysia, lulusan pendidikan agama tradisional di Mesir. Kepada beliau kami bertanya soal liberal-liberalan ini.
Lalu Cikgu Ustadz bercerita tentang kisah selepas Perang Khandaq. Saat itu, Nabi memerintahkan para sahabat agar berangkat ke perkampungan Bani Quraizhah. Beliau berpesan, “Jangan ada satu pun yang salat Asar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah.”
Rombongan pun berangkat. Sialnya, sampai menjelang waktu Asar habis, mereka belum juga sampai ke kampung yang dituju.
Maka para sahabat terbelah dalam dua pendapat. Kelompok pertama ngotot untuk salat Asar di tempat tujuan sebagaimana pesan Nabi, yang artinya ketika waktu Asar sudah lewat. Kelompok kedua keukeuh bahwa maksud Nabi adalah agar mereka berjalan cepat, sehingga tiba di kampung Bani Quraizhah ketika waktu Asar masih ada. Maka ketika ternyata target waktu tersebut gagal, mereka tetap salat Asar di jalan.
Belakangan, ternyata Nabi tidak menyalahkan keduanya.
“Jadi,” kata Cikgu Azizi, “kelompok yang pertama itu berpatokan pada teks, alias ortodoks. Yang kedua menafsir maksud, alias liberal. Nabi tidak menyalahkan satu pun di antara mereka. Maka, menghadapi pertentangan antara ortodoks dan liberal ini, kita tidak usah terlalu tegang.”
Lho, lho, lho, ini kenapa ending tulisannya jadi bijaque begini? Terus kapan kita gontok-gontokannya?