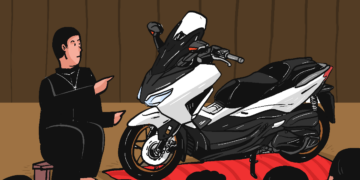MOJOK.CO – Setiap kali saya melihat orang ribut soal toleransi, saya sering teringat kampus kecil tempat saya sebagai muslim menempuh pendidikan tinggi, UKSW Salatiga.
Saya kuliah di sebuah universitas Kristen. Namanya, Universitas Kristen Satya Wacana, atau yang lebih sering disingkat UKSW. Kampus ini berdiri di Salatiga, kota kecil di Jawa Tengah yang tidak pernah benar-benar sibuk, tapi juga tidak pernah sepenuhnya sepi.
Kota yang ritmenya pelan, tapi justru karena itu terasa manusiawi. Kota yang kalau malam cepat sunyi, tapi anehnya selalu bikin rindu.
Yang sering bikin orang lain heran, saya seorang muslim. Dan tidak, pengalaman saya kuliah di kampus Kristen ini sama sekali tidak seperti skenario sinetron toleransi yang sering dibayangkan orang-orang.
Tidak ada adegan saya merasa terasing. Tidak ada momen harus menunduk atau merasa “berbeda”. Di UKSW, agama saya bukan identitas utama. Ia tidak pernah jadi pembuka percakapan, apalagi masalah.
Saya datang sebagai mahasiswa, diperlakukan sebagai mahasiswa, dan dinilai sebagai mahasiswa. Sesederhana itu.
Padahal, dari namanya saja sudah jelas: Universitas Kristen Satya Wacana. Tidak ada embel-embel “inklusif”, “multikultural”, atau “berbasis kebhinekaan” yang biasanya terpampang besar di baliho kampus lain.
Namun, justru di situlah keanehannya. UKSW tidak ngomongin toleransi, tidak sibuk mengiklankan toleransi. Ia menjalankannya dengan cara yang nyaris membosankan karena begitu normal.
Hari-hari awal kuliah saya lalui seperti mahasiswa baru pada umumnya. Salah masuk kelas, nyasar ke gedung fakultas lain, sok kenal senior padahal lupa nama, dan pura-pura tenang saat jadwal kuliah berubah mendadak.
Tidak ada sesi interogasi iman. Tidak ada tatapan penuh kecurigaan. Tidak ada pertanyaan klasik, “Kamu muslim kok kuliah di sini?”
Yang ada justru pertanyaan jauh lebih relevan dengan kehidupan mahasiswa: “Kamu kos di mana?” atau “Sudah nemu makan murah belum?”
Dan di situlah saya mulai sadar, bahwa barangkali toleransi terbaik memang yang tidak merasa perlu diperlihatkan.
UKSW Salatiga yang tidak ribut soal identitas
Salatiga adalah kota yang tidak gemar ribut. Ia tidak berlomba menjadi metropolitan. Tidak pula sibuk membangun citra. Hidup berjalan apa adanya, pelan, dan relatif tertib. Suasana itu terasa menular sampai ke kampus UKSW Salatiga.
Di ruang kelas, dosen mengajar tanpa beban identitas mahasiswa. Agama hanya dibahas jika memang relevan dengan materi. Diskusi berjalan sehat. Tugas tetap menumpuk tanpa ampun.
Deadline tetap kejam tanpa kompromi. Tidak ada perlakuan istimewa, tapi juga tidak ada diskriminasi. Saya tidak pernah merasa perlu “menyesuaikan diri” agar diterima.
Dalam hal-hal kecil, sikap itu terasa jelas. Ketika ada acara kampus, makanan halal tidak pernah menjadi isu besar yang harus diperjuangkan dengan wajah sungkan. Ia tersedia begitu saja, seolah memang sudah sewajarnya demikian. Tidak dirayakan, tapi juga tidak diabaikan.
Di UKSW, perbedaan tidak dijadikan bahan pidato panjang atau seminar berjudul muluk. Ia dijalani saja, seperti lalu lintas Salatiga yang relatif tertib tanpa banyak klakson.
Saya sering berpikir, mungkin toleransi yang paling sehat memang yang seperti ini. Tidak merasa sedang berbuat baik. Tidak merasa paling terbuka. Tidak sibuk mengklaim diri paling benar. Hanya memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya.
Baca halaman selanjutnya “Creative Minority” yang tidak berhenti di poster