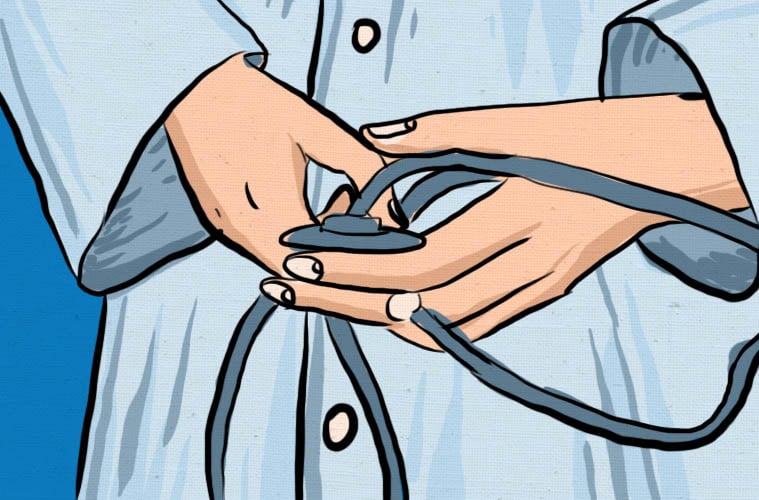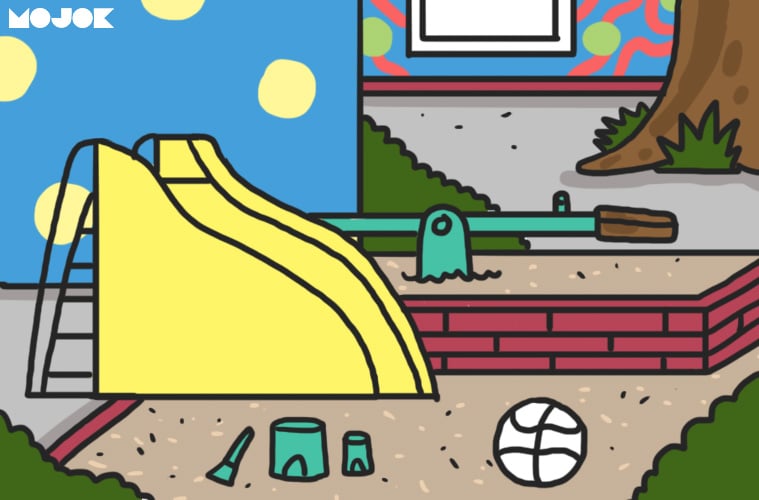MOJOK.CO – Perawat ini menulis kisah rekan seprofesinya yang jadi PDP dan harus dirawat layaknya pasien positif corona. Diceritakan dalam perspektif orang pertama.
Suatu malam di ruang isolasi, saat saya sedang tertidur, tiba-tiba saya terbangun karena leher terasa tercekik. Seperti dicekik oleh dua tangan yang kokoh. Kuku-kuku jari membiru, jari tangan kram dan kesemutan. Rasanya ingin muntah.
Alat pulse oximeter yang terpasang di jari, menunjukkan nilai saturasi saya 93 persen, heart rate saya mencapai 134 kali per menit, jantung berdetak lebih kencang, ini membuat tubuh saya semakin lelah.
Keringat dingin membanjiri tubuh. Saya terus gelisah, berusaha mencari posisi untuk mendapatkan oksigen. Padahal di hidung saya selang oksigen tak pernah lepas, tapi rasanya tetap sesak. Saya segera menelepon ke perawat melalui Video Call.
Perawat bilang saya jangan panik, saya harus tenang agar oksigen untuk tubuh saya cukup. Saya diminta bersabar, karena salah satu dari mereka sedang lari ke IGD meminjam APD. Persediaan APD mereka sudah habis. RS sudah memesan ke distributor tapi barang yang langka membuat pengiriman terhambat.
Saya berprofesi sebagai perawat. Ini adalah pengalaman yang saya rasakan saat saya terdiagnosa pnemonia, dan menjadi pasien dalam pengawasan (PDP).
Sekarang saya tahu bagaimana rasanya hidup dalam ruang isolasi. Sekarang saya paham, bagaimana harus melawan stigma orang-orang yang dulunya dekat, kini menjauh karena takut tertular.
Ya, semua ini pengalaman karena wabah pandemi COVID-19 itu.
Sudah berhari-hari belakangan ini, batuk makin berat dan sesak. “Mungkin efek dari kedinginan, asmaku kambuh,” begitu pikir saya.
Semua diawali beberapa hari sebelumnya, ketika saya sedang bekerja. Saat itu, saya merasa meriang, meski suhu tubuh masih menunjukkan angka normal, 37 derajat Celcius. Saya mulai khawatir jika terinfeksi.
Sepulang kerja, saya langsung datang ke IGD untuk memeriksakan diri. Dokter memberitahu bahwa akan ada pemeriksaan darah dan foto x-ray dada untuk saya. Saya nurut saja.
Setelah hasil foto keluar, gambaran paru menunjukkan tanda adanya infeksi, pnemonia. Lalu saya pun segera dirawat di ruang isolasi dan dijadikan PDP.
Apa, PDP? Pasien dalam pengawasan?
Yang ada dalam pikiran pertama adalah, “Apakah aku akan segera meninggalkan dunia ini? Apa yang harus kulakukan? Apa reaksi keluarga, dan teman-teman kerjaku? Bagaimana dengan nasib pasien yang tadi kurawat?”
Saya menangis.
Malam pertama di ruang isolasi, saya masih menangis. Sendiri, kesepian, ketakutan, terasing. Sedih karena tak ada yang berani mendekat dan tak ada yang mau membesuk.
Saya ini seorang perawat, tapi COVID-19 membuat saya jadi seperti penjahat.
Saya membayangkan, saat ini semua teman-teman kerja saya pasti berada dalam kecemasan, bahwa merekapun akan dijadikan ODP. Tapi sekali lagi, bagaimana nanti nasib pasien-pasien saya?
Siapa yang akan merawat mereka, jika semua perawat menjadi ODP? Bagaimana kalau ada di antara merekapun nanti akan jadi PDP?
Saya ini hanya perawat. Diserang berbagai virus itu sudah biasa, tapi virus COVID-19 ini membuat saya merasa melakukan kesalahan besar. Saya bagai seorang pembunuh.
Belum lagi saya harus melawan stigma yang salah tentang COVID-19. Saya mendapat pesan singkat yang alih-alih mendoakan, namun malah meminta merahasiakan kondisi saya. Saya dilarangnya mengupload dan curhat ke medsos tentang apa yang saya rasa.
Ini menyedihkan. Tak hanya beban fisik yang harus saya tanggung, tapi saya harus tetap menjaga mental agar tetap sehat. Belum lagi mendengar jika beberapa teman perawat yang bukan dari unit kerja saya, menangis karena takut tertular karena sudah melakukan kontak dengan saya sebelumnya.
Selama 24 jam, saya tak bisa lepas dari selang oksigen ini. Saat ke kamar mandi, saya pernah coba melepasnya, tapi itu hanya mampu beberapa menit, saya tak kuat, dada ini terasa terikat tali-tali besar yang kokoh.
Teman-teman perawat dan dokter datang sesekali. Saat datang mereka menggunakan APD lengkap. Saya menawarkan diri pada perawat yang bertanggung jawab, agar mereka menyiapkan semua botol infus dan obat-obatan di meja saya. Meski saya masih lemah dan meriang, saya masih bisa mengganti infus dan minum obat sendiri.
Ini juga untuk mengurangi intensitas mereka masuk ke kamar saya. Paling tidak agar bisa menghemat APD mereka yang masih terbatas jumlahnya.
Saat siang, saya hanya berbaring lemah. Menonton televisi terasa membosankan, bermain gadget kadang membuat kepala semakin pusing. Saya hanya bisa menghitung hari, sesekali chat dengan keluarga, bertanya-tanya berapa lama waktu yang saya miliki, dan menghubungi kerabat, teman untuk meminta maaf pada mereka untuk segala salah yang pernah saya lakukan.
Saat-saat seperti ini saya merasa begitu dekat dengan Tuhan. Hanya inilah yang menguatkan saya untuk tetap semangat dan yakin bahwa saya akan baik-baik saja.
Saat malam, adalah saat yang paling saya takutkan. Karena batuk aktif disertai sesak, sehingga saya kesulitan bernafas dan sulit untuk tidur. Jika kondisi agak memburuk seperti yang terjadi di awal tulisan tadi, rekan perawat akan datang, dengan APD seadanya.
ADP itu hanya baju pelindung plus jas hujan sekali pakai. Face shield-nya pun hanya dari plastik mika. Rekan perawat ini segera membantu. Menggantikan oksigen nasal kanul yang sedang saya pakai dengan jenis Non-Rebreathing Mask (NRM) jenis terapi oksigen yang mencegah terhirupnya kembali C02, sehingga memaksimalkan O2 yang masuk saat menarik nafas.
Perawat menaikkan jumlah oksigen ke angka 10 liter. Setelah itu saya diberi obat dengan dosis dinaikkan.
Butuh sekitar tiga jam untuk kembali nyaman. Tiga jam yang saya lalui yang terasa bagai tiga abad. Saya membayangkan bagaimana jika kondisi yang saya alami itu terjadi pada pasien dengan komplikasi. Pasti lebih berat lagi.
Jika kondisi begitu, perawat pun tak bisa berbuat apa-apa. Kalau perawat memaksa memberi pertolongan atas nama kemanusiaan tanpa APD dan si perawat tahu bahwa penyakit pasien ini bisa menular kepadanya, itu sama saja misi bunuh diri.
Sebagai seorang perawat dan juga seorang PDP, saya memaklumi situasi ini. Bukan hanya untuk melindungi dirinya, tapi agar perawatan untuk pasien dengan COVID-19 ini bisa maksimal. Agar banyak pasien yang tertolong.
Menjadikan ini sebagai “perang” yang bisa dimenangkan, bukan pertempuran-pertempuran kecil dengan harga kelewat mahal.
Setelah menunggu tujuh hari hari perawatan di ruang Isolasi, hasil PCR pun keluar. Dan syukur, saya dinyatakan negatif. Ternyata saya hanya mengidap pnemonia biasa. Hal yang menjadi pertanyaan, kenapa harus selama ini? Dokter menjelaskan karena jumlah antreannya lima ratusan.
Saya bergidik mendengarnya. Bayangkan jika lima ratusan yang hasilnya belum selesai dibaca itu positif, bagaimana dengan orang di sekitarnya yang masih berkeliaran, mudik, jajan, dan berinteraksi dengan banyak orang?
Meski begitu, saya ingin kita semua harus optimis. Sengeri apapun, sebenarnya kita masih bisa melakukan segala tindakan pencegahan. Selama seluruh komponen warga negara bisa bekerja sama, membantu kami para tenaga kesehatan.
Kalian cukup lakukan hand hygiene, cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, atau gunakan hand sanitizer, lindungi wajah dengan masker dari droIplet atau percikan ludah yang mungkin akan menyentuh area wajah.
Tak perlu repot coba membantu kami di rumah sakit. Cukup kalian jaga jarak, tetap di rumah, beraktivitas dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan hindari diri sendiri maupun keluarga berisiko tertular. Itulah bantuan terbesar yang bisa kami peroleh sebagai petugas kesehatan menghadapi perang melawan pandemi ini.
Jangan biarkan oksigen dalam dadamu dirampas, sebab itu bukan tugas corona, biarkan itu tetap—dan selalu—jadi tugas rindu saja.
BACA JUGA Kesehatan Mental dalam Isu Pandemi Corona atau tulisan rubrik ESAI lainnya.